Tuntutan Faur (Disegerakan) – Terjemah Syarah al-Waraqat
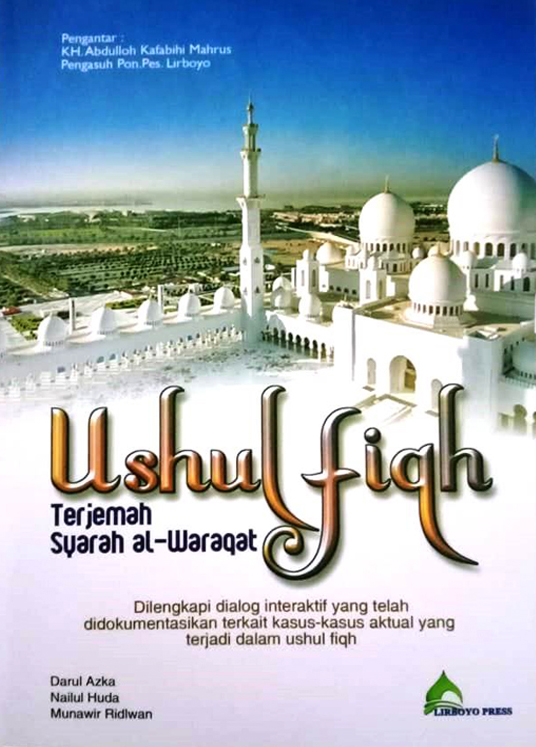
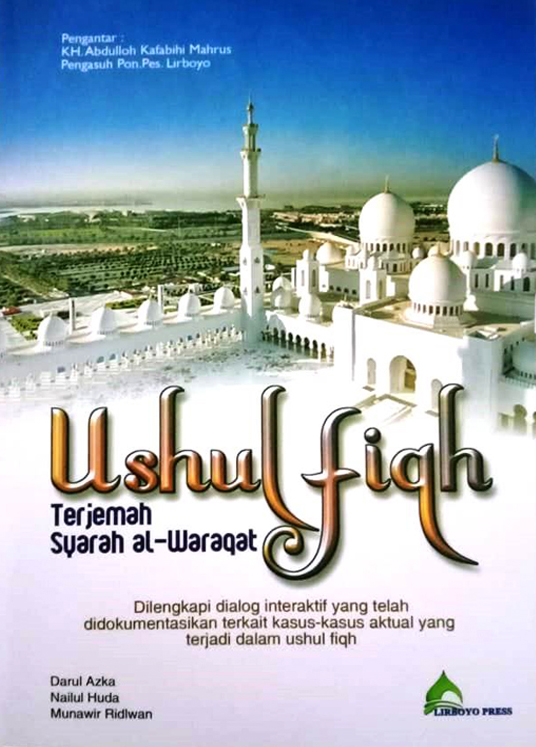
وَ لَا يَقْتَضِيْ الْفَوْرَ) لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ إِيْجَادُ الْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ اخْتِصَاصٍ بِالزَّمَانِ الْأَوَّلِ دُوْنَ الزَّمَانِ الثَّانِيْ وَ قِيْلَ يَقْتَضِي الْفَوْرَ وَ عَلَى ذلِكَ يُحْمَلُ قَوْلُ مَنْ يَقُوْلُ إِنَّهُ يَقْتَضِي التِّكْرَارَ.
Amr juga tidak menuntut faur (segera dijalankan), karena tujuan dari amr adalah terealisasinya perbuatan tanpa terikat dengan ketentuan di waktu awal, bukan waktu yang kedua (setelahnya). Menurut sebagian pendapat, amr menuntut segera dijalankan. Dan pada pendapat inilah, jalur arahan versi yang menyatakan bahwa amr menuntut adanya pengulangan.
Menurut pensyarah, selaras dengan amr yang tidak menuntut faur (segera dilakukannya perbuatan yang dituntut), maka amr juga tidak menuntut ta’khīr (ditundanya perbuatan tersebut). Amr hanya menunjukkan tuntutan dilakukannya sebuah perbuatan. Pendapat ini diungkapkan Imām asy-Syāfi‘ī dan Ashḥāb-nya dan dipilih oleh al-Amudī, al-Baidhawī dan Ibn Ḥājib serta di-shaḥīḥ-kan dalam kitab Jam‘-ul-Jawāmi‘. Pendapat kedua menyatakan bahwa amr menuntut faur. Diungkapkan oleh sebagian Ashḥāb asy-Syāfi‘ī, dan al-Karkhī dari kalangan Ḥanafiyyah. Mengambil dalīl QS. al-A‘rāf: 12:
مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ
“Apakah yang menghalangimu untuk bersujūd (kepada Ādam) di waktu Aku menyuruhmu.”
Dalam ayat ini Allah s.w.t. mencela Iblīs atas keengganannya bersujūd kepada Nabi Ādam a.s. seketika itu, sedangkan amr dalam hal ini bersifat mutlak. Seandainya amr tidak menuntut faur, maka tentunya tidak ada celaan bagi Iblīs. (221)
Menurut pendapat bahwa amr tidak menetapkan faur (disegerakan di waktu awal), diperbolehkan melaksanakan perbuatan yang diperintahkan di setiap waktu dari semua waktu yang ditentukan syara‘. Apakah wājib melakukan ‘azm (niat/bertekad) untuk melaksanakannya, ketika hendak mengakhirkan dari waktu pertama. Dan mencukupi dilaksanakan pada waktu apapun, baik ada ‘azm atau tidak, selama masih dalam batas waktu yang ditentukan syara‘.
Referensi:
إِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤَخِّرَ الْفِعْلَ إِلَى الْوَقْتِ الثَّانِيْ بَدَلًا مِنَ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْزِمَ عَلَى الْفِعْلِ فِيْ ثَانِي الْوَقْتِ لِيَجُوْزَ لَهُ التَّأْخِيْرُ أَمْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَزْمُ؟ الْجُمْهُوْرُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَزْمُ عَلَى الْفِعْلِ فِي الْوَقْتِ الثَّانِيْ وَ فِيْ أَيِّ وَقْتٍ فَعَلَ الْمَأْمُوْرَ بِهِ أَجْزَأَهُ عَزَمَ أَوْ لَمْ يَعْزِمْ اهــــ (الْوَجِيْزُ صــــ 144).
“Ketika seorang mukallaf hendak mengakhirkan perbuatan yang diperintahkan di waktu kedua, sebagai ganti dari waktu pertama, apakah wājib baginya melakukan ‘azm untuk melaksanakannya di waktu kedua agar diperbolehkan mengakhirkan, ataukah tidak wajib melakukan ‘azm? Menurut Jumhur tidak berkewajiban ‘azm untuk melaksanakannya ketika hendak mengakhirkan di waktu kedua. Di waktu apapun perbuatan tersebut dilakukan, maka hukumnya mencukupi baginya, baik ada ‘azm atau tidak (selama masih dalam batas waktu yang ditentukan)”. (al-Wajīz, hal. 144).