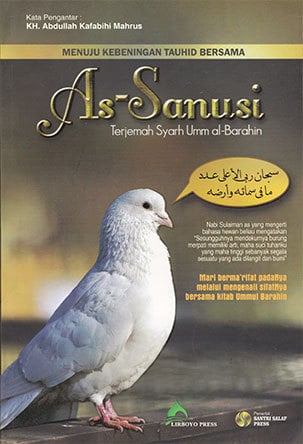8. Tujuh Sifat Ma‘ānī.
[صـــ] (ثُمَّ يَجِبُ لَهُ تَعَالَى سَبْعَ صِفَاتٍ تُسَمَّى صِفَاتُ الْمَعَانِيْ).
(8). Kemudian wajib bagi Allah ta‘ālā tujuh sifat yang disebut sifat ma‘ānī.
Syarḥ.
[شــــ] مُرَادُهُمْ بِصِفَاتِ الْمَعَانِيْ: اَلصِّفَاتُ الَّتِيْ هِيَ مَوْجُوْدَةٌ فِيْ نَفْسِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ حَادِثَةً كَبَيَاضِ الْجِرْمِ مَثَلًا وَ سَوَادِهِ، أَوْ قَدِيْمَةً كَعِلْمِهِ تَعَالَى وَ قُدْرَتِهِ، فَكُلُّ صِفَةٍ مَوْجُوْدَةٌ فِيْ نَفْسِهَا فَإِنَّهَا تُسَمَّى فِي الْاصْطِلَاحِ صِفَةً مَعْنًى.
Maksud ‘ulamā’ dengan istilah sifat-sifat ma‘ānī adalah sifat-sifat yang wujud dengan mempertimbangkan dirinya sendiri, baik bersifat ḥādits, seperti warna putih suatu benda dan warna hitamnya, umpamanya, ataupun bersifat qadīm, seperti ‘ilmu dan qudrah Allah ta‘ālā. Maka setiap sifat yang wujud dengan mempertimbangkan dirinya sendiri dalam istilah ilmu kalām disebut sifat makna (ma‘ānī).
وَ إِنْ كَانَتِ الصِّفَةُ غَيْرَ مَوْجُوْدَةٍ فِيْ نَفْسِهَا، فَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً لِلذَّاتِ مَا دَامَتِ الذَّاتُ غَيْرَ مُعَلِّلَةٍ بِعِلَّةٍ سُمِّيَتْ صِفَةً نَفْسِيَّةً أَوْ حَالًا نَفْسِيَّةً، وَ مِثَالُهَا التَّحَيُّزُ لِلْجِرْمِ وَ كَوْنُهُ قَابِلًا لِلْأَعْرَاضِ مَثَلًا.
Bila suatu sifat tidak wujud dengan mempertimbangkan dirinya sendiri, maka bila wajib bagi dzāt, selama dzāt tersebut tidak di-‘illat-i dengan suatu ‘illat, maka disebut sifat nafsiyyah atau ḥāl nafsiyyah, seperti mengambil tempat secukupnya bagi benda, dan keberadaannya menerima sifat-sifat yang datang padanya, umpamanya.
وَ إِنْ كَانَتِ الصِّفَةُ غَيْرَ مَوْجُوْدَةٍ فِيْ نَفْسِهَا إِلَّا أَنَّهَا مُعَلِّلَةٌ بِعِلَّةٍ إِنَّمَا تَجِبُ لِلذَّاتِ مَا دَامَتْ عِلَّتُهَا قَائِمَةً بِالذَّاتِ سُمِّيَتْ صِفَةً مَعْنَوِيَّةً، وَ مِثَالُهَا كَوْنُ الذَّاتِ عَالِمَةً أَوْ قَادِرَةً مَثَلًا.
Bila suatu sifat tidak wujud dengan mempertimbangkan dirinya sendiri, namun ter-‘illat-i dengan suatu ‘illat dan hanya wajib bagi dzāt selama ‘illat itu ada padanya maka disebut sifat ma‘nawiyyah, seperti keberadaan suatu dzāt ‘ālimatan (yang mengetahui) dan qādiratan (yang mampu), umpamanya.
7&8. Qudrah dan Irādah.
[صـــ] (وَ هِيَ الْقُدْرَةُ وَ الْإِرَادَةُ، الْمُتَعَلِّقَانِ بِجَمِيْعِ الْمُمْكِنَاتِ).
(7 dan 8). Tujuh sifat ma‘ānī tersebut adalah qudrah dan irādah yang berhubungan dengan seluruh perkara yang mumkin.
Syarḥ.
[صـــ] يَعْنِيْ أَنَّ الْقُدْرَةَ وَ الْإِرَادَةَ مُتَعَلَّقُهُمَا وَاحِدٌ، وَ هُوَ الْمُمْكِنَاتث دُوْنَ الْوَاجِبَاتِ وَ الْمُسْتَحِيْلَاتِ، إِلَّا أَنَّ جِهَةَ تَعَلُّقِهِمَا بِالْمُمْكِنَاتِ مُخْتَلِفَةٌ.
Maksudnya, sungguh yang berhubungan dengan qudrah dan irādah adalah satu, yaitu mumkināt (perkara-perkara yang mungkin wujud dan mungkin tidak wujud), tidak yang wajib dan yang mustahil; namun, sisi hubungannya dengan mumkināt berbeda-beda.
فَالْقُدْرَةُ صِفَةٌ تُؤْثِرُ فِيْ إِيْجَادِ الْمُمْكِنِ وَ إِهْدَامِهِ، وَ الْإِرَادَةُ صِفَةٌ تُؤْثِرُ فِي اخْتِصَاصِ أَحَدِ طَرَفَيِ الْمُمْكِنِ مِنْ وُجُوْدٍ أَوْ طُوْلٍ أَوْ قَصْرٍ – وَ نَحْوِهَا بِالْوُقُوْعِ بَدَلًا عَنْ مُقَابِلِهِ، فَصَارَ تَأْثِيْرُ الْقُدْرَةِ فَرْعَ تَأْثِيْرِ الْإِرَادَةِ، إِذْ لَا يُوْجِدُ مُوْلَانَا جَلَّ وَ عَزَّ مِنَ الْمُمْكِنَاتِ أَوْ يُعْدِمُ بِقُدْرَتِهِ إِلَّا مَا أَرَادَ تَعَالَى وُجُوْدَهُ أَوْ إِعْدَامَهُ.
Qudrah adalah sifat yang berpengaruh mewujudkan dan meniadakan mumkin; sedangkan irādah adalah sifat yang berpengaruh mengkhususkan (menentukan) salah satu dari dua opsi mumkin, yaitu wujud, panjang, pendek, dan semisalnya, menjadi wujud sebagai ganti dari lawannya. Maka pengaruh qudrah merupakan cabang dari pengaruh irādah, sebab Allah – jalla wa ‘azza – tidak mewujudkan atau meniadakan mumkināt dengan qudrah-Nya, kecuali apa yang dikehendaki-Nya diwujudkan atau ditiadakan-Nya.
وَ تَأْثِيْرِ الْإِرَادَةِ عَلَى وِفْقِ الْعِلْمِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ، فَكُلُّ مَا عَلِمَ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنَّهُ يُكَوِّنُ مِنَ الْمُمْكِنَاتِ أَوْ لَا يُكَوَّنُ، فَذلِكَ مُرَادُهُ جَلَّ وَ عَزَّ.
Menurut Ahl-us-Sunnah wal-Jamā‘ah, pengaruh irādah Allah itu cocok dengan ilmu-Nya. Sebab itu, setiap mumkināt yang diketahui Allah – tabāraka wa ta‘ālā – akan diwujudkan atau tidak akan diwujudkan, maka itulah yang dikehendaki-Nya.
وَ الْمُعْتَزِلَةُ، قَبَحَهُمُ اللهُ تَعَالَى، جَعَلُوْا تَعَلُّقَ الْإِرَادَةِ تَابِعًا لِلْأَمْر، فَلَا يُرِيْدُ عِنْدَهُمْ مَوْلَانَا جَلَّ وَ عَزَّ إِلَّا مَا أَمَرَ بِهِ مِنَ الْإِيْمَانِ وَ الطَّاعَةُ سَوَاءٌ وَقَعَ ذلِكَ أَمْ لَا.
Golongan Mu‘tazilah – semoga Allah ta‘ālā memperbanyak keburukan mereka – menjadikan hubungan irādah mengikuti perintah-Nya, sehingga menurut mereka Allah – jalla wa ‘azza – tidak menghendaki kecuali perkara yang diperintahkan-Nya, yaitu keimanan dan ketaatan, baik terjadi maupun tidak.
فَعِنْدَنَا إِيْمَانُ أَبِيْ جَهْلٍ مَأْمُوْرٌ بِهِ غَيْرُ مُرَادٍ لَهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى، لِأَنَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ عَلِمَ عَدَمَ وُقُوْعِهِ، وَ كُفْرُ أَبِيْ جَهْلٍ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَ هُوَ وَاقِعٌ بِإِرَادَةِ اللهِ تَعَالَى وَ قُدْرَتِهِ.
Maka menurut Ahl-us-Sunnah wal-Jamā‘ah, iman Abū Jahal itu diperintahkan namun tidak dikehendaki oleh Allah – tabāraka wa ta‘ālā – , karena Allah jalla wa ‘azza – mengetahui tidak akan terjadinya; sedangkan kekufuran Abū Jahal dilarang oleh Allah, namun terjadi dengan irādah dan qudrah-Nya.
وَ عِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ، قَبَحَ اللهُ تَعَالَى رَأْيَهُمْ، إِيْمَانُهُ هُوَ الْمُرَادُ للهِ تَعَالَى لَا كُفْرُهُ، فَلَزِمَهُمْ أَنْ يَقَعَ نَقْصٌ فِيْ مُلْكِ مَوْلَانَا جَلَّ وَ عَزَّ، إِذْ وَقَعَ فِيْهِ عَلَى قَوْلِهِمْ مَا لَا يُرِيْدُهُ، تَعَالَى مَنْ لَهُ مُلْكُ السَّموَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا، تَعَالَى اللهُ عَنْ ذلِكَ عُلُوًّا كَبِيْرًا.
Sementara menurut Mu‘tazilah – semoga Allah ta‘ālā menampakkan keburukan pendapat mereka – iman Abū Jahal itulah yang dikehendaki oleh Allah ta‘ālā, bukan kekufurannya. Konsekuensinya, terjadi kekurangan bagi kekuasaan Allah – jalla wa ‘azza – , sebab berpijak pada pendapat mereka, telah terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki Allah. Maha Luhur Allah yang bagi-Nya kerajaan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Maha Luhur Allah dari hal seperti itu dengan seluhur-luhurnya.
وَ بِالْجُمْلَةِ فَالتَّعَلُّقَاتُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ ثَلَاثَةُ مَرْتَبَةٍ: تَعَلُّقُ الْقُدْرَةِ، وَ تَعَلُّقُ الْإرَادَةِ، وَ تَعَلُّقُ الْعِلْمِ بِالْمُمْكِنَاتِ، فَالْأَوَّلُ مُرَتَّبٌ عَلَى الثَّانِيْ، وَ الثَّانِيْ مُرَتَّبٌ عَلَى الثَّالِثِ.
Kesimpulannya, menurut Ahl-us-Sunnah wal-Jamā‘ah secara umum ta‘alluqāt (hubungan dalam ranah penalaran, bukan ranah kenyataan) ada tiga level, yaitu: hubungan qudrah, hubungan irādah, dan hubungan ilmu Allah dengan mumkināt. Yang pertama ada karena yang kedua, dan yang kedua ada karena yang ketiga.
وَ إِنَّمَا لَمْ تَتَعَلَّقِ الْقُدْرَةُ وَ الْإِرَادَةُ بِالْوَاجِبِ وَ الْمُسْتَحِيْلِ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ وَ الْإِرَادَةَ لَمَّا كَانَتَا صِفَتَيْن مُؤْثِرَتَيْنِ، وَ مِنْ لَازِمِ الْأَثَرِ أَنْ يَكُوْنَ مَوْجُوْدًا بَعْدَ عَدَمٍ، لَزِمَ أَنَّ مَا لَا يَقْبَلُ الْعَدَمَ أَصْلًا كَالْوَاجِبِ لَا يَقْبَلُ أَنْ يَكُوْنَ أَثَرًا لَهُمَا، وَ إِلَّا لَزِمَ تَحْصِيْلُ الْحَاصِلِ؛ وَ مَا لَا يَقْبَلُ الْوُجُوْدَ أَصْلًا كَالْمُسْتَحِيْلِ لَا يَقْبَلُ أَيْضًا أَنْ يَكُوْنَ أَثَرًا لَهُمَا، وَ إِلَّا لَزِمَ قَلْبُ الْحَقَائِقِ بِرُجُوْعِ الْمُسْتَحِيْلِ عَيْنَ الْجَائِزِ.
Qudrah dan irādah tidak berhubungan dengan perkara yang wājib dan yang mustaḥīl karena keduanya merupakan dua sifat yang mempengaruhi, di mana kelaziman suatu pengaruh adalah wujud setelah ketiadaan, maka hal wujud setelah ketiadaan, maka hal itu memastikan bahwa sesuatu yang sama sekali tidak menerima ketiadaan, seperti perkara wajib, tidak bisa menjadi atsar (pengaruh) bagi qudrah dan irādah. Bila tidak demikian maka akan memastikan adanya taḥshīl-ul-ḥāshil (menghasilkan sesuatu yang sudah ada); dan sesuatu yang sama sekali tidak menerima (tidak bisa) wujud seperti perkara yang mustaḥīl, juga tidak bisa menjadi atsar (pengaruh) bagi qudrah dan irādah. Bila tidak demikian maka pasti membalik berbagai hakikat, seperti perkara mustahil menjadi perkara jā’iz.
فَلَا قَصُوْرَ أَصْلًا فِيْ عَدَمِ تَعَلُّقِ الْقُدْرَةِ وَ الْإِرَادَةِ الْقَدِيْمَتَيْنِ بِالْوَاجِبِ وَ الْمُسْتَحِيْلِ، بَلْ لَوْ تَعَلَّقْتَا بِهِمَا لَزِمَ حِيْنَئِذٍ الْقُصُوْرُ، لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى هذَا التَّقْدِيْرِ الْفَاسِدِ أَنْ يَجُوْزَ تَعَلُّقُهُمَابِإِعْدَامِ أَنْفُسِهِمَا، بَلْ وَ بِإِعْدَامِ الذَّاتِ الْعَلِيَّةِ، وَ بِإِثْبَاتِ الْأُلُوْهِيَّةِ لِمَنْ لَا يَقْبَلُهَا مِنَ الْحَوْادِثِ وَ سَلْبِهَا عَمَّنْ تَجِبُ لَهُ، وَ هُوَ مَوْلَانَا جَلَّ وَ عَزَّ. وَ أَيُّ نَقْصٍ وَ فَسَادٍ أَعْظَمُ مِنْ هذَا؟
Maka tidak ada kekurangan sama sekali dalam tidak adanya hubungan qudrah dan irādah yang qadīm dengan perkara yang wājib dan mustaḥīl. Bahkan bila keduanya berhubungan dengan perkara yang wājib dan mustaḥīl, justru akan ada kekurangan. Sebab pengandaian yang salah seperti ini akan berkonsekuensi bolehnya hubungan keduanya meniadakan dirinya sendiri, bahkan bisa meniadakan Dzāt Allah Yang Maha Luhur, menetapkan sifat ketuhanan bagi makhluk yang tidak dapat menerimanya, dan menafikannya dari Dzāt yang wajib menerimanya, yaitu Allah – jalla wa ‘azza – . Adakah kekurangan dan kerusakan yang lebih besar dari hal ini?
وَ بِالْجُمْلَةِ فذلِكَ التّقْدِيْرُ الْفَاسِدِ يَؤَدِّيْ إِلَى تَخْلِيْطٍ عَظِيْمٍ لَا يَبْقَى مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْإِيْمَانِ وَ لَا شَيْءٌ مِنَ الْعَقْلِيَّات أَصْلًا.
Kesimpulannya, pengandaian yang salah semacam itu mengarahkan pada kesalahan besar yang sama sekali tidak akan menyisakan keimanan dan hukum-hukum ‘aqliyyah sedikit-pun.
وَ لِخَفَاءِ هذَا الْمَعْنَى عَلَى بَعْضِ الْأَغْبِيَاءِ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ صَرَّعَ بِنَقِيْضِ ذلِكَ فَنَقَلَ عَنِ ابْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمِلَلِ وَ النَّحَلِ: إِنَّهُ تَعَالَى قَادِرٌ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا، إِذْ لَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ لَكَانَ عَاجِزًا.
Karena begitu samarnya pemahaman ini bagi sebagian orang bodoh dari golongan ahli bid‘ah, secara terang-terangan ia menyatakan kebalikannya, kemudian mengutip pendapat Ibn Ḥazm yang dalam al-Milalu wan-Nihal menyatakan: “Sungguh Allah ta‘ālā Maha Mampu untuk beranak, sebab andaikan Ia tidak mampu melakukannya niscaya ia adalah dzāt yang lemah.”
فَانْظُرْ اخْتِلَالَ عَقْلِ هذَا الْمُبْتَدِعِ كَيْفَ غَفَلَ عَمَّا يَلْزَمُهُ عَلَى هذِهِ الْمَقَالَةِ الشَّنِيْعَةِ مِنَ اللَّوَازِمِ الَّتِيْ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ وَهْمٍ، وَ كَيْفَ فَاتَهُ أَنَّ الْعَجْزَ إِنَّمَا يَكُوْنُ لَوْ كَانَ الْقَصُوْرُ جَاءَ مِنْ نَاحِيَةِ الْقُدْرَةِ، أَنَّمَا إِذَا كَانَ لِعَدَمِ تَعَلُّقِ الْقُدْرَةِ فَلَا يَتَوَهَّمُ عَاقِلٌ أَنَّ هذَا عَجْزٌ.
Lihatlah kerancuan akal ahli bid‘ah ini. Bagaimana ia lalai dari konsekuensi-konsekuensi yang ditatapkannya berdasarkan pendapat keji ini, yang akan masuk pada wahm (prasangka); dan bagaimana ia tidak memahami bahwa ketidakmampuan Allah hanya terjadi bila muncul dari arah sifat qudrah-Nya? Adapun bila ketidakmampuan itu karena tidak adanya hubungan sifat qudrah (pada suatu objek), maka orang berakal tidak akan salah sangka bahwa hal ini merupakan ketidakmampuan Allah.
وَ ذَكَرَ الْأُسْتَاذُ أَبُوْ إِسْحَاقٍ الاِسْفِرَايِنِيُّ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْهُ هذَا الْمُبْتَدِعُ وَ أَشْيَاعُهُ ذلِكَ بِحَسَبِ فَهْمِهِمِ الرَّكِيْكِ مِنْ قِصَّةِ إِدْرِيْسٍ (ع) حَيْثُ جَاءَهُ إِبْلِيْسٌ فِيْ صُوْرَةِ آدَمَ وَ هُوَ يَخِيْطُ وَ يَقُوْلُ فِيْ كَلِّ دَخْلَةِ الْإِبْرَةِ وَ خَرْجَتِهَا: سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ للهِ، جَاءَهُ بِقِشْرَةِ بَيْضَةٍ، فَقَالَ لَهُ: آللهُ تَعَالَى يَقْدِرُ أَنْ يَجْعَلَ الدُّنْيَا فِيْ هذِهِ الْقِشْرَةِ؟ فَقَالَ لَهُ فِيْ جَوَابِهِ: اللهُ تَعَالَى قَادِرٌ أَنْ يَجْعَلَ الدُّنْيَا فِيْ سَمِّ هذِهِ الْإِبْرَةِ، وَ نَخَسَ إِحَدَى عَيْنَيْهِ فَصَارَ أَعْوَرَ.
Al-Ustādz Abū Isḥāq al-Isfirāyinī menyebutkan, sungguh sumber pertama kali yang diambil oleh ahli bid‘ah ini dan golongannya dengan pemahamannya yang ruwet adalah kisah Idrīs a.s. saat Iblīs yang menjelma dengan wujud Ādam mendatanginya, di mana dirinya sedang menjahit dan setiap masuk keluarnya jarum mengatakan: “Subḥānallāh wal-ḥamdulillāh”, sementara Iblīs datang kepadanya dengan membawa kulit telur, lalu berkata kepadanya: “Apakah Allah ta‘ālā mampu menjadikan dunia di dalam kulit telur ini?” Idris a.s. menjawabnya: “Allah ta‘ālā Maha Mampu menjadikan dunia di dalam lubang jarum ini”, kemudian beliau menusuk salah satu matanya, sehingga ia menjadi bermata satu.
قَالَ: وَ هذَا وَ إِنْ لَمْ يُرْوَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ (ص) فَقَدْ ظَهَرَ وَ انْتَشَرَ ظُهُوْرًا لَا يُرَدُّ.
Al-Ustādz Abū Isḥāq berkata: “Meskipun kisah ini tidak diriwayatkan dari Rasūlullāh s.a.w., namun telah masyhur dan tersebar luas, dengan kemasyhuran yang tidak terbantahkan.”
قَالَ: وَ قَدْ أَخَذَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ مِنْ جَوَابِ إِدْرِيْسَ (ع) أَجْوِبَةً فِيْ مَسَائِلَ كَثِيْرَةٍ مِنْ هذَا الْجِنْسِ. وَ أَوْضَحَ هذَا الْجَوَابَ فَقَالَ: إِنْ أَرَادَ السَّائِلُ أَنَّ الدُّنْيَا عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ وَ الْقَشْرَةَ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقُلْ مَا يَعْقِلُ فَإِنَّ الْأَجْسَامَ الْكَثِيْرَةَ يَسْتَحِيْلُ أَنْ تَتَدَاخَلَ وَ تَكُوْنَ فِيْ حَيْزٍ وَاحِدٍ. وَ إِنْ أَرَادَ أَنَّهُ يُصَغِّرُ الدُّنْيَا قَدْرَ الْقَشْرَةِ وَ يَجْعَلُهَا فِيْهَا، وَ يُكَبِّرُ الْقَشْرَةَ قَدْرَ الدُّنْيَا وَ يَجْعَلُ الدُّنْيَا فِيْهَا فَلِعُمْرِيْ اللهُ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى ذلِكَ وَ عَلَى أَكْبَرَ مِنْهُ.
Al-Ustādz Abū Isḥāq berkata: “Abu al-Ḥasan al-Asy‘arī telah mengambil berbagai jawaban dari banyak permasalahan yang sejenis dari jawaban Idrīs a.s. tersebut, dan menjelaskan jawaban ini, kemudian berkata: “Bila penanya menghendaki dunia tetap pada keadaannya dan kulit telur ada pada keadaannya, maka ia tidak menanyakan sesuatu yang dapat diterima akal. Sebab, jisim yang banyak mustaḥīl saling masuk-memasuki dan berada dalam satu tempat kecil. Bila ia menghendaki Allah mengecilkan dunia seukuran kulit telur dan menjadikannya di dalamnya, atau membesarkan kulit telur seukuran dunia dan menjadikan dunia di dalamnya, maka Demi umurku, Allah ta‘ālā mampu melakukannya, dan melakukan yang lebih hebat lagi darinya.”
قَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ: وَ إِنَّمَا لَمْ يَفْصِلْ إِدْرِيْسٌ (ع) الْجَوَابَ هكَذَا لِأَنَّ السَّائِلَ مُتَعَنِّتٌ، وَ لِهذَا عَاقَبَهُ عَلَى هذَا السُّؤَالِ بِنَخْسِ الْعَيْنِ، وَ ذلِكَ عُقُوْبَةُ كُلِّ سَائِلٍ مِثْلَهُ.
Sebagian Masyāyikh mengatakan: “Nabi Idrīs a.s. tidak memerinci jawabannya seperti ini karena penanyanya keras kepala. Sebab itu, beliau menghukumnya dengan menusuk matanya. Itulah hukuman setiap orang yang bertanya sepertinya.”