Tahun Pertama Hijriah – Nurul Yaqin
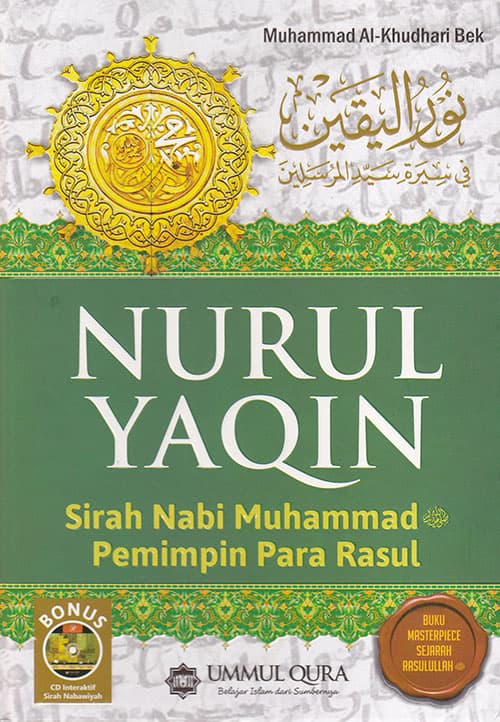
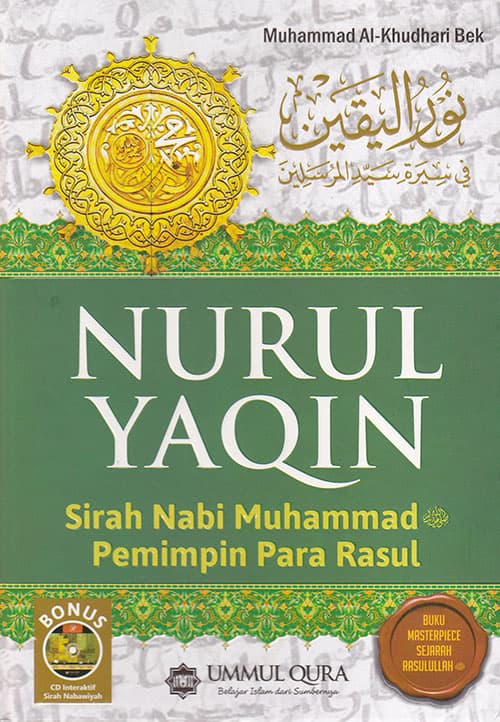
Selanjutnya, Rasūlullāh s.a.w. mulai merencanakan pembangunan masjidnya di tempat bekas menderumnya unta Beliau, yaitu di depan tempat Bani Najjār. Sebelumnya, tempat tersebut merupakan penjemuran kurma milik dua anak laki-laki yatim di bawah pemeliharaan As‘ad bin Zurārah. Rasūlullāh s.a.w. memanggil kedua anak laki-laki itu, lalu menawarkan harga tempat penjemuran kurma tersebut untuk dijadikan tempat mendirikan masjid. Namun, kedua anak itu berkata: “Kami menghibahkannya kepadamu, wahai Rasūlullāh.” Rasūlullāh s.a.w. tidak mau menerima pemberian dari kedua anak yatim itu, lalu Beliau membelinya dari mereka.
Di tanah tersebut terdapat kuburan kaum musyrikīn dan beberapa lubang galian serta pohon-pohon kurma. Kemudian kuburannya digali dan dipindahkan, sedangkan tanah-tanah yang berlubang diratakan dan pohon-pohon kurmanya ditebang. Selanjutnya, Rasūlullāh s.a.w. memerintahkan kaum Muslimīn membuat batu bata, dan dimulailah pembangunannya. Mereka membuat kedua tiang penopang pintunya dari batu dan atap masjid itu dari pelepah daun kurma, sedangkan tiang-tiangnya dari batang pohon kurma. Tinggi temboknya hanya sedikit jika diukur dengan orang yang tegak berdiri. Dalam pekerjaan ini, Rasūlullāh s.a.w. sendiri langsung turun untuk memberikan semangat kepada kaum Muslimīn yang bekerja. Sambil bekerja mereka mengumandangkan syair dan Rasūlullāh s.a.w. ikut ber-syair bersama mereka. Syair yang mereka ucapkan seperti berikut:
Ya, Allah, tiada kebaikan melainkan akhirat
Maka rahmatilah kaum Muhājirīn dan Anshār. (131)
Arah qiblat diletakkan di sebelah kiri masjid dan menghadap ke Bait-ul-Maqdis, dan masjid itu mempunyai tiga pintu. Tanahnya diberi batu-batu kecil karena bila hujan turun tanahnya becek sehingga Rasūlullāh s.a.w. memerintahkan supaya tanahnya dilapisi dengan batu-batu kecil. Masjid tidak diberi hiasan apa pun; tidak pula permadani dan juga tidak ada tikarnya. Kemudian Rasūlullāh s.a.w. membangun dua kamar di sebelah masjid: satu untuk Saudah Binti Zam‘ah dan yang lain untuk ‘Ā’isyah. Kedua kamar tersebut bersebelahan dan letaknya menempel pada tembok bangunan masjid. Kemudian dibangun pula kamar-kamar lainnya manakala ada istri lainnya lagi.
Allah swt telah mewajibkan shalat kepada kaum Muslimīn supaya mereka selalu dalam keadaan ingat akan kebesaran Allah Yang Maha Tinggi, sehingga mereka akan selalu menaati perintah-perintahNya. Allah s.w.t. berfirman:
“Sesungguhnya shalat itu mencegah (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar.” (QS. al-‘Ankabūt [29]: 45)
Kemudian Allah menjadikan shalat yang paling utama adalah shalat yang dilakukan secara berjamā‘ah untuk mengingatkan kaum muslimīn terhadap satu sama lain dalam urusan keperluan mereka dan guna mempererat ikatan kerukunan dan persatuan di antara mereka.
Bila waktu shalat telah tiba, sangat diperlukan adanya perbuatan yang bisa menyadarkan orang yang lalai dan mengingatkan orang yang lupa sehingga semuanya bisa berjamā‘ah.
Rasūlullāh s.a.w. bermusyāwarah bersama para shahabat untuk memilih pekerjaan yang lebih utama guna mewujudkan tujuan tersebut. Sebagian dari para shahabat ada yang mengatakan bahwa sebaiknya mereka memancangkan bendera bila waktu shalat telah tiba. Mereka menolak usulan tersebut mengingat pekerjaan itu tidak mengingatkan orang yang sedang tidur atau orang yang sedang lalai. Sebagian shahabat yang lain mengusulkan agar menyalakan api di tempat yang tinggi. Usulan itu pun ditolak oleh mereka. Sebagiannya lagi mengusulkan agar dibunyikan terompet. Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang Yahūdī sebagai panggilan untuk melakukan misa mereka. Rasūlullāh s.a.w. tidak menyukai cara tersebut, sebab beliau sangat tidak suka meniru perbuatan orang-orang Yahūdī dalam hal apa pun. Kemudian ada shahabat yang mengemukakan agar memakai lonceng, yaitu hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang Nashrānī. Hal ini juga dibenci oleh Rasūlullāh s.a.w. Kemudian ada di antara shahabat yang mengusulkan agar bila waktu shalat tiba, ada seseorang yang berseru untuk itu. Akhirnya, usulan inilah yang diterima oleh Rasūlullāh s.a.w. Di antara para shahabat yang diberi tugas untuk mengumandangkan seruan itu adalah ‘Abdullāh bin Zaid al-Anshārī. Tatkala ia sedang dalam keadaan antara setengah tidur dan setengah terjaga, tiba-tiba tampaklah seseorang yang berdiri di hadapannya, lalu orang tersebut berkata: “Maukah engkau aku ajari kalimat-kalimat yang akan engkau serukan sebagai panggilan untuk shalat?” Ia menjawab: “Tentu saja aku mau.” Orang itu lalu berkata: “Katakanlah: Allāhu Akbar, Allāhu Akbar (Allah Maha Besar), sebanyak dua kali, dan selanjutnya engkau membaca syahadat sebanyak dua kali; kemudian katakanlah, ḥayya ‘alā-sh-shalāh (marilah shalat) sebanyak dua kali, kemudian ḥayya ‘alā-l-falāḥ (marilah menuju kepada kebahagiaan) dua kali. Kemudian bertakbīrlah kepada Allah sebanyak dua kali, dan terakhir ucapkanlah, lā ilāha illallāh’ (tiada ilāh yang berhak disembah selain Allah).”
Setelah bangun, ‘Abdullāh bin Zaid segera menghadap Rasūlullāh s.a.w. lalu menceritakan apa yang telah dilihatnya dalam mimpinya itu. Rasūlullāh s.a.w. pun bersabda: “Sungguh itu mimpi yang benar.” Setelah itu, Rasūlullāh s.a.w. bersabda: “Ajarkanlah kalimat-kalimat tersebut kepada Bilāl karena ia lebih keras suaranya daripada engkau.” Ketika Bilāl menyerukan panggilan tersebut, tiba-tiba datanglah ‘Umar seraya menyingsingkan kainnya lalu berkata: “Demi Allah, wahai Rasūlullāh, sungguh aku telah memimpikan hal yang serupa.” (142) apabila mengumandangkan adzān untuk shalat Shubuḥ, sesudah kalimat, ḥayya ‘alā-l-falāḥ, Bilāl menambahkan kalimat “Ash-Shalātu khairun minan-naum (shalat itu lebih baik daripada tidur)”. Kemudian Rasūlullāh s.a.w. membenarkan hal tersebut. (153)
Rasūlullāh s.a.w.selalu memerintahkan kepada Bilāl pada setiap fajar Ramadhān agar mengumandangkan adzān dua kali. Adzān yang pertama untuk membangunkan orang-orang untuk melaksanakan sahur, dan adzān yang kedua untuk shalat Shubuḥ. (164)
Adapun adzān untuk shalat Jum‘at pada mulanya diserukan bilamana khathīb duduk di mimbar. Hal ini berlaku sejak masa Rasūlullāh s.a.w. hingga masa (khilafah) Abū Bakar dan ‘Umar. Namun, pada masa (khilafah) ‘Utsmān dan ketika orang-orang Islām semakin bertambah banyak, ‘Utsmān menambahkan satu adzān lainnya yang dikumandangkan di az-zaurā’ (tempat di pasar). (175)
Ketika Hisyām bin Mālik memegang tampuk kekuasaan, adzān yang ditambahkan oleh Khalīfah ‘Utsmān yang dikumandangkan di az-zaurā’ (pasar), ia pindahkan (pelaksanaannya) di atas menara. Selanjutnya, adzan yang tadinya dilakukan di atas menara, yaitu adzān yang dilakukan sewaktu imām menaiki mimbar sebagaimana pada zaman Rasūlullāh s.a.w., dilakukan di hadapan khatīb. Dengan demikian, adzān (pertama) di dalam masjid yang dilakukan di hadapan khathīb merupakan bid‘ah yang dibuat oleh Hisyām bin ‘Abd-il-Mālik. Seruan adzān ini tidak ada artinya karena maksud adzān adalah untuk melakukan panggilan shalat. Seruan adzān yang dilakukan di dalam masjid ini tidak berarti apa-apa bagi orang yang ada di dalam masjid, sedangkan orang-orang yang ada di luar masjid tidak dapat mendengar adzān tersebut. Demikianlah menurut keterangan yang dikemukakan oleh Syaikh Muḥammad bin Ḥajj dalam kitab al-Madkhal.
Al-Ḥāfizh Ibnu Ḥajar dalam kitab Fatḥ-ul-Bārī mengatakan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh orang sebelum shalat Jum‘at yaitu seruan untuk shalat Jum‘at berupa dzikir dan membaca shalawat kepada Nabi s.a.w. hanya terdapat di beberapa negeri saja, tidak di semua negeri Islām. Dalam hal ini lebih baik ittibā‘ kepada ‘ulamā’ salaf. Demikianlah menurut keterangan yang dikemukakan oleh Ibnu Ḥajar dalam kitab Fatḥ-ul-Bārī’.
Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa sunnah Rasūlullāh s.a.w. dalam masalah adzān shalat Jum‘at ialah bahwa bila imām telah duduk di mimbar, mu’adzdzin menyerukan adzān di atas menara. Apabila Khutbah telah selesai, barulah iqāmah untuk shalat diserukan.
Iqāmah adalah seruan untuk mendirikan shalat di dalam masjid. Sehubungan dengan masalah ini, nash (teks) riwayat-riwayat haditsnya berbeda-beda. Menurut Imām Syāfi‘ī, iqāmah diucapkan satu kali-satu kali, kecuali kalimat “qad qāmat-ish-shālah” (shalat telah didirikan). Kalimat ini diucapkan secara genap (dua kali). Menurut Imām Mālik, kalimatnya hanya diucapkan ganjil (satu kali-satu kali), tetapi menurut Imām Abū Ḥanīfah, semua kalimatnya dibaca dua kali. (186)
Sebagaimana Allah telah menguji kaum Muslimīn sewaktu mereka berada di Mekah melalui kaum musyrikin Quraisy, Allah s.w.t. juga memberikan cobaan kepada mereka di Madīnah melalui orang Yahūdī yang tinggal di Madīnah. Orang Yahūdī itu terdiri dari Bani Qainuqā‘, Bani Quraizhah, dan Bani Nadhīr. Sesungguhnya mereka menampakkan permusuhan dan kebenciannya terhadap Rasūlullāh s.a.w. dan kaum Muslimīn karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah kebenaran itu nyata bagi mereka. Padahal sebelum itu, ketika berperang melawan orang-orang ‘Arab musyrik, mereka selalu mencari kemenangan dengan menyebut akan datangnya seorang Nabi yang sudah dekat waktunya.
Namun, setelah datang Nabi yang telah mereka kenal, para pemimpin mereka merasa tinggi hati; mereka memustahilkan kenabian dari anak cucu Nabi Ismā‘īl a.s. Akhirnya, mereka ingkar terhadap al-Qur’ān yang diturunkan oleh Allah karena kesombongan mereka, padahal mereka mengetahui bahwa Rasūlullāh Muḥammad datang membenarkan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasūl sebelumnya. Kitāb al-Qur’ān yang diturunkan kepada Rasūlullāh s.a.w. menjelaskan hal-hal yang telah dirusak oleh ta’wīl mereka. Namun, mereka membuang al-Qur’ān dan seolah-olah tidak mengetahuinya.
Di antara hal-hal yang mereka cela dalam Islām adalah penghapusan hukum-hukum (dalam kitab sebelumnya). Mereka tidak mengetahui bahwa Yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui lebih mengetahui daripada mereka tentang apa-apa yang dibutuhkan oleh umat manusia. Sesungguhnya manusia itu bertabiat selalu ingin maju.
Rasūlullāh s.a.w. pada mulanya hidup di tengah-tengah masyarakat ‘Arab yang ummi. Mereka sama sekali tidak mengerti apa pun tentang keyakinan-keyakinan ulūhiyyah. Amat bijaksanalah jika syarī‘at Islām diturunkan kepada mereka secara bertahap. Seandainya Allah s.w.t. mengharamkan mereka meminum khamar dan memakan riba, kemudian mereka diperintahkan shalat, zakat, dan sebagainya, yang merupakan perintah dan larangan yang didatangkan oleh syarī‘at Islām, niscaya tiada seorang pun dari mereka yang mau menerima Islām mengingat mereka mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda, dan mereka tenggelam ke dalam banyak kesesatan. Rasūlullāh s.a.w. datang kepada mereka dengan membawa perintah dari Allah secara berangsung-angsur sehingga akhirnya akal mereka dapat ditundukkan dan jiwa mereka dapat dibersihkan.
Seluruh hukum Islām diturunkan oleh Allah s.w.t. setelah terjadinya suatu peristiwa yang menuntut (turunnya suatu hukum), agar lebih berkesan di dalam hati. Namun, orang-orang Yahūdī hendak mengkhianati taqdīr dan hanya mau melakukan hal-hal sesuai hawa nafsu mereka sendiri. Al-Qur’ān telah membantah mereka dengan ḥujjah yang menunjukkan bahwa mereka sebenarnya mengetahui, dan jiwa mereka jauh dari jalan kebenaran. Mengenai hal itu, Allah s.w.t. berfirman: “Katakanlah: ‘Jika kalian (menganggap bahwa) kampung akhirat (surga) itu khusus untuk kalian di sisi Allah, bukan untuk orang lain maka inginilah kematian kalian jika kalian memang benar’.” (QS. al-Baqarah [2]: 94). Pada ayat selanjutnya, Allah s.w.t. langsung memastikan bahwa mereka tidak akan mau menjawab tantangan ini, yaitu melalui firman-Nya: “Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya karena kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat oleh tangan mereka (sendiri). Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang aniaya.” (QS. al-Baqarah [2]: 95)
Seandainya mereka mengetahui bahwa diri mereka benar-benar berada dalam kebenaran, niscaya mereka tidak akan menangguh-nangguhkan (jawaban dari) tantangan tersebut karena caranya sangat mudah sekali. Namun, sikap mereka itu tak lain hanyalah terdorong oleh keinginan kuat mereka untuk mendustakan Rasūlullāh s.a.w. yang jujur lagi dapat dipercaya. Ternyata belum ada satu nukilpun yang menyatakan bahwa ada seseorang di antara mereka yang mengharapkan hal tersebut (ingin mati) sekalipun hal itu hanyalah diungkapkan secara lisan. Meskipun demikian, ternyata hidayah Rasūlullāh s.a.w. ini dapat diterima dengan jelas oleh salah seorang pemimpin Bani Qainuqā‘, yaitu ‘Abdullāh bin Salām. Ia rela meninggalkan hawa nafsunya dan masuk Islām. Hal ini dilakukannya setelah mendengar bacaan al-Qur’ān.
Sebelum masuk Islām, ia (‘Abdullāh bin Salām) dianggap oleh kaumnya sebagai pemimpin mereka. Kini, setelah ia masuk Islām, mereka menganggapnya sebagai orang yang kurang akal. Penilaian ini mereka kemukakan setelah mereka mendengar berita tentang keislamannya. Alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual diri sendiri dengan kekafiran kepada apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Setelah perasaan memusuhi Islam tertanam kuat di dalam hati, mereka berupaya sekuat tenaga untuk memadamkan cahaya Allah. “Namun, Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya.” (QS. at-Taubah [9]: 32)
Aksi orang Yahūdī ini ternyata mendapat dukungan dari sebagian orang ‘Arab Madīnah yang mata hatinya dibutakan oleh Allah s.w.t., dan mereka menyembunyikan kekafiran mereka karena takut jiwa mereka terancam. Pemimpin orang-orang munāfiq ini adalah ‘Abdullāh bin Ubay bin Salūl dari kabilah Khazraj. Sedianya, sebelum kedatangan Rasūlullāh s.a.w., ia akan diangkat menjadi pemimpin penduduk kota Madīnah.
Tidak diragukan lagi bahwa bahaya kaum munāfiqīn itu dirasakan oleh kaum Muslimīn lebih berat ketimbang bahaya orang-orang kafir sendiri. Pasalnya, orang-orang munāfiq itu dapat berbaur dengan kaum Muslimīn sehingga dapat mengetahui rahasia-rahasianya, kemudian mereka menyiarkannya kepada musuh kaum Muslimīn, yaitu orang Yahūdī dan lain-lainnya seperti yang pernah terjadi berkali-kali.
Adapun prinsip yang menjadi pegangan Rasūlullāh s.a.w. (dalam memperlakukan munāfiqīn) ialah beliau menerima lahiriah mereka dan menyerahkan batiniah mereka kepada Allah s.w.t. Sekalipun demikian, Rasūlullāh s.a.w.sering meninggalkan Madīnah dan selalu menyerahkan urusan kota Madīnah kepada kaum Anshār. Belum pernah beliau menyerahkan urusan kota Madīnah kepada seseorang yang tanda-tanda kemunafikan dirinya dapat dibaca, sebab Rasūlullāh s.a.w. telah mengetahui seandainya mereka dipercaya untuk melakukan suatu pekerjaan maka tidak ayal lagi mereka akan memperoleh kesempatan untuk menimpakan kemudaratan kepada kaum Muslimīn. Dalam hal ini terdapat pelajaran penting bagi para pemimpin Islām, ya‘ni jangan mempercayakan urusan-urusan penting kecuali kepada orang yang tidak tampak kenifakan atau menampakkan hal-hal yang berbeda dengan apa yang tersimpan di dalam hatinya.
Sudah diketahui bahwa di Madīnah terdapat dua golongan yang menentang kaum Muslimīn, yaitu kaum Yahūdī dan kaum munāfiq. Namun, Rasūlullāh s.a.w. tetap menerima lahiriah mereka. Kemudian Beliau s.a.w. mengadakan perjanjian yang isinya ialah tidak boleh berperang dan tidak boleh menyakiti; mereka tidak boleh meminta bantuan kepada seorang pun untuk memerangi Rasūlullāh s.a.w.; apabila Madīnah diserang musuh maka mereka harus membantunya; dan sebaliknya Rasūlullāh s.a.w. membiarkan mereka memeluk agamanya.