Syarat & Rukun Puasa – Panduan Puasa Terlengkap (3/5)
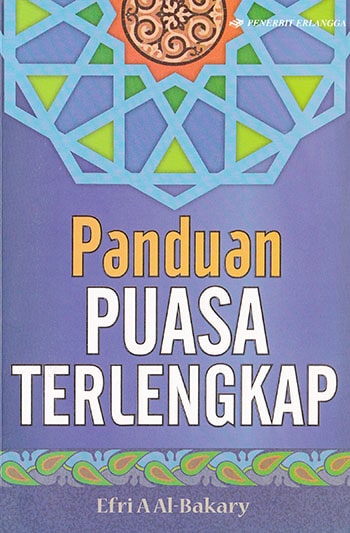
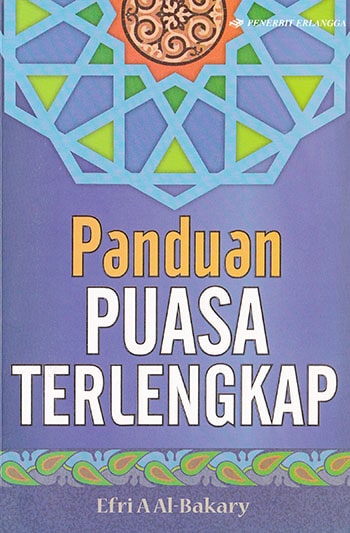
Keislaman seseorang merupakan syarat sah-tidaknya puasa. Artinya, seorang kafir yang melakukan puasa di bulan Ramadhān dihukumkan tidak sah karena ketidakislamannya. Apabila orang kafir tersebut masuk Islam di Bulan Ramadhān maka ia langsung terkena kewajiban puasa, sekalipun Ramadhān akan berakhir tiga atau dua hari lagi. Puasa yang sudah berlangsung sebelumnya tak perlu diqadhā’ (diganti).
Madzhab Ḥanafī memiliki pendapat pada satu kondisi yang lebih spesifik. Jika seorang kafir masuk Islam di siang hari di bulan Ramadhān maka ia wajib langsung berpuasa di siang itu sampai saat berbuka tiba. Pendapat itu kemudian dilanjutkan dengan kewajiban mengqadhā’ (mengganti) bagian puasa yang tertinggal pada hari itu karena ia sudah mendapati sebagian puasa di hari itu. Madzhab Mālikī dan Syāfi‘ī berpendapat dalam kasus ini si mu’allaf hanya ditekankan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan tidak wajib mengqadhā’.
Bāligh dan berakal adalah syarat mutlak bagi seorang yang berpuasa. Dengan syarat ini, orang gila, anak kecil, dan orang mabuk adalah orang-orang tidak wajib berpuasa. Jika anak kecil tidak diwajibkan karena belum bāligh, maka orang gila dan orang mabuk tidak wajib puasa karena ketidaksehatan akal dan kesadarannya.
Namun jumhur ‘ulamā’ mengqiyaskan (mengibaratkan) tuntutan pendidikan anak dalam shalat, yang diajarkan Nabi s.a.w. pada pasal puasa. Orang tua diharuskan menyuruh anaknya berpuasa jika anak sudah berusia 7 tahun dan memukulnya dengan pukulan yang tak menyakitkan serta tak mencederai jika si anak tidak mau berpuasa pada usia 10 tahun.
Pendapat ini tak disetujui oleh Madzhab Mālikī yang menganggap penganalogian itu tidak tepat. Madzhab Mālikī berpendapat sebelum anak bāligh dengan tanda keluar mani karena mimpi bersenggama ia tidak wajib puasa.
Kondisi-kondisi di mana kemampuan dan kesehatan itu tidak dimiliki secara temporer maupun permanen membatalkan syarat ini. Orang sakit, tua renta, dan orang yang sedang dalam berjalanan (musafir), tidak diwajibkan puasa. Mereka diperbolehkan berbuka sebagaimana dijelaskan surah al-Baqarah [2] ayat 184. Jarak perjalanan yang membolehkan tidak berpuasa dihukumkan sama dengan jarak perjalanan pada pasal mengqashar dan menjama‘ shalat, yakni dua marhalah – setara dengan 75 kilometer. Termasuk orang yang dipandang berat menjalankan puasa adalah wanita hamil dan menyusui.
Wanita yang haidh dan nifās tidak wajib menjalankan puasa tapi mesti menggantikannya di waktu yang lain.
Rukun puasa disepakati hanya satu, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkannya sejak fajar sampai terbenamnya matahari. Namun Madzhab Mālikī dan Syāfi‘ī menambahkan rukun ini dengan niat. Ayat ke 187 surah al-Baqarah [2] mendasari rukun puasa tersebut:
“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam…..”
Ayat ini berbicara bahwa seseorang boleh tetap makan dan minum serta bersenggama dengan istri, sampai fajar tiba. Setelah fajar tiba, ia menahan semua hal itu, karena perbuatan itu membatalkan puasa, sampai saat berbuka tiba. Kebutuhan-kebutuhan itu menjadi halal kembali saat malam hari hingga fajar berikutnya tiba, begitu seterusnya.
Sedangkan yang mendasari penambahan niat sebagai rukun puasa didasari sabda Rasūlullāh s.a.w.:
“Sesungguhnya setiap ‘amal itu tergantung dengan niat.” (HR. Bukhārī, Muslim, dan Aḥmad bin Ḥanbal).
Imām Syāfi‘ī dan Imām Mālik menambahkan argumentasinya dengan menyatakan bahwa puasa termasuk ibadah Maḥdhah (murni) yang merupakan ibadah yang dipandang tidak sah dikerjakan tanpa niat, sebagaimana shalat, namun jumhur ‘ulamā’ berpendapat niat berada pada wilayah syarat puasa, bukan rukun puasa.
Para fuqahā’ (‘ulamā’ fikih) merangkum beberapa kesunnahan dalam berpuasa. Sunnah-sunnah itu tersebut di antaranya:
Anjuran ini memenuhi aspek rasional dan spiritual sekaligus. Orang yang mengakhirkan sahurnya secara logis akan lebih kuat menjalankan puasa karena pendeknya jarak antara makan terakhirnya dengan berbuka. Sedangkan makan sahur sendiri dijamin oleh Rasūlullāh s.a.w. dengan aspek spiritual karena berkah yang menyelimutnya. Rasūlullāh s.a.w. bersabda:
“Bersahurlah kamu karena dalam makan sahur itu terdapat berkah.” (HR. Bukhārī dan Muslim).
Rasūlullāh s.a.w. bersahur di ketika hampir Shubuḥ. Antara waktu beliau selesai bersahur dengan shalat Shubuḥ, hanya sekadar selesai membaca 50 ayat al-Qur’ān saja.
Diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim dari Zaid ibn Tsābit, ujarnya:
“Kami telah bersahur bersama Rasūlullāh s.a.w. kemudian kami berdiri mengerjakan shalat Shubuḥ. Aku bertanya kepada Zaid: “Berapa lama tempo antara habis makan sahur dengan shalat?” Zaid menjawab: kadar 50 ayat al-Qur’ān.”
Diriwayatkan Abū Dāūd dari al-Irbādh ibn Saryah, ujarnya:
“Rasūlullāh memanggil aku makan sahur seraya berkata: “Mari kepada ghadā (makan tengah hari) yang mendapat berkah.”
Dinamai sahur dengan ghada makanan tengah hari, karena sahur itu dekat kepada makan tengah hari. Sekiranya seseorang ragu tentang terbit fajar, maka ia boleh makan dan minum, sehingga jelas terbit fajar, jangan ia berpegang pada keraguannya; karena Allah menjadikan batas makan dan minum adalah “nyata fajar” bukan disangka telah terbit fajar. Allah berfirman:
“Dan makanlah, minumlah, sehingga jelas kepadamu benang putih daripada benang hitam yaitu fajar.” (QS. al-Baqarah [2]: 187).
Seorang lelaki berkata kepada Ibn ‘Abbās: “Saya bersahur tetapi jika saya ragu-ragu telah terbit fajar, saya pun berhenti.” Berkata Ibn ‘Abbās: “Makanlah selama engkau masih ragu-ragu.”
Berkata Abū Dāūd, kata ‘Abdullāh: “Apabila seseorang ragu tentang fajar, maka ia boleh makan, sehingga ia yakin telah terbit fajar”. Inilah madzhab Ibn ‘Abbās, al-Auzā‘ī, dan Aḥmad.
An-Nawawī berkata: “Telah sepakat madzhab asy-Syāfi‘ī menetapkan boleh makan bagi orang yang ragu-ragu tentang terbit fajar.”
Sahur sendiri adalah aktivitas penuh keberkahan, sebab sahur mengikuti sunnah dan menyalahi ahl-ul-kitāb. Diriwayatkan oleh Muslim dari ‘Āmir Ibn ‘Āsh, bahwa Rasūlullāh s.a.w. bersabda: “Yang membedakan antara puasa kita dengan puasa Yahudi dan Nasrani ialah makan sahur.”
Hadits-hadits di atas selayaknya direnungkan oleh mereka yang tak mau, atau malas bersahur, dengan alasan mendatangkan mulas perut dan sebagainya. Sahur merupakan kesunnahan yang membuat kita dapat menjaga ibadah di antara waktu sahur dengan terbit fajar, yaitu membaca al-Qur’ān dan agar kita dapat mengerjakan Shubuḥ di awal waktunya. Tentu hal itu semua sama sekali tidak menyukarkan kita. Rasūlullāh s.a.w. bersabda:
“Bersahur itu suatu keberkahan. Maka janganlah kamu meninggalkannya, walaupun hanya dengan seteguk air, karena sesungguhnya Allah dan malaikat-Nya bershalawat atas orang yang bersahur.” (HR. Aḥmad).
Menyegerakan berbuka adalah perbuatan yang ditradisikan oleh Rasūlullāh s.a.w. setiap kali beliau berpuasa: “Manusia (yang mengerjakan puasa) senantiasa dalam kebaikan selama mereka mempercepat berbuka.” (HR. Bukhārī dan Muslim).
Sebuah hadits Qudsi riwayat Aḥmad bin Ḥanbal, at-Tirmidzī, dan Nasā’ī, menguatkan hal itu dengan menyebut bahwa Allah s.w.t. “memandang” hamba-Nya yang menyegerakan berbuka sebagai hamba yang paling mencintai-Nya. Orang berpuasa disunnahkan langsung berbuka jika waktunya tiba sekalipun hanya dengan sebutir kurma dan seteguk air.
Waktu berbuka sendiri adalah apabila telah pasti terbenam matahari dengan penglihatan kita sendiri, atau dengan penglihatan orang lain yang boleh dipercaya ucapannya. Diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim dari ‘Umar bahwa Rasūlullāh s.a.w. bersabda:
“Apabila telah datang malam dari sini dan telah berlalu siang dari sini, serta telah terbenam matahari, maka telah berbukalah orang yang berpuasa.”
Rasūlullāh s.a.w. berbuka sebelum shalat Maghrib dengan sedikit makanan. Sesudah shalat Maghrib, barulah beliau menyempurnakan makannya.
Diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abd-il-Barr dari Anas Ibn Mālik, ia berkata:
“Tiada pernah sekali juga aku melihat Rasūlullāh s.a.w. melaksanakan shalat Maghrib terlebih dahulu sebelum berbuka, walaupun berbukanya dengan seteguk air saja.”
Dalam berbuka, kita dianjurkan untuk terlebih dahulu menyantap makanan yang ringan atau manis. Adapun makanan utama untuk berbuka puasa ialah makanan yang mengandung dzāt yang manis yang menyegarkan badan dan menambah kesehatan dan tidak dimasak dengan api, seperti buah kurma, pisang, limau, sawo, dan sebagainya. Diriwayatkan dari Abū Ya‘lā, dari Anas, ia berkata: “Rasūlullāh s.a.w. suka berbuka puasa dengan tiga buah kurma atau sesuatu yang tidak dimasak dengan api.”
Diriwayatkan oleh Abū Dāūd, at-Tirmidzī, dari Anas, ia berkata:
“Rasūlullāh s.a.w. berbuka dengan kurma basah sebelum shalat (Maghrib), jika tak tersedia, maka beliau berbuka dengan kurma kering dan jika tak tersedia kurma kering, beliau menciduk beberapa ciduk (air).”
Diriwayatkan oleh Abū Dāūd dan at-Tirmidzī dari Sulaimān ibn ‘Āmir, bahwa Rasūlullāh s.a.w. bersabda:
“Apabila kamu berbuka, hendaklah dengan kurma. Jika tidak memperoleh kurma, hendaklah berbuka dengan air, karena air itu membersihkan.”
Dari hadits-hadits ini kita dapat kesan yang tegas, bahwa sangat disukai kita berbuka dengan makanan yang manis-manis dan yang tidak kena api, baik kurma ataupun selainnya, yang disukai itu bukanlah dzāt kurma, tetapi makanan-makanan yang manis menyegarkan badan dan menambahkan kesehatan dan tidak dimasak dengan api.
Sebenarnya memakan makanan-makanan yang manis seperti kurma lebih banyak manfaatnya untuk menguatkan tubuh, terutama untuk mata (penglihatan). Sedangkan air sangat berguna untuk membasahkan hati yang telah kering sepanjang hari.
Diriwayatkan oleh ad-Dāruquthnī dari ‘Abbās:
“Ketika berbuka Rasūlullāh s.a.w. selalu berdoa: “Wahai Tuhanku, untuk Engkau aku berpuasa dan dengan rezeki Engkau kami berbuka. Maka terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha Mengetahui.” Atau dengan doa: “Wahai Tuhanku, untuk Engkau aku berpuasa dan dengan rezeki Engkau aku berbuka, aku mengakui kesucian Engkau (dan dengan kuasa Engkau aku dapat menyucikan) dan memuji Engkau. Wahai Tuhanku, terimalah dariku; sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”
Diriwayatkan oleh ad-Dāruquthnī, dari Ibn ‘Umar, bahwa di kala berbuka Rasūlullāh s.a.w. berdoa: “Wahai Tuhanku, telah hilang haus dan telah basah segala urat dan mudah-mudahan pahala tetap jika Allah menghendakinya.”
Ibnu ‘Umar r.a. di saat berbuka selalu berdoa: “Wahai Tuhanku! Sesungguhnya aku bermohon kepada-Mu dengan rahmat-Mu yang melengkapi segala sesuatu, supaya Engkau mengampuni aku.”
Rasūlullāh s.a.w. bersabda:
“Apabila seseorang dalam keadaan berpuasa, tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor dan tidak boleh berteriak-teriak. Apabila ia dimaki atau diserang orang lain, maka katakanlah: “Saya sedang berpuasa”.” (HR. Bukhārī dan Muslim).
Selain hal-hal yang telah disebutkan, bertadarrus al-Qur’ān dan beri‘tikaf di masjid merupakan sunnah-sunnah yang masyhur memiliki nilai yang sangat tinggi nilainya di bulan Ramadhān.