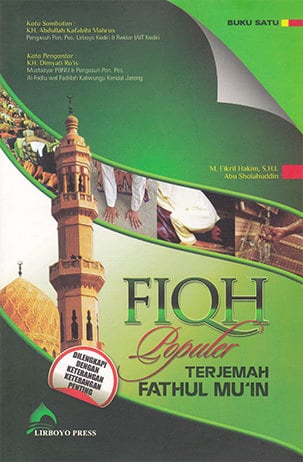وَ مِنْهُ أَرَتَّ يُدْغِمُ فِيْ غَيْرِ مَحَلِّهِ بِإِبْدَالٍ، وَ أَلْثَغَ يَبْدُلُ حَرْفًا بِآخَرَ. فَإِنْ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ وَ لَمْ يَتَعَلَّمْ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، وَ إِلَّا صَحَّتْ كَاِقْتِدَائِهِ بِمِثْلِهِ، وَ كُرِهَ اقْتِدَاءٌ بِنَحْوِ تَأْتَاءَ، وَ فَأْفَاءَ، وَ لَاحِنٍ بِمَا لَا يُغَيِّرُ مَعْنًى، كَضَمِّ هَاءِ “للهِ” وَ فَتْحِ دَالٍ “نَعْبُدُ”، فَإِنْ لَحَنَ لَحْنًا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى فِي الْفَاتِحَةِ كَ “أَنْعَمْتَ” بِكَسْرٍ أَوْ ضَمٍّ، أَبْطَلَ صَلَاةَ مَنْ أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ وَ لَمْ يَتَعَلَّمْ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْآنٍ. نَعَمْ، إِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ صَلَّى لِحُرْمَتِهِ، وَ أَعَادَ لِتَقْصِيْرِهِ. قَالَ شَيْخُنَا: وَ يَظْهُرُ أَنَّهُ لَا يَأْتِيْ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ، لِأَنَّهُ غَيْرُ قُرْآنٍ قَطْعًا، فَلَمْ تَتَوَقَّفْ صِحَّةُ الصَّلَاةِ حِيْنَئِذٍ عَلَيْهَا، بَلْ تَعَمُّدُهَا وَ لَوْ مِنْ مِثْلِ هَذَا مُبْطِلٌ. اِنْتَهَى.
Termasuk ummī adalah “Aratta”, yaitu orang yang meng-idghāmkan huruf di selain tempatnya besertaan mengganti huruf tersebut. (45) Juga “Altsagh”, yaitu orang yang mengganti huruf dengan huruf lain. (46) Orang-orang tersebut jika ada kemampuan untuk belajar, tapi mereka tidak mau belajar, maka shalatnya tidak sah. Kalau tidak mungkin, maka shalatnya sah saja, sebagaimana sah pula imām ma’mūm sama-sama ummī. Makruh berma’mūm kepada imām yang selalu mengulang huruf tā’ (47) dan fā’ (48) dan juga dengan imām lahn (49) yang tidak sampai mengubah ma‘na, (50) misalnya membaca dhammah pada (هَاءِ)-nya lafazh (للهِ) atau membaca fatḥah (دَالٍ)-nya lafazh (نَعْبُدُ). Apabila lahn itu sampai mengubah ma‘na dalam fātiḥah, seperti membaca kasrah atau dhammah pada tā’-nya lafazh (أَنْعَمْتَ), maka shalat orang yang mampu untuk belajar, tapi tidak mau belajar adalah batal. Sebab yang dibaca itu bukan Qur’ān lagi. Benar hal itu membatalkan, namun jika waktu shalat telah mendesak, maka ia tetap wajib shalat demi menghormati waktu, dan nanti ia wajib mengulanginya, sebab kecerobohannya. Guru kami berkata: Yang jelas, orang yang lahn tersebut tidak boleh membaca kalimat tersebut, sebab apa yang dibaca pasti bukan Qur’ān lagi, sedang keabsahan shalat tidak digantungkan terhadap kalimat itu, bahkan kesengajaan membaca dengan lahn sekalipun kejadian yang seperti ini juga dapat membatalkan shalat.
أَوْ فِيْ غَيْرِهَا: صَحَّتْ صَلَاتُهُ، وَ الْقُدْوَةُ بِهِ، إِلَّا إِذَا قَدَرَ وَ عَلِمَ وَ تَعَمَّدَ، لِأَنَّهُ حِيْنَئِذٍ كَلَامُ أَجْنَبِيٍّ. وَ حَيْثُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ هُنَا يَبْطُلُ الْاِقْتِدَاءُ بِهِ. لكِنْ لِلْعَالَمِ بِحَالِهِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَ اخْتَارَ السُّبْكِيُّ مَا اقْتَضَاهُ قَوْلُ الْإِمَامِ لَيْسَ لِهذَا قِرَاءَةُ غَيْرِ الْفَاتِحَةِ، لِأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِمَا لَيْسَ بِقُرْآنٍ، بِلَا ضَرُوْرَةٍ مِنَ الْبُطْلَانِ مُطْلَقًا.
Kalau lahn itu terjadi bukan pada fātiḥah, maka shalatnya tetap sah, begitu juga berma’mūm dengannya kecuali sebenarnya ia mampu membaca secara benar, mengetahui hukum serta sengaja melakukannya sebab berarti ia berkata berupa ucapan lain. Apabila shalat menjadi batal lantaran lahn pada selain fātiḥah ini, maka batal pula berma’mūm dengannya. Namun, menurut Imām al-Māwardī, yang batal hanyalah bagi ma’mūm yang mengerti keadaannya. Imām as-Subkī memilih pendapat yang sesuai dengan pendapat Imām al-Ḥaramain: Bagi orang seperti di atas, tidak boleh membaca selain fātiḥah, sebab ia nanti akan mengucapkan perkataan yang bukan Qur’ān, yaitu perbuatan yang membatalkan shalat tanpa ada darurat, secara mutlak.
(وَ لَوِ اقْتَدَى بِمَنْ ظَنَّهُ أَهْلًا) لِلْإِمَامَةِ (فَبَانَ خِلَافُهُ) كَأَنْ ظَنَّهُ قَارِئًا، أَوْ غَيْرَ مَأْمُوْمٍ، أَوْ رَجُلًا، أَوْ عَاقَلًا فَبَانَ أُمِّيًّا، أَوْ مَأْمُوْمًا، أَوِ امْرَأَةً، أَوْ مَجْنُوْنًا، أَعَادَ الصَّلَاةَ وُجُوْبًا لِتَقْصِيْرِهِ بِتَرْكِ الْبَحْثِ فِيْ ذلِكَ (لَا) إِنِ اقْتَدَى بِمَنْ ظَنَّهُ مُتَطَهِّرًا فَبَانَ (ذَا حَدَثٍ) وَ لَوْ حَدَثًا أَكْبَرَ، (أَوْ) ذَا (خَبَثٍ) خَفِيٍّ، وَ لَوْ فِيْ جُمْعَةٍ إِنْ زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِيْنَ: فَلَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ، وَ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ عَالِمًا لِانْتِفَاءِ تَقْصِيْرِ الْمَأْمُوْمِ، إِذْ لَا أَمَارَةَ عَلَيْهِمَا، وَ مِنْ ثَمَّ حَصَلَ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ. أَمَّا إِذَا بَانَ ذَا خَبَثٍ ظَاهِرٍ فَيَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ عَلَى غَيْرِ الْأَعْمَى لِتَقْصِيْرِهِ، وَ هُوَ مَا بِظَاهِرِ الثَّوْبِ، وَ إِنْ حَالَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُوْمِ حَائِلٌ. وَ الْأَوْجَهُ فِيْ ضَبْطِهِ أَنْ يَكُوْنَ بِحَيْثُ لَوْ تَأَمَّلَهُ الْمَأْمُوْمُ رَآهُ، وَ الْخَفِيُّ بِخِلَافِهِ. وَ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِي التَّحْقِيْقِ عَدَمَ وُجُوْبِ الْإِعَادَةِ مُطْلَقًا. (وَ صَحَّ اِقْتِدَاءُ سَلِيْمٍ بِسَلِسٍ) لِلْبَوْلِ أَوِ الْمَذْيِ أَوِ الضُّرَاطِ، وَ قَائِمٌ بِقَاعِدٍ، وَ مُتَوَضِّىءٌ بِمُتَيَمِّمٍ لَا تَلْزَمُهُ إِعَادَةٌ.
Apabila berma’mūm pada seseorang yang dikira berhak menjadi imām, tetapi ternyata tidak, misalnya dikira qāri’, bukan ma’mūm, orang laki-laki atau berakal sehat, tetapi ternyata mereka adalah ummī, berma’mūm, wanita, atau orang gila, maka ia wajib mengulangi shalatnya. Demikian ini, karena kelalaian tidak mau meneliti dahulu. Tidak wajib mengulanginya bagi orang yang berma’mūm kepada imām yang dikira suci, tetapi ternyata menanggung hadats – sekalipun hadats besar – , atau membawa najis yang samar, sekalipun hal itu terjadi pada shalat Jum‘at, bila telah melebihi 40 orang. Sekalipun sang imām mengerti akan hadats dan najis pada dirinya, sebab tiada kelalaian pada ma’mūm, karena tiada tanda akan najis dan hadats yang dapat diketahuinya. Dari sini, maka bagi ma’mūm tetap mendapat fadhīlah jamā‘ah. Apabila imām yang dikira suci tersebut menanggung najis (51) yang lahir (kelihatan), maka ma’mūm wajib mengulangi shalat, karena kelalaiannya. Najis lahir adalah najis yang terdapat di luar baju, sekalipun antara imām dan ma’mūm terdapat penghalang. Pendapat yang aujah dalam membatasi najis lahir, adalah najis yang apabila ma’mūm mau memperhatikan benar-benar, maka akan melihatnya. Sedangkan najis yang samar, adalah sebaliknya. Imām an-Nawawī dalam kitab at-Taḥqīq membenarkan untuk tidak wajib mengulangi shalat secara mutlak. (52) Sah orang yang sehat berma’mūm pada imām yang beser kencing, madzi atau kentut. Orang yang berdiri sah berma’mūm pada imām yang shalat duduk, orang yang berwudhū’ pada imām yang tayammum yang tidak wajib mengulangi shalatnya. (53).
(وَ كُرِهَ) اِقْتِدَاءٌ (بِفَاسِقٍ وَ مُبْتَدِعٍ) كَرَافِضِيِّ، وَ إِنْ لَمْ يُوْجَدْ أَحَدٌ سِوَاهُمَا مَا لَمْ يَخْشَ فِتْنَةً وَ قِيْلَ: لَا يَصِحُّ الْاِقْتِدَاءُ بِهِمَا. وَ كُرِهَ أَيْضًا اِقْتِدَاءٌ بِمُوَسْوِسٍ وَ أَقْلَفَ، لَا بِوَلَدِ الزِّنَا، لكِنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى. وَ اخْتَارَ السُّبْكِيُّ وَ مَنْ تَبِعَهُ انْتِقَاءَ الْكَرَاهَةِ إِذَا تَعَذَّرَتِ الْجَمَاعَةُ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تُكْرَهُ خَلْفَهُ، بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنَ الْاِنْفِرَادِ. وَ جَزَمَ شَيْخُنَا بِأَنَّهَا لَا تَزُوْلُ حِيْنَئِذٍ، بَلِ الْاِنْفِرَادُ أَفْضَلُ مِنْهَا. وَ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: وَ الْأَوْجَهُ عِنْدِيْ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.
Makruh Berma’mūm Kepada Imām yang Fāsiq dan Berbuat Bid‘ah.
Makruh berma’mūm pada imām yang fāsiq dan yang berbuat bid‘ah, (54) misalnya orang Rāfidhī, sekalipun tidak terdapat imām selainnya. Hal ini jika memang tidak khawatir terjadi fitnah kalau tidak berma’mūm dengan mereka. Ada yang mengatakan: Berma’mūm dengan mereka hukumnya tidak sah. Makruh juga berma’mūm pada imām yang waswas (55) dan orang yang belum khitan. Tidak makruh berma’mūm pada anak hasil zina, tetapi hal ini menyelisihi keutamaan. Imām as-Subkī dan pengikutnya memilih bahwa berma’mūm pada imām-imām tersebut, tidak makruh lagi, jika memang hanya mereka saja yang ditemukan. Bahkan jamā‘ah dalam keadaan seperti itu, adalah lebih utama daripada shalat sendirian. Guru kami memutuskan tidak hilangnya hukum makruh dalam keadaan tersebut, bahkan yang lebih utama adalah shalat sendirian. Yang aujah bagiku (56) adalah apa yang dikatakan oleh Imām as-Subkī r.a.
[تَتِمَّةٌ]: وَ عُذْرُ الْجَمَاعَةِ كَالْجُمْعَةِ، مَطَرٌ يَبُلُّ ثَوْبَهُ لِلْخَبَرِ الصَّحِيْحِ: “أَنَّهُ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ يَوْمَ مَطَرٍ يَبُلُّ أَسْفَلَ النِّعَالِ” بِخِلَافِ مَا لَا يَبُلُّهُ. نَعَمْ، قَطْرُ الْمَاءِ مِنْ سُقُوْفِ الطَّرِيْقِ عُذْرٌ، وَ إِنْ لَمْ يَبُلَّهُ، لِغَلَبَةِ نَجَاسَتِهِ أَوِ اسْتِقْذَارِهِ. وَ وَحْلٌ لَمْ يَأْمَنْ مَعَهُ التَّلَوُّثُ بِالْمَشْيِ فِيْهِ أَوِ الزَّلَقِ، وَ حَرٌّ شَدِيْدٌ، وَ إِنْ وُجِدَ ظِلًّا يَمْشِيْ فِيْهِ، وَ بَرْدٌ شَدِيْدٌ، وَ ظُلْمَةٌ شَدِيْدَةٌ بِاللَّيْلِ، وَ مَشَقَّةُ مَرَضٍ وَ إِنْ لَمْ تُبِحِ الْجُلُوْسَ فِي الْفَرْضِ، لَا صُدَاعٌ يَسِيْرُ وَ مُدَافَعَةُ حَدَثٍ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ رِيْحٍ، فَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ مَعَهَا. وَ إِنْ خَافَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ لَوْ فَرَّغَ نَفْسَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ وَ حُدُوْثُهَا فِي الْفَرْضِ لَا يُجَوِّزُ قَطْعَهُ، وَ مَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِيْ هذِهِ: إِنِ اتَّسَعَ الْوَقْتَ، بِحَيْثُ لَوْ فَرَّغَ نَفْسَهُ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كَامِلَةً، وَ إِلَّا حَرُمَ التَّأْخِيْرُ لِذلِكَ. وَ فَقْدُ لِبَاسٍ لَائِقٍ بِهِ وَ إِنْ وَجَدَ سَاتِرَ الْعَوْرَةِ، وَ سَيْرُ رُفْقَةٍ، لِمُرِيْدِ سَفَرٍ مُبَاحٍ وَ إِنْ أَمِنَ، لِمَشَقَّةِ اسْتِيْحَاشِهِ وَ خَوْفُ ظَالِمٍ عَلَى مَعْصُوْمٍ مِنْ عِرْضٍ أَوْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ، وَ خَوْفٌ مِنْ حَبْسٍ غَرِيْمٍ مُعْسِرٍ، وَ حُضُوْرُ مَرِيْضٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَحوَ قَرِيْبٍ بِلَا مُتَعَهِّدٍ لَهُ، أَوْ كَانَ نَحْوَ قَرِيْبٍ مُحْتَضَرًا، أَوْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَضَرًا، لكِنْ يَأْنَسُ بِهِ، وَ غَلَبَةُ نُعَاسٍ عِنْدَ انْتِظَارِهِ لِلْجَمَاعَةِ، وَ شِدَّةُ جُوْعٍ، وَ عَطَشٍ، وَ عَمَى حَيْثُ لَمْ يَجِدْ قَائِدًا بِأَجْرَةِ الْمِثْلِ. وَ إِنْ أَحْسَنَ الْمَشْيَ بِالْعَصَا.
‘Udzur-‘udzur Berjamā‘ah
(Penutup). ‘Udzur (57) jamā‘ah, begitu juga shalat Jum‘at (58) adalah:
(1. Hujan yang sampai membasahi pakaian, berdasarkan sebuah hadits shaḥīḥ bahwa Nabi s.a.w. memerintahkan agar melakukan shalat di rumah masing-masing di waktu hujan yang sampai membasahi bagian bawah sandal. Lain halnya jika hujan tidak sampai membasahinya. Memang benar, namun tetesan air dari atap-atap rumah di tepi jalan, sekalipun tidak sampai membasahinya, adalah dianggap suatu ‘udzur, lantaran kemungkinan besar air najis atau kotor.
(2. Jalan berlumpur yang sulit menghindari terkenanya lumpur tersebut ketika berjalan atau tergelincir.
(3. Amat panas, sekalipun menemukan naungan untuk berjalan.
(4. Amat dingin.
(5. Amat gelap di malam hari.
(6. Sakit parah, sekalipun dengan kadar sakit yang belum boleh duduk dalam melakukan shalat fardhu. Tidak termasuk ‘udzur sedikit pusing kepala.
(7. Menahan hadats, baik itu air kencing, berak atau kentut. Maka, makruhlah shalat dengan menahan hadats, sekalipun khawatir tertinggal jamā‘ah bila memenuhi hadatsnya terlebih dulu, sebagaimana yang diterangkan oleh segolongan ‘ulamā’. Tidak diperbolehkan memutus shalat fardhu saat hadats terjadinya hadats di tengah-tengah melakukan shalat itu. (59) Masalah menahan hadats termasuk ‘udzur, jika waktu shalat masih longgar, kira-kira bila digunakan untuk mengosongkan diri dari hadats, masih cukup waktu untuk shalat dengan sempurna. Kalau waktu sudah sempit, maka haram menunda shalat sebab itu.
(8. Tidak menemukan pakaian yang pantas, sekalipun menemukan penutup aurat.
(9. Berangkatnya teman-temannya bepergian bagi orang yang akan bepergian yang mubāḥ, (60) sekalipun ia aman sebab beratnya kegelisahan dalam perjalanannya.
(10. Takut terhadap orang zhālim bagi orang yang berhak untuk dilindungi, (61) baik yang dikhawatirkan itu berupa harga diri, jiwa ataupun harta.
(11. Takut akan ditahan oleh pihak yang menghutangi bagi orang yang berhutang yang belum dapat membayar.
(12. Merawat orang yang sakit, sekalipun bukan sanak kerabatnya yang tidak ada orang yang merawatnya atau sanak kerabatnya sakit keras atau tidak sakit keras, tapi merasa gembira atas rawatannya.
(13. Sangat mengantuk (62) pada waktu menunggu jamā‘ah.
(14. Sangat lapar dan dahaga.
(15. Buta, jika tidak ada penuntun jalan yang mau digaji dengan harga umum, sekalipun dapat berjalan dengan menggunakan tongkat.
[تَنْبِيْهٌ]: إِنَّ هذِهِ الْأَعْذَارَ تَمْنَعُ كَرَاهَةَ تَرْكِهَا حَيْثُ سُنَّتْ، وَ إِثْمَهُ حَيْثُ وَجَبَتْ، وَ لَا تَحْصَلُ فَضِيْلَةُ الْجَمَاعَةِ كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوْعِ، وَ اخْتَارَ غَيْرُهُ مَا عَلَيْهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُوْنَ مِنْ حُصُوْلِهَا إِنْ قَصَدَهَا لَوْ لَا الْعُذْرُ قَالَ فِي الْمَجْمُوْعِ: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تَرَكَ الْجُمْعَةَ بِلَا عُذْرٍ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِيْنَارٍ، أَوْ نِصْفَهُ، لِخَبَرِ أَبِيْ دَاودَ وَ غَيْرِهِ.
(Peringatan). Semua ‘udzur di atas dapat menghapus kemakruhan meninggalkan jamā‘ah, sekira dihukumi sunnah, dan menghilangkan dosanya sekira dihukumi wajib berjamā‘ah. Dan tidak bisa mendapat fadhīlah jamā‘ah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imām an-Nawawī dalam al-Majmū‘. Selain Imām an-Nawawī memilih pendapat sebagaimana pendapat golongan ‘ulamā’ mutaqaddimīn, bahwa fadhīlah jamā‘ah tetap didapatkan, jika bermaksud melakukan jamā‘ah andaikan tidak ada ‘udzur. (63) Imām an-Nawawī dalam kitab al-Majmū‘ berkata: Sunnah bagi orang yang meninggalkan Jum‘at tanpa ‘udzur agar bersedekah satu dinar atau setengah dinar, sebagaimana yang diterangkan hadits Abū Dāwūd dan lainnya.