Surat-Surat Sang Sufi | Pendahuluan (4/5)
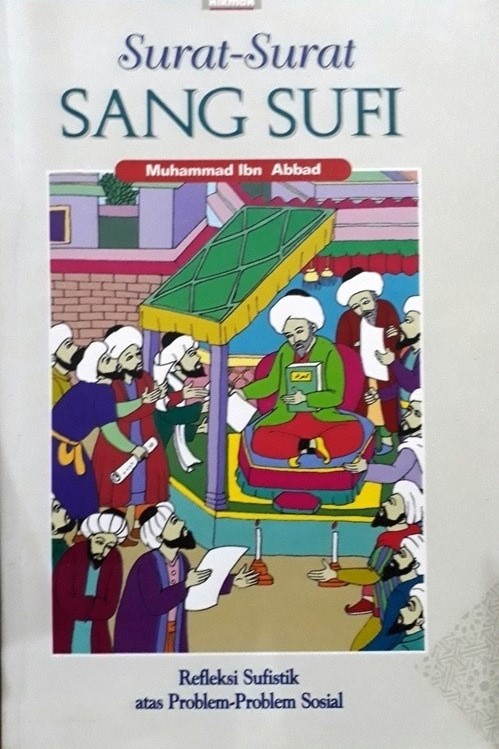
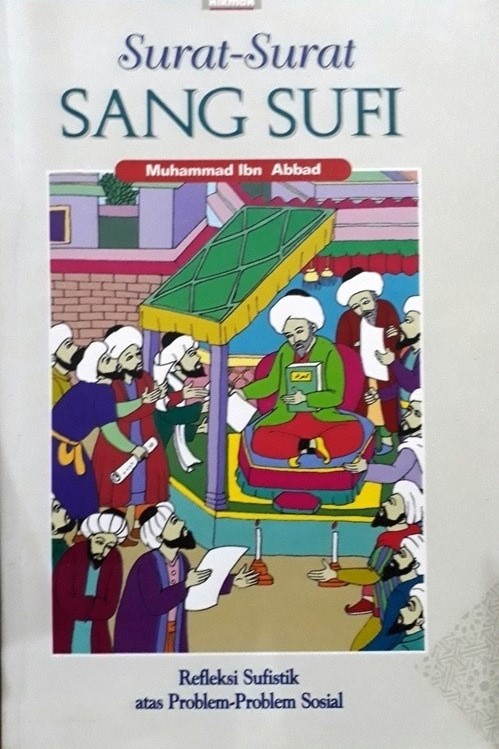
4. Ibn ‘Abbad dan Tasawuf Maroko
Lebih dari seabad sebelum tarikat Syadziliyah berdiri kukuh di Aleksandria, tasawuf sudah mulai berkembang di ibukota Almuhadiyah di Marakesh. Pada umumnya bernada kezuhudan, dan berkisar di seputar syaikh-syaikh yang juga merupakan fakih-fakih terkemuka.57 Enam kelompok sufi, yang bukan merupakan “tarikat” dalam artinya yang tepat, berkembang di Maroko, memiliki asal-usul yang berkembang pada diri Abu Madyan, “kakek spiritual” Syadzili. Kemudian sejak dari akhir abad ke duabelas sampai dari akhir abad ketigabelas, Maroko menyaksikan kepudaran tertentu ruh dikalangan kelompok-kelompok sufi lebih besar yang terlembagakan. Diantara tanda-tanda kepunahan itu adalah faksionalisme, hilangnya motivasi dari dalam, dan formalism dalam ibadah.
Namun, di saat yang sama dimulailah kebangkitan kembali. “Tasawuf disekeliling Tarikat”, (-demikian sebutan Paul Nwiya-seorang orientalis-ed.), mengambil bentuk ibadah populer, yang basisnya pada mulanya di dusun-dusun Maroko. Sebagai suatu jenis kesalehan yang amat pribadi, maka tidak berpusat pada kehidupan komunitas formal, seperti yang terjadi pada tarikat. Sebagaian orang memilih hidup sebagai zahid di zawiyah-zawiyah, namun kehidupan mereka mendekati kehidupan pertapa. Waktunya tepat bagi jenis spiritualitas yang mendorong pencapaian kehidupan batiniah yang tegar dan yang membolehkan para pengikutnya untuk tetap terlibat dalam urusan-urusan sehari-hari sebagai mana layaknya kebanyakan orang. Sebelum Ibn ‘Abbad menulis karyanya yang berjudul Tanbih, pengaruh Syadziliyah sudah terasa di Maroko. Ibn ‘Abbad adalah sufi Maroko pertama yang disebut secara eksplisit sebagai anggota tarikat itu. Namun kalau bukan karena tumbuhnya ketaatan pribadi di luar struktur tarikat, Syadziliyah tentu tak akan begitu saja diterima, seperti yang terjadi di Maroko.
Menurut Nwiya, karakteristik paling jelas dari tasawuf pra-Syadziliyah di Maroko adalah sudah terintegrasikannya tasawuf itu dalam kehidupan Islam resmi. Kaum sufi tidak bersikap menjauhkan diri dari studi-studi religius tradisional atau dari urusan dan fungsi yang lebih duniawi dalam kehidupan masyarakat. Karakter kedua adalah bahwa ini merupakan suatu tasawuf yang sangat dipengaruhi oleh Al-Ghazali (meninggal 1111), yang reputasinya sudah diselamatkan oleh Ibn ‘Abbad Tumart sang pembaru (meninggal 1130) dari upaya Almurawiyah pada suatu damnatio memoriae.58 Keberhasilan Al-Ghazali dalam mendamaikan studi-studi religius tradisional dengan tasawuf, khususnya sangat jelas pada masa dinasti Mariniyah (Marinid) (setelah 1248). Para fakih Mariniyah setidaknya tidak terang-terangan memusuhi tasawuf. Karya-karya tasawuf termasuk dalam daftar bacaan kesukaan sultan disamping teks-teks Maliki klasik, dan para penguasa memperlihatkan perhatian cukup baik pada guru-guru spiritual di masa mereka.59
Di tengah-tengah kehancuran tasawuf yang terorganisasikan, dan pembaruan kesalehan personal secara luas, berdiri sosok Ibnu ’Abbad, yang tentu saja figur paling penting di Afrika Utara antara 1200 dan 1400.
Riwayat Hidup dan Surat-Surat Ibn ‘Abbad
Ibn ‘Abbad lahir pada 1332 di Ronda, sebuah kota puncak bukit di Spanyol, yang waktu itu berada di bawah kekuasaan dinasti Mariniyah. Pada usia tujuh tahun dia menghafal Al-Quran dan mulai mempelajari hukum Maliki yang dikodifikasikan oleh Ibn Abi Zayd dari Qayrawan (meninggal 996) dalam Risalahi. Pada tahun 1340, Sultan Mariniyah, Abu Al-Hasan menderita kekalahan di Spanyol dan terpaksa membatasi upaya militernya di sana. Meningkatnya penakhlukan kembali oleh orang-orang Kristen, membuat kehadiran orang muslim di Spanyol semakin sulit. Pada 1437, Ibn ‘Abbad pindah ke Fez, ibukota Maroko.
Sultan Abu Al-Hasan (1331-1348) berupaya menjadikan ibukotanya sebagai pusat utama ilmu dan kebudayaan. Dia melindungi seni dan membantu kolese-kolese teologi baru, dan mengundang guru-guru ternama. Ayah Ibn ‘Abbad menjadi khatib di masjid Qashbah, sementara Ibn ‘Abbad melanjutkan kembali studinya di bidang agama. Mentor paling termahsyur Ibn ‘Abbad, Al-Syarif Al-Tilimsani (meninggal 1369), diakui secara luas sebagai pemimpin kebangkitan kembali Malikisme. Dia amat alim dalam ilmu prinsip-prinsip hukum (ushul) sehingga dianugerahi hak langka, yaitu berhak melakukan ijtihad. Tilimsani mengajar Ibn ‘Abbad, pertama di Tlencem, dan kemudian ketika sang guru datang ke Fez atas undangan Sultan Abu ‘Inan.
Selama masa tinggal pertama di Fez, Ibn ‘Abbad mungkin tinggal di pondokan pelajar di kolose teologi tertua yang masih ada, yaitu madrasah Halfawiyin. Dari Al-Abili (meninggal 1356) dia mempelajari risalah teologi Asy’ariyah. Al-Irsyad, yang ditulis oleh Al-Juwayni (meninggal 1248), salah seorang guru Al-Ghazali, dan beberapa tulisan Ibn-Hajib (meninggal 1248) tentang hukum. Seperti Tilimsani, Al-Abili mendorong pembaruan hukum Maliki; dia mengkritik kekakuan mazhab-mazhab yang disponsori negara dan stagnasi yang dialami mazhab-mazhab itu.
Dengan diawasi Al-Maqqari (meninggal 1337), Ibn ‘Abbad membaca himpunan hadis Nabi karya Muslim dan juga karya-karya lain yang telah dipelajari sebelumnya dari Tilimsani. Dari Al-‘Imrani (meninggal 1286) dia mempelajari himpunan hadis Malik Ibn Anas (meninggal 795), Al-Muwaththa’. ‘Imrani adalah seorang fakih kenamaan yang disebut-sebut sangat tertarik kepada tasawuf. Seperti alim-alim Maliki lainnya, dia menulis beberapa ulasan tentangn Al-Mudawwanah karya Sahnun (meninggal 8554)- bagamana pun juga karya paling berpengaruh di bidang fiqih Afrika Utara. Ikhtisar klasik Al-Baradzi’I (Qayrawan abad kesepuluh) tentang Mudawwanah merupakan sumber lain bagi pendidikan Ibn’Abbad, mungkin ketika dia tinggal di madrasah Bou ‘Inaniyah yang baru selesai pembangunannya itu. Dalam surat ke-6 dia memuji Abu Thalib Al-Makki, dengan mengatakan bahwa Qut Al-Qulub karya Abu Thalib itu amat penting bagi kehidupan spiritual. Sebagaimana pentingnya Al-Mudawwanah bagi fiqih: sempurna dan tak bisa digantikan oleh yang lain.
Dua alim lain Maliki perlu disebutkan disini. Ibn ‘Abbad menulis surat ke-16 untuk Abu Ishaq Ibrahim al-Syathibi dari Granada (meninggal-1388). Muwafaqat karyanya merupakan sumbangsih utamanya pada suasana studi-studi keagamaan yang kiranya telah berkembang secara dramatis meskipun memiliki banyak sekali luka lama yang perlu disebuhkan. Akhirnya Ibn ‘Abbad menyebut-nyebut Ahmad Al-Qabbab (meninggal 1375), juga dalam surat ke-16. Seperti Al-Abili, Al-Qabbab berupaya menyuntikkan kehidupan baru kedalam studi-studi keagamaan yang terhuyung-huyung akibat pukulan keras yang dilancarkan pukulan Almuhadiyah terhadap studi-studi itu.60
Ibn Khaldun mengatakan bahwa “kalangan ulama Maliki tidak pernah henti-hentinya menulis komentar , penjelasan, dan synopsis tentang karya-karya utama ini. “61
Pendidikan yang diterima Ibn ‘Abbad di bangku sekolah tentang hukum agama itu luas, namun sangat tradisional, agak kaku dan dalam gaya Maroko. Nwiya menunjukkan tidak adanya secara mencolok mata, nama Fakhr Al-Din Al-Razi (meninggal 1209) dari sekian nama tokoh yang dibaca Ibn ‘Abbad. Sekitar tahun 1300 ada pemisahan antara gaya studi hukum yang dilakukan di Fez dan di Tunis. Tunis menjadi lebih spekulatif di bawah pengaruh Fakhr Al-Din Al-Razi, yang menurut M.Mahdi, “mempengaruhi persesuain baru antara pengetahuan filsafat rasional dan studi-studi agama.62 Sementara itu di Fez tetap lebih konservatif di bawah pengaruh Ibn Al-Hajib.63
Meskipun dengan latar belakang studi-studi hukum tradisional yang luas, Ibn ‘Abbad menolak, dalam Surat-Suratnya, untuk membahas langsung pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dengan mengatakan bahwa dia kurang memiliki keahlian yang diperlukan untuk itu.
Barangkali Ibn ‘Abbad mengenal tasawuf lewat salah seorang guru hukumnya, sebab banyak diantara mereka itu adalah sufi. Beberapa gurunya resmi berhubungan dengan tarikat-tarikat yang sudah diakui, tapi mereka mengajar tasawuf secara pribadi, dengan memakai karya-karya klasik Al-Maliki, Al-Ghazali dan Suhrawardi.
Setelah meninggalnya Sultan Abu ‘Inan, pada tahun 1358, Fez rupanya mengalami suatu episode yang amat kacau. Terdapat tujuh belas sultan antara 1358 dan 1367. Tak lama setelah meninggalnya sultan, Ibn ‘Abbad pergi ke Barat. Ke Sale, kota di tepi laut Atlantik. Di sana Ibn ‘Asyir (sekitar 1300-1362) menjadi tokoh poros dalam kebangkitan tasawuf di luar tarikat. Peziarah dari segenap penjuru Maroko datang mengunjungi Syaikh ini untuk mendapatkan berkahnya. Ibn ‘Abbad terus menjadi murid terbaik syaikh ini. Dia banyak membaca tasawuf berbagai cabang serta gayanya. Setidak-tidaknya dia memutuskan untuk mendukung Syadziliyah. Itulah informasI dari Ibn Al-Sakkak (meninggal 1451), Penulis Magribi pertama yang menulis dengan jelas tentang Syadziliyah. Dia pun mengatakan bahwa, ketika masih anak-anak, dia pernah bertemu Ibn ‘Abbad yang usianya jauh lebih tua dan sering makan bersamanya.64
Ibn ‘Abbad pergi ke Sale untuk menghindari kondisi hidup yang sedang sekarat di Fez, dan untuk mencari keselamatan spiritual. Gurunya memandangnya dalam “kelas tersendiri”. Berkat kemandiriian dan keinginannya untuk menempuh jalannya sendiri, sang murid tidak terkuasai oleh intensitas gurunya. Ibn ‘Asir sangat halus perasaannya, karena terus-menerus berpuasa dan makan hanya dua kali sehari. Inilah praktek lama sufi yang disebut “Puasa Daud”, yang dimaksudkan untuk menjaga agar sang zahid tidak terbiasa dengan puasa atau rasa kenyang.65 Selaras kecintaannya kepada tulisan-tulisan Al-Muhasibi, Ibn ‘Asyir menekankan praktik menguji hati nurani. Dia adalah sufi shaw yang tegar.
Pada sekitar 1362 atau 1363, setelah meninggalnya Ibn ‘Asyir, Ibn ‘Abbad meninggalkan Sale menuju Tangiers. Di sana dia berguru kepada sufi yang kurang begitu dikenal, Abu Marwan ‘Abn Al-Malik. Setelah tinggal disana dalam waktu yang tidak diketahui, sang pencari ini kembali ke Fez. Selama berada kembali di Fez, Ibn ‘Abbad kembali berkenalan dengan Yahya Al-Sarraj (sekitar 1344-sekitar 1400), pendiri cabang -Fez dari sebuah keluarga yang berakar di Ronda, dan penerima beberapa Surat ini. Ibn ‘Abbad juga menjadi sahabat karib Abu Al-Rabi’ Sulayman Al-Anfasi (sekitar 1377-1377). Atas permintaan kedua sahabat inilah dia menulis Tanbih, yang terselesaikan antara 1370-1372.
Ibn ‘Abbad kembali ke Sale pada tanggal yang tidak begitu jelas, dan tinggal di sana sampai sekitar 1375. Kebanyakan (jika tidak semuanya), korespondensinya dilakukan sejak sebelum tahun itu. Sekitar 1375 dia diangkat menjadi Imam dan Khatib masjid Qayrawiyin di Fez, institusi agama dan ilmu tertua dan paling bergensi di Afrika Utara. Sultan Abu Al-‘Abbas Ahmad (pemerintahan pertama 1373-1384) rupanya melakukan pengangkatan itu berdasarkan reputasi Ibn ‘Abbad akan integritas pribadi, dan kemahsyuran Tanbih-nya. Prospek pengambilalihan pos khatib ketika khutbah telah turun derajatnya menjadi sedikit lebih dari sekedar menyampaikan sesuatu secara hafalan tanpa pemikiran mendalam bagi banyak khatib, tentunya menimbulkan tantangan. Dengan merenungkan seni dalam salah satu Surat,66 terlihat dia mencatat lima jenis khatib yang menurutnya tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik. Sebagian hanya mengulang-ulang khutbah yang sama setiap Jumat; sebagian mengulangnya dengan sedikit variasi; sebagian berkhutbah tanpa mengaitkan pesan-pesan mereka dengan kebutuhan-kebutuhan yang berubah; sebagian memperlihatkan kebutuhan-kebutuhan itu, namun tidak dapat mengaitkan pesan mereka secara efektif dengan kebutuhan-kebutuhan itu; dan sebagian juga kurang taat, dan semata-mata aktor-aktor yang berlagak. Khatib sejati adalah khatib yang memberikan nasihat dan mengajar orang selaras dengan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari mereka yang mendesak, dan mampu memadukan gaya penyampaian dengan tema yang telah dipilihnya. Ibn ‘Abbad lebih menyukai gaya didaktis ketimbang gaya menasihati atau peringatan. Karena orang itu memerlukan peringatan, dia selalu menempatkan dirinya sebagai terikat kepada kewajiban yang diwajibkan pada audiensinya.
Masih ada seratus dua puluh empat khutbah dalam sebuah manuskrip, yang telah dianalisis oleh Paul Nwiya. Khutbah Jumat lazimnya terdiri atas dua bagian: bagian pertama mengembangkan tema yang sesuai dengan keadaan, dan bagian kedua membahas topik baku, yaitu solawat atas Nabi, para Sahabatnya, para istrinya, para penerusnya, dan umat Islam, dengan menyebutkan nama khalifah atau sultan umat Islam. Hanya satu diantara khutbah-khutbah Ibn ‘Abbad yang masih ada dan mengandung bagian kedua itu. Tapi bagian pembuka dari tiap-tiap bagian itu dimulai dengan deksologi (zikir), doa pendek untuk Nabi; dan Syahadat, yang semuanya diikuti oleh jamaah. Khutbah itu disampaikan sekitar dua puluh menit.
Frase-frase yang memukau, ritmis, pendek dan tepat, dimaksudkan untuk menandingi prosa bersajak kitab suci. Karena doktrin Islam itu sederhana, maka pembicara perlu mengandalkan kedalaman berbahasa Arab, tanpa sekaligus membawakan sekadar suara yang indah namun tidak mengandung pengaruh personal dan tantangan moral. Ibn ‘Abbad suka menggunakan hati nurani langsung jamaahnya, dengan didukung oleh Al-Quran dan hadits. Berupaya menarik perhatian melalui intonasi yang tepat. Dia mengaitkan tema-temanya dengan keadaan: Selama bulan Ramadhan, dia berbicara tentang puasa, dan tentang perlunya terlebih dahulu menyucikan hati agar tindakan fisik ini memerlukan makna spiritual. Selama bulan haji, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan terakhir makna Hijriah, dia menyerukan agar memeriksa keadaan hati nurani selama tahun-tahun yang lewat. Bila datang tahun baru, di bulan Muharram dia menganjurkan bersedekah. Ibn ‘Abbad tidak memandang khutbah umum itu sebagai forum yang tepat untuk menyampaikan masalah-masalah tasawuf. Dia membahas tasawuf dalam surat-surat pribadi yang berisi bimbingan spiritual.
Selama seperempat terakhir abad keempatbelas, dinasti Mariniyah mengalami kemunduran. Kota besar Fez mengalami kesulitan politik besar dan lebih dari sekadar keresahan spiritual. Gambaran sosok Ibn ‘abbad yang tinggal di rumah kecil di dekat masjid, menarik sederetan anak kecil berjalan di belakangnya ketika Ibn ‘Abbad menuju ke masjid, dan yang memperlihatkan kebutuhan orang sedapat mungkin, merupakan gambaran tentang keyakinan dan harapan pada saat terjadi ketidakstabilan dan ketidakpastian. Menjelang akhir hayatnya, dia menulis kepada seorang sahabat, Abu Al-‘Abbas Al-Marrakusyi, bahwa dia merasa jenuh dengan Fez dan sudah lelah dengan kewajiban-kewajibannya, pasrah dengan kesehatannya yang memburuk serta sedang mempersiapkan diri menyongsong datangnya kematian. Nwiya mengatakan bahwa Ibn ‘Abbad tetap membujang sampai akhir hayatnya. Sebagian sumber mengatakan ia tidak pernah menikah. Kalau memang dia menikah pada akhir hayatnya, tentu dia melakukannya karena keinginan mengikuti contoh Nabi, bukan karena dirinya lebih menyukainya. Dia tidak pernah pergi haji ke Makkah.
Pada 17 Juni 1390, Ibn ‘Abbad di makamkan di hadapan sultan dan banyak penduduk Fez. Meskipun lokasi-lokasi makamnya tidak lagi diketahui, toh konon tetap menjadi tujuan penziarah selama bertahun-tahun. Sampai 1936, Serikat Pekerja Pembuat Sepatu mengadakan perayaan untuknya setiap tahun, sebab dia telah menjadi pelindung mereka.66
(bersambung)