Surat-Surat Sang Sufi | Pendahuluan (3/5)
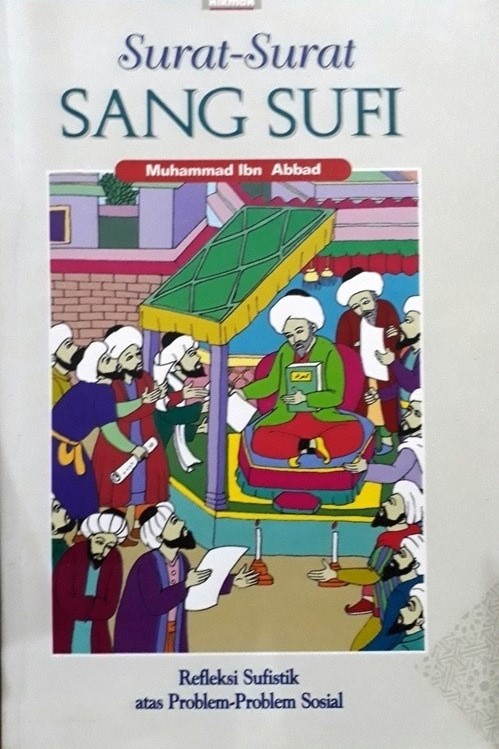
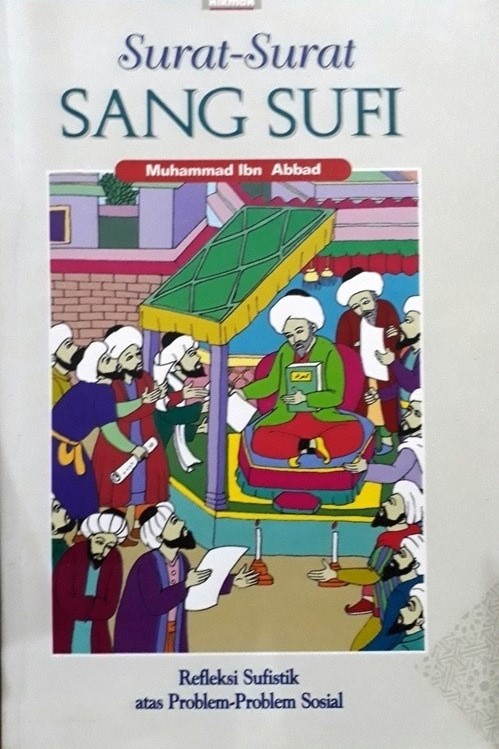
(lanjutan)
3. Tarikat Syadziliyyah
Kelahiran Tarikat Syadziliyyah terjadi melalui dua tahap, di Tunis dan di Mesir. Ibn Masyisy menasihati Abu Al-Hasan agar menyendiri di sebuah gua dekat dusun Syadzila (-dari sini nisbat nama Al-Syadzili, Asy-Syadzali, atau Asy-Syadzili muncul-ed.), antara Tunis dan Qayrawan. Al-Syadzili mematuhinya, namun terkadang masih memberikan ceramah, dan mulai menarik pengikut. Pada 1240 dia pergi ke Tunis. Di sana dengan dibantu Sultan Hafshid Abu Zakariya (memerintah dari 1228 sampai 1249), dia mulai mempersiapkan pembentukan tarikat itu dengan “empat puluh sahabat.” Di antaranya seseorang yang bernama Al-Shaqalli (bukan orang yang dikutip secara panjang lebar oleh Ibn ‘Abbad dalam surat ke-8) dan seorang tokoh yang tetap lebih penting, Abu Al-Abbas Al-Mursi (1219-1287). Keberhasilan yang cepat diraih Syadzili jelas memancing amarah ulama setempat, sehingga pada 1244 atau 1252, dia pindah ke Aleksandria. Al-Shaqalli tetap tinggal sebagai juru bicara dan koresponden di Tunis. Tarikat ini terus tumbuh pesat di Mesir di bawah tiga syaikh pertamanya: Al-Syadzili sendiri, Al-Mursi, dan Ibn ‘Athaillah dari Aleksandria (1252-1309).38
Menurut Nwiya, Ibn Masyisy telah dituduh berbuat sesat. Karena dia itu seorang Idrisi, maka dia dikaitkan dengan pandangan-pandangan Syi’ah-atau bagaimana pun juga pandangan-pandangan yang dianggap tidak sepenuhnya “ortodoks” – yang sebelumnya telah dihubungkan dengan dinasti Idrisiyah (sekitar 788-985). Syadzili juga berbicara tentang suksesi spiritual, dalam pengertian yang sulit diterima oleh otoritas Sunni. Al-Mursi kemudian menguraikan watak- sejati suksesi secara lebih eksplisit, dengan mengatakan bahwa tarikat itu bukan dari Timur dan juga bukan dari Barat, tetapi berasal langsung dari putra ‘Ali (cucu Muhammad) yaitu, Hasan. Mursi dengan demikian sedang menunjukkan bahwa suksesi guru-guru spiritual dalam tarikat didasarkan, bukan pada penyerahan khirqah, tapi pada bimbingan Allah untuk menghubungkan hamba-hamba-Nya secara spiritual dengan Nabi. Teori ini amat berbeda dengan teori tarikat-tarikat Sunni sebelumnya, dan permulaan kehabisan ini menandakan awal dari spiritualitas mistikal jenis baru.
Teori baru suksesi ini mengatakan bahwa Syadzili sendiri “menitis” dalam diri tokoh-tokoh penerus yang memimpin tarikat ini. Syaikh bukan lagi semata-mata pemimpin yang bertugas menyampaikan doktrin; dia juga membawa dirinya sendiri dalam kapasitasnya sebagai kutub alam semesta (quthb).39 Ketika Mursi menjadi syeikh pada 1258, dia memandang dirinya berada diatas faqih; karena dia dan juga Syadzili memandang hanya pengetahuan pengalaman tentang Allah sajalah-bukan sekedar prestasi intelektual semata-yang merupakan pengetahuan sejati. Di antara kitab-kitab yang disukai Syadzili dan Mursi adalah Khatm Al-Awliya’ (Penutup Para Wali) karya Al-Hakim Al-Tarmidzi (meninggal sekitar 932) dan Kitab Al-Mawaqif (Kitab tentang tempat Berhenti) karya Niffari (meninggal 965). Khatm Al-Awliya’ mengembangkan teori yang memperlihatkan bahwa wali memiliki struktur hirarki dan kutub atau “penutup”, sebagaimana ada penutup para nabi, yaitu Muhammad. Dengan demikian, “kutub” mendapatkan status yang secara kasar sejajar dengan status Nabi sendiri. Karya luar biasa Niffari juga mendukung gagasan yang mengatakan bahwa seorang sufi dapat (seperti Muhammad), cukup dekat dengan Allah untuk bercakap-cakap dengan-Nya.40
Salah satu jalan terbaik untuk mengetahui suasana spritualitas adalah merasakan nada dan mood doa-doa yang dibawakannya. Dalam surat ke-13, Ibn ‘Abbad menganjurkan agar orang yang dikirimnya surat menggunakan “Doa Agung” Al-Syadzili, dan memuji manfaat-manfaat doa itu sedemikian rupa. Inilah terjemahan “Doa Lautan” termahsyur Al-Syadzili, yang digunakan oleh syaikh dalam berdoa selama banyak kali menyeberangi Laut Merah dalam perjalanannya ke dan dari Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Hingga saat sekarang pun doa itu masih popular. Ibn Baththuthah, salah seorang tokoh yang sezaman dengan Ibn ‘Abbad, menganggap cukup penting untuk menyertakan doa ini dalam perjalanan-perjalanan-nya. Berikut ini terjemahan doa itu oleh H.A.R. Gibb:
Ya Allah, Yang Maha Tinggi, Yang Maha Agung, Yang Maha Penyantun, Yang Maha Mengetahui-ed.. Dikaulah Tuhanku, dan pengetahuan-Mu cukup bagiku. Betapa sempurna Tuhanku, betapa sempurna kecukupanku oleh Pencukupku. Dikau menolong siapa-siapa yang Dikau kehendaki, karena Dikau Mahakuasa, Maha Penyayang. Kami mohon Dikau untuk menjaga kami dari dosa dalam gerak dan diam kami, kata-kata dan maksud-maksud kami, dalam keraguan, dorongan tercela dan imajinasi sia-sia, yang membuat hati kami tidak dapat melihat hal-hal yang ghaib. Sesungguhnya orang-orang mukmin telah berusaha dan tergoncang sedih, dan ketika si pemuas kepentingan diri dan yang berjiwa rendah mengatakan, “Bagi kami, janji-janji Allah dan Rasul-Nya tak lebih hanyalah khayalan.” Dikau menegakkan dan menolong kami, dan menundukkan bagi kami lautan ini seperti Dikau tundukkan lautan bagi Musa, seperti Dikau tundukkan api bagi Ibrahim, dan seperti Dikau tundukkan gunung-gunung dan besi bagi Daud, dan seperti Dikau tundukkan angin dan setan serta jin bagi Sulaiman. Tundukkan bagi kami setiap lautan-Mu di bumi dan di langit, di dunia kasat-indera dan di dunia gaib, lautan kehidupan ini dan lautan kehidupan mendatang. Tundukkan bagi kami segalanya, Duhai Yang di “Tangannya” kekuasaan atas segalanya.
Kaf Ha Ya ‘Ayn Shad 3x. Tolonglah kami, sebab Dikaulah sebaik-baik pembuka jalan; ampunilah dosa-dosa kami, sebab Dikaulah sebaik-baik pengampun; perlihatkan rahmat kepada kami, sebab Dikaulah sebaik-baik yang memperlihatkan rahmat; berilah rizki kami, sebab Dikaulah sebaik-baik pemberi rizki. Bimbinglah kami, dan selamatkanlah kami dari tangan mereka yang berbuat keji, dan berilah kami angin lembut sesuai dengan Ilmu-Mu; hembuskanlah atas kami dari khazanah Rahmat-Mu, dan bawalah kami dengan kendaraan kemurahan-Mu, (sehingga kami) dengan demikian terselamatkan dari dosa, dan kami pun merasakan kesejahteraan kehidupan spiritual maupun material dan juga dikehidupan mendatang; sesungguhnya Dikaulah penentu segalanya. Ya Allah, lancarkanlah semua urusan kami; tentramkan hati dan jasmani kami, dan anugerahilah kami kesehatan dan kesejahteraan kehidupan spiritual dan material. Jadilah Dikau Sahabat dalam perjalanan kami, dan Penjaga rumah tangga ketika kami tak ada di rumah. Corenglah wajah-wajah musuh-musuh kami, dan ubahlah mereka menjadi makhluk-makhluk keji dimanapun mereka berada; lalu mereka pun tak akan mampu melawan kami.
Kalau Kami kehendaki, Kami akan membuat gelap pandangan mereka, dan mereka pun akan saling bersegera mencari jalan; lalu bagaimanakah perasaan mereka? Jika kami kehendaki, Kami akan mengubah mereka di mana pun mereka berada dan mereka tak akan dapat maju dan tak dapat kembali (-untuk detail silakan cari terjemah Hizbul Bahr–ed.)”41
Constance Padwick mencatat bahwa Nabi disebut-sebut telah mengajarkan doa kepada Syadzili melalui sebuah mimpi. Syaikh ini lalu mengumpulkan para pengikutnya, dan mengatakan agar menyuruh anak-anak mereka menghafal doa ini. Doa ini jelas dipandang mengandung semacam kekuatan magis, disamping nilai ibadahnya yang besar.42 Perhatikan perbedaan diantara kualitas doa itu yang hampir menyerupai azimat, dan doa Al-Syadzili berikut ini, yang mendekati Allah persis seperti doa Ibn ‘athaillah dalam aphorisme-aphorismenya (segera akan dibahas):
Ya Allah, jika aku meminta tolong kepada-Mu, aku meminta sesuatu disamping-Mu. Kalau aku meminta apa yang Dikau jaminkan bagiku, aku memperlihatkan kecurigaan akan Dikau, berarti aku telah berbuat doa syirik. Sifat-sifat-Mu yang agung itu hakikat, mana bisa aku bersama-Mu? Sifat-sifat itu mengatasi sebab-sebab, mana bisa aku dekat dengan-Mu ? Sifat-sifat itu tinggi di atas debu bumi, mana bisa yang menopangku selain-Mu?43
Beberapa karakter khas spiritualitas Tarikat Syadziliyah sudah terlihat sejak awal keberadaan tarikat itu. Selain kepercayaan mereka bahwa Kutub atau poros alam semesta akan selalu menjadi anggota tarekat itu. Juga prinsip yang kuat bahwa menjadi anggota tarikat itu merupakan takdir yang ditetapkan jauh sebelumnya. Pada mulanya Syadziliyah tidak memiliki formula doa umum yang vocal atau ritual yang khas. Mereka tidak menarik diri dari pergaulan masyarakat, atau mengenakan pakaian yang akan menunjukkan kefakiran diri mereka, dan mereka bukanlah tarikat peminta-minta.44 Karena alasan ini dan alasan serupa lainnya, Mackeen menyatakan bahwa “satu fakta yang mendasar lagi penting bahwa Syadziliyah lahir dari lingkungan urban, yang tentu saja karena bukan berontak terhadap lingkungan itu, tapi hasil dari pola-pola kehidupan politik, agama, dan ekonomi yang ada.”45
Jika dapat menilai dari uraian Trimingham tentang majlis-majlis zikir komunal yang lebih belakangan dari tarikat itu, jelaslah Syadziliyah selama berabad-abad mengarah ke pengalaman dan pengungkapan yang lebih ekstatis,46 tapi mood-nya kelihatannya telah jauh lebih shahw. Setidak-tidaknya selama satu setengah abad pertamanya. Namun telah terjadi kontiniutas mendasar dalam spiritualitas tarikat itu “tidak menarik bagi kelas bawah” ,yang memerlukan sarana yang lebih menarik untuk masuk ke tarikat, dan tidak menarik pula bagi kalangan penyair. Tapi terutama berkaitan dengan kelas menengah, kalangan pejabat dan pegawai pemerintah yang terdidik dalam metode Syadziliyah untuk menunaikan tugas-tugas mereka menarik murid-murid baru di Mesir dan memberikan kepada mereka pendidikan menyeluruh dibidang spiritual, adalah cabang dari tarikat Syadziliyah. Sebuah tarikat yang mengilhami manusia untuk menyucikan kehidupan sehari-hari.”47
Satu bagian penting dari “pendidikan spiritual” berkaitan dengan proses “afiliasi”, atau pengupayaan agar ada hubungan spiritual dengan guru spiritual pertama. Menurut sebuah buku pedoman Syadziliyah dari sekitar tahun 1909, dalam pendidikan itu ada empat tingkatan:
Yang pertama, adalah melalui jabatan tangan hangat, pemberian tugas-tugas zikir, pengenaan jubah dan serban; semata-mata sebagai sarana untuk mendapatkan berkat dan afiliasi.
Yang kedua, berkenaan pendidikan dalam bidang hadits (melalui sederetan perawi yang handal) dan terdiri atas bacaan tulisan-tulisan tarikat tanpa menerima penjelasan tentang maknanya; dan ini juga semata-mata demi memperoleh berkat dan afiliasi.
Yang ketiga, adalah pendidikan dalam pemahaman (meneliti secara cermat bukti batiniah) dan terdiri atas penjelasan tentang kitab-kitab agar dapat memahami maknanya. Ini juga tidak melibatkan pelaksanaan metode-metode aktualnya.
Sebagai aturan, ketiga bagian ini hanyalah yang lazim dilakukan, dan siswa pengikut latihan boleh mendapatkan sejumlah syaikh untuk memandunya semampu mereka.
Yang keempat, adalah melaksanakan pendidikan aktual (tadrib), menerima instruksi (tahdzib) dan menjalani perkembangan progresif melalui pengabdian, dengan cara mujahadah (peniadaan kedirian), menuju kepencerahan (musyahadah, yang terjemahannya adalah kontemplasi atau penglihatan kontlemplatif dalam surat-surat yang diterjemahkan disini) dan meniadakan diri kedalam keesaan (al-fana’fi al-tawhid) dan kekal didalamnya (al-baqa’ bihi). Proses ini tidak boleh dilakukan oleh murid, kecuali kalau diizinkan oleh gurunya.48
Sebagai pembimbing spiritual dan pemimpin lokal Syadziliyah, Ibn ‘Abbad memiliki kepedulian pada masalah-masalah ini, meskipun biasanya tidak dengan cara sedemikian sistematis. Pembahasannya mengenai peranan guru spiritual, dalam Surat ke-16, menunjukkan bahwa pemikirannya tentang “keanggotaan” dalam tarikat itu sangat luwes.
Seperti yang sangat sering terjadi dalam lembaga-lembaga manusia, “pendiri” Sadziliyah mewariskan ruh, bukan kerangka untuk gedung. Dia memasrahkan tugas melembagakan dan mamajukan ruh itu kepada para pengikutnya. Mursi adalah orang yang pertama yang membentuk tarikat itu menjadi tempat tinggal eksklusif ketika dia memberikan untuk kelompok ini tempat khusus dan masjid di Aleksandria. Ibn ‘Athaillah adalah orang pertama yang menangkap ruh itu dalam tulisan, khususnya dalam sketsa-sketsa bibliografinya tentang Syadzili dan Mursi, dan dalam karyanya, Al-Hikam (Kitab tentang Kearifan). Ibn ‘Athaillah menulis bahwa peranan Mursi dalam tarikat itu “berupa memajukan ilmu Syaikh Abu Al-Hasan (Al-Syadzili), menebarkan sinarnya, dan menjelaskan misteri-misterinya, sedemikian rupa sehingga orang berbondong datang kepadanya dari seluruh negeri,”49 Namun berkat popularitas luar biasa Hikam, tarikat itu bisa kembali ke Afrika Utara, yang dari negeri inilah tarikat itu pernah disingkirkan.
Ibn ‘Athaillah lahir sekitar 1250 di Aleksandria. Ayah dan kakeknya sama-sama faqih Maliki;50 meskipun keduanya terutama tidak tertarik kepada gerakan sufi pada mulanya, jelas sang ayah merasa tertarik kepada tasawuf setelah bertemu Syadzili. Victor Danner mengatakan bahwa ayah Ibn ‘Athaillah sangat mungkin murid Syadzili maupun Mursi.51 Ibn ‘Athaillah sendiri tetap curiga kepada kaum sufi untuk beberapa lama, dan sangat menekuni studi-studi hukum dan hadis. Nwiya berteori : bahwa dia pada akhirnya berubah sikap setelah berbincang dengan sahabat-sahabat Mursi. Sekitar 1276 Ibn ‘Athaillah bertemu muka dengan Mursi. Hal itu merupakan awal dari hubungan yang berlanjut selama sekitar dua belas tahun, dan selama masa ini Mursi memandu Ibn ‘Athaillah melewati serangan krisis pribadi. Seperti telah disebutkan dalam bagian sebelumnya, yaitu Kehadiran Allah, Mursi menjelaskan bahwa seorang mukmin dapat mengalami hanya satu dari empat hal pada waktu tertentu: bahkan kesengsaraan, godaan, ketaatan, pembangkangan. Allah memperlakukan hamba-hamba-Nya dengan satu di antara dua cara pertama, dan para hamba memberikan tanggapan dengan satu diantara dua cara kedua. Ketika seseorang menerima berkah, Allah mengharap rasa syukur. Ketika seseorang mengalami cobaan, Allah mengharapkan agar karunia-Nya diakui. Jika seseorang membangkang, Allah mengharapkan agar hamba-Nya itu memohon ampun.
Salah satu dilema pribadi Ibn ‘Athaillah adalah sama dengan kebingungan yang dialami salah seorang koresponden Ibn ‘Abbad: Haruskah sufi murid tetap berhubungan dengan kalangan faqih? Syeikh Mursi meyakinkan orang yang dinasehatinya. Berdasarkan pendekatan khas tarikat, bahwa dia tidak perlu mengakhiri pergaulannya. Namun Ibn ‘Athaillah terus mengalami ketegangan sedemikian, sehingga dia percaya dia harus memilih mencari salah satu; pengetahuan atau Allah; bukan kedua-duanya. Sekali lagi Mursi meyakinkannya bahwa Allah dapat mengubah seseorang menjadi hamba-Nya, tak masalah dengan pekerjaannya (-profesinya-ed.)
Akhirnya Ibn ‘Athaillah dapat menyelesaikan konflik itu. Setelah meninggalkan Mursi pada 1288, Mursi yang menjadi Syaikh ini terus mengajar hukum dan tasawuf di Kairo, hingga meninggal dunia pada 1308. Selama karirnya lebih dua dekade di Kairo, Ibn Athaillah terlibat perdebatan dengan Ibn Taimiyah (meninggal 1328), seorang faqih Hambali yang juga seorang sufi. Seluk beluk pertukaran pandangan diantara mereka tidak sepenuhnya relevan dengan menempuh jalan tengah antara monism-Ibn Taimiyah menyatakan bahwa Ibn ‘Arabi (meninggal 1240) telah berbuat keliru karena menganut monism-dan antropomorfisme. Sedang Ibn ‘Athaillah menuduh Ibnu Taimiyah melakukan antropomorfisme. Kalau kita lihat ke Kitab tentang Kearifan, yang amat penting untuk mengapresiasi Ibn ‘Abbad, maka akan semakin jelas betapa Ibn ‘Athaillah telah menempuh jalan itu.
Kitab Al-Hikam barangkali merupakan karya terawal Ibn ‘Athaillah, dan tak pelak lagi tetap merupakan kitabnya yang paling terkenal. Nwiya menyebutkan “kitab doa resmi” tarikat itu; karya itu telah digunakan sebagai buku pedoman tasawuf oleh tarikat-tarikat lain juga. Itu merupakan bagian dari gaya sastra yang berkembang selama abad keduabelas dan ketogeneses, “renaisan” tasawuf menurut Nwiya.
Gaya ini kiranya timbul dari praktik sufi yang sudah berjalan lama, yaitu mengisahkan “kehidupan” seorang Syaikh besar dalam bentuk koleksi ucapan-ucapannya. Akhirnya para syaikh itu merekam apothegm (kata-kata singkat, tajam dan mengena) mereka sendiri dalam buku-buku mereka tersendiri. Abu Madyan dan Ibn ‘Arabi adalah dua orang sufi termahsyur yang menggunakan bentuk itu sebelum Ibn ‘Athaillah. Sedangkan Ibn ‘Athaillah hampir pasti mengenal gaya itu seperti yang telah dikembangkan salah seorang pendahulunya.
Kitab Al-Hikam merupakan sebuah kitab doa, namun bukan semata-mata pujian, permohonan atau penyesalan (tobat). Juga merupakan doa yang bersifat bertanya dan tajam yang tak pernah sama sekali mendengar jawaban puncaknya dan tak pernah benar-benar sampai pada tujuan yang menyenangkan. Segala yang dicari sang pencari merupakan sebab bagi berlanjutnya pencarian itu. Hikam merupakan percakapan dengan Allah dan sekaligus perbincangan dengan Allah. Dengan menggunakan tamsil Al-Quran dan terminology Asy’ariyyah yang dipadu dengan peringatan al-Junayd dan al-Muhasibi mengenai shahw, Ibn ‘Athaillah mengeksplorasi dua aspek misteri Allah.
Allah sepenuhnya transenden, namun Dia menjadikan dirinya dikenal oleh hamba-hamba-Nya tanpa mengaburkan perbedaan tak terbatas antara Pencipta dan makhluk. Pada zaman Ibn ‘Athaillah, senantiasa terjadi debat antara kaum sufi yang mengatakan bahwa persatuan substantial antara makhluk dan Pencipta bisa saja terjadi dalam apa yang disebut “kesatuan wujud” (wahdat al-wujud). Mereka yang berpendapat bahwa puncak kesatuan itu berupa puncak “penyaksian” atau kotemplasi (wahdat al-syuhud). Ibn ‘Athaillah mengajarkan konsep yang terakhir ini, dimana yang berkontemplasi dan yang jadi sasaran kontemplasi tetap mempertahankan identitas masing-masing.
Kehadiran Tuhan meliputi segala ciptaan, seperti Cahaya lelangit dan bumi (QS 24 : 35). Hakikat pengalaman mistis adalah semakin bertambahnya kemampuan untuk menangkap, (-melalui kegelapan nyata makhluk-makhluk itu keberadaan mereka sendiri. Ini merupakan proses yang tak pernah berakhir, yaitu proses menyingkap, melucuti ilusi imajinasi yang mengatakan bahwa objek tertentu dalam pengalaman biasa itu Tuhan Sendiri, padahal itu bukan Tuhan. Paradoksnya adalah, bahwa semakin seseorang merasa bahwa Tuhan itu dekat, maka dia semakin mengalami bahwa Dia itu jauh. Ketika Ibn ‘Athaillah dan Ibn ‘Abbad berbicara tentang “kepastian” dalam pengalaman religius, yang mereka maksudkan bukanlah keamanan. Yaitu keamanan yang kiranya hasil dari perasaan bahwa “segenap hukum” telah ditaati secara seksama, atau keamanan yang dapat terasakan ketika mengalami kegembiraan spiritual (basth, “pelapangan”).
Sebagaimana Nwiya menganalisis situasi, manusia diciptakan bukan untuk bergembira, dan juga bukan untuk berduka (qabdh, “penyempitan”), namun karena Allah. Karena itu Allah tidak pernah membiarkan seseorang dalam salah satu dari dua keadaan ini, namun memperlakukan hamba-hamba-Nya kadang melewati suka-cita dan kadang melewati duka-cita. “Tiap-tiap kedatangan merupakan keberangkatan baru,” dan “setiap penyingkapan merupakan panggilan untuk menerobos tabir-tabir lain.52
Selama abad-abad itu, Kitab Al-Hikam memberikan inspirasi kepada banyak ulasan. Salah satunya yang paling popular adalah Tanbih (instruksi, petunjuk) karya Ibn ‘Abbad. Kita akan melihat dengan eksplisit lagi tulisan-tulisan Ibn ‘Abbad nanti, namun kelihatannya memadai untuk menyebutkan di sini sebagai ciri penting uraian kembali dan perenungan pribadinya tentang Hikam, sehingga dapat menyoroti kontinuitas pikiran dan ruh dari satu generasi Syadziliyah ke generai selanjutnya. Ibn ‘Abbad mengutip Hikam dalam Surat-Suratnya, lebih sering dibanding yang dikutipnya dari karya lain, dengan kekecualian Al-Quran. Pengulasan-pengulasan setelah Ibn ‘Abbad terus membuktikan kekuatan dan pengaruh Hikam dan Tanbih karya Ibn ‘Abbad, sebab banyak diantara mereka mengutipnya seakan dia itu otoritas terkemuka. Salah satu dari pengulas belakangan itu, Ahmad Zarruq (meninggal 1493), mengatakan bahwa Hikam bagi tasawuf adalah seperti mata bagi tubuh. Ia mengandung empat jenis pengetahuan yang penting bagi ajaran sufi: perintah dan peringatan, kezuhudan, pengetahuan tasawuf yang diperoleh dan dipompakan, serta ilmu penyingkapan.53
Ditulis antara 1370 dan 1372 atas permintaan dua sahabat karib, wacana meditatif Ibn ‘Abbad mengenai Hikam mengungkapkan beberapa tema pokok. Landasan pikiran adalah gagasan lipat dua tentang transendensi Allah dan akibat wajahnya, kehampaan segala yang bukan Allah. Prinsip ini segera menimbulkan dilema moral. Perbuatan manusia sepenuhnya tidak efektif. Selanjutnya, memandang perbuatan, baik dan buruk, sebagai efektif, berarti menyatakan bahwa makhluk bersaing dengan penciptanya. Karena itu Ibn ‘Abbad amat menekankan kebajikan pasif seperti pasrah, tawakal, percaya penuh kepada rencana dan petunjuk Allah. Inilah yang oleh Ibn ‘Abbad disebut “pembersihan petunjuk diri”. Pasrah adalah realisasi praktis penilaian teosentris penuh yang menyangkal bahwa makhluk mampu meneguhkan sang “Pencipta”.54
Dalam bentuknya yang ekstrim, pasrah dapat meninggalkan individu benar-benar sendiri dan tanpa berpaling kepada masyarakat untuk mendapatkan dukungan. Meskipun menekankan kemahakuasaan Tuhan, Ibn Abbad dengan tegas membela kemerdekaan manusia. Nanti kita akan kembali kebeberapa tema dari Tanbih ketika tema-tema itu secara khusus berhubungan dengan soal-soal yang diangkat dalam Surat-Suratnya ini.55
Sebelum melihat kehidupan dan karya-karya Ibn ‘Abbad dengan latar belakang tasawuf Afrika Utara abad keempatbelas, posisi Ibn ‘Athaillah dalam, memandang evolusi Tasawuf Syadziliyah bisa diikhtisarkan seperti ini. Ibn ‘Atha’ memandang Syadzili sebagai orang yang ditetapkan Allah sebagai pewaris Nabi Muhammad. Allah telah menegaskan universalitas peranan perantara Syadzili, melalui karamah-karamah yang pada gilirannya menunjukkan posisi sang syaikh sebagai poros-spiritual alam semesta. Setiap wali meneruskan dan memanifestasikan-secara esoteris yang hanya dapat dijangkau oleh mereka yang sudah ditahbiskan-Cahaya seperti yang telah dimanifestasikan para nabi di tengah-tengah masyarakat.
Kemudian Mursi mewarisi peranan-spiritual quthb dari Syadzili, dan lahirlah Tarikat Syadziliyah. Ibn ‘Athaillah dan juga Ibn ‘Abbad tak pernah mengaku memiliki status quthb. Namun semua orang sepakat bahwa tulisan-tulisan mereka menempatkan mereka berdua sebagai peserta pendiri tarikat itu.56
Pendek kata, kalau di dalam Kristen, spiritualitas yang mengandung beraneka nada dan tekanan (seperti apostolik, mendicant, kontemplatif, cenobitic), mengembangkan dan mewujudkan ruh berbagai ordo religius (seperti seperti Benedictine, Dominican, Jesuit, Vincentian, Paulist, dan lain-lain), maka tarikat Syadziliyah mewakili salah satu di antara banyak spiritualitas Islam. Ibn ‘Abbad memberikan satu contoh konkret spiritualitas Islam. Ibn ‘Abbad memberikan satu contoh konkret spiritualitas itu dalam tindakan.
(bersambung)