Sifat Kedua Yang Wajib Bagi Allah – Qidam – Terjemah Kifayat-ul-‘Awam
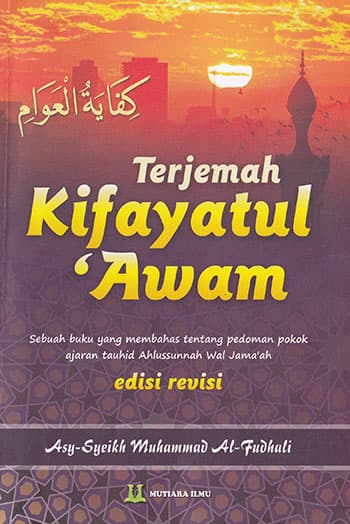
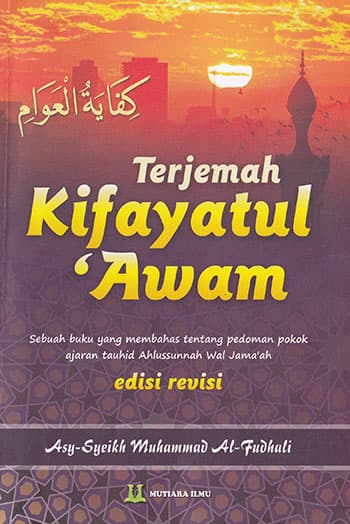
الصِّفَةُ الثَّانِيَةُ الْوَاجِبَةُ لَهُ تَعَالَى الْقِدَمُ وَ مَعْنَاهُ عَدَمُ الْأَوَّلِيَّةِ.
“Sifat kedua yang wājib bagi Allah s.w.t. adalah Qidam dan ma‘nanya adalah: Tidak berpermulaan.”
فَمَعْنَى كَوْنِ اللهِ تَعَالَى قَدِيْمًا لَا أَوَّلَ لِوُجُوْدِهِ بِخِلَافِ زَيْدٍ مَثَلًا فَوُجُوْدُهُ لَهُ أَوَّلٌ وَ هُوَ خَلْقُ النُّطْفَةِ الَّتِيْ خُلِقَ مِنْهَا.
“Maka ma‘na keadaan Allah itu Qidam adalah: Tidak ada permulaan bagi wujūd-Nya. Lain halnya dengan si Zaid umpamanya, maka wujūdnya itu memiliki permulaan yaitu penciptaan nuthfah (setetes air) yang dia diciptakan darinya.”
وَ اخْتُلِفَ هَلِ الْقَدِيْمُ وَ الْأَزَلِيُّ بِمَعْنًى وَاحِدٍ أَوْ مُخْتَلِفَانِ.
“Dan diperselisihkan apakah qadīm dan azalī itu berma‘na satu ataukah berbeda”.
فَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ عَرَّفَهُمَا بِقَوْلِهِ مَا لَا أَوَّلَ لَهُ وَ يُفَسِّرُ مَا بِشَيْءٍ أَيْ الْقَدِيْمُ وَ الْأَزَلِيُّ الشَّيْءُ الَّذِيْ لَا أَوَّلَ لَهُ فَيَشْمَلُ ذَاتَ اللهِ وَ جَمِيْعَ صِفَاتِهِ.
“Maka barang siapa yang berpendapat dengan yang pertama (berma‘na satu) maka dia mendefinisikan keduanya itu dengan perkataan (مَا لَا أَوَّلَ لَهُ) dan dia mentafsirkan (مَا) dengan “sesuatu” dalam arti qadīm dan azalī adalah sesuatu yang tidak memiliki permulaan”. “Maka sesuatu itu mencakup akan dzāt Allah dan semua sifat-sifatnya.”
وَ مَنْ قَالَ بِالثَّانِيْ عَرَّفَ الْقَدِيْمَ بِقَوْلِهِ مَوْجُوْدٌ لَا أَوَّلَ لَهُ وَ عَرَّفَ الْأَزَلِي بِمَا لَا أَوَّلَ لَهُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ مَوْجُوْدًا أَوْ غَيْرَ مَوْجُوْدٍ فَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الْقَدِيْمِ.
“Dan barang siapa yang berpendapat dengan kedua (ya‘ni berbeda) maka dia mendefinisikan qadīm dengan perkataan (مَوْجُوْدٌ لَا أَوَّلَ لَهُ) “maujūd yang tidak memiliki permulaan”. Dan dia mendefinisikan azalī dengan (مَا لَا أَوَّلَ لَهُ) bersifat lebih umum di mana keadaannya bisa maujūd atau tidak maujūd. Maka azalī itu lebih umum daripada qadīm.”
فَيَجْتَمِعَانِ فِيْ ذَاتِهِ تَعَالَى وَ صِفَاتِهِ الْوُجُوْدِيَّةِ فَيُقَالُ لِذَاتِهِ تَعَالَى أَزَلِيَّةٌ وَلِيَّةٌ وَ لِقُدْرَتِهِ تَعَالَى أَزَلِيَّةٌ.
“Maka berkumpullah keduanya (qadīm dan azalī) pada dzāt Allah s.w.t. dan pada sifat-sifatnya yang maujūd. Maka dikatakan bagi dzāt Allah s.w.t. itu azalī (dan qadīm) dan bagi qudrat Allah s.w.t. (dikatakan juga) azalī (dan qadīm).”
وَ يَنْفَرِدُ الْأَزَلِيُّ فِي الْأَحْوَالِ كَكَوْنِ اللهِ تَعَالَى قَادِرًا عَلَى الْقَوْلِ بِهَا فَإِنَّ كَوْنَ اللهِ تَعَالَى قَادِرًا يُقَالُ لَهُ أَزَلِيٌّ عَلَى هذَا الْقَوْلِ وَ لَا يُقَالُ لَهُ قَدِيْمٌ لِمَا عَرَفْتَ أَنَّ الْقَدِيْمَ لَا بُدَّ فِيْهِ مِنَ الْوُجُوْدِ وَ الْكَوْنُ قَادِرً لَمْ يَرْتَقِ إِلَى دَرَجَةِ الْوُجُوْدِ لِأَنَّهُ حَالٌ.
“Dan azalī itu menyendiri pada aḥwāl (sifat-sifat ma‘nawiyyah) seperti keadaan Allah s.w.t. itu berkuasa berdasarkan pendapat (yang setuju) dengan aḥwāl itu. Maka sesungguhnya keadaan Allah s.w.t. itu berkuasa dikatakan baginya azalī berdasarkan pendapat ini (pendapat kedua) dan tidak dikatakan baginya qadīm karena apa yang telah anda ketahui bahwa qadīm itu haruslah ada padanya berupa wujūd sedangkan keadaan berkuasa tidak naik ke derajat wujūd karena dia adalah ḤĀL.”
وَ الدَّلِيْلُ عَلَى قِدَمِهِ تَعَالَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدِيْمًا كَانَ حَادِثًا لِأَنَّهُ لَا وَاسِطَةَ بَيْنَ الْقَدِيْمِ وَ الْحَادِثِ فَكُلُّ شَيْءٍ انْتَفَى عَنْهُ الْقِدَمُ ثَبَتَ لَهُ الْحُدُوْثُ.
“Dan dalil atas qidamnya Allah s.w.t. adalah sesungguhnya Dia jika tidak qadīm maka dia itu ḥādits (baru) karena tidak ada perantara (sesuatu yang di tengah-tengah) antara qadīm dan ḥādits. Maka setiap sesuatu yang terhapus dari qidam, tetaplah baginya baru.”.
وَ إِذَا كَانَ تَعَالَى حَادِثًا افْتَقَرَ إِلَى مُحْدِثٍ يُحْدِثُهُ وَ افْتَقَرَ مُحْدِثٍ وَ هكَذَا.
“Dan jika Allah s.w.t. itu ḥādits niscaya Dia membutuhkan kepada Muḥdits yang menjadikan-Nya baru dan Muḥdits-Nya pun membutuhkan kepada Muḥdits (yang lain) dan begitu seterusnya.”
فَإِنْ لَمْ تَقِفْ الْمُحْدِثُوْنَ لَزِمَ التَّسَلْسُلُ وَ هُوَ تَتَابُعُ الْأَشْيَاءِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ وَ التَّسَلْسُلُ مُحَالٌ.
“Maka jika tidak pernah berhenti Muḥdits-muḥdits itu, lazimlah tasalsul ya‘ni berturut-turutnya segala sesuatu secara satu persatu kepada apa-apa yang tidak ada penghabisannya dan tasalsul itu adalah mustaḥīl.”
وَ إِنِ انْتَهَت الْمُحْدِثُوْنَ بِأَنْ قِيْلض إِنَّ الْمُحْدِثَ الَّذِيْ أَحْدَثَ اللهَ أَحْدَثَهُ اللهُ لَزِمَ الدَّوْرُ وَ هُوَ تَوَقُّفُ شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ.
“Dan jika berhenti muḥdits-muḥdits itu dengan dikatakan: sesungguhnya muḥdits yang menjadikan Allah itu telah dijadikan (terlebih dahulu) oleh Allah maka lazimlah DAUR ya‘ni bergantungnya sesuatu atas sesuatu yang lain yang (juga) telah bergantung atasnya.”
Daur itu bisa terjadi dengan hanya satu wāsithah (perantara) kalau muḥditsnya hanya dua atau lebih dari satu wāsithah dengan sebab muḥditsnya lebih dari dua.
Contoh daur yang wāsithah-nya cuma satu adalah: “Zaid menjadikan ‘Amar dan ‘Amar menjadikan Zaid”. Ini menunjukkan bahwa ‘Amar bergantung kepada Zaid (karena Zaid menjadikannya) dan Zaid pun bergantung kepada ‘Amar (karena ‘Amar telah menjadikannya). Maka jelaslah arti dari “Bergantungnya sesuatu atau sesuatu yang lain yang juga bergantung atasnya.” Atau sesuai dengan contoh di sini” ‘Amar bergantung atas si Zaid di mana dia (Zaid) juga bergantung kepada ‘Amar.”
Pada contoh tersebut wāsithah-nya satu ya‘ni ‘Amar karena yang jadi Muḥdits dua ya‘ni Zaid dan ‘Amar.
Adapun contoh Daur yang wāsithah-nya lebih dari dua adalah Zaid menjadikan ‘Amar, ‘Amar menjadikan Bakar dan Bakar menjadikan Zaid.”
Maka di sini Bakar bergantung kepada Zaid dengan perantaraan bergantungnya dia (si Bakar) kepada ‘Amar yang juga bergantung kepada si Zaid, sedangkan keadaan Zaid sendiri juga bergantung kepada Bakar.
Pada contoh tersebut wāsithah-nya lebih dari satu ya‘ni ‘Amar dan Bakar karena muḥditsnya lebih dari dua ya‘ni Zaid, ‘Amar dan Bakar.
فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ للهِ تَعَالَى عَزَّ وَ جَلَّ مُحْدِثٌ كَانَ مُتَوَقِّفًا عَلَى هذَا الْمُحْدِثِ وَ قَدْ فَرَضْنَا أَنَّ اللهَ أَحْدَثَ هذَا الْمُحْدِثَ فَيَكُوْنُ الْمُحْدِثُ مُتَوَقِّفًا عَلَى اللهِ.
“Maka sesungguhnya jika Allah ta‘ālā ‘azza wa jalla itu memiliki Muḥdits niscaya Allah itu bergantung kepada Muḥdits ini, sedangkan kita telah mewajibkan bahwa Allah yang menjadikan muḥdits ini maka muḥdits tersebut bergantung (juga) kepada Allah.”
وَ الدَّوْرُ مُحَالٌ أَيْ لَا يُتَصَوَّرُ فِي الْعَقْلِ وُجُوْدُهُ وَ الَّذِيْ أَدَّى إِلَى الدَّوْرِ وَ التَّسَلْسُلِ الْمُحَالَيْنِ فَرْضُ حُدُوْثِهِ تَعَالَى عَزَّ وَ جَلَّ فَيَكُوْنُ حُدُوْثُهُ تَعَالَى مُحَالًا لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُؤَدِّيْ إِلَى الْمُحَال مُحَالٌ.
“Dan daur itu adalah mustaḥīl dalam arti tidak didapatkan pada akal akan wujūdnya. Dan sesuatu yang menghantarkan kepada Daur dan Tasalsul yang mustahil keduanya adalah pewajiban barunya Allah ta‘ālā ‘azza wa jalla, maka barunya Allah s.w.t. adalah mustaḥīl karena setiap sesuatu yang menyebabkan kepada yang mustaḥīl adalah mustaḥīl.”
فَحَاصِلُ الدَّلِيْلُ أَنْ تَقُوْلَ لَوْ كَانَ اللهُ غَيْرَ قَدِيْمٍ بِأَنْ كَانَ حَادِثًا لَافْتَقَرَ إِلَى مُحْدِثٍ فَيَلْزَمُ الدَّوْرُ أَوِ التَّسَلْسُلُ وَ هُمَا مُحَالَانِ فَيَكُوْنُ حُدُوْثُهُ مُحَالًا فَثَبَتَ قِدَمُهُ وَ هُوَ الْمَطْلُبُ.
“Maka kesimpulan dalīl itu adalah bahwa anda berkata: Kalau Allah itu tidak qadīm berarti dia baru (hadits) niscaya dia membutuhkan kepada muḥdits maka lazimlah Daur dan Tasalsul dan keduanya adalah mustaḥīl. Maka jadilah barunya Allah itu mustaḥīl maka tetaplah qidamnya dan dialah yang dituntut.”
وَ هذَا الدَّلِيْلُ الْإِجْمَالِيُّ لِقِدَمِهِ تَعَالَى وَ بِهِ يَخْرُجُ الْمُكَلَّفُ مِنْ رِبْقَةِ التَّقْلِيْدِ الَّذِيْ يُخْلِدُ صَاحِبَهُ فِي النَّارِ عَلَى رَأْيِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ وَ السَّنُوْسِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ.
“Dan inilah dalīl ijmālī bagi qidamnya Allah s.w.t. dan dengannya keluarlah si mukallaf dari kekangan taqlīd yang mengekalkannya di dalam neraka sebagaimana pendapat Ibnu-ul-‘Arabī dan Sanūsī sebagaimana yang telah terdahulu (keterangannya).”