Qadha’ dan Fidyah – Panduan Puasa Terlengkap (5/5)
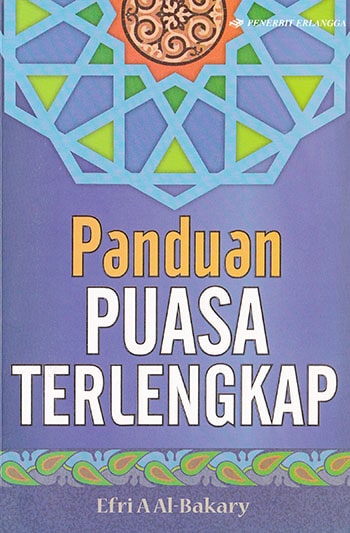
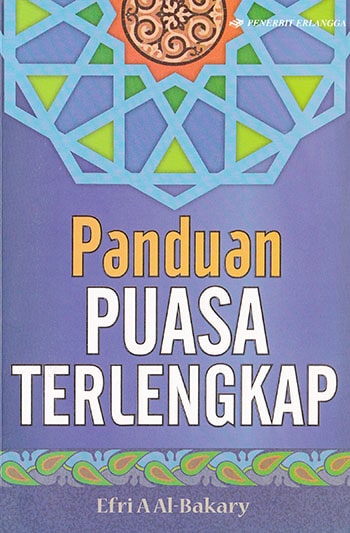
Qadhā’ adalah ganti atau membayar kewajiban yang ditinggalkan. Mengqadhā’ puasa yaitu membayar puasa yang ditinggalkan, dapat dilakukan sepanjang hari, kapan saja di bulan selain bulan Ramadhān. Tapi sebagian ‘ulamā’ menetapkan bahwa mengqadhā’ puasa Ramadhān yang ditinggalkan wajiblah beriring-iringan, tak boleh berselang-selang. Tetapi sebagian ‘ulamā’ lain membolehkan berselang-selang.
Diriwayatkan oleh ad-Dāruquthnī dari Ibn ‘Umar bahwasanya Rasūlullāh s.a.w. bersabda:
“Qadhā’ Ramadhān boleh berselang dan boleh pula dengan beriring-iringan.”
Apabila seseorang meninggalkan puasa lima hari umpamanya, maka ia boleh mengqadhā’nya sehari, berselang, dan boleh juga terus-menerus kelima hari asal dalam tahun itu juga menjelang Ramadhān yang berikutnya.
Disebutkan dalam al-Baḥar, bahwa Dāūd berkata: “Hendaklah orang yang mengqadhā’ puasanya menyesuaikan waktu qadhā’ dengan waktu meninggalkan puasa. Jika ditinggalkan puasa itu di awal bulan, hendaklah ia mengqadhā’nya di awal bulan pula.”
Mengqadhā’ puasa Ramadhān tidak wajib dilaksanakan segera namun boleh diakhirkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhārī dari ‘Ā’isyah: “Atasku ada puasa Ramadhān, maka aku tidak mengqadhā’nya sampai datang bulan Sya‘bān tahun berikutnya.”
Apabila seseorang tidak meng-qadhā’ sampai menjelang bulan Ramadhān yang berikutnya, maka menurut sebagian ‘ulamā’ diwajibkan atas orang itu memberi fidyah (denda) selain tetap wajib meng-qadhā’ puasanya. Tetapi ‘ulama’ Ḥanafiyyah tidak mewajibkan fidyah, baik diakhirkan karena ‘udzur, atau bukan. Mālik, asy-Syāfi‘ī, Aḥmad, dan Isḥāq sependapat dengan ‘ulamā’ Ḥanafiyyah. Dalīl yang dapat dipegang untuk pendapat ini tidak ada. Maka pendapat ‘ulamā’ Ḥanafiyyah yang hak dalam hal ini. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzī dari Ibn ‘Umar, bahwa Rasūlullāh s.a.w. bersabda:
“Barang siapa meninggal dan ada puasa Ramadhān yang telah ia ditinggalkan, maka hendaklah diberi makan atas namanya sehari seorang miskin.”
Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbās: “Apabila seseorang lelaki sakit dalam bulan Ramadhān, kemudian ia meninggal dunia, padahal ia tidak berpuasa, diberi makanlah atas namanya (difidyahkan). Tak ada qadhā’ atasnya, Dan jika puasa nadzar hendaklah diqadhā’kan oleh walinya.”
Dari hadits di atas, ‘ulamā’ mewajibkan fidyah atas orang yang meninggalkan puasa yang tidak dapat mengqadhā’nya sebelum ia meninggal dunia. Ibnu ‘Abbās berkata: “Jika ia meninggalkan puasa tanpa ‘udzur, wajiblah difidyahkan dan jika dengan ‘udzur, maka tidak.”
Asy-Syāfi‘ī berkata: “Jika ia tidak mengqadhā’nya hingga sampai setahun dengan ketiadaan ‘udzur, wajiblah difidyahkannya dan jika ada ‘udzur, maka tidak.”
An-Nakha‘ī berkata: “Tidak wajib atas mereka memberikan fidyah, karena Tuhan menyuruh mengqadhā’nya dan tidak menyebut urusan fidyah.”
Ibn ‘Abd-il-Ḥaqq berkata dalam al-Aḥkām: “Tak ada hadits yang shaḥīḥ yang menyuruh kita memberi fidyah untuk puasa si mati.”
Kaffārat adalah ganjaran atau hukuman. Kaffārat jatuh pada seseorang jika ia melakukan persetubuhan secara sengaja di bulan puasa. Namun jika ia tak sengaja atau lupa, maka tak mengapa. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah dari Ibn ‘Abbās. Rasūlullāh s.a.w. bersabda:
“Bahwasanya Allah tiada menyalahkan ummatku karena mengerjakan sesuatu kesalahan (kesilapan), karena lupa dan karena dipaksa.”
Ada tiga pendapat tentang orang yang bersetubuh dalam bulan Ramadhān:
Memeluk istri atau merangkulnya lalu keluar mani, tidak mewajibkan kaffārat. Demikian pulalah pendapat Abū Ḥanīfah: “Setiap macam inzāl (keluar mani) mewajibkan kaffārat, kecuali inzāl karena mengulang-ulang pandang, tak ada kaffārat dan tak ada qadhā’.”
Tetapi Mālik, Abū Tsaur mewajibkan meng-qadhā’ dan kaffārat. Pendapat ini dinukilkan juga dari ‘Athā’, al-Ḥasan, Ibnu Mubārak, dan Isḥāq. Mereka berpendapat bahwa kaffārat wajib dilakukan untuk mengganti puasa yang rusak karena bersetubuh bukan dalam faraj (kemaluan).
‘Ulamā’ berpendapat, jima‘ (persetubuhan) yang sempurna ialah jima‘ dalam keadaan sadar. Karenanya orang yang berjima‘ dalam keadaan lupa tidak rusak puasanya. Kaffārat ini sendiri hanya berlaku bagi puasa Ramadhān. Sedangkan bagi puasa sunnah tidak berlaku.
Mengenai pasal ini, ada baiknya seorang istri yang hendak melakukan puasa sunnah meminta idzin terlebih dahulu kepada suami dikarenakan hal ini menyangkut suami juga. Ada hak istri atas suami dan ada hak suami atas istri. Jika tidak meminta idzin atau tidak memberi tahu suami, ditakutkan akan ada perselisihan yang tidak baik.
Rasūlullāh s.a.w. bersabda: “Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, kemudian dia tidak menyambutnya sehingga malam itu suaminya tidur dalam keadaan marah terhadapnya maka para malaikat akan melaknatnya hingga waktu Shubuḥ.” (Muttafaqun ‘Alaih).
Sabda Rasūlullāh s.a.w.: “Seandainya aku (dibolehkan) memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain maka pasti aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya.” (HR. Muslim).
Untuk menghindari penyalahan hak inilah harus ada idzin suami bagi istri yang hendak berpuasa sunnah. Sang suami juga janganlah egois, ia hendaknya mendorong dan memberikan idzin sebab istri yang shālihaḥ dan gemar beribadah akan menjadi ladang pahala juga baginya kelak.
Rasūlullāh s.a.w. bersabda: “Tidak halal bagi seorang istri berpuasa sementara suaminya ada bersamanya kecuali dengan idzinnya.” (HR. Bukhārī dan Muslim). Sementara di dalam lafazh Aḥmad disebutkan: “Tidaklah seorang istri berpuasa satu hari saja sementara suaminya ada bersamanya kecuali dengan idzinnya kecuali puasa Ramadhān.”