Pernikahan dan Kehidupan Beliau s.a.w. Sebelum Bi’tsah – Nurul Yaqin (1/2)
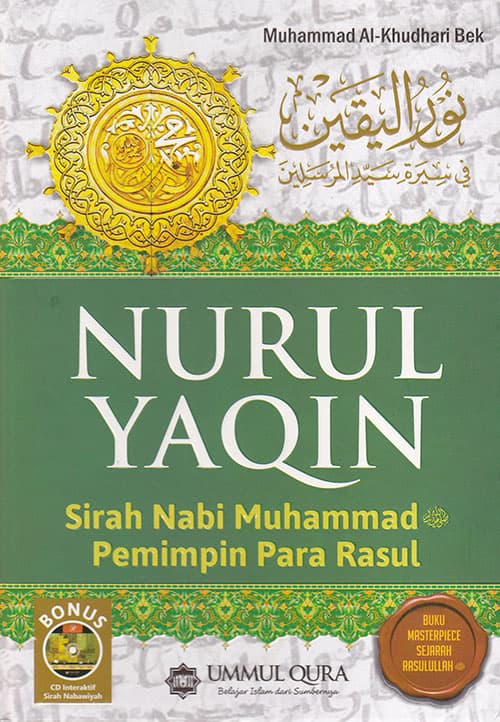
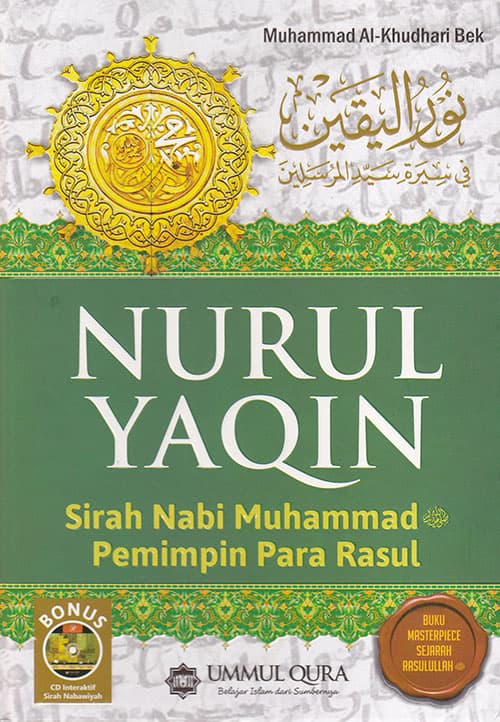
PASAL 3
Ketika kedua pekerjanya telah sampai di Makkah dan melihat keuntungannya yang besar, Khadījah merasa tertarik dengan al-Amīn s.a.w. lalu mengutus seseorang untuk meminangkan Beliau untuk dirinya. Ketika itu usianya 40 tahun, ia seorang bangsawan paling mulia di kalangan Quraisy dan memiliki kekayaan yang melimpah. Lalu al-Amīn s.a.w. bersama paman-pamannya berangkat menuju rumah paman Khadījah, ‘Amru bin Asad, lalu melamarnya dengan perantara pamannya, Abū Thālib. Kemudian ia (Khadījah) dinikahkan oleh pamannya. Pada hari itu Abū Thālib berkhutbah, yang isinya:
“Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai keturunan Ibrāhīm, benih dari Ismā‘īl, anak cucu Ma‘ad dan keturunan Mudhar, menjadikan kita sebagai pemelihara dan pengurus Ka‘bah, menjadikan rumah yang diziarahi, haram, dan aman bagi kita, serta menjadikan kita sebagai pemimpin manusia.
Kemudian, anak saudaraku, Muḥammad bin ‘Abdullāh, ini tidak ada yang menyamai kehormatan, keutamaan, dan kepandaiannya. Meskipun ia sedikit hartanya, tapi bukankah harta akan lenyap, urusan akan berubah, dan harta merupakan pinjaman yang harus dikembalikan (kepada Pemilik-nya, Allah). Demi Allah, setelah ini ia memiliki berita yang besar dan gagasan yang mulia. Perkenankan ia melamar putri kalian dan menginginkan wanita mulia kalian, Khadījah. Ia akan memberikan mahar sekian untuknya.” (282)
Dengan ini maka sempurnalah pernikahannya. Sebelumnya, Khadījah pernah menikah dengan Abū Hālah. Ia telah meninggal dunia dan memiliki seorang putra dari Khadījah, namanya Hālah. Dan ia menjadi anak tiri baginda Nabi s.a.w.
Ketika Nabi merumur 35 tahun terjadi banjir bandang di kota Makkah yang menyebabkan tembok-tembok Ka‘bah roboh. Setelah sebelumnya juga hancur sebagian karena tragedy kebakaran. Oleh sebab itu, kaum Quraisy ingin menghancurkannya sekalian untuk direnovasi. Ketika itu Ka‘bah merupakan bangunan tinggi melebihi (tinggi) manusia. Maka berkumpullah para kabillah untuk merenovasinya, tapi mereka merasa segan untuk menghancurkannya karena kemuliaan Ka‘bah di hati mereka. Maka berkatalah al-Walīd bin Mughīrah kepada mereka: “Kalian ingin menghancurkannya dalam rangka memperbaiki atau merusak?” Mereka menjawab: “ Untuk memperbaiki.” Lalu ia berkata: “Sesungguhnya Allah tidak akan membinasakan orang-orang yang melakukan perbaikan.”
Lalu ia memulai merubuhkan Ka‘bah dan orang-orang mengikutinya. Mereka merubuhkannya sampai pondasi pertama yang dahulu dibangun oleh Nabi Ismā‘īl a.s. Pada pondasi itu mereka menemukan lembaran-lembaran yang berisi kata-kata hikmah. Inilah adat yang biasa dilakukan oleh orang yang membangun pertama kali sebuah bangunan terkenal sebagai tadzkirah (pengingat) untuk generasi selanjutnya mengenai amalan pendahulu mereka.
Merekapun mulai merenovasi Ka’bah dengan menggunakan biaya yang bukan berasal dari harta hasil pelacuran dan bukan pula harta riba. Para pemuka-pemuka Quraisy pun ikut memikul batu-batu di atas pundak mereka. Al-‘Abbās dan Rasūlullāh adalah termasuk yang mengangkut batu-batu itu. (293) sementara arsitek dari bangunan Ka‘bah yang direnovasi ini adalah sesorang arsitek dari Romawi bernama Baqum. Setiap rukun (sudut) bangunan Ka‘bah dikhususkan untuk sekelompok tokoh tertentu. Mereka mengangkut batu-batu ke rukun tersebut, lalu membangunnya. Dalam proses renovasi itu, ternyata mereka kekurangan dana halal untuk menyelesaikannya sesuai dengan pondasi yang dibangun Nabi Ismā‘īl a.s., lalu mereka mengeluarkan batu-batu dari pondasinya dan hanya membangun tembok pendek sebagai tanda bahwa itu termasuk bagian Ka‘bah. Setelah renovasi selesai, tinggi Ka‘bah mencapai 18 hasta. Ini berarti ditambah 9 hasta dari tinggi semulanya. Bagian pintunya diletakkan lebih tinggi dari tanah sehingga tidak bisa dimasuki kecuali dengan tangga.
Ketika mereka hendak meletakkan Ḥajar Aswad ke tempatnya semula maka para pemuka kabilah itu berselisih mengenai siapa yang akan meletakkannya. Mereka terus berselisih sampai nyaris memicu api peperangan. Perselisihan ini terus berlanjut hingga empat malam. Pada saat itu orang yang paling tua di antara kaum Quraisy yakni Abū Umayyah bin Mughīrah al-Makhzūmī, paman Khālid bin Walīd, berkata kepada mereka untuk menengahi: “Wahai kaumku, janganlah kalian berselisih! Tunjukkanlah seseorang di antara kalian yang kalian ridhai keputusannya.”
Merekapun berkata: “Kita akan menyerahkan urusan ini kepada orang yang pertama kali masuk Masjid-il-Ḥarām.” Ternyata orang yang pertama masuk Masjid-il-Ḥarām ialah Muḥammad s.a.w., al-Amīn. Maka tenteramlah hati semua orang atas pilihan itu karena mereka mengetahui sifat amanah dan kejujuran Beliau s.a.w. Mereka berkata: “Inilah al-Amīn yang kami ridai, inilah Muḥammad.” Karena mereka biasa menyerahkan keputusan kepada baginda Nabi ketika tidak menemukan jalan keluar. Setelah mereka memberitahukan kepada Muḥammad bahwa dialah orang yang terpilih untuk memutuskan perkara mereka, maka Beliau s.a.w. meletakkan selendangnya dan berkata: “Setiap kepala kabilah hendaknya memegang ujung selendangnya.” Kemudian beliau meletakkan Ḥajar Aswad di tengah selendang dan memerintahkan mereka untuk mengangkatnya sampai ke tempatnya lalu Beliau s.a.w. yang meletakkannya di tempat asalnya. Demikianlah sengketa tersebut diselesaikan. Hal semacam ini sering menyebabkan pecahnya pertempuran antar orang ‘Arab seandainya Allah tidak memberikan kepada mereka seorang yang cerdas semisal Abū Umayyah yang menunjukkan mereka kepada kebaikan, dan juga seorang yang bijaksana semisal Nabi Muḥammad s.a.w. yang dapat memutuskan perkara dengan apa yang mereka ridhai.
Perselisihan kaum Quraisy seperti ini tidaklah mengherankan karena Baitullāh merupakan qiblat bangsa ‘Arab dan Ka‘bah tempat mereka berhaji. Maka dari itu, setiap pekerjaan yang dilakukan demi Ka‘bah menjadi mulia dan memiliki kebanggaan tersendiri, dan memang ia merupakan rumah pertama yang dijadikan oleh Allah menjadi tempat ibadah berdasarkan persaksian al-Qur’ān: “Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia ialah Baitullāh yang di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqām Ibrāhīm, barang siapa memasukinya (Baitullāh itu) menjadi amanlah dia.” (Āli-‘Imrān: 96-97)
Kabilah yang diamanahi untuk mengatur urusan Ka‘bah setelah anaknya Ismā‘īl pada mulanya ialah kabilah Jurhum. Namun, karena mereka membangkang dan berbuat zhālim terhadap orang-orang yang masuk Makkah maka kabilah Khuzā‘ah sepakat untuk mengusir mereka dari Baitullāh. Setelah itu, kepengurusan Ka‘bah dipegang oleh Bani Khuzā‘ah selama beberapa masa. Kemudian jabatan ini diambil oleh Quraisy pada masa Qushay bin Kilāb, dan oleh karenanya mereka aman di negerinya karena kabilah-kabilah ‘Arab memang segan kepadanya. Jika mereka berlindung kepada Qushay maka ia merupakan benteng yang kuat dan aman bagi mereka dari gangguan orang-orang jahat. Allah s.w.t. menganugerahkan hal ini kepada mereka sebagaimana yang telah dijelaskan melalui firman-Nya:
Surat al-‘Ankabūt [29]: 67:
أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَ يُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ
“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri mereka) Tanah Suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok.”
Muḥammad s.a.w. tidak mewarisi apa-apa dari ayahnya, bahkan dia dilahirkan dalam keadaan yatim, miskin dan disusukan kepada Bani Sa‘ad. Ketika sampai pada usia yang cukup untuk bekerja maka Beliau mulai menggembala kambing bersama saudara-saudara sepersusuannya di daerah pedalaman. Begitu pula ketika kembali ke Makkah, beliau menggembalakan ternak milik penduduk kota Makkah dengan upah beberapa qirath emas sebagaimana yang telah dikisahkan oleh Imām al-Bukhārī dalam Shaḥīḥnya (304).
Tidak mengherankan jika para nabi melepaskan dirinya dari gemerlapnya kehidupan duniawi dan kesibukan-kesibukannya karena hal ini memang suatu keharusan bagi mereka. Seandainya mereka berada dalam kekayaan yang melimpah niscaya perkara duniawi akan melalaikannya dari (meraih) kebahagiaan ukhrawī yang abadi. Oleh sebab itu, kita pasti melihat semua syarī‘at ilāhī sepakat menganggap baik perbuatan zuhud terhadap dunia dan menjauhi kemewahannya. Kehidupan para nabi terdahulu merupakan saksi yang paling agung dalam hal ini. Nabi ‘Īsā a.s. adalah manusia yang paling zuhud terhadap dunia, begitu pula Nabi Mūsā dan Nabi Ibrāhīm a.s. sewaktu kecil mereka tidak hidup dalam kemewahan, tapi mereka hidup dalam kesederhanaan. Demikianlah hikmah yang paling agung dari Allah yang sengaja ditampakkan oleh Allah kepada nabi-nabiNya supaya mereka menjadi teladan bagi para pengikutnya dalam mencegah diri dari mengejar keduniawian. Karena perkara duniawi itu merupakan penyebab malapetaka dan musibah.
Selain itu, menggembalakan kambing atau domba bukan hanya dilakukan oleh Nabi Muḥammad s.a.w. Menggembalakan kambing juga mengandung hikmah yang sangat besar. Sebab, jika seseorang menggembalakan kambing atau domba selaku hewan yang paling lemah, niscaya hatinya akan dipenuhi dengan kasih-sayang dan jiwanya akan menjadi lemah-lembut. Oleh karena itu, ketika ia beralih untuk menuntun umat manusia maka ia telah memiliki modal utama yaitu dirinya terlepas dari sifat egois dan tidak ada kecenderungan untuk menganiaya sehingga ia menjadi orang yang mempunyai kondisi paling ideal untuk mengemban tugas berat ini.