Pembicaraan Mengenai Mukallaf – Terjemah Kifayat-ul-‘Awam
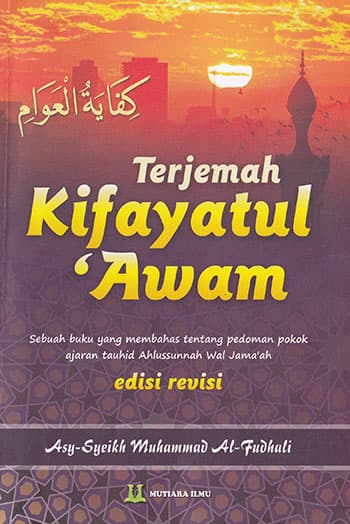
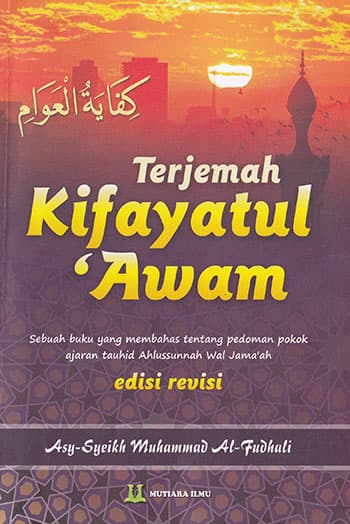
Perkataan Mushannif dengan (عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ) “atas setiap Mukallaf” maksudnya adalah manusia dan jinn, bukan malaikat karena malaikat tidak tergolong mukallaf atas qaul yang taḥqīq. Karena itulah Mushannif melambangkan Mukallaf itu dengan (مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى) “dari laki-laki dan perempuan” agar malaikat tidak termasuk karena malaikat tidak bersifat dengan laki-laki dan perempuan.
Batasan Mukallaf di sini adalah yang berakal serta sehat pancaindranya (meskipun hanya pendengaran dan penglihatan) serta sudah sampai da‘wah kepadanya. Maka tidaklah termasuk anak kecil (meskipun sudah mumayyiz), orang gila dan orang yang kehilangan pancaindra (seperti buta dan tuli) serta orang yang tidak sampai da‘wah padanya.
Maka bukanlah setiap dari mereka itu tergolong Mukallaf. Adapun adanya tuntutan beribadah dari anak kecil yang mumayyiz seperti shalat dan puasa bukan karena dia itu Mukallaf melainkan sebagai targhīb (penggemaran) baginya agar dia menjadi terbiasa dengan ibadah tersebut ….. In syā’ Allāh.
بَلْ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ إِنَّ فَهْمَ هذِهِ الثَّلَاثَةِ هِيَ نَفْسُ الْعَقْلِ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهَا أَيْ لَمْ يَعْرِفْ مَعْنَى الْوَاجِبِ وَ مَعْنَى الْمُسْتَحِيْلِ وَ مَعْنَى الْجَائِزِ فَلَيْسَ بِعَاقِلٍ.
“Bahkan telah berkata Imām Ḥaramain: Sesungguhnya pemahaman tiga perkara ini adalah akal itu sendiri. Maka barang siapa yang tidak mengetahuinya, artinya tidak mengetahui ma‘na wājib, ma‘na mustaḥīl dan ma‘na jā’iz maka dia itu orang yang tidak berakal.”
فَإِذَا قِيْلَ هُنَا الْقُدْرَةُ وَاجِبَةٌ للهِ كَانَ الْمَعْنَى قُدْرَةُ اللهِ لَا يُصَدِّقُ الْعَقْلُ بِعَدَمِهَا لِأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الَّذِيْ لَا يُصَدِّقُ الْعَقْلُ بِعَدَمِهِ كَمَا تَقَدَّمَ.
“Maka jika dikatakan di sini: Qudrat itu wājib bagi Allah”, maka ma‘nanya adalah: “Qudrat Allah itu, akal tidak membenarkan dengan ketiadaannya” karena wājib itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh akal dengan ketiadaannya sebagaimana telah terdahulu (keterangannya).”
وَ أَمَّا الْوَاجِبُ بِمَعْنَى مَا يُثَابُ عَلَى فُعِلِهِ وَ يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ فَهُوَ مَعْنًى آخَرُ لَيْسَ مُرَادًا فِيْ عِلْمِ التَّوْحِيْدِ فَلَا يَشْتَبِهْ عَلَيْكَ الْأَمْرُ.
“Adapun wājib dengan ma‘na: Sesuatu yang diberi pahala karena mengerjakannya dan diberi siksa karena meninggalkannya” maka dia adalah ma‘na lain yang tidak dimaksudkan dalam ‘Ilmu Tauḥīd, maka janganlah kamu samar atau bimbang atas perkara itu.”
نَعَمْ لَوْ قِيْلَ يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ اعْتِقَادُ قُدْرَةِ للهِ تَعَالَى كَانَ الْمَعْنَى يُثَابُ عَلَى ذلِكَ وَ يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِ ذلِكَ.
“Akan tetapi…. kalau dikatakan: Wājib atas mukallaf untuk meng-i‘tiqād-kan qudrat Allah ta‘ālā maka jadilah ma‘nanya “diberi pahala atas i‘tiqād itu dan diberi siksa karena meninggalkan i‘tiqād tersebut”.
فَفُرِّقُ بَيْنَ أَنْ يُقَالَ اِعْتِقَادُ كَذَا وَاجِبٌ وَ بَيْنَ أَنْ يُقَالَ الْعِلْمُ مُثَلًا وَاجِبٌ لِأَنَّهُ إِذَا قِيْلَ الْعِلْمُ وَاجِبُ للهِ تَعَالَى كَانَ الْمَعْنَى أَنَّ عِلْمَ اللهِ تَعَالَى لَا يُصَدِّقُ الْعَقْلُ بِعَدَمِهِ وَ أَمَّا إِذَا قِيْلَ اِعْتِقَادُ الْعِلْمِ وَاجِبٌ كَانَ الْمَعْنَى يُثَابُ إِنِ اعْتَقَدَ ذلِكَ وَ يُعَاقَبُ إِنْ لَمْ يَعْتَفِدْ.
“Maka dibedakan antara perkataan mereka: “i‘tiqād yang seperti ini …. adalah wājib” dan antara perkataan mereka: “‘Ilmu itu umpamanya adalah wājib karena jika dikatakan ‘Ilmu itu wājib bagi Allah ta‘ālā maka ma‘nanya adalah bahwa ‘ilmu Allah ta‘ālā itu, akal tidak membenarkan dengan ketiadaannya.
Dan jika dikatakan: Meng-i‘tiqād-kan ‘ilmu itu adalah wājib maka ma‘nanya adalah diberi pahala jika dia meng-i‘tiqād-kan yang demikian itu dan diberi siksa jika dia tidak meng-i‘tiqād-kannya.”
فَاحْرَصْ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَكُنْ مِمَّنْ قَلَّدَ فِيْ عَقَائِدِ الدِّيْنِ فَيَكُوْنَ إِيْمَانُكَ مُخْتَلِفًا فِيْهِ فَتَخْلُدُ فِي النَّارِ عِنْدَ مَنْ يَقُوْلُ لَا يَكْفِي التَّقْلِيْدُ.
“Maka berhati-hatilah atas perbedaan antara keduanya dan janganlah engkau menjadi di antara orang-orang yang bertaqlīd dalam ‘aqīdah-‘aqīdah agama, karena sebab itu maka jadilah imanmu masih diperselisihkan di dalamnya, lantas engkau kekal di dalam neraka, menurut orang yang berkata: “tidak cukup taqlīd itu”.
Mushannif menganjurkan agar kita selalu menjaga perbedaan antara dua perkataan yang sama-sama berhukum wājib sedangkan pengertian wājib untuk masing-masing dari dua perkataan itu tidak sama.
Kalau seseorang berkata: “Allah itu wājib bersifat qudrat” maka pengertian wājib di sini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh akal akan ketiadaannya, ini berarti bahwa qudrat Allah itu tidak bisa dibenarkan ketiadaannya oleh akal. Sedangkan jika seseorang itu berkata: “Mengi‘tiqādkan bahwa Allah itu bersifat qudrat adalah wājib maka pengertian wājib di sini adalah sesuatu yang diberi pahala kalau dikerjakan dan diberi siksa kalau ditinggalkan. Ini berarti bahwa kalau kita meng-i‘tiqād-kan bahwa Allah bersifat qudrat maka kita memperoleh pahala dan kalau yang kita i‘tiqādkan sebaliknya maka jadilah kita diberi siksa.
Nah! Perbedaan ma‘na wājib pada dua perkataan seperti di atas haruslah kita jaga baik-baik agar tidak keliru penempatannya.
Mushannif juga menganjurkan agar kita sebaiknya tidak termasuk orang-orang yang taqlīd dalam masalah ‘aqīdah-‘aqīdah agama karena kalau kita taqlīd dalam masalah tersebut maka iman kita jadi mukhtalif (masih diperselisihkan) karena sebagian ‘ulamā’ ya‘ni yang berpendapat dengan cukupnya taqlīd menyatakan bahwa telah tsubūt (tetap) iman kita. Sedangkan sebagian lagi yang berpendapat dengan ketidakcukupan taqlīd menyatakan bahwa iman kita belum tsubūt (tetap).
Maka kalau kita taqlīd, kita kekal di dalam neraka berdasarkan pendapat yang kedua ini karena itu berarti iman kita belum tsubūt. Adapun jika kita tidak taqlīd maka para ‘ulamā’ telah sepakat mengenai telah tsubūt-nya iman kita.
قَالَ السَّنُوْسِيُّ وَ لَيْسَ يَكُوْنُ الشَّخْصُ مُؤْمِنًا إِذَا قَالَ: أَنَا جَازِمٌ بِالْعَقَائِدِ وَ لَوْ قُطِعْتُ قَطْعًا قَطْعًا لَا أَرْجِعُ عَنْ جَزْمِيْ هذَا
“Sanūsī telah berkata: Dan seseorang tidak menjadi mu’min jika dia berkata: Saya mantap dengan ‘aqīdah-‘aqīdah itu dan andai saya (diancam) untuk dipotong dengan beberapa potongan niscaya saya tidak akan mencabut kemantapan (jazam) saya ini.”
بَلْ لَا يَكُوْنُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَعْلَمَ كُلَّ عَقِيْدَةٍ مِنْ هذِهِ الْخَمْسِيْنَ بِدَلِيْلِهَا وَ تَقدِيْمَ هذَا الْعِلْمِ فَرْضًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ الْعَقَائِدِ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ أَسَاسًا يَنْبَغِيْ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.
“Bahkan dia tidak akan menjadi mu’min sehingga dia mengetahui akan setiap ‘aqīdah dari yang 50 ini dengan dalīlnya (yang ijmālī) dan (mengetahui pula bahwa) mendahulukan ‘ilmu ini adalah fardhu sebagaimana dikutip dari kitab Syarḥ-ul-‘Aqā’id, karena pengarangnya (ya‘ni Sa‘dī Taftazānī) telah menjadikan ‘ilmu ini sebagai dasar yang terbina atasnya barang yang selainnya.