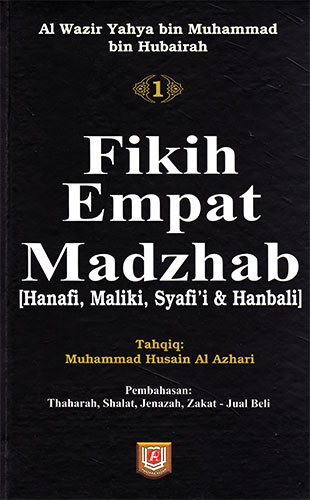[……] (681) atau Bab: Orang Yang Mati Syahid.
- Keempat Imām madzhab (Mālik, Abū Ḥanīfah, Aḥmad bin Ḥanbal, dan asy-Syāfi‘ī) berbeda pendapat tentang kaum pemberontak dan pembegal yang tewas.
Mālik, asy-Syāfi‘ī, dan Aḥmad berkata: “Mereka tetap dimandikan dan dishalati.”
Abū Ḥanīfah berkata: “Mereka tidak dimandikan dan tidak dishalati.” (682).
Aku mengatakan (683): “Tidak menshalati mereka (kaum pemberontak dan begal) tidak sama dengan tidak menshalati orang-orang yang mati syahid, karena orang-orang yang mati syahid tidak dishalati karena kemuliaan mereka, sementara mereka (kaum pemberontak dan begal) tidak dishalati sebagai hukuman bagi mereka agar menjadi efek jera bagi orang-orang seperti mereka (yang tidak tewas).”
- Mereka berbeda pendapat, apakah membaca (surah al-Fātiḥah) merupakan syarat sahnya shalat jenazah?
Abū Ḥanīfah dan Mālik berkata: “Tidak perlu membaca.”
Asy-Syāfi‘ī, dan Aḥmad berkata: “Harus membaca, karena ia merupakan syarat sahnya.” (684).
- Mereka sepakat bahwa takbir dalam shalat jenazah ada empat. Setelah takbir pertama membaca surah al-Fātiḥah, setelah takbir kedua membaca shalawat atas Nabi s.a.w., setelah takbir ketiga mendoakan mayat dan kaum muslimin, dan setelah takbir keempat mengucapkan salām ke sebelah kanan. Kecuali Abū Ḥanīfah dan Mālik yang berkata: “Setelah takbir pertama membaca Ḥamdalah dan memuji Allah tanpa perlu membaca surah al-Fātiḥah.” (685).
- Mereka berbeda pendapat, apakah imam tetap diikuti bila dia takbir lebih dari empat kali?
Abū Ḥanīfah, Mālik dan asy-Syāfi‘ī berkata: “Dia tidak boleh diikuti.”
Menurut Aḥmad, dalam hal ini ada beberapa riwayat.
Pertama, dia boleh diikuti pada takbir kelima. Pendapat ini dipilih oleh al-Khiraqī. (686).
Kedua, seperti madzhab Aḥmad.
Ketiga, boleh mengikutinya sampai takbir ketujuh. (687).
- Mereka sepakat bahwa berdiri dalam shalat jenazah disyariatkan.
- Mereka berbeda pendapat bahwa berdiri termasuk salah satu syarat sahnya shalat jenazah. Kecuali Abū Ḥanīfah yang mengatakan: “Ia bukan syarat sahnya, tapi hanya fardhu seperti fardhu-fardhu lainnya yang gugur bila ada ‘udzur.”
Faidah dari perbedaan pendapat ini adalah, apabila penguasa sakit dan melakukan shalat jenazah dengan duduk maka hikumnya dibolehkan, menurut Abū Ḥanīfah, dan shalatnya sah. (688).
- Mereka berbeda pendapat tentang bolehnya mengulang shalat jenazah.
Abū Ḥanīfah berkata: “Shalat jenazah tidak boleh diulang, kecuali bila wali mayat hadir lalu yang menunaikan shalat orang lain, maka shalat boleh diulang agar si wali tersebut shalat.”
Mālik berkata: “Apabila shalat jenazah telah dilaksanakan secara berjama‘ah dengan idzin imām (penguasa) maka tidak perlu diulang. Apabila wali hadir dan telah shalat maka tidak perlu diulang.”
Asy-Syāfi‘ī dan Aḥmad berkata: “Hukumnya boleh diulang.” (689).
- Mereka berbeda pendapat tentang posisi imām dari mayat, baik laki-laki maupun perempuan.
Abū Ḥanīfah berkata: “Imām berdiri sejajar dengan dada mayat.”
Mālik berkata: “Bila mayatnya laki-laki maka ma’mūm berdiri sejajar dengan bagian tengah tubuhnya, sedangkan bila mayatnya perempuan maka sejajar dengan kedua bahunya,”
Menurut fuqahā’ Syāfi‘iyyah, dalam hal ini ada dua pendapat bila mayatnya laki-laki.
Pertama, imām berdiri sejajar dengan dadanya.
Kedua, imām berdiri sejajar dengan kepalanya. Pendapat inilah yang paling kuat. Sedangkan bila mayatnya perempuan maka imām berdiri sejajar dengan bagian tengah tubuhnya (perutnya). Dalam hal ini hanya ada satu pendapat.
Aḥmad berkata: “Imām berdiri di dekat dada mayat laki-laki, sedangkan bila mayatnya perempuan berdiri di dekat perutnya (bagian tengah tubuhnya).” (690).
Aku (Ibnu Hubairah) mengatakan: “Inilah pendapat yang benar menurutku. Alasannya telah dijelaskan dalam buku kami ini.” (691).
- Mereka berbeda pendapat tentang shalat di kuburan.
Abū Ḥanīfah berkata: “Apabila mayat dimakaman sebelum walinya menshalatinya maka sang wali harus menshalatinya dan dia (si mayat) dishalati sampai 3 hari. Sedangkan bila walinya telah menshalatinya maka tidak perlu dishalati lagi.”
Mālik berkata: “Apabila mayat telah dimakamkan tapi belum dishalati, atau telah dishalati tanpa idzin imām maka shalatnya harus diulang – menurut salah satu dari dua riwayat – Sedangkan bila dia telah dishalati atas idzin imām maka shalatnya tidak perlu diulang. Wali menshalati setelah imām.”
Asy-Syāfi‘ī berkata: “Mayat tetap dishalati selama tidak diketahui bahwa jasadnya telah rusak, meskipun walinya telah menshalatinya.”
Menurut fuqahā’ Syāfi‘iyyah, dalam hal ini ada empat pendapat.
Pertama, si mayat dishalati sampai satu bulan.
Kedua, dia dishalati selama belum diketahui bahwa jasadnya telah rusak, meskipun walinya telah menshalatinya.
Ketiga, dia dishalati oleh orang-orang yang berhak mendapat warisannya saat wafat, karena mereka-lah orang-orang yang disuruh menshalatinya. Adapun orang yang lahir setelah kematiannya atau baru mendengar informasi setelah kematiannya maka dia tidak perlu menshalatinya.
Keempat, dia dishalati selamanya.
Aḥmad berkata: “Dia dishalati sampai satu bulan meskipun walinya telah menshalatinya.” (692).
- Mereka berbeda pendapat tentang laki-laki yang meninggal dunia dan tidak ada yang menshalati jenazahnya kecuali kaum perempuan.
Abū Ḥanīfah dan Aḥmad berkata: “Mereka menshalatinya secara berjamā‘ah dan imām mereka berada di tengah.”
Mālik dan asy-Syāfi‘ī berkata: “Mereka menshalatinya sendiri-sendiri.” (693).