Niat dalam Tinjauan Syariat – Ikhlas Tanpa Batas
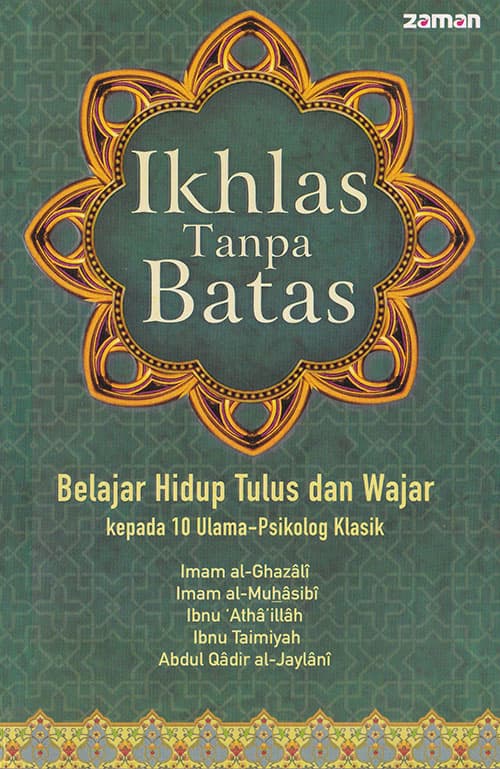
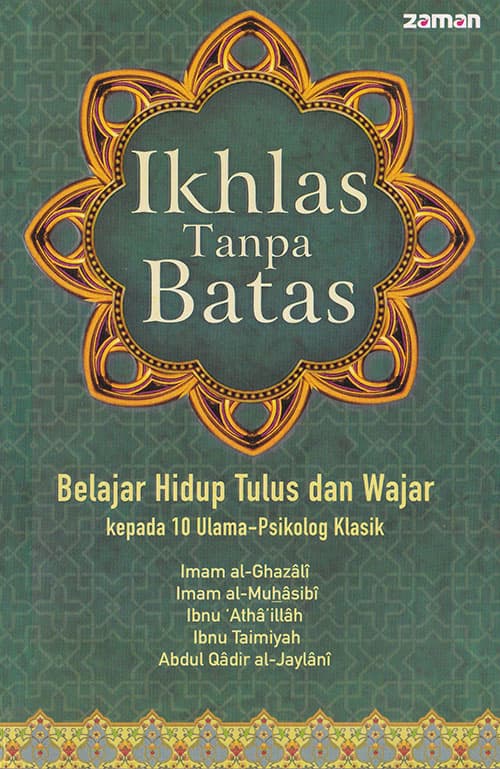
Niat itu berfokus di hati menurut kesepakatan ulama. Kalau orang berniat dalam hatinya, dan tidak mengucapkannya, itu sudah cukup menurut kesepakatan ulama, terkecuali menurut sebagian pengikut asy-Syāfi‘ī yang salah dalam memahami maksud asy-Syāfi‘ī; asy-Syāfi‘ī pernah menyatakan bahwa awal shalat adalah perkataan, padahal yang dia maksud bukanlah niat melainkan takbīr.
Niat itu mengikuti pengetahuan. Siapa mengetahui apa yang mau dia kerjakan, tentulah ia sudah meniatkannya secara otomatis. Seumpama orang yang dihidangi makanan, bila ia tahu ia ingin memakannya, pastilah ia sedang meniatkannya secara otomatis. Bahkan, kalaulah manusia dibebani untuk mengerjakan suatu amal tanpa niat, itu berarti mereka dibebani sesuatu yang tak sanggup mereka lakukan. Setiap orang, bila ingin memperbuat amal, yang disyariatkan ataupun yang tidak disyariatkan, maka pengetahuannya telah bersemayam di hatinya dan inilah niat.
Jika orang tahu bahwa ia ingin bersuci, shalat, atau puasa, tentulah ia sudah meniatkannya. Dikatakan tak berniat bila ia tidak mengetahui apa yang ia inginkan, seperti orang yang lupa akan janabah lalu mandi sekadar untuk membersihkan atau menyegarkan diri, atau seperti orang yang sedang mengajari orang cara berwudhu’ dan ia tidak berkehendak wudhu’ untuk dirinya sendiri, atau seperti orang yang tidak tahu besok masuk bulan Ramadhān, lalu ia tak meniatkan puasa.
Muslim yang tahu besok adalah bulan Ramadhān dan dia ingin puasa Ramadhān, maka otomatis ia sudah berniat, dan ia tidak perlu mengucapkannya. Orang yang tidak tahu apakah besok masuk bulan Ramadhān, lalu meniatkan puasa Ramadhān atau puasa sunnah, lalu jelas bagi dia bahwa hari itu masuk Ramadhān, maka sekalipun ucapan dan hatinya berbeda, yang berlaku adalah apa yang ada di hatinya, bukan yang dilafalkannya.
Orang yang yakin masih ada waktu shalat, lalu ia niat shalat adā’an, lalu jelaslah bagi dia bahwa waktu shalat sudah lewat; atau orang yang yakin waktu shalat sudah lewat, lalu ia niat shalat sebagai qadhā’, lalu teranglah baginya bahwa waktu shalat belum lewat; kedua-duanya sama-sama sah.
Jelaslah bahwa niat pada saat tahu adalah demi kemudahan, dan menghindari rasa was-was.
Akan tetapi, apakah melafalkan niat dianjurkan? Sebagian pengikut Abū Ḥanīfah, asy-Syāfi‘ī, dan Aḥmad berpendapat: ini dianjurkan agar lebih tegas. Sebagian pengikut Mālik dan Aḥmad berpendapat lain: itu tak dianjurkan, bahkan bid‘ah. Tak ada satu pun riwayat dari Nabi s.a.w., sahabat, dan tabi‘in yang menerangkan bahwa mereka melafalkan niat, baik dalam shalat, bersuci, ataupun puasa. Mereka berpendapat: niat itu otomatis terwujud begitu orang mengetahui perbuatan yang ingin ia lakukan. Niat itu ada di hati, namun ada orang yang yakin niat itu bukan di hati dan karenanya melafalkannya, sehingga justru tak terwujud “niat”-nya.
Ulama sepakat bahwa niat dengan jahar (suara keras) tidaklah boleh, bagi imam, makmum, ataupun orang yang shalat sendirian. Tidak pula mengulangi niat itu dianjurkan. Perselisihan di antara mereka hanyalah pada pelafalan niat dengan suara pelan; apakah ini makruh atau anjuran.