Khilaf Mengenai Tetapnya Hukum dengan Akal atau Syara’ – Terjemah Kifayat-ul-‘Awam
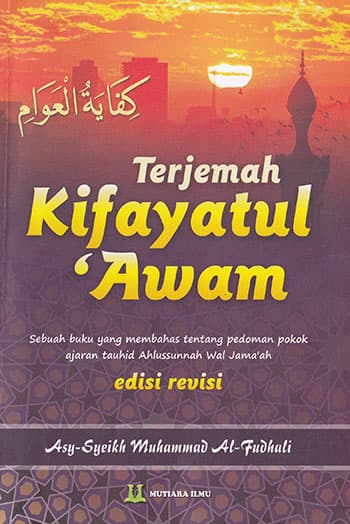
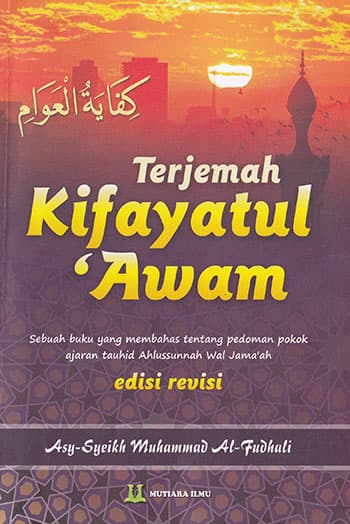
Di dalam kata-kata “WĀJIB” itu tidak ada kaitan dengan (شَرْعًا) “menurut syara‘” sebagaimana Sanūsī mengkaitkannya dalam kitab (شَرْحُ الصُّغْرَى) dengan ibarat: (وَ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ شَرْعًا) “Dan wajib atas setiap mukallaf menurut syara‘……”
Hal ini disebabkan karena syara‘ tidak hanya khusus untuk kewajiban seperti itu (ya‘ni hukum mengetahui akidah yang 50) karena hukum-hukum itu semuanya ditetapkan dengan syara‘ sebagaimana madzhabnya Asyā‘irah. Karena itulah Sanūsī tidak lagi mengkaitkannya seperti itu dalam kitab (شَرْحُ الْكُبْرَى).
Dalam hal ini Mu‘tazilah berpendapat bahwa hukum-hukum itu menjadi tetap dengan akal berdasarkan atas (التَّحْسِيْنُ) “sikap menganggap baik” dan (التَّقْبِيْحُ) “sikap menganggap jelek” yang keduanya bersifat ‘aqlī (dapat dilakukan dengan akal).
Sedangkan syara‘ hanyalah datang sebagai penguat bagi akal tersebut.
Yang demikian itu adalah karena perbuatan dengan tidak memandang kepada apa-apa yang didatangkan syara‘, adakalanya bersifat BAIK dan adakalanya bersifat JELEK.
Perbuatan yang bersifat baik mempunyai 4 tingkatan:
Adapun perbuatan yang bersifat jelek maka dia hanya punya satu tingkatan yaitu: “Bahwa perbuatan itu adalah perbuatan di mana pelakunya berhak untuk memperoleh celaan dan orang yang meninggalkannya berhak untuk memperoleh pujian”. Maka ketika itu akal dapat menyimpulkan bahwa perbuatan itu ḤARĀM.
Inilah kesimpulan dari apa yang telah dikutip oleh Syaikh Ibn-ul-Qāsim dari Sa‘dī perihal madzhab Mu‘tazilah. Dan zhāhir dari apa yang telah ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan “BAIK” adalah apa-apa yang selain “JELEK” sehingga tercakuplah tiap-tiap dari yang makrūh dan mubāḥ.
Adapun golongan Maturidiyyah maka pendapatnya adalah bahwa hukum-hukum itu menjadi tetap dengan syara‘ kecuali hukum “KEWAJIBAN MENGETAHUI (MA‘RIFAT) KEPADA ALLAH S.W.T.” karena hukum ini menjadi tetap dengan akal. Akan tetapi ketetapannya itu bukan (لِلتَّحْسِيْنِ الْعَقْلِيْ) “karena akal menganggapnya sesuatu yang baik” sebagaimana dikatakan oleh Mu‘tazilah melainkkan (لِوُضُوْحِهِ) “karena sudah terang dan jelasnya”. Maka akal-lah yang menjelaskan hukum seperti itu sebagaimana halnya seorang rasul.
Seperti inilah yang dikatakan oleh an-Nasafī dalam (بَحْرُ الْكَلَامِ).
Disepakati bahwa yang menerbitkan hukum-hukum itu adalah Allah s.w.t. bukan yang selain-Nya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qāsim. Hanya saja perbedaan antara tiga pendapat adalah sebagai berikut:
Di antara tiga pendapat tersebut maka yang benar adalah pendapat Asyā‘irah.