Jejak-Jejak Wali Allah | Pendahuluan | Beberapa Akhlak Sufi (4/5)
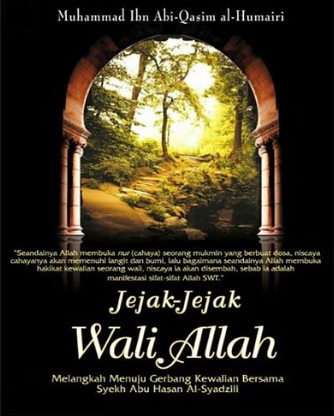
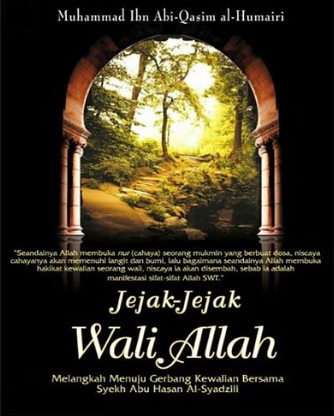
(lanjutan)
5. Kaum Sufi dan Jalan Menuju Allah SWT
Awal jalan menuju Allah SWT adalah taubat. Dengan taubat seorang salik (penempuh jalan) atau murid memulai kehidupan baru yang berbeda dari kehidupan yang ia jalani sebelumnya; perbedaan yang sangat besar, bahkan perbedaan yang mendasar. Kehidupan baru itu mempunyai karakteristik istimewa sebagai kehidupan yang bertabiat akhlaqi (moralis). Karenanya, dalam kehidupan baru ini sudah semestinya muncul pada dirinya suatu rasa kewajiban dan komitmen terhadap pelaksanaan sekumpulan besar nilai-nilai, etika-etika, kondisi-kondisi, dan perbuatan perbuatan yang tidak dilaksanakannya dalam kehidupan sebelumnya.
Konsekuensi menempuh jalan baru ini, sang salik harus menghitung kembali urutan prioritas dan menentukan tujuan dan sasaran-sasaran yang sesuai dengan tuntutan kehidupan yang ia songsong. Maka, ketika sebelumnya dia sibuk dengan dunia dan keindahannya, membiarkan dirinya berada dalam hawa nafsu duniawi, tenggelam dalam kesenangan-kesenangannya, berpaling dari akhirat dan perhitungannya, maka sekarang dia bangun dari tidur panjang dan sadar dari kelenaannya. Sehingga dia berlomba dengan kematian, waspada terhadap kelalaian dan kelepasan, menghidupkan malamnya, menghauskan diri siang harinya, zuhud (menjauhi) terhadap kesenangan yang faná dan mengharap kenikmatan abadi, dengan selalu menghadirkan keagungan Allah SWT, menerima ketaatan dengan berharap pahala dari-Nya, takut akan siksa-Nya, mengagungkan kedudukan Nya, serta penuh keridhaan dan cinta kepada-Nya.
Sehingga apabila benar-benar telah terjadi pada dirinya perubahan jiwa dan perasaan ini dari kehidupan lama menuju kehidupan baru, maka dia telah meletakkan kedua kakinya di awal jalan menuju Allah SWT. Yaitu, jalan yang membutuhkan kesabaran dan kerja keras (mujahadah). Suatu jalan, sebagaimana dikemukakan oleh para sufi, yang modal dasarnya adalah ketulusan, bekalnya adalah kesabaran, dan makanan pokoknya adalah ketakwaan. Maka, siapa yang tidak mempunyai modal dasar ketulusan, dia tidak mendapatkan keuntungan. Siapa yang tidak berbekal kesabaran, dia akan terputus di tengah jalan. Dan, siapa yang tidak mengonsumsi makanan pokok ketakwaan, dia akan binasa.1
Kaum sufi menggambarkan detik-detik penentuan yang menjadi awal langkah perjalanan, dan terjadinya perubahan besar. Ini sebagai cahaya kilat yang muncul tiba-tiba menyerupai kilatan setruman listrik atau cahaya yang seketika bersinar terang setelah kegelapan yang pekat. Mereka juga menggambarkannya sebagai cahaya yang mempunyai tabiat yang menawan dan mengalahkan; menguasai jiwa secara sempurna, meliputinya secara penuh, dan memaksanya sedemikian rupa untuk mengubah pola hidupnya serta membelokkan arah perjalanannya.
Dalam perubahan ini, tirai menjadi tersingkap, mata hati terbuka, karat-karat pandangan batin lenyap, dan kehendak mengarah kepada pandangan yang baru. Oleh karena itu, sebagian sufi menyebut saat-saat penentuan ini dengan kelahiran baru karena sosok pelakunya laksana orang yang baru terlahir kembali. Karena itu, sebagian mereka tidak memberikan jawaban tentang usianya dalam hitungan waktu yang sebenarnya, ketika ditanya usia sesungguhnya. Dia lebih senang mengatakan usia yang telah ia jalani semenjak terjadinya perubahan pada dirinya tersebut.
Kondisi-kondisi dan faktor-faktor awal pada saat-saat penentuan ‘kelahiran baru’ ini, waktu terjadinya berbeda beda dalam kehidupan para salik tersebut. Sebagian mereka mengalaminya pada masa-masa awal dalam kehidupan mereka, bahkan barangkali terjadi pada salah seorang mereka ketika berada dalam tahun-tahun pertama usianya. Sahal bin Abdullah (at-Tustary-ed.) misalnya, yang dibesarkan dalam lingkungan yang saleh sehingga sejak masa anak-anak dia telah meletakkan kedua kakinya di jalan menuju Allah SWT.
Buku-buku biografi menceritakan kepada kita bahwa dia dibesarkan di rumah pamannya. Pamannya itu adalah salah seorang yang gemar beribadah. Apabila dia bangkit untuk melaksanakan shalat, Sahal bangun bersamanya. Pamannya khawatir terhadap Sahal sehingga dia menasihati Sahal untuk pergi tidur. Dia berkata, “Segera tidurlah! Kamu sungguh menyibukkan hatiku.” Namun, anak itu, Sahal, tidak mempedulikan nasihat pamannya. Dia terus terjaga sampai pamannya kembali ke pembaringan.
Pamannya, Muhammad bin Siwar, berkeinginan untuk tidak menghalangi Sahal dari kebaikan. Dia berkata kepadanya, “Katakanlah dalam hatimu ketika tubuhmu sedang bolak-balik di pembaringanmu, sebanyak tiga kali tanpa menggerakkan mulutmu: ‘Allah Maa’i, Allah Syaahidi, Allah Nazhirun llayya‘ (Allah bersamaku, Allah menyaksikanku, Allah memandang kepadaku).” Sahal melaksanakannya selama tiga hari, kemudian memberitahu pamannya. Lalu, pamannya meminta agar dia menambahkannya lagi hingga sebelas kali.
Sahal menemukan adanya kenyamanan dalam hatinya, kebahagiaan dan kelezatan dalam perasaan dan jiwanya, sehingga hatinya semakin cerah dan terbuka kepada ketaatan, ibadah, tafakkur, selalu ingat, dan zikir. Dia terus melakukan amalan tersebut hingga setahun dan kemudian memberitahukan hal itu kepada pamannya. Sang paman berpesan kepadanya untuk terus melakukannya sepanjang hidupnya, karena hal itu sangat berguna baginya di dunia dan akhirat.
Kemudian, dia berkata kepadanya, “Sahal, orang yang Allah SWT selalu bersamanya, memandang kepadanya, dan menyaksikannya, apakah dia maksiat kepada-Nya? Jauhilah maksiat!” Sahal kemudian mengerti bahwa muraqabah (pengawasan) Allah, merasakan keagungan dan kebesaran-Nya, dan menyebut-Nya dengan hati dan lidah tidak akan sempurna kecuali apabila hal itu telah mampu menghalanginya dari maksiat kepada Allah SWT.
Maka, dia berjanji dalam dirinya untuk melakukan ketaatan dan bertekad bulat untuk selalu melakukannya. Itulah fondasi kehidupan yang dijalani oleh Sahal. Secara perlahan, ia mendaki tingkatan tingkatannya, menaiki tangga-tangganya, semenjak awal usia anak-anaknya sampai cahaya-cahaya ilham dan makna makna iman mulai bersinar di dalam hatinya, hingga ia menjadi salah seorang tokoh besar sufi yang mendapatkan kesaksian dengan ketinggian kedudukan.2
(bersambung)