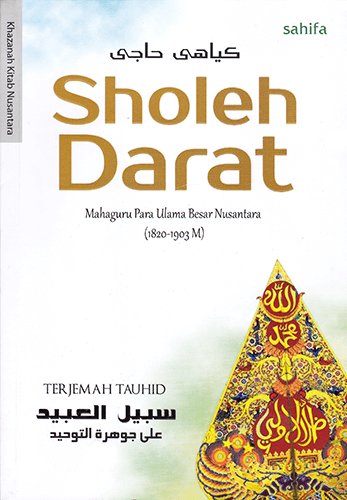Adapun i‘rāb kalimat yang pertama, yaitu (لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ), ketahuilah lafazh (لَا) berma‘na nafyi-l-jinsi (menolak dan meniadakan jenis yang umum), maka pengamalan lafazh (لَا) seperti (إِنَّ), yaitu me-nashab-kan isim-nya dan me-rafa‘-kan khabar-nya. Lafazh (إِلهَ) menjadi isim-nya (لَا), mabnī fatḥah, tanpa tanwīn karena menyimpan ma‘na huruf (مِنْ), jika dikira-kirakan berbunyi (لَا مِنْ إِلهَ), karena pada asalnya kalimat (لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ) merupakan jawaban pertanyaan (هَلْ مِن إِلهٍ غَيْرُ اللهِ), maka dijawab (لَا مِنْ إِلهَ إِلَّا اللهُ), kemudian (مِنْ) dibuang, menjadi (لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ). Karena asalnya seperti itu, maka huruf (لَا) me-nafi-kan sesuatu secara umum, maksudnya meniadakan semua tuhan selain Allah, yang ada hanya Allah saja.
Adapula yang berpendapat bahwa lafazh (إِلهَ) itu mabnī fatḥah karena murakkab, lafazh (لَا إِلهَ) mirip lafazh (خَمْسَةَ عَشَرَ), tidak boleh di-tanwīn, karena jika di-tanwīn maka (لَا) akan berma‘na nafy-ul-waḥīdah (menafikan satu) yang pengamalannya seperti (لَيْسَ), seperti kalimat: (لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ) “tidak ada seorang lelaki dalam rumah”, maksudnya ada banyak lelaki di rumah, yang tidak ada hanya satu, hal ini tidak boleh berlaku dalam kalimat musyārafah.
Jumlah yang terdiri dari (لَا) dan isim-nya dalam maḥāl rafa‘ berkedudukan menjadi mubtada’, sedangkan khabar-nya dibuang jika dikira-kirakan berupa lafazh (مَوْجُوْدٌ), maka kalimat aslinya adalah (لَا إِلهَ مَوْجُوْدُ حَقٍّ إِلَّا اللهُ). Ada pula yang berpendapat bahwa (لَا) tidak ber-‘amal (tidak berfungsi sebagai ‘āmil – SH.), karenanya tidak memiliki khabar, ini menurut Imām Sibawaih.
Para ahli ilmu mengatakan: “I‘rāb yang paling utama untuk lafazh jalālah adalah rafa‘, karena yang masyhur dalam al-Qur’ān adalah rafa‘”. Adapula yang berpendapat bolehnya membaca nashab. Adapun perinciannya jika dibaca rafa‘ ada 5 pendapat, yang mu‘tamad dan mu‘tabar ada 2, sedangkan yang 3 ghairu mu‘tabar. (103).
- Lafazh jalālah, dibaca rafa‘ menjadi badal dari dhamīr yang menjadi khabar-nya (لَا) yang dibuang, atau jadi badal dari isim-nya (لَا), karena menurut Imām Sibawaih, isim-nya (لَا) ber-‘amal rafa‘. Dinamakan badal syai’ min syai’ atau badal kull min kull, tapi hanya penamaan saja, hakikatnya tidak seperti itu, karena (إِلهَ) yang di-nafi-kan bukanlah (إِلهَ) yang ditetapkan setelah (إِلَّا), berbeda dengan contoh: (جَاءَ زَيْدٌ أَخُوْكَ) (زَيْدٌ) dan (أَخُوْكَ) itu sama, satu orang. Oleh karena itu, orang yang mengucapkan kalimat musyarrafah (dua kalimat syahadat) ketika mengucapkan (إِلَّا اللهُ), hatinya wajib ingat untuk menetapkan Allah sebelum mengucapkan (إِلَّا اللهُ), jika tidak maka kufur. Adapula yang menamai badal muthābiq, maksudnya, cocok dalam lafazhnya saja tapi tidak pada ma‘nanya.
- Lafazh jalālah, dibaca rafa‘ menjadi khabar-nya (لَا), sedangkan (إِلَّا) berma‘na (غَيْرُ), tidak ber-‘amal, kalimat aslinya: (لَا إِلهَ مَوْجُوْدٌ إِلَّا اللهُ), lafazh (إِلَّا) menjadi istitsnā’ dari dhamīr muqaddar dan menjadi khabar, maka menjadi (لَا إِلهَ غَيْرُ اللهُ). Ketika lafazh (غَيْرُ) dibuang dan diganti dengan lafazh (إِلَّا) maka rafa‘-nya lafazh (غَيْرُ) jatuh pada lafazh jalālah, karena maksud kalimat musyarraf adalah menolak tuhan-tuhan selain Allah.
- Ini pendapat yang tidak mu‘tabar juga tidak mu‘tamad.
- Lafazh jalālah, dibaca rafa‘ menjadi sifat dari isim-nya (لَا), lafazh (إِلَّا) berma‘na (غَيْرُ), bukan huruf istitsnā’, lafazh (إِلَّا) dan lafazh jalālah menjadi satu sebagai sifat dari isim-nya (لَا), jika dikira-kirakan berupa (لَا إِلهَ غَيْرُ اللهُ), ini pendapat yang dha‘īf.
- Lafazh (لَا إِلهَ) menjadi khabar muqaddam, dan lafazh (إِلَّا اللهُ) menjadi mubtada’ mu’akhkhar, lafazh (اللهُ) berasal dari lafazh (إِلهَ), ketika menginginkan meringkas ketuhanan hanya hak Allah saja, didatangkan lafazh (لَا) dan (إِلَّا) sebagai adatu ḥasri, maka menjadi kalimat (لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ) ini pendapat yang dha‘īf.
- Lafazh jalālah, dibaca rafa‘ menjadi nā’ib-ul-fā’il, karena lafazh (إِلهَ) diartikan (مَأْلُوْه) yang berasal dari kata (إِلهَ), artinya (مَعْبُوْد) “dzāt yang disembah”, maka kalimat aslinya adalah (لَا مَعْبُوْدَ بِحَقٍّ إِلَّا اللهُ.). Pendapat ini juga dha‘īf.
Itulah penjelasan lima pendapat ‘ulamā’ dalam membaca rafa‘ ism-ul-jalālah (إِلَّا اللهُ).
Adapun jika ism-ul-jalālah dibaca nashab, maka ada dua pendapat (104).
- Dibaca nashab karena menjadi istitsnā’ dari dhamīr di-khabar, karena setiap istitsnā’ dalam kalām tāmm yang nafi boleh dibaca rafa‘ menjadi badal dan boleh dibaca nashab menjadi mustatsnā, seperti contoh:
مَا قَامَ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدٌ أَوْ إِلَّا زَيْدًا.
- Dibaca nashab menjadi shifat dari isim-nya (لَا), isim-nya (لَا) mabnī fatḥah dalam maḥāl nashab, menjadi shifat dari lafazh yang dibaca nashab otomatis ikut dibaca nashab, ketika lafazh (إِلَّا اللهُ), menjadi shifat dari isim-nya (لَا), maka pasti lafazh (إِلَّا) berma‘na (غَيْرُ), seperti ketika engkau berkata: (لَا إِلهَ غَيْرُ اللهُ), kemudian lafazh (غَيْرُ) dibuang dan diganti dengan (إِلَّا) maka nashab-nya berpindah ke lafazh jalalah. Ini adalah pendapat yang dha‘īf. Sebab, zhāhirnya lafazh hanya menunjukkan “meniadakan sifat ketuhanan bagi selain Allah.” seperti perkataanmu: (لَا إِلهَ غَيْرُ اللهُ). Kalimat ini hanya menolak adanya tuhan selain Allah, dan menetapkan tuhan secara tidak jelas, hanya secara tersirat saja, bukan secara tersurat. Padahal dalam masalah tauhid, diwajibkan menafikan tuhan selain Allah dan menetapkan Allah harus secara tersurat yang jelas, tidak cukup hanya dengan tersirat. Karena itulah pendapat ini ditolak, Wallāhu a‘lam.
Tujuh perincian pendapat di atas adalah penjelasan tentang i‘rāb kalimat thayyibah, ini sudah cukup bagi orang-orang awam yang bodoh dan tidak mengerti bahasa ‘Arab seperti saya dalam mengetahui i‘rāb kalimah musyarrafah. Penjelasan lebih lengkapnya tertulis dalam kitab-kitab yang besar.
Setelah engkau mengetahui i‘rāb kalimat thayyibah, engkau wajib mengetahui ma‘nanya. Adapun ma‘na kalimat thayyibah ini, tidak diragukan lagi bahwa kalimah ini mengandung nafi (meninadakan) dan itsbāt (menetapkan) (105):
فَالْمَنْفِيُّ كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ حَقِيْقَةِ لَا إِلَهَ غَيْرُ مَوْلَانَا جَلَّ وَ عَزَّ.
“Sesuatu yang di-nafi-kan dan ditolak adalah setiap hakikat tuhan selain Allah s.w.t.”
وَ الْمُثْبِتُ مِنْ تِلْكَ الْحَقِيْقَةِ فَرْدٌ وَاحِدٌ وَ هُوَ مَوْلَانَا جَلَّ وَ عَزَّ.
“Sesuatu yang ditetapkan dari beberapa hakikat tersebut hanyalah satu, yaitu Tuhan kita Allah s.w.t. Yang Maha Agung dan Maha Mulia.”
Dalam aturan tatabahasa ‘Arab, ketika ingin memberitahu sesuatu yang sudah pasti, agar orang yang diberitahu tidak ragu-ragu, maka pada awal kalimat menggunakan lafazh (لَا) untuk nafi (me-nafi-kan atau meniadakan), dan di akhirnya menggunakan lafazh (إِلَّا) untuk itsbāt (menetapkan). Karenanya dalam al-Qur’ān disebutkan:
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ
“Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Ilāh (sesembahan, tuhan) selain Allah.” (QS. Muḥammad [47]: 19).
Tujuannya untuk memberitahu kekhususan sifat ketuhanan hanya pada Allah saja, tidak ada sifat ketuhanan bagi selain Allah, baik secara akal ataupun syara‘. Hakikat (إِلهَ) adalah Dzāt yang wajib ada yang pasti disembah, baik secara suka rela maupun terpaksa. Dari sini bisa dipahami bahwa lafazh (إِلهَ) itu umum, maksudnya dilihat dari segi ma‘na, lafazh (إِلهَ) masih menerima bilangan (lebih dari satu), tetapi dalil yang tegas mencegah adanya tuhan selain Allah s.w.t. Itulah ma‘na lafazh (اللهُ) setelah lafazh (إِلَّا). Isim a‘zham setelah (إِلَّا) bukanlah (إِلهَ), lafazh jalālah itu juz’i, berupa nama untuk Dzāt Allah, ia tidak menerima bilangan. Jika ma‘na (إِلهَ) sama dengan (اللهُ), maka adanya istitsnā’ tidak ada gunanya, karena akan terjadi “mengecualikan sesuatu dari sesuatu tersebut”, seperti contoh:
مَا قَامَ الْقَوْمُ إِلَّا الْقَوْمُ.
“Kaum tidak berdiri kecuali kaum.”
Jika seperti itu, maka tidak bisa didapatkan ma‘na tauhid dalam kalimat: (لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ).
Kesimpulannya, lafazh (إِلهَ) itu umum berma‘na “dzāt yang disembah secara benar”, sedangkan lafazh (اللهُ) adalah “nama dzāt yang esa wujudnya.” Kesimpulan ma‘nanya adalah:
لَا مُسْتَحِقَّ لِلْعُبُوْدِيَّةِ مَوْجُوْدٌ إِلَّا الْفَرْدُ الَّذِيْ هُوَ خَالِقُ الْعَالَمِ جَلَّ وَ عَزَّ.
“Tidak ada Dzāt yang berhak untuk disembah selain Dzāt tunggal pencipta alam yang Maha Agung dan Mulia.”