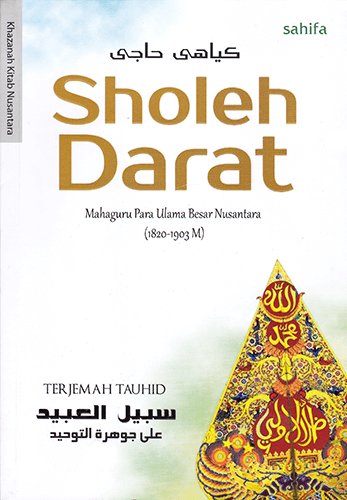Iman pada Qadhā’ dan Qadar
Syaikh Ibrāhīm al-Laqqānī meneruskan penjelasan penolakannya pada pendapat madzhab Qadariyyah.
Beliau berkata:
| وَ وَاجِبٌ إِيْمَانُنَا بِالْقَدَرِ |
وَ بِالْقَضَا كَمَا أَتَى فِي الْخَبَرِ. |
“Dan wajib kita beriman dengan qadhā’ dan qadar karena ada keterangannya di dalam hadits.”
Lafazh (وَاجِبٌ) merupakan khabar muqaddam, sedang lafazh (إِيْمَانُنَا) adalah mubtada’ mu’akhkhar.
Makna bait ini adalah kita wajib beriman pada kepastian Allah yang ada sejak zama azali, sebagaimana penjelasan dalam hadits.
Penjelasan
Bait ini menolak keyakinan golongan Qadariyyah yang tidak mempercayai qadhā’ dan qadar sejak zaman azali. Mereka berkeyakinan bahwa segala sesuatu saat ini tidak ada hubungannya dengan ketetapan di zaman azali.
Madzhab Qadariyyah terbagi menjadi dua golongan, yaitu: (90)
- Golongan Qadariyyah yang tidak mengakui adanya qadhā’ dan qadar sejak zaman azali.
- Golongan Qadariyyah yang menyatakan bahwa seorang hamba mempunyai qudrah dan mampu menciptakan perbuatannya sendiri.
Pendapat golongan Qadariyyah ini dibantah oleh bait:
| فَخَالِقٌ لِعَبْدِهِ وَ مَا عَمِلْ |
مُوَفِّقٌ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَصِلْ. |
“Maka Allah-lah yang menciptakan hamba-Nya dan apa-apa yang dia perbuat, serta memberikan taufiq kepada siapapun yang Dia kehendaki untuk sampai (kepada ridha-Nya).”
Orang yang beriman kepada qadhā’ dan qadar pasti akan ridhā dan rela pada ketetapan qadhā’ dan qadar Allah.
Pertanyaan: (91)
Jika ada yang bertanya kepadamu: “Kenapa kita wajib ridha pada qadhā’ dan qadar? Bukankah itu berarti mewajibkan kita ridha pada kekufuran berarti kufur, dan ridha pada kemaksiatan berarti maksiat?”
Jawaban:
Salah satu pendapat menyatakan: “Kekufuran dan kemaksiatan adalah muqdhā (sesuatu yang di-qadhā’) dan maqdūr (sesuatu yang di-taqdīr-kan), bukan qadhā’ dan qadar, yang wajib adalah ridha pada qadhā’ dan qadar, bukan pada muqdhā dan maqdūr”.
Pendapat lain menyatakan: “Kekufuran dan kemaksiatan memiliki dua sisi. Pertama, kekufuran dan kemaksiatan adalah sesuatu yang dikehendaki, dikuasai, dan dimengerti oleh Allah. Kedua, kekufuran dan kemaksiatan yang muncul dari kasb manusia. Karenanya, kita wajib membenci dan menolak kasb manusia berupa kufur dan maksiat, bukan malah membenci qadhā’ dan qadar Allah.”
Imām al-Asy‘arī dan Imām al-Māturīdī berbeda pendapat dalam mendefinisikan qadhā’ dan qadar Allah. Menurut Imām al-Asy‘arī, qadar adalah penciptaan Allah pada sesuatu disertai irādah-Nya. Dari sini bisa dipahami bahwa qadar adalah sifat dari pekerjaan, maka qadar adalah sesuatu yang baru. Sedangkan qadhā’ adalah irādah Allah. qadhā’ merupakan sifat Dzāt, maka qadhā’ adalah qadīm (dahulu).
الْأَشْيَاءُ فِي الْأَزَلِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ فِيْمَا لَا يَزَالُ.
“Kondisi sesuatu di zaman azali, sesuai dengan kondisi saat ini.”
Sedangkan menurut Imām al-Māturīdī, qadhā’ adalah penciptaan Allah pada sesuatu. Dari sini bisa difahami bahwa qadar adalah sifat pekerjaan, maka qadar adalah sesuatu yang baru. (92).
Kesimpulannya, menurut Imām al-Asy‘arī, qadar adalah ḥadīs (baru), sedangkan qadhā’ adalah qadīm (dahulu), sedangkan menurut Imām al-Māturīdī, qadhā’ adalah ḥadīts (baru).
Setelah seorang mukallaf mengetahui bahwa iman pada qadhā’ dan qadar wajib, maka tidak diperbolehkan beralasan dengan menggunakan qadhā’ dan qadar yang belum terjadi. Misal, seseorang yang akan berbuat zina berkata: “Sudah menjadi qadar dan kehendak Allah bahwa aku akan melakukan zina.” Ucapan seperti ini haram, bahkan dosanya lebih besar dibandingkan melakukan zina, atau setelah melakukan zina seseorang berkata: “Sudah menjadi qadar dan kehendak Allah aku berzina”, ucapan tersebut sebagai dalih agar tidak terkena had zina, hukumnya tetap haram. (93).
Adapun jika beralasan dengan qadhā’ dan qadar yang telah terjadi untuk menolak orang-orang yang mencelanya, maka diperbolehkan. (94) Misal, ada seseorang yang mencela atau menghina pengemis atau orang yang bermaksiat, kemudian orang yang dihina berkata: “Wahai fulan, adakah orang yang suka jika dia menjadi orang miskin? Dan siapa yang suka jika kelak akan masuk neraka? Aku juga ingin menjadi orang kaya, bukan pengemis, aku ingin menjadi orang yang taat beribadah, bukan ahli maksiat, tapi qadar dan kehendak Allah menjadikan aku seperti ini.”
Ucapan seperti itu diperbolehkan, sebagaimana penjelasan hadits yang menceritakan bahwa rūḥ Nabi Ādam a.s. bertemu dengan rūḥ Nabi Mūsā kalīmullāh.
Nabi Mūsā a.s. bertanya kepada Nabi Ādam a.s.: “Wahai ayahanda, Nabi Ādam, engkau adalah ayah semua manusia, mengapa engkau menjadi penyebab keluarnya anak cucumu dari surga dengan memakan buah dari pohon yang terlarang?”
Nabi Ādam a.s. menjawab: “Wahai Mūsā, engkau adalah orang yang telah dipilih oleh Allah untuk diberi firman secara langsung, Allah juga memberimu kitab Taurāt, bagaimana bisa engkau mencelaku dalam hal yang telah ditetapkan oleh Allah terhadapku? 40 tahun sebelum penciptaanku, Allah telah menetapkan bahwa aku akan makan buah pohon itu.” Jawaban Nabi Ādam tak terbantahkan, dan Nabi Mūsā pun terdiam. (95)
Perkataan Syaikh Ibrāhīm al-Laqqānī (كَمَا أَتَى فِي الْخَبَرِ.) maksudnya adalah sebagaimana sabda Rasūlullāh s.a.w.: “Seseorang belum beriman (secara sempurna) sebelum meyakini empat hal: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, beriman bahwa aku adalah utusan Allah, beriman adanya hari kebangkitan setelah mati, dan beriman pada qadar Allah, baik-buruknya, manis-pahitnya, semua dari Allah”. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam rukun iman. (96).