Hukum Sah – Terjemah Syarah al-Waraqat
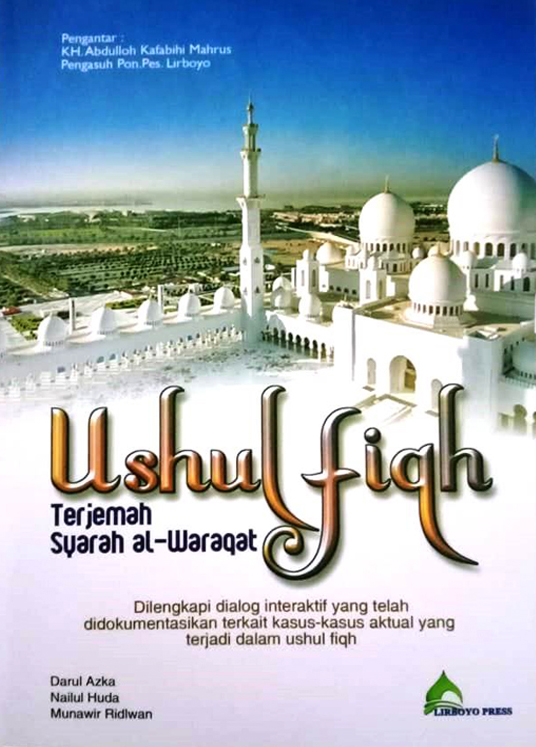
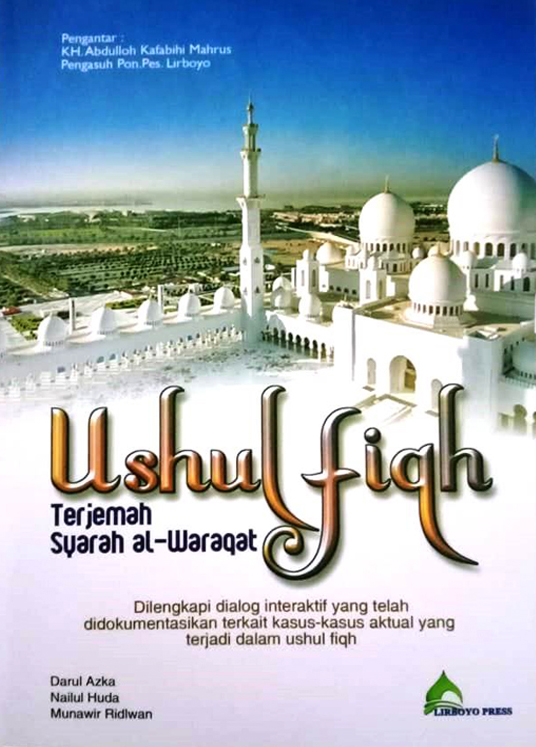
(وَ الصَحِيْحُ) مِنْ حَيْثُ وَصْفُهُ بِالصِّحَّةِ (مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النُّفُوْذُ وَ يُعْتَدُّ بِهِ) بِأَنِ اسْتَجْمَعَ مَا يُعْتَبَرُ فِيْهِ شَرْعًا، عَقْدًا كَانَ أَوْ عِبَادَةً.
Sah ditinjau dari sesuatu itu disifati sah yaitu perkara yang berkaitan dengan nufūdz, dan i‘tidād. Yakni di saat perkara tersebut telah melengkapi hal-hal yang dipertimbangkan syara‘, baik berupa akad atau ibadah.
Hukum shaḥīḥ ialah:
(مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النُّفُوْذُ وَ يُعْتَدُّ بِهِ)
“Sesuatu yang telah berhubungan dengan nufūdz, dan i‘tidād.”
Nufūdz adalah tercapainya suatu tujuan, seperti jual-beli, tujuannya ialah supaya pembeli dapat memiliki barang yang dibeli dan penjual dapat hak milik atas uang yang diterima. Sedangkan i‘tidād ialah telah melengkapinya seseorang atas perkara yang telah ditetapkan syara‘ seperti syarat dan rukun.
Dari pengertian di atas, ketika ibadah diyatakan sah, berarti syarat dan rukun di dalamnya telah terpenuhi (dalam ibadah tidak ada istilah nufūdz). Dan ketika jual-beli dinyatakan sah, maka artinya jual-beli tersebut telah berkaitan dengan dua hal. Pertama, nufūdz, dengan pengertian pembeli boleh menggunakan barang yang dibeli, begitu juga pihak penjual mendapat hak milik atas uang yang diterima. Kedua, i‘tidād, dengan pengertian si pembeli dan penjual telah melaksanakan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual-beli.
Catatan: secara istilah, akad dapat disifati dengan nufūdz dan i‘tidād. Sedangkan ibadah hanya disifati dengan i‘tidād saja.
Apakah standar atau tolok ukur sah tidaknya ibadah atau akad?
Jawab:
Dalam ibadah ada dua aspek, persangkaan orang mukallaf dan kenyataan sebenarnya. Sedangkan dalam akad hanya kenyataan sebenarnya.
Referensi:
(قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَسْتَجْمِعْ) الخ….. ثُمَّ الْعِبْرَةُ فِي استِجْمَاعِهِ الشُّرُوْطِ أَوْ عَدَمِ اسْتِجْمَاعِهِ فِي الْعِبَادَاتِ بِمَا فِيْ ظَنِّ الْمُكَلَّفِ وَ نَفْسِ الْأَمْرِ فَلِذَا لَوْ صَلَّ عَلَى اعْتِقَادِ أَنَّهُ مُطَهِّرٌ فَبَانَ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَنَّهُ مُحْدِثٌ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ يَكُوْنُ أَدَاءً إِنْ بَقِيَ الْوَقْتُ وَ قَضَاءً إِنْ خَرَجَ الْوَقْبُ وَ بِمَا فِي الْوَاقِعِ فِي الْعُقُوْدِ فَلِذَا لَوْ بَاعَ مَالَ مُوَرَّثَهُ مُعْتَقِدًا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَوْتَهُ صَحَّ الْبَيْعُ. (النَّفَحَاتُ صــــ 22).
“(Ucapan pensyarah: tidak melengkapi) ….. tolok ukur melengkapi syarat atau belum dalam permasalahan ibadah yaitu sesuai dengan persangkaan orang mukallaf dan juga kenyataan sebenarnya. Dengan demikian seumpama ada seseorang melakukan shalat dengan berkeyakinan dirinya telah suci, namun setelah shalat ternyata nyata-nyata ia berhadats, maka ia wajib mengulangi shalatnya, dan dihukumi adā’ jika waktu shalat masih tersisa, dan dihukumi qadha’ jika waktu sudah habis. Dan dalam permasalahan akad, yang menjadi tolok ukur yaitu kenyataan sebenarnya. Dengan demikian seumpama ada seseorang yang menjual harta orang yang akan diwarisinya (semisal ayahnya) dengan berkeyakinan bahwa ayahnya masih hidup, namun kenyataannya ternyata ayahnya sudah meninggal, maka penjuanlannya dianggap sah.”