Hukum Muqallad Dalam Masalah ‘Aqidah – Terjemah Kifayat-ul-‘Awam
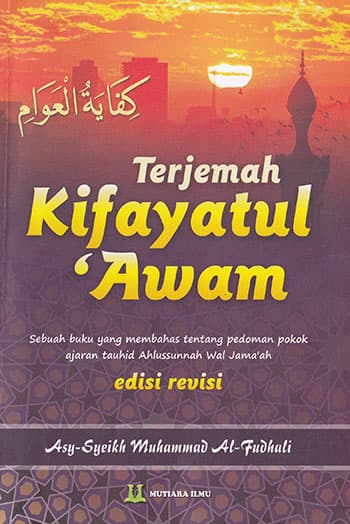
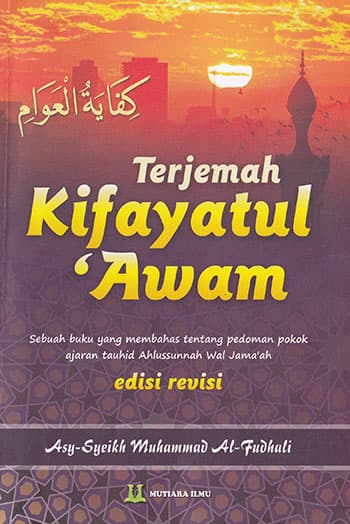
وَ أَمَّا التَّقْلِيْدُ وَ هُوَ أَنْ يَعْرِفَ الْعَقَائِدَ الْخَمْسِيْنَ وَ لَمْ يَعْرِفْ لَهَا دَلِيْلًا إِجْمَالِيًّا أَوْ تَفْصِيْلِيًّا فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَكْفِي التَّقْلِيْدُ وَ الْمُقَلِّدُ كَافِرٌ وَ ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ الْعَرَبِيِّ وَ السَّنُوْسيُّ وَ أَطَالَ فِيْ شَرْحِ الْكُبْرَى فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ يَقُوْلُ بِكِفَايَةِ التَّقْلِيْدُ لكِنْ نُقِلَ أَنَّ السَّنُوْسِيَّ رَجَعَ عَنْ ذلِكَ وَ قَالَ بِكِفَايَةِ التَّقْلِيْدِ لكِنْ لَمْ نَرَ فِيْ كُتُبِهِ إِلَّا الْقَوْلَ بِعَدَمِ كِفَايَتِهِ.
“Adapun taqlīd ya‘ni mengetahui ‘aqīdah-‘aqīdah yang 50 dan tidak mengetahui akan dalīl-nya yang ijmālī atau tafshīlī maka para ‘ulamā’ berbeda pendapat dalam hal ini.”
Sebagian ‘ulamā’ berkata: “Tidak mencukupi taqlīd itu dan orang yang bertaqlīd adalah kafir.” Ibn-ul-‘Arabī (ya‘ni: Imām Abū Bakar al-Faqīh) dan Sanūsī mengikuti pendapat ini. Dan di dalam Kitab (شَرْحِ الْكُبْرَى) Syarḥ-il-Kubrā, Sanūsī memperpangjang pembicaraan dalam hal penolakannya atas orang yang berkata dengan kecukupan taqlīd. Akan tetapi kami tidak pernah melihat dalam kitab-kitabnya kecuali perkataan dengan ketiadaan cukupnya taqlīd itu.”
Perselisihan ‘ulamā’ dalam hal taqlīd bermula dari perselisihan mereka perihal “Hukum Nazhar (berfikir) dalam masalah ‘aqīdah-‘aqīdah tersebut yang kesimpulannya adalah sebagai beriktu:
– Pendapat pertama menunjukkan cukupnya taqlīd dalam masalah iman. Akan tetapi beserta durhaka secara mutlak (baik dia punya kemampuan berfikir atau tidak).
– Pendapat kedua juga menunjukkan cukupnya taqlīd dalam masalah iman. Akan tetapi beserta durhaka jika dia punya kemampuan untuk berfikir. Sedangkan jika dia tidak punya kemampuan untuk berfikir maka tidak durhaka. Pendapat inilah yang benar.
– Pendapat ketiga menunjukkan tidak cukupnya taqlīd dalam masalah iman dan orang-orang yang bersifat dengan taqlīd itu adalah kafir.
– Pendapat keempat menunjukkan cukupnya taqlīd secara mutlak.
Sebagian orang ada yang mencela ‘Ilmu Kalām dan menyatakan haram berfikir dalam masalah tersebut. Pendapat ini sangat dha‘īf dan bagi orang yang berakal dia tidak ragu-ragu perihal rusaknya.
Berkata al-Yūsī: “Dan Sanūsī telah menasabkan pendapat ini di dalam Kitab (شَرْحُ الْوُسْطَى) kepada sebagian golongan Mubtadi‘ah (الْمُبْتَدِعَةِ) di mana beliau (Sanūsī) berkata: Dan apa-apa yang telah dihikayatkan dari sebagian golongan Mubtadi‘ah seperti Haswiyyah dan yang lainnya perihal haramnya berfikir dalam masalah Tauḥīd maka bagi siapa saja yang berakal tidaklah samar-samar perihal rusak dan sesatnya orang yang mengi‘tiqādkannya karena pendapat tersebut bertentangan dengan al-Qur’ān, Sunnah dan Ijma‘ kaum muslimin. Dan mengenai apa yang mereka campur-baurkan dengannya di mana para sahabat radhiyallāhu ‘anhum tidak pernah membicarakannya adalah merupakan satu kebohongan dan perbuatan yang mengada-ada.
Dan sungguh telah dikatakan orang kepada Qādhī Abū Thayyib bahwa ada satu kaum mencela ‘Ilmu Kalām, maka beliau mendendangkan syairnya:
عَابَ الْكَلَامُ أُنَاسٌ لَا خَلَاقَ لَهُمْ
وَ مَا عَلَيْهِ إِذَا عَابُوْهُ مِنْ ضَرَرٍ
مَا ضَرَّ شَمْسُ الضُّحَى فِي الْأُفُقِ طَالِعَةْ
أَنْ لَا يَرَى ضَوْئَهَا مَنْ لَيْسَ ذَا بَصَرٍ.
“Orang-orang yang tidak mempunyai bagian itu telah mencela ‘Ilmu Kalām dan tidaklah berbahaya atas ‘Ilmu Kalām jika mereka mencelanya.
Matahari pagi yang sedang terbit di Ufuq Timur tidak rusak lantaran orang yang tidak mempunyai mata tidak dapat melihat cahayanya.”
Tempat tidak benarnya ucapan orang yang mencela ‘Ilmu Kalām itu adalah jika ‘Ilmu Kalām tersebut masih tetap pada zhāhir-nya (apa adanya). Tetapi jika yang dimaksud oleh mereka itu ‘Ilmu Kalām yang sudah bercampur dengan filsafat maka pencelaan mereka itu adalah benar. Dan mungkin ‘Ilmu Kalām yang seperti inilah yang dimaksud oleh Imām Syāfi‘ī dalam ucapannya:
لَأَنْ يَلْقَى الْعَبْدُ رَبَّهُ بِكُلِّ ذَنْبٍ مَا عَدَا الشِّرْكِ أَحْسَنُ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ بِعِلْمِ الْكَلَامِ.
“Sungguh bahwa seorang hamba yang menemui Tuhannya dengan segala macam dosa selain syirik adalah lebih baik daripada dia menemui-Nya dengan ‘Ilmu Kalām.”
Perkataan sebagian ‘Ulamā’ dengan (لَا يَكْفِي التَّقْلِيْدُ) ya‘ni tidak cukup taqlīd itu dalam hal iman tentunya didasarkan pada hukum berfikir yang wājib sebagaimana wajib ushūl seperti yang sudah diterangkan perkataan sebagian ‘Ulamā’ yang seperti itu mengandung satu kemusykilan karena melazimkan adanya pengkafiran sebagian besar orang mu’min yang awam. Dan yang demikian itu termasuk aib karena Nabi Muḥammad s.a.w. adalah yang paling banyak pengikutnya berdasarkan riwayat yang menerangkan bahwa ummat Muḥammad Yang Mulia itu adalah 2/3 penduduk surga.
Dalam hal ini, Sanūsī menjawab di dalam (شَرْحِ الْصُّغْرَى) bahwa yang dimaksud dengan dalīl yang wajib atas sekalian mukallaf untuk mengetahuinya adalah dalīl ijmālī dan tidak diragukan bahwa dalīl tersebut tidak begitu sulit mencapainya bagi sebagian bersar ummat. Maka tidaklah disyaratkan cara berfikir sebagaimana orang-orang Mutakallimīn berupa penguraian dalīl dan sistematika (pengaturan)-nya serta menolak segala keraguan yang timbul atasnya bahkan tidak disyaratkan adanya kemampuan untuk mengungkapkan dalīl-dalīl ijmālī yang sudah bermuara di dalam hati.