Fiqh Tradisionalis – Bab I Muqaddimah – Seputar Taqlid
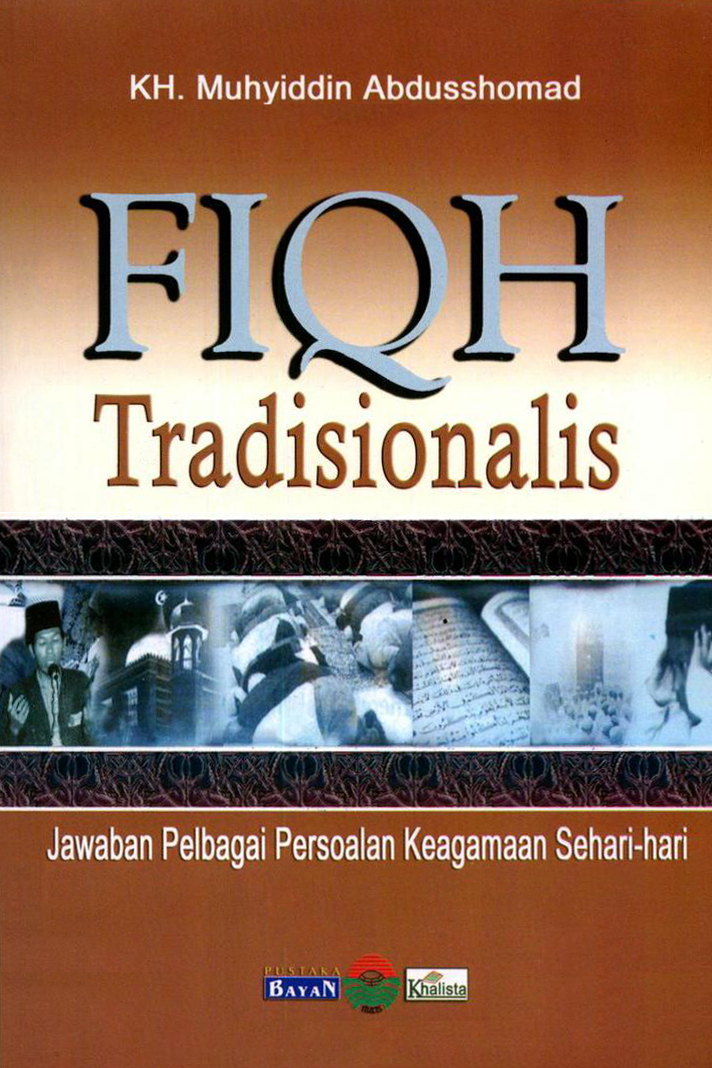
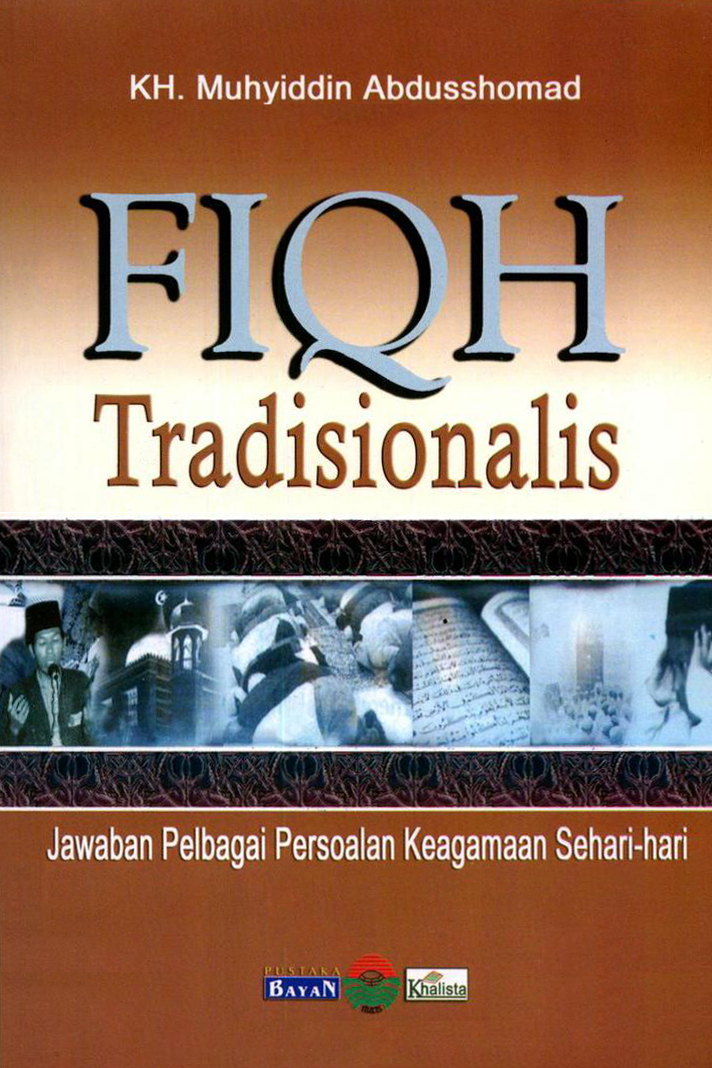
Soal:
Secara kodrati, manusia di dunia ini terbagi menjadi dua kelompok besar. Ada yang ‘alim (pintar dan cerdas serta ahli dalam bidang tertentu) dan ada ‘awam (yang kurang mengerti dan memahami suatu permasalahan). Sudah tentu yang tidak paham butuh bantuan yang pintar. Di dalam literatur fiqh, hal itu dikenal dengan istilah taqlid atau ittiba’. Lalu apa yang dimaksud dengan taqlid atau ittiba’ itu? Dan apa perbedaan antara keduanya?
Jawab:
Muhammad Sa’id Ramadhân al-Bûthi mendefinisikan taqlid sebagai berikut:
والتقليد هو اتباع قول انسان دون معرفة الحجة على صحة ذلك القول ، وان توفرت معرفة الحجة على صحة التقليد نفسه . (اللامذهبية اخطر بدعة تهدد الشريعة الاسلامية ، ٦٩.)
“Taqlid adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengerti dalil yang digunakan atas keshahihan pendapat tersebut, walaupun mengetahui tentang keshahihan hujjah taqlid itu sendiri. “1(Al-Lâmadzhabiyyah Akhtharu Bid’ah Tuhaddid al-Syari’ał. al-Islâmiyyah, 69).
Taqlid itu hukumnya haram bagi seorang mujtahid dan wajib bagi orang yang bukan mujtahid. Imam al-Suyûthî mengatakan:
ثم الناس مجتهد وغيره . فغير المجتهد يلزمه التقليد مطلقا . عاميا كان أو عالما ، لقوله تعالى : فاسئلوا أهل الــــــــذكر إن كنتم لاتعلمون .(الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع . ج۲ ص ٤٩٢).
“Kemudian, manusia itu ada yang menjadi mujtahid dan ada yang tidak. Bagi yang bukan mujtahid wajib bertaqlid secara mutlaq, baik ia seorang awam ataupun orang yang alim. Berdasarkan firman Allah SWT (QS. Al-Anbiya’ 7), “Bertanyalah kamu kepada orang yang ahli (dalam bidangnya) jika kalian tidak tahu.” (Al-Kawkab al-Sâthi’ fî Nazhm Jam’ al-Jawâmi’, 492).
Dengan demikian, taqlid itu tidak hanya terbatas pada orang awam saja. Orang-orang ‘alim yang sudah mengetahui dalil pun masih dalam kategori seorang muqallid. Selama belum sampai pada tingkatan mujtahid, mereka tetap wajib ber-taqlid, sebab pengetahuan mereka hanya sebatas dalil yang digunakan, tidak sampai kepada proses, metode dan seluk-beluk dalam menentukan suatu hukum. Al-‘Allamah Thayyib bin Abi Bakr al-Hadhrami menegaskan:
أما العالم الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد فهو كالعامي في وجوب التقلــيد (مطلب الإيقاظ فيا الكلام على شيء من غرر الألفاظ ، ۸۷)
“Orang ‘alim yang tidak sampai pada tingkatan ijtihad, maka hukumnya seperti orang awam, dalam hal kewajiban ber-taqlid” (Mathlab al. iqâzh fi al-Kalâm ‘alâ Syai’in min Ghurar al-Alfâzh, 87)
Jadi, tidak semua taqlid itu tercela. Yang tidak terpuji hanyalah taqlid buta (a’maa) yang menerima suatu pendapat mentah-mentah, tanpa mengerti dan berusaha untuk mengetahui dalilnya. Sedangkan taqlid nya orang ‘alim yang belum sampai pada tingkatan mujtahid, adalah hal yang terpuji bahkan dianjurkan. Hal itu tentu lebih baik daripada ‘memaksakan’ dia untuk berijtihad padahal tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya.
Taqlid adalah sesuatu yang niscaya bagi setiap orang Islam. Setidak-tidaknya ketika awal melaksanakan bagian dari ajaran Islam. Seperti orang yang bersedekap di dalam shalat, mengangkat tangan ketika takbiratul ihrâm, dia tentu melakukannya walaupun masih belum meneliti dalilnya, apakah shahih ataukah tidak.
Jika di kemudian hari dia tahu argumentasinya, maka kala berarti dia telah keluar dari taqlid a’mâ (taqlid buta) yang tercela itu. Namun demikian dia tetap berstatus sebagai seorang muqallid, karena tidak tahu dalil-dalil tersebut secara detail. Setidaknya, dalam cara mengambil suatu kesimpulan hukum, ia masih mengikuti metode dari imam mujtahid tertentu.
Taqlid itu sesungguhnya berlaku dalam berbagai persoalan di dalam kehidupan ini. Seorang dokter, misalnya, ketika memberikan resep obat kepada pasiennya, tentu dia mengambilnya dari apotik, bukan dari obat hasil temuannya sendiri. Dia cukup membeli produk perusahaan obat tertentu yang bonafit. Begitu juga seorang guru Geografi ketika menerangkan kepada murid muridnya bahwa bumi itu bulat, dia hanya mengikuti teori Galileo Galilei dan Thomas Copernicus, bukan dari hasil penelitiannya sendiri. Dan begitu seterusnya.
Kemudian, bagaimana dengan Imam Abû Dâwûd yang meriwayatkan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal:
وقال لي أحمد لا تقلدني ولا مالكا ولا الـشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا . (القــول المفيد للإمام محمد بـن على الشوكاني 61).
“Imam Ahmad berkata kepadaku, “Janganlah kamu ber-taqlid kepadaku, juga kepada Imam Malik, Imam Syafi’i, al-Auza’i, dan al-Tsauri. Tapi galilah dalil-dalil hukum itu sebagaimana yang mereka lakukan.” (Al-Qawl al-Mufid li al-Imâm Muhammad bin ‘Ali al-Syawkânî, 61).
Coba perhatikan dengan seksama, kepada siapa Imam Ahmad bin Hanbal berbicara? Beliau menyampaikan ucapan itu kepada Abû Dâwûd pengarang Kitab Sunan Abi Dawud yang memuat lima ribu dua ratus delapan puluh empat hadits lengkap dengan sanadnya. Tidak kepada masyarakat kebanyakan. Sehingga wajar, kalau Imam Ahmad mengatakan hal itu kepada Imam Abu Dawud, sebab ia telah memiliki kemampuan untuk berijtihad. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Syaikh Waliyullah al-Dahlawi ketika mengomentari pendapat Ibn Hazm:
“Pendapat Ibn Hazm yang mengatakan bahwa taqlid itu haram dan seterusnya) itu hanya berlaku bagi orang yang mempunyai kemampuan ijtihad walaupun hanya dalam satu masalah.” (Hujjatullah al-Balighah, juz 1, hal 443-444).
Membebani ‘awam al-muslimin (masyarakat kebanyakan) dengan ijtihad sendiri-sendiri, jelas memberatkan dan mustahil karena minat setiap orang pada bidang-bidang ilmu pengetahuan itu berbeda-beda. Sedangkan yang menekuni ilmu agama tidak banyak. Bagi yang “tidak sempat” mempelajari ilmu agama, ia harus bertanya dan mengikuti orang-orang yang paham tentang masalah agama.
Al-Qur’an sudah menyatakan agar ada sekelompok orang yang menekuni ilmu agama, tidak perlu semuanya. Sehingga mereka dapat memberikan fatwa kepada yang lainnya. Allah SWT berfirman:
“Tidak seharusnya semua orang mukmin berangkat ke medan perang Mengapa tidak berangkat satu rombongan dari tiap-tiap golongan untuk mempelajari dengan mendalam ilmu agama agar mereka dapat memberikan peringatan (pelajaran) kepada kaumnya apabila mereka sudah kembali. Mudah-mudahan mereka waspada.” (QS. al-Taubah, 122).
Sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang terpilih. Meskipun begitu, kualitas keilmuan mereka tidak sama, dan tidak semua mereka menjadi mujtahid. Sebagian mereka menjadi mufti, sebagian lain bertanya dan mengikuti apa yang difatwakan sahabat yang lain. Dan Rasûlullah SAW mengutus beberapa sahabat ke berbagai daerah untuk menyebarkan agama Islam serta menyelesaikan semua persoalan yang terjadi, baik dalam bidang ibadah dan mu’amalat, sosial kemasyarakatan, menjelaskan halal haram dan semacamnya. Lalu penduduk di daerah itu mengikuti apa yang difatwakan para sahabat tersebut.
Kaitannya dengan ittibâ’, sebagian orang ada yang membedakan dengan taqlid. Namun sebenarnya tidak ada perbedaan dalam kedua kata itu. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Syaikh al-Búthi:
ولا فرق بين أن يسمى هذا العمل تقليدا أواتباعا. فكلاهما بمعنى واحد، ولم يثبت أي فرق لغوي بينهما. (اللامذهيبة أخطر بـدعة تهدد الشريعة الإسلامية، ص ٦٩).
“Tidak ada perbedaan kalau perbuatan itu disebut dengan taqlid atau ittiba. Sebab kedua kata itu mempunyai arti yang sama. Dan tidak terbukti adanya perbedaan secara bahasa antara keduanya.” (Al Lâmadzhabiyyah Akhtharu Bid’ah Tuhaddid al-Syari’ah al Islâmiyah, 69).
Bahkan kata ittiba’ tidak selalu berarti baik. Tidak jarang di dalam al-Qur’ân, ittibâ’ ditujukan untuk sesuatu yang tidak terpuji, sebagaimana firman Allah SWT:
و لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين . (البقرة ، ١٦٨)
“Dan janganlah kamu mengikuti (ittibâ’) langkah-langkah setan, karena sesungguhnya dia merupakan musuh yang nyata bagi kalian.” (QS. Al-Baqarah, 168).
Berdasarkan hal tersebut berarti taqlid merupakan sunnatullah (hukum alam) yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya ataupun diperjuangkan untuk dihapus. Namun demikian, bukan berarti umat Islam harus terperangkap pada taqlid buta, karena akan menggambarkan keterbelakangan serta rendahnya kualitas individu umat Islam. Itulah sebabnya ulama pesantren mencetak ulama yang mumpuni.