Fiqh Tradisionalis – Bab I Muqaddimah – Masalah Hadits Dha’if
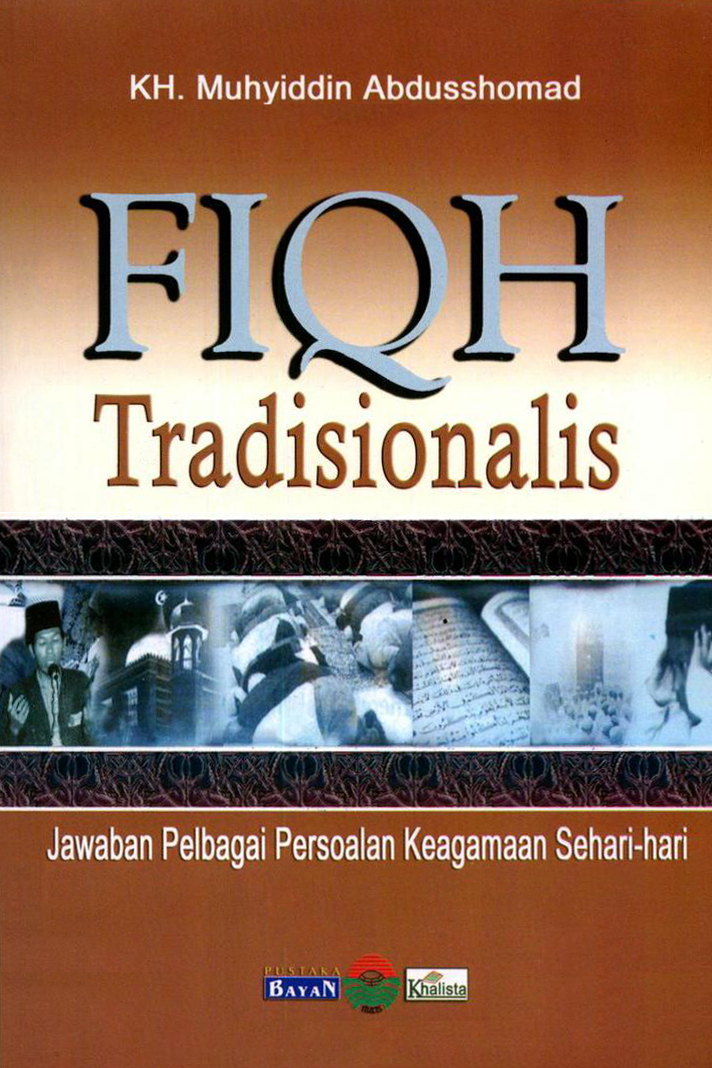
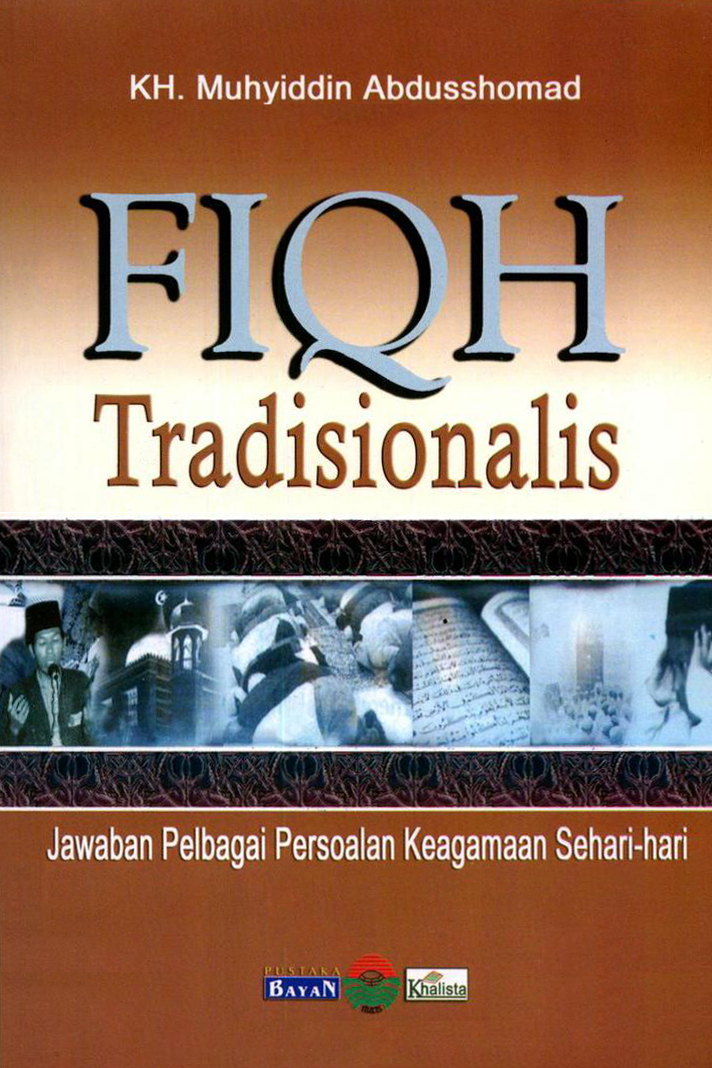
Soal:
Sebagai salah satu sumber hukum Islam, Hadits berfungsi menjelaskan, mengukuhkan serta ‘melengkapi’ firman Allah SWT yang terdapat dalam al-Qur’ân. Di antara berbagai macam Hadits itu, ada istilah Hadits Dha if. Dalam pengamalannya, terjadi silang pendapat di antara ulama. Sebagian kalangan ada yang tidak membenarkan untuk mengamalkan Hadits Dha’if. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Hadits tersebut bukan dari Nabi Muhammad SAW. Lalu apakah sebenarnya yang disebut Hadits Dha’if itu? Benarkah kita tidak boleh mengamalkan Hadits Dha’if?
Jawab:
Secara umum Hadits itu ada tiga macam. Pertama, Hadits Shahih, yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang adil, punya daya ingatan yang kuat, mempunyai sanad (mata rantai orang-orang yang meriwayatkan Hadits) yang bersambung ke Rasûlullah SAW, tidak memiliki kekurangan serta tidak syadz (menyalahi aturan umum). Para ulama sepakat bahwa hadits ini dapat dijadikan dalil, baik dalam masalah hukum, aqidah dan lainnya. Kedua, Hadits Hasan, yakni hadits yang tingkatannya berada di bawah Hadits Shahih, karena para periwayat hadits ini memiliki kualitas yang lebih rendah dari para perawi Hadits Shahih. Hadits ini dapat dijadikan sebagai dalil sebagaimana Hadits Shahih. Ketiga, Hadits Dha’if, yakni hadits yang bukan Shahih dan juga bukan Hasan, karena diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai perawi Hadits, atau para perawinya tidak mencapai tingkatan sebagai perawi Hadits Hasan.
Hadits Dha’if ini terbagi menjadi dua. Pertama, ada riwayat lain yang dapat menghilangkan dari ke-dha’if-annya. Hadits semacam ini disebut Hadits Hasan li Ghairih, sehingga dapat diamalkan serta boleh dijadikan sebagai dalil syar’i. Kedua, hadits yang tetap dalam ke-dha’if-annya. Hal ini terjadi karena tidak ada riwayat lain yang menguatkan, atau karena para perawi hadits yang lain itu termasuk orang yang dicurigai sebagai pendusta, tidak kuat hafalannya atau fasiq.
Dalam kategori yang kedua ini, para ulama mengatakan bahwa Hadits Dha’if hanya dapat diberlakukan dalam fadhâ’il al-a’mal1. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa telah terjadi ijma’ di kalangan ulama tentang kebolehan mengamalkan Hadits Dha’if jika berkaitan dengan fadha’il al-a’mâl ini. Sedangkan dalam masalah hukum, tafsir ayat al-Qur’an, serta akidah, maka apa yang termaktub dalam Hadits Dha’if tersebut tidak dapat dijadikan pedoman. Sebagaimana yang disitir oleh Sayyid ‘Alawi al-Mâliki dalam kitabnya Majmu’ Fatawi wa Rasâ’il:
أجمع أهل الحديث وغيرهم على أن الحـــــــديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال وممن قال بذلك الإمام أحمد ابن حنبل وابن المبارك والـسـفيانان والعنبري وغيرهم . فقد نُقل عنهم أنهم قالوا إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل تساهلنا . (مجموع فـتـاوىورسائل، ٢٥١).
“Para ulama ahli hadits dan lainnya sepakat bahwa Hadits Dha’if dapat dijadikan pedoman dalam masalah fadhâ’il al-a’mal. Diantara ulama yang mengatakannya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Ibn Mubarak, dua Sufyan, al- Anbari, serta ulama lainnya. (Bahkan) Ada yang menyatakan, bahwa mereka pernah berkata, “Apabila kami meriwayatkan (hadits) menyangkut perkara halal ataupun yang haram, maka kami akan berhati-hati. Tapi apabila kami meriwayatkan hadits tentang fadhâ’il al-a’mâl, maka kami melonggarkannya.” (Majmû’ Fatâwî wa Rasa’il, 251)
Bahkan Imam Ahmad mengatakan:
ان ضعيف الحديث يقدم على رأي الرجال (مجموع فتاوى ورسائل ، ٢٥١)
“Sesungguhnya hadits dha’if itu didahulukan dari pendapat seseorang.” (Majmu’ Fatawi wa Rasa’il, 251)
Namun begitu, kebolehan ini harus memenuhi tiga syarat2. Pertama, bukan hadits yang sangat dha’if. Karena itu, tidak boleh mengamalkan hadits yang diriwayatkan oleh orang yang sudah terkenal sebagai pendusta, fasiq, orang yang sudah terbiasa berbuat salah dan semacamnya. Kedua, masih berada di bawah naungan ketentuan umum serta kaidah-kaidah yang universal. Dengan kata lain, hadits tersebut tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama, tidak sampai menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ketiga, tidak berkeyakinan bahwa perbuatan tersebut berdasarkan Hadits Dha’if, namun perbuatan itu dilaksanakan dalam rangka ihtiyâth (berhati-hati dalam masalah agama)3.
Maka, dapat kita ketahui, walaupun Hadits Dha’if diragukan kebenarannya, namun tidak serta-merta ditolak dan tidak dapat diamalkan. Dalam hal-hal tertentu masih diperkenankan mengamalkannya dengan syarat-syarat sebagai mana tersebut di atas.