Dalil Ijmali dan Tafshili – Terjemah Kifayat-ul-‘Awam
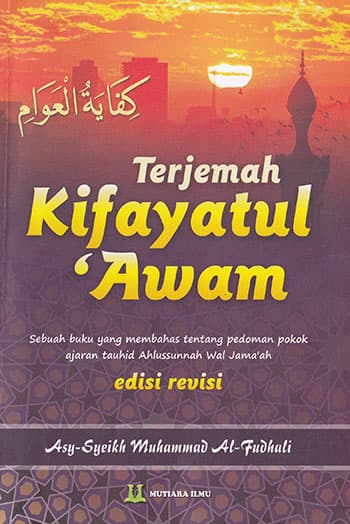
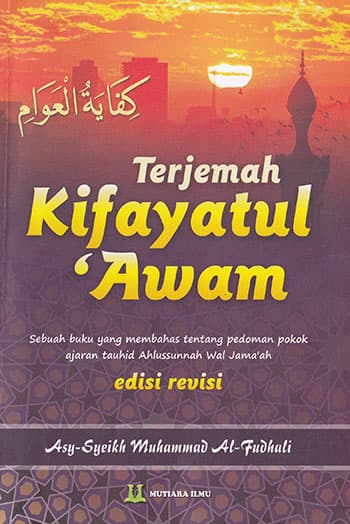
قَالَ بَعْضُهُمْ يُشْتَرَطَ أَنْ يَعْرِفَ الدَّلِيْلَ التَّفْصِيْلِيِّ لكِنِ الْجُمْهُوْرُ عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي الدَّلِيْلُ الْإِجْمَالِيْ لِكُلِّ عَقِيْدَةٍ مِنْ هذِهِ الْخَمْسِيْنَ.
“Berkata sebagian mereka (para ‘ulamā’): Disyaratkan agar setiap muslim mengetahui dalīl yang tafshīlī. Akan tetapi jumhur (sebagian besar ‘ulamā’ ‘Ilmu Kalām) menetapkan bahwa cukup dalīl ijmālī bagi setiap ‘aqīdah yang 50 ini.”
وَ الدَّلِيْلُ التَّفْصِيْلِيُّ مِثَالُهُ إِذَا قِيْلَ مَا لدَّلِيْلُ عَلَى وُجُوْدِهِ تَعَالَى أَنْ يُقَالُ هذِهِ الْمَخْلُوْقَاتُ فَيَقُوْلُ لَهُ السَّائِلُ الْمُخْلُوْقَاتُ دَالَّةٌ عَلَى وُجُوْدِ اللهِ تَعَالَى مِنْ جِهَةِ إِمْكَانِهَا أَوْ مِنْ جِهَةِ وُجُوْدِهَا بَعْدَ عَدَمٍ فَيُجِيْبُهُ.
“Dan dalīl tafshīlī itu, misalnya adalah: jika dikatakan apakah dalīl atas wujudnya Allah s.w.t.? Maka dijawablah dengan “sekalian makhluq ini!” Lantas si penanya berkata kepadanya (penjawab): sekalian makhluq itu menunjukkan atas wujudnya Allah s.w.t. dari segi imkān-nya atau dari segi wujudnya sesudah tidak ada (‘adam)? Maka ia pun menjawabnya.”
Maksudnya: Setelah ditanya tentang dalīl dari wujudnya Allah s.w.t. lantas dia menjawab dengan sekalian makhluq ini, kemudian si penanya mengembangkan jawaban tersebut dengan bertanya lagi bahwa kalau sekalian makhluq ini sebagai dalil wujudnya Allah s.w.t. maka manakah jihat dilālah (arah pendalilan)nya? Apakah dari imkān-nya makhluq ini ataukah dari segi adanya makhluq ini sesudah tidak ada? Maka diapun tidak diam melainkan kembali menjawab pertanyaan yang kedua tersebut dengan berkata: sekalian makhluq ini menunjukkan atas wujudnya Allah s.w.t. dari segi imkān-nya dan diapun juga menerangkan wajh-ud-dilālah (bentuk pendalilan)nya dengan berkata “sekalian makhluq ini adalah mumkin (bisa ada, bisa pula tidak ada) dan setiap yang mungkin haruslah mempunyai dzāt yang menjadikan. Dan dzāt itu tentunya adalah Allah” Ini kalau dia memilih bahwa bahwa jihat dilālah itu adalah imkān.
Dan jika dia memilih bahwa jihat dilālah itu adalah wujūd ba‘da ‘adam maka diapun akan berkata “sekalian makhluq ini ada sesudah tidak ada dan setiap yang ada sesudah tidak ada haruslah dia mempunyai dzāt yang menjadikan(-nya ada), maka sekalian makhluq ini haruslah mempunyai dzāt yang menjadikan. Dan dzāt itu tentunya adalah Allah.
وَ أَمَّا إِذَا لَمْ يُجِبْهُ بَلْ قَالَ لَهُ هذِهِ الْمَخْلُوْقَاتُ فَقَطْ وَ لَمْ يَعْرِفْ مِنْ جِهَةِ إِمْكَانِهَا أَوْ وُجُوْدِهَا بَعْدَ عَدَمٍ فَيُقَالُ لَهُ دَلِيْلٌ إِجْمَالِيٌّ وَ هُوَ كَافٍ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ.
“Dan jika dia tidak menjawabnya melainkan dia berkata kepada si penanya dengan: sekalian makhluq ini saja sedangkan dia tidak mengetahui (apakah) dari segi imkān-nya atau dari segi wujudnya sesudah tidak ada maka dikatakanlah (ucapan dengan (هذِهِ الْمَخْلُوْقَاتُ) itu), dalīl ijmālī. Dan dia (dalīl ijmālī) adalah cukup menurut jumhur.”