Biografi Beliau Secara Global Sebelum Kenabian – Ar-Rahiq-ul-Makhtum – al-Mubarakfuri
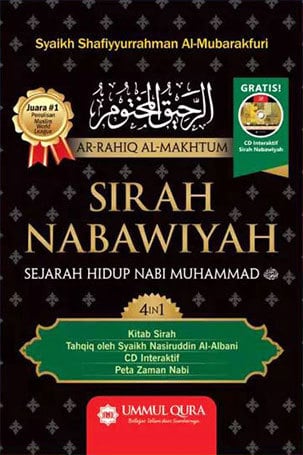
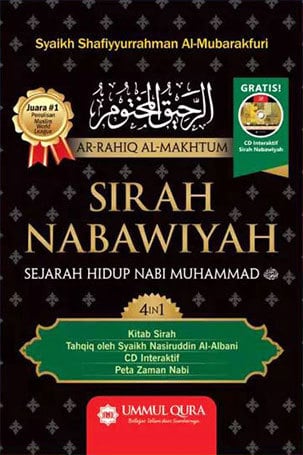
Nabi s.a.w. telah menghimpun sekian banyak kelebihan dari berbagai lapisan manusia selama pertumbuhan beliau. Beliau menjadi seorang sosok yang unggul dalam pemikiran yang jitu, pandangan yang lurus, mendapat sanjungan karena kecerdikan, kelurusan pemikiran, pencarian sarana dan tujuan. Beliau lebih suka berdiam berlama-lama untuk mengamati, memusatkan pikiran dan menggali kebenaran. Dengan akalnya beliau mengamati keadaan negerinya. Dengan fitrahnya yang suci beliau mengamati lembaran-lembaran kehidupan, keadaan manusia dari berbagai golongan.
Beliau merasa risih terhadap khurafat dan menghindarinya. Beliau berhubungan dengan manusia, dengan mempertimbangkan keadaan dirinya dan keadaan mereka. Selagi mendapatkan yang baik, maka beliau bersekutu di dalamnya. Jika tidak, maka beliau lebih suka dengan kesendiriannya. Beliau tidak minum khamar, tidak mau makan daging hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala, tidak mau menghadiri upacara atau pertemuan untuk menyembah patung. Bahkan sejak kecil beliau senantiasa menghindari jenis penyembahan yang batil ini, sehingga tidak ada sesuatu yang lebih beliau benci selain penyembahan kepada patung-patung ini, dan hampir-hampir beliau tidak sanggup menahan kesabaran tatkala mendengar sumpah yang disampaikan kepada Lāta dan ‘Uzzā. (341).
Ibnu Katsīr meriwayatkan bahwa Rasūlullāh s.a.w. pernah bersabda: “Tidak pernah terlintas dalam benakku suatu keinginanku untuk mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyyah kecuali hanya dua kali. Namun, kemudian Allah ta‘ālā menjadi penghalang antara diriku dengan keinginan itu. Setelah itu aku tidak lagi berkeinginan sedikit pun hingga Allah ta‘ālā memuliakan aku dengan risalah-Nya. Suatu malam aku pernah berkata kepada seorang pemuda yang sedang menggembala kambing bersamaku di suatu bukit di Makkah: “Awasilah kambing-kambing gembalaanku, karena aku hendak masuk Makkah dan hendak mengobrol di sana seperti yang dilakukan para pemuda yang lain.”
Rekanku itu berkata: “Aku akan melaksanakannya.” Maka aku beranjak pergi. Di samping rumah pertama yang kulewati di Makkah, aku mendengar suara tabuhan rebana. Aku bertanya: “Ada apa ini?” Orang-orang menjawab: “Pesta pernikahan Fulān dan Fulānah.”
Aku ikut duduk-duduk di sana dan mendengarkan. Namun, Allah ta‘ālā menutup telingaku dan aku langsung tertidur, hingga aku terbangun karena sengatan matahari besok harinya. Aku kembali menemui rekanku dan dia langsung menanyakan keadaanku. Maka aku mengabarkan apa yang terjadi. Pada malam lainnya aku berkata seperti itu pula dan berbuat hal yang sama. Namun, lagi-lagi aku mengalami kejadian yang sama seperti malam sebelumnya. Maka setelah itu, aku tidak lagi ingin berbuat hal yang buruk.” (352) (363).
Imām al-Bukhārī meriwayatkan dari Jābir bin ‘Abdillāh r.a., yang berkata: “Tatkala Ka‘bah sedang direnovasi, Rasūlullāh s.a.w. ikut bergabung bersama ‘Abbās mengambil batu. ‘Abbās berkata kepada beliau: “Angkatlah jubahmu hingga ke atas lutut agar engkau tidak terluka oleh batu.” Namun, karena itu beliau justru terjerembab ke tanah. Maka beliau menghujamkan pandangan ke langit, kemudian bersabda: “Ini gara-gara jubahku, ini gara-gara jubahku.” Lalu beliau mengikatkan jubahnya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau setelah itu tidak pernah terlihat beliau menampakkan auratnya.” (374).
Rasūlullāh s.a.w. juga menonjol di tengah kaumnya karena perkataan yang lemah-lembut, akhlaknya yang utama, sifat-sifatnya yang mulia. Beliau adalah orang yang yang paling utama kepribadiannya di tengah kaumnya, paling bagus akhlaknya, paling terhormat dalam pergaulannya dengan para tetangga, paling lemah-lembut, paling jujur perkataannya, paling terjaga jiwanya, paling terpuji kebaikannya, paling baik amalnya, paling banyak memenuhi janji, paling bisa dipercaya, hingga mereka menjulukinya al-Amīn, karena beliau menghimpun semua keadaan yang baik dan sifat-sifat yang diridhai orang lain.
Keadaan beliau juga digambarkan Umm-ul-Mu’minīn, yaitu Khadījah binti Khuwailid r.a.: “Beliau membawa bebannya sendiri, memberi orang miskin, menjamu tamu, dan menolong siapapun yang hendak menegakkan kebenaran.” (385).
Saya (al-Albānī) katakan: hadits ini adalah lemah dan Dr. Al-Būthī yang tertipu oleh pernyataan shahih sesuai syarat Muslim oleh al-Ḥākim menunjukkan bahwa al-Būthī tidak memiliki pengetahuan tentang al-Ḥākim yang mudah menyatakan shaḥīḥ suatu hadits dalam kitabnya al-Mustadrak, seperti yang telah diketahui oleh orang-orang yang konsentrasi dalam ilmu yang mulia ini (ilmu hadits), dan buku-buku Musthalaḥ-ul-Ḥadīts dipenuhi dengan peringatan tentang hal ini.
As-Suyūthī mengatakan di dalam kitab Alfiyyah-nya:
Betapa banyak ia (al-Ḥākim) mempermudah dalam pen-shaḥīḥ-an
Hingga hadits munkar dan maudhū‘ yang tertolak pun dinyatakan shaḥīḥ.
Karena itu, adz-Dzahabī dalam at-Talkhīsh mengutip dan mengkritisi ratusan hadits maudhū‘ yang diriwayatkan oleh al-Ḥākim di dalam al-Mustadrak, padahal adz-Dzahabī sendiri kadang-kadang berbuat sama dalam men-shaḥīḥ-kan beberapa hadits dan di buku-bukunya yang lain dinyatakan dha‘īf.
Di samping itu, saya telah menjelaskan dua cacat sanad tersebut di dalam Takhrīju Fiqh-is-Sīrati lil-Ghazālī, hal. 32-33, dan di situ saya menukil dari Ibnu Katsīr yang berkata: “Hadits ini gharīb jiddan dan bisa jadi ini dari dia sendiri. Artinya, mauqūf pada dirinya.”
Adapun hadits riwayat ath-Thabrānī dari dari ‘Ammār, di dalamnya terdapat sejumlah perawi yang tidak dikenal, seperti diungkapkan oleh al-Ḥaitsamī dalam al-Majma‘ dan saya menyebutkan dalam takhrīj sebelumnya dan al-Būthī – semoga Allah memaafkan kami dan dia – tidak berkomentar tentang hal ini. (Saya – al-Malaḥ – tambahkan di sini bahwa hadits ‘Ammār bertentangan dengan hadits ‘Alī karena di dalamnya disebutkan: ….. dua tradisi [jahiliyyah]: pertama, aku tertidur, dan kedua, aku terhalang oleh obrolan malam kaumku.).
Takhrīj hadits tersebut diringkas darinya kecuali ungkapannya: “diriwayatkan oleh Ibn-ul-Atsīr” karena ini ada pada dirinya dan berarti dari tārīkh-nya. Saya tidak mengangkat penisbatan seperti ini karena di antara aturan baku peneliti hadits, mereka tidak bersandar kepada berita-berita yang mursal dan mu‘dhal, yang di-mursal-kan (disebutkan redaksinya langsung) begitu saja tanpa sanad, terutama hadits seperti ini yang tidak sinkron dengan kesempurnaan dan kemaksuman Rasūlullāh s.a.w. walaupun telah diinterpretasikan dan ditakwilkan oleh Dr. Al-Būthī di hal. 39-40. Sebab, takwil itu bagian dari pembenaran, sedangkan kami perlu menutup beberapa celah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya tujuan tertentu menurut berbagai perbedaan pendekatan mereka, dengan mengedepankan kritik ilmiah modern yang benar. Sebab, bila suatu hadits itu tidak shaḥīḥ, tidak ada alasan yang bisa membenarkan seseorang untuk menakwil, sesuai kesepakatan.” (al-Malah).