Aminah & ‘Abd-ul-Muththalib Wafat, dll – Sejarah Hidup Muhammad – Haekal
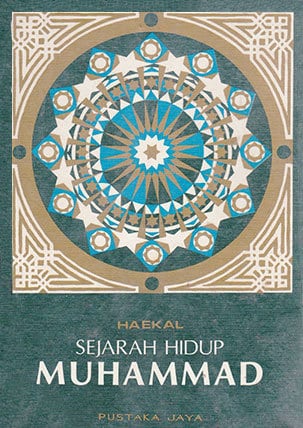
Penerbit: PUSTAKA JAYA
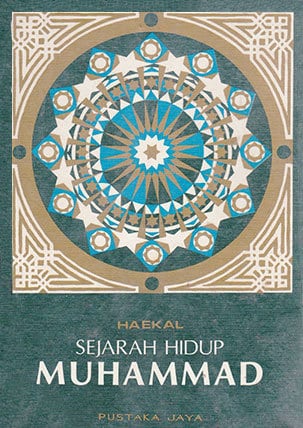
Sesudah cukup sebulan mereka tinggal di Madīnah, Āminah sudah bersiap-siap akan pulang. Ia dan rombongan kembali pulang dengan dua ekor unta yang membawa mereka dari Makkah. Tetapi di tengah perjalanan, ketika mereka sampai di Abwā’ (21) ibunda Āminah menderita sakit, yang kemudian meninggal dan dikuburkan pula di tempat itu.
Anak itu oleh Umm Aiman dibawa pulang ke Makkah, pulang menangis dengan hati yang pilu, sebatang kara. Ia makin merasa kehilangan; sudah ditakdirkan menjadi anak yatim. Terasa olehnya hidup yang makin sunyi, makin sedih. Baru beberapa hari yang lalu ia mendengar dari Ibunda keluhan duka kehilangan Ayahanda semasa ia masih dalam kandungan. Kini ia melihat sendiri di hadapannya, ibu pergi untuk tidak kembali lagi, seperti ayah dulu. Tubuh yang masih kecil itu kini dibiarkan memikul beban hidup yang berat, sebagai yatim-piatu.
Lebih-lebih lagi kecintaan ‘Abd-ul-Muththalib kepadanya. Tetapi sungguhpun begitu, kenangan sedih sebagai anak yatim-piatu itu bekasnya masih mendalam sekali dalam jiwanya sehingga di dalam Qur’ān pun disebutkan, ketika Allah mengingatkan Nabi akan nikmat yang dianugerahkan kepadanya itu: “Bukankah engkau dalam keadaan yatim-piatu? Lalu diadakan-Nya orang yang akan melindungimu? Dan menemukan kau kehilangan pedoman, lalu ditunjukkanNya jalan itu?” (Qur’ān, 93: 6-7)
Kenangan yang memilukan hati ini barangkali akan terasa agak meringankan juga sedikit, sekiranya ‘Abd-ul-Muththalib masih dapat hidup lebih lama lagi. Tetapi orang tua itu juga meninggal, dalam usia delapanpuluh tahun, sedang Muḥammad waktu itu baru berumur delapan tahun. Sekali lagi Muḥammad dirundung kesedihan karena kematian kakeknya itu, seperti yang sudah dialaminya ketika ibunya meninggal. Begitu sedihnya dia, sehingga selalu ia menangis sambil mengantarkan keranda jenazah sampai ke tempat peraduan terakhir.
Bahkan sesudah itupun ia masih tetap mengenangkannya sekalipun sesudah itu, di bawah asuhan Abū Thālib pamannya ia mendapat perhatian dan pemeliharaan yang baik sekali, mendapat perlindungan sampai masa kenabiannya, yang terus demikian sampai pamannya itupun akhirnya meninggal.
Sebenarnya kematian ‘Abd-ul-Muththalib ini merupakan pukulan berat bagi Keluarga Hāsyim semua. Di antara anak-anaknya itu tak ada yang seperti dia: mempunyai keteguhan hati, kewibawaan, pandangan yang tajam, terhormat dan berpengaruh di kalangan ‘Arab semua. Dia menyediakan makanan dan minuman bagi mereka yang datang berziarah, memberikan bantuan kepada penduduk Makkah bila mereka mendapat bencana. Sekarang ternyata tak ada lagi dari anak-anaknya itu yang akan dapat meneruskan. Yang dalam keadaan miskin, tidak mampu melakukan itu, sedang yang kaya hidupnya kikir sekali. Oleh karena itu maka Keluarga Umayyah yang lalu tampil ke depan akan mengambil tampuk pimpinan yang memang sejak dulu diinginkan itu, tanpa menghiraukan ancaman yang datang dari pihak Keluarga Hāsyim.
Pengasuhan Muḥammad di pegang oleh Abū Thālib, sekalipun dia bukan yang tertua di antara saudara-saudaranya. Saudara tertua adalah Ḥārith, tapi dia tidak seberapa mampu. Sebaliknya ‘Abbās yang mampu, tapi dia kikir sekali dengan hartanya. Oleh karena itu ia hanya memegang urusan siqāya (pengairan) tanpa mengurus rifāda (makanan). Sekalipun dalam kemiskinannya itu, tapi Abū Thālib mempunyai perasaan paling halus dan terhormat di kalangan Quraisy. Dan tidak pula mengherankan kalau ‘Abd-ul-Muththalib menyerahkan asuhan Muḥammad kemudian kepada Abū Thālib.
Abū Thālib mencintai kemenakannya itu sama seperti ‘Abd-ul-Muththalib juga. Karena kecintaannya itu ia mendahulukan kemenakan daripada anak-anaknya sendiri. Budi pekerti Muḥammad yang luhur, cerdas, suka berbakti dan baik hati, itulah yang lebih menarik hati pamannya. Pernah pada suatu ketika ia akan pergi ke Syām membawa dagangan – ketika itu usia Muḥammad baru duabelas tahun – mengingat sulitnya perjalanan menyeberangi padang pasir, tak terpikirkan olehnya akan membawa Muḥammad. Akan tetapi Muḥammad yang dengan ikhlas menyatakan akan menemani pamannya itu, itu juga yang menghilangkan sikap ragu-ragu dalam hati Abū Thālib.
Anak itu lalu turut serta dalam rombongan kafilah, hingga sampai di Bushra di sebelah selatan Syām. Dalam buku-buku riwayat hidup Muḥammad diceritakan, bahwa dalam perjalanan inilah ia bertemu dengan rahib Bahirah, dan bahwa rahib itu telah melihat tanda-tanda kenabian padanya sesuai dengan petunjuk cerita-cerita Kristen. Sebagian sumber menceritakan, bahwa rahib itu menasehatkan keluarganya supaya jangan terlampau dalam memasuki daerah Syām, sebab dikuatirkan orang-orang Yahudi yang mengetahui tanda-tanda itu akan berbuat jahat terhadap dia.
Dalam perjalanan itulah sepasang mata Muḥammad yang indah itu melihat luasnya padang pasir, menatap bintang-bintang yang berkilauan di langit yang jernih cemerlang. Dilaluinya daerah-daerah Madyan, Wādi-l-Qurā serta peninggalan bangunan-bangunan Tsamūd. Didengarnya dengan telinganya yang tajam segala cerita orang-orang ‘Arab dan penduduk pedalaman tentang bangunan-bangunan itu, tentang sejarahnya masa lampau. Dalam perjalanan ke daerah Syām ini ia berhenti di kebun-kebun yang lebat dengan buab-buahan yang sudah masak, yang akan membuat ia lupa akan kebun-kebun di Thā’if serta segala cerita orang tentang itu. Taman-taman yang dilihatnya dibandingkannya dengan dataran pasir yang gersang dan gunung-gunung tandus di sekeliling Makkah itu. Di Syām ini juga Muḥammad mengetahui berita-berita tentang Kerajaan Rumawi dan agama Kristennya, didengarnya berita tentang Kitab Suci mereka serta oposisi Persia dari penyembah api terhadap mereka dan persiapannya menghadapi perang dengan Persia.
Sekalipun usianya baru dua belas tahun, tapi dia sudah mempunyai persiapan kebesaran jiwa, kecerdasan dan ketajaman otak, sudah mempunyai tinjauan yang begitu dalam dan ingatan yang cukup kuat serta segala sifat-sifat semacam itu yang diberikan alam kepadanya sebagai suatu persiapan akan menerima risalah (misi) maha besar yang sedang menantinya. Ia melihat ke sekeliling, dengan sikap menyelidiki, meneliti. Ia tidak puas terhadap segala yang didengar dan dilihatnya. Ia bertanya kepada diri sendiri: Di manakah kebenaran dari semua itu?
Tampaknya Abū Thālib tidak banyak membawa harta dari perjalanannya itu. Ia tidak lagi mengadakan perjalanan demikian. Malah sudah merasa cukup dengan yang sudah diperolehnya itu. Ia menetap di Makkah mengasuh anak-anaknya yang banyak sekalipun dengan harta yang tidak seberapa. Muḥammad juga tinggal dengan pamannya, menerima apa yang ada. Ia melakukan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh mereka yang seusia dia. Bila tiba bulan-bulan suci, kadang ia tinggal di Makkah dengan keluarga, kadang pergi bersama mereka ke pekan-pekan yang berdekatan dengan ‘Ukkāz, Majannā dan Dzu-l-Majāz, mendengarkan sajak-sajak yang dibawakan oleh penyair-penyair Mudhahhabāt dan Mu‘allaqāt (32). Pendengarannya terpesona oleh sajak-sajak yang fasih melukiskan lagu cinta dan puisi-puisi kebanggaan, melukiskan nenek moyang mereka, peperangan mereka, kemurahan hati dan jasa-jasa mereka. Didengarnya ahli-ahli pidato di antaranya orang-orang Yahudi dan Nashrānī yang membenci paganisma ‘Arab. Mereka bicara tentang Kitab-kitab Suci ‘Īsā dan Mūsā, dan mengajak kepada kebenaran menurut keyakinan mereka. Dinilainya semua itu dengan hati nuraninya, dilihatnya ini lebih baik daripada paganisma yang telah menghanyutkan keluarganya itu. Tetapi tidak sepenuhnya ia merasa lega.
Dengan demikian sejak muda-belia takdir telah mengantarkannya ke jurusan yang akan membawanya ke suatu saat bersejarah, saat mula pertama datangnya wahyu, tatkala Tuhan memerintahkan ia menyampaikan Risālah-Nya itu. Yakni Risālah kebenaran dan petunjuk bagi seluruh umat manusia.