6-3 Masalah Umum – ‘Aqa’iduna – Syaikh Makarim Syirazi
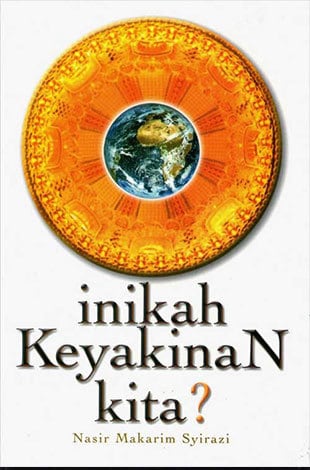
Inikah Keyakinan Kita?
Oleh: Nasir Makarim Syirazi
(Judul Asli: ‘Aqū’idunā)
Penerjemah: Toha al-Musawa
Penerbit: Penerbit al-Mu‘ammal
Diketik oleh: Zaidah Melani
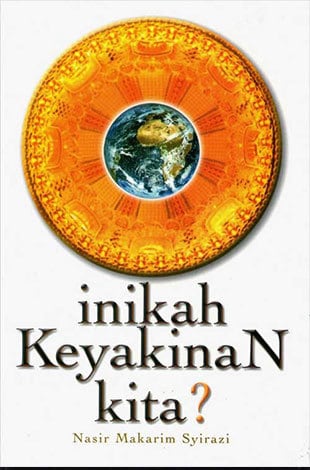
Inikah Keyakinan Kita?
Oleh: Nasir Makarim Syirazi
(Judul Asli: ‘Aqū’idunā)
Penerjemah: Toha al-Musawa
Penerbit: Penerbit al-Mu‘ammal
Diketik oleh: Zaidah Melani
Kita meyakini bahwa seseorang berkewajiban untuk menyembunyikan aqidah dan keyakinannya di hadapan orang yang memiliki sifat fanatik dan radikal, yang tidak bisa berbicara dengan bahasa logika. Jika ternyata di balik penampakan akidah dan keyakinan itu terdapat bahaya yang mengancam kehidupan atau sesuatu yang lain sepertinya, dan di sisi lain dalam menampakkan hal itu tidak terdapat manfaat yang dapat diperoleh, maka perbuatan semacam inilah yang disebut dengan taqiyyah. Pembolehan tentang hal ini kita sandarkan dari dua ayat al-Qur’ān, ditambah dengan argumentasi akal.
Dalam sebuah ayat yang menceritakan tentang seseorang mu’min di antara pengikut Fir‘aun, Allah SWT berfirman:
Dan seorang laki-laki yang beriman dari pengikut-pengikut Fir‘aun yang menyembunyikan imannya. (al-Mu’min: 28)
Maka kata:
يكتم إيمانه
telah menjelaskan tentang masalah taqiyyah. Apakah dapat dibenarkan bagi seorang mukmin pengikut Fir‘aun tersebut untuk menampakkan keimanannya, sedangkan dirinya terancam, padahal tidak ada sesuatu apapun yang dapat diraihnya?
Sebagaimana, al-Qur’ān telah memerintahkan untuk ber-taqiyyah kepada sebagian kaum mukmin pada awal kemunculan Islam, yang hidup di bawah cengkraman kaum musyrikin. Allah SWT berfirman:
Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir sebagai wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. (Āli ‘Imrān: 28)
Karenanya, taqiyyah berarti menyembunyikan akidah, pada waktu jiwa, harta, dan yang berkaitan dengannya terancam bahaya di hadapan musuh yang memiliki sifat fanatik dan radikal, tanpa adanya manfaat yang dapat diraih. Dalam kondisi semacam ini, wajib bagi setiap manusia untuk tidak menjerumuskan diri pada kebinasaan dan menghilangkan kemampuan yang ada. Sebaliknya, diharuskan baginya untuk menjaga hal-hal tersebut pada situasi dan kesempatan yang dibutuhkan.
Oleh karena itu, Imām Ja‘far ash-Shādiq berkata:
“Taqiyyah merupakan perisai seorang mu’min.”
Perisai merupakan ungkapan indah yang menjelaskan tentang taqiyyah sebagai sarana untuk menjaga diri dari musuh.
Dan peristiwa terkenal yang dialami oleh ‘Ammār bin Yāsir r.a. dalam mempraktikkan taqiyyah di hadapan kaum musyrik, mendapat persetujuan dari Nabi Saw.
Benar, menyembunyikan bala tentara dari penglihatan musuh dalam medan perang dan menutup berbagai rahasia pasukan dari musuh, atau semisalnya, merupakan salah satu bentuk taqiyyah dalam kehidupan manusia. Secara umum, taqiyyah berarti penyembunyian, di mana penampakan yang berkaitan dengannya akan menyebabkan terjerumusnya seseorang ke dalam bahaya tanpa ada tujuan yang jelas, yang akan dapat diraih. Ini merupakan kesimpulan akal maupun syariat, yang tidak hanya dilakukan oleh kaum Syī‘ah saja. Bahkan, segenap kaum muslimin di segala penjuru dunia, atau bahkan setiap orang yang berakal, akan melakukannya di saat kondisi memaksakannya untuk melakukan hal tersebut.
Sangatlah mengherankan sekali jika ada seseorang yang mengatakan bahwa taqiyyah hanya dilakukan oleh para kaum Syī‘ah dan pengikut Ahl-ul-Bait saja. Sehingga, taqiyyah pun dijadikan sebagai alat untuk bahan celaan atas diri mereka. Padahal, masalah taqiyyah ini tidak mengandungi kesamaran sedikit pun dan konsep tersebut diambil dari al-Qur’ān, hadits-hadits, perilaku para sahabat, juga telah disetujui dan diterapkan oleh para pemilik akal sehat di seluruh penjuru dunia.
Kita meyakini bahwa penyebab utama adanya kesalahpahaman dalam persoalan ini adalah sebagai akibat tidak adanya pengetahuan yang cukup tentang akidah Syī‘ah. Atau, dikarenakan tertipu oleh bisikan musuh-musuh Islam. Kita meyakini bahwa apa yang telah kita sampaikan di atas akan dapat memberikan penjelasan dan menghilangkan keraguan yang berkaitan dengan masalah tersebut.
Harus pula dijelaskan di sini bahwa terkadang taqiyyah diharamkan dalam beberapa situasi dan keadaan. Situasi di mana asas-asas agama, al-Qur’ān, atau pemerintahan Islam berada dalam ancaman bahaya. Dalam situasi semacam ini, setiap pribadi muslim diharuskan untuk menampakan akidah dan keyakinannya, walaupun dia akan menjadi korban. Kita meyakini bahwa apa yang telah dilakukan oleh Imām Ḥusain a.s. pada tragedi Karbalā’ adalah untuk mewujudkan hal tersebut. Lantaran para penguasa Bani Umayyah telah menjerumuskan asas-asas Islam ke dalam jurang marabahaya, maka Imām Ḥusain a.s. pun merelakan diri untuk berkorban guna menghadapi semua bahaya yang mengancamnya.
Kita meyakini dan konsisten dengan semua jenis peribadahan yang telah ditekankan oleh al-Qur’ān dan as-Sunnah, seperti sholat lima kali dalam sehari semalam, yang termasuk dalam kategori sarana terpenting dalam hubungan antara hamba dan Sang Pencipta; puasa pada Bulan Ramadhān sebagai sarana terpenting untuk meningkatkan kekuatan iman, penyucian diri, ketaqwaan, dan mengekang hawa nafsu.
Kita juga meyakini kewajiban hukum haji bagi orang yang telah mampu, sekali dalam hidupnya. Itu juga merupakan sarana untuk mendapatkan ketaqwaan, memperkuat hubungan kasih sayang, dan menjadi penyebab (terpeliharanya) kehormatan kaum muslimin. Sebagaimana, termasuk pula kewajiban yang jelas dalam Islam adalah menyerahkan zakat mal, khumus, amar ma’rūf nahi munkar, berjihad dalam menghadapi para durjana yang menyerang Islam dan kaum muslimin.
Tentu saja, secara rinci terdapat sedikit perbedaan di antara kita dengan sebagian kelompok Islam tentang hal-hal tertentu. Sebagaimana juga terjadi perbedaan pendapat dalam permasalahan hukum-hukum peribadahan di antara empat mazhab dalam tubuh Ahl-us-Sunnah sendiri.
Dari penjelasan di atas, kita meyakini akan diperbolehkannya menggabungkan shalat Zhuhur dan ‘Ashar, juga Maghrib dan ‘Isyā’ (walaupun, jika dipisahkan akan lebih utama). Kita meyakini bahwa Nabi Saw membolehkan kita untuk melaksanakan penggabungan tersebut dengan alasan untuk menghilangkan kesulitan dalam pengamalannya.
Dalam kitab Shaḥīḥ-ut-Tirmidzī yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbās r.a. disebutkan bahwa beliau berkata: “Rasūlullāh Saw menggabungkan antara shalat Zhuhur dan ‘Ashar, juga antara Maghrib dan ‘Isyā’ sewaktu berada di kota Madīnah tanpa adanya (hal-hal) yang menyebabkan rasa takut dan hujan.”
Ibnu ‘Abbās ditanya, “Apa yang dikehendaki oleh beliau?”
Ibnu ‘Abbās menjawab, “Beliau hendaki menghilangkan kesulitan bagi umatnya.”
Ya, beliau (Rasūlullāh Saw) memperbolehkan untuk menggabung shalat pada situasi-situasi yang dapat menyebabkan kesulitan bagi umat beliau apabila dilakukan secara terpisah. Sekarang ini, kita hidup di zaman yang penuh dengan kesibukan-kesibukan dalam lalu-lintas kemasyarakatan, khususnya yang bekerja di pusat-pusat industri. Terpaku dengan waktu-waktu yang telah ditentukan untuk shalat lima waktu terkadang akan menyebabkan, bagi sebagian orang, terpaksa untuk meninggalkan shalat. Oleh karena itu, melaksanakan dispensasi yang diberikan Nabi Saw semacam itu, tak diragukan lagi, akan membantu setiap orang untuk berkonsisten dengan pelaksanaan shalat. Cobalah anda renungkan!