6-2 Masalah Umum – ‘Aqa’iduna – Syaikh Makarim Syirazi
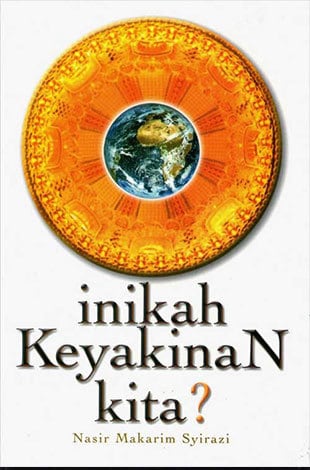
Inikah Keyakinan Kita?
Oleh: Nasir Makarim Syirazi
(Judul Asli: ‘Aqū’idunā)
Penerjemah: Toha al-Musawa
Penerbit: Penerbit al-Mu‘ammal
Diketik oleh: Zaidah Melani
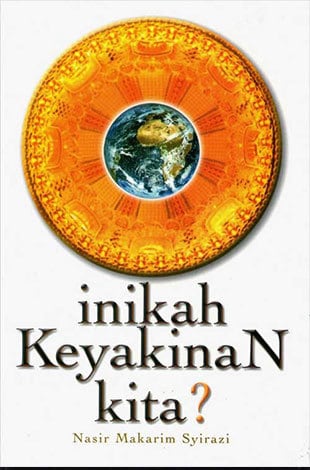
Inikah Keyakinan Kita?
Oleh: Nasir Makarim Syirazi
(Judul Asli: ‘Aqū’idunā)
Penerjemah: Toha al-Musawa
Penerbit: Penerbit al-Mu‘ammal
Diketik oleh: Zaidah Melani
Kita meyakini bahwa alam ciptaan merupakan bentuk keteraturan yang terbaik. Dalam arti, keteraturan yang diterapkan di alam semesta merupakan keteraturan yang paling baik, sehingga alam semesta ini menjadi tetap berjalan dengan baik pula. Segala sesuatu di alam semesta ini berjalan menurut sistem penciptaannya dan sesuai dengan aturan yang ada. Tidak didapat sesuatu pun yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Jika terdapat keburukan dalam kehidupan komunitas manusia, maka hal itu dikarenakan ulah tangan manusia itu sendiri.
Perlu diulang dan ditekankan di sini, kita meyakini bahwa keadilan Ilahi merupakan tonggak utama bagi berdirinya pandangan dunia keislaman. Tanpa hal tersebut, niscaya konsep tauhid, kenabian, dan kebangkitan akan sangat mudah digoyahkan. Renungkanlah hal ini!
Berkenaan dengan hal ini, Imām Ja‘far ash-Shādiq a.s. berkata:
Sesungguhnya asas agama adalah tauhid, keadilan… adapun yang berkaitan dengan tauhid adalah hendaknya engkau jauhkan dari Tuhanmu segala apa yang diperbolehkan bagimu. Adapun yang berkaitan dengan konsep keadilan adalah hendaknya tidak kau kaitkan terhadap penciptamu segala hal yang engkau cela. (Biḥār al-Anwār, jil. V, hal. 17, hadits ke-23)
Dasar sandaran fiqih kita—sebagaimana yang telah kita singgung—mencangkup empat hal:
Pertama, kitab Allah SWT yang berupa “Al-Qur’ān yang mulia”, yang merupakan prinsip dasar segala pengetahuan dan hukum Islam.
Kedua, sunnah Nabi Saw dan para Imām suci Ahl-ul-Bait a.s.
Ketiga, konsensus (ijma‘) para ulama dan para pakar fiqih yang mampu menyingkap pandangan manusia suci (ma‘shūm).
Keempat, dalil akal, yaitu dalil akal yang dapat dipastikan (qath’ī). Adapun dalil akal yang bersifat sangkaan (zhannī) seperti qiyās atau istiḥsān tidak dapat dijadikan sebagai pedoman sandaran hukum fikih. Jika seorang mujtahid beranggapan bahwa terdapat masalah pada sesuatu, di mana hukum yang akan diberikan untuk objek tersebut tidak terdapat dalam al-Qur’ān maupun hadits, maka dia tidak dapat mengatasnamakan hukum itu sebagai hukum Allah. Sebagaimana, kita juga tidak dapat kembali kepada qiyās yang bersifat prasangka atau semisalnya, dalam menyingkap hukum syariat. Adapun jika dalam kondisi-kondisi yang yakin—seperti yakin akan keburukan perbuatan zhalim, berbohong, mencuri, dan khianat—maka hukum akal pada kondisi tersebut dapat diterima dan dapat diungkap hukum syariat sesuai dengan kaidah: “Setiap yang dihukumi oleh akal, maka syariat pun akan menghukuminya dengan sama.”
Tentu, yang benar adalah bahwa kita memiliki berbagai riwayat yang cukup dari Nabi Saw dan para Imām suci Ahl-ul-Bait a.s. berkenaan dengan hukum-hukum yang diperlukan oleh seorang mukallaf dalam masalah-masalah peribadahan, politik, ekonomi, dan kemasyarakatan, karenanya kita sama sekali tidak perlu lagi untuk memenuhi kebutuhan itu dengan menggunakan dalil-dalil yang bersifat praduga dan sangkaan belaka. Bahkan dalam masalah-masalah terbaru (Al-Masā’il al-Mustaḥdatsah), baik secara prinsip maupun secara global, telah tertera dalam hadits hadits dari Nabi Saw maupun para Imām suci Ahl-ul-Bait a.s. Dengan semua itu, untuk menyingkap hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah terbaru, kita tidak lagi memerlukan dalil-dalil yang bersifat sangkaan, bahkan cukup dengan kembali kepada hukum-hukum yang bersifat universal.
Kita meyakini bahwa pintu ijtihad selalu terbuka untuk semua permasalahan hukum syariat. Para pemuka di antara para pakar fikih (fuqahā’) berhak untuk menggali dasar hukum Allah yang bersumberkan dari empat sumber-sumber yang telah disebutkan di atas. Sehingga, mereka dapat menyiapkan hukum bagi individu-individu yang belum memiliki kelayakan untuk melakukan penggalian hukum tersebut. Meski terkadang hukum-hukum yang mereka keluarkan berbeda dengan apa yang telah dikeluarkan oleh para pakar fiqih yang telah lalu, dan kita meyakini bahwa banyak pribadi yang memerlukan pandangan hukum fikih, maka sudah selayaknya untuk merujuk kepada pendapat para pakar fikih yang masih hidup, yang memiliki kemampuan untuk mengetahui segala situasi yang terdapat pada waktu dan tempat di mana dia berada. Jika hal itu telah terwujud, maka sudah selayaknya para pakar tersebut diikuti (di-taqlīd-i).
Adalah kemestian yang gamblang bahwa seorang awam harus merujuk kepada orang yang memiliki spesialisasi di bidangnya, termasuk dalam permasalahan fikih. Para pakar fikih tersebut dalam istilah kita sering disebut sebagai para marja’ (pribadi-pribadi yang menjadi rujukan— penerj.). Tidak diperkenankan taqlīd kepada para pakar fiqih yang telah meninggal dunia; bagi orang yang baru akan mengikutinya. Namun, menjadi keharusan bagi segenap umat untuk mengikuti para pakar fiqih yang masih hidup, agar fikih dapat tetap bergerak dan berjalan menuju kesempurnaan.
Kita meyakini, tidak ada kekosongan hukum dalam Islam. Dalam arti, Islam telah menjelaskan seluruh hukum yang dibutuhkan oleh manusia sampai hari kiamat kelak. Hukum-hukum tersebut terkadang dengan bentuk khusus, kadang pula terangkum dalam bentuk yang lebih universal. Oleh karena itu, kita tidak menganggap bahwa para pakar fiqih memiliki otoritas dalam menentukan hukum. Akan tetapi, mereka berkewajiban untuk menggali hukum Allah dari empat dasar yang telah disebutkan, dan kemudian memberitakannya kepada segenap umat.
Bagaimana mungkin agama ini akan menjadi agama yang sempurna tanpa hukum-hukum fikih yang sempurna dan mencakup semua zaman? Sedangkan, dalam surat Al-Mā’idah—yang umumnya dianggap sebagai surat terakhir yang turun kepada Nabi Muḥammad Saw—Allah berfirman:
Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan nikmatKu kepadamu, dan telah Aku Ridhai Islam sebagai agama bagimu. (Al-Mā’idah: 3)
Sebagaimana Rasūlullāh Saw pun, dalam sebuah hadits yang diungkapkan beliau sewaktu melaksanakan haji wada’ (terakhir atau perpisahan), bersabda:
“Wahai sekalian manusia, demi Allah, tiada sesuatu yang dapat mendekatkan kalian kepada surga, dan Tiada sesuatu yang dapat menjauhkan kalian dari neraka kecuali telah kuperintahkan kepada kalian. Sebagaimana tiada sesuatu yang dapat mendekatkan kalian kepada neraka, dan tiada sesuatu yang menjauhkan kalian dari surga kecuali yang telah kuperintahkan kepada kalian.”(Ushūl-ul-Kāfī, jil. II, hal. 74; Biḥār-ul-Anwār, jil. LXVII, hal. 96)
Diriwayatkan dari Imām Ja‘far ash-Shādiq dalam sebuah hadits terkenal, di mana beliau berkata:
“Tiada yang ditinggalkan oleh ‘Alī a.s. sesuatu apapun kecuali telah dia tulis, walaupun berkaitan dengan…”
Sebagaimana telah disebutkan, maka tidak perlu lagi untuk menggunakan dalil-dalil yang berdasarkan pada prasangka seperti qiyās dan istiḥsān.