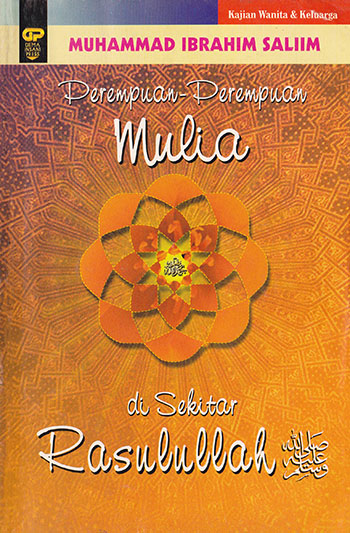5. KHANSĀ’ BINTI KHADZDZAM
Sebagai seorang istri, Islam telah memposisikan wanita sebagaimana layaknya. Bersama-sama dengan suami, dia juga bertanggung-jawab atas urusan rumah tangga. Bahkan, di luar urusan rumah tangga, seorang istri pun harus membantu suaminya.
Tidak benar jika Islam dianggap mengekang kebebasan kaum wanita. Bahkan sejak dini, Islam telah memberikan kebebasan kepada kaum wanita kebebasan dalam menentukan calon suami, kebebasan berpendapat, dan sebagainya. Makanya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Islam – dalam hal kebebasan berpendapat – lebih mendengarkan pendapat kaum wanita daripada kaum laki-laki.
Bahkan, sampai ambang pintu perceraian, Islam masih menghormati kedudukan seorang wanita. Misalnya, jika seorang suami memutuskan hubungannya dengan istrinya (cerai) sebelum digauli (dijima‘), suami harus membayar setengah mahar yang telah ditentukan. Namun, jika suami mencerai istrinya setelah digauli, si suami harus membayar mahar itu secara utuh. Dan pada saat itu, si suami tidak bisa semena-mena berkata: “Dari sisi keturunan dan kedudukan, dia (si istri) masih di bawahku.
Seorang wanita hendaknya harus memahami betul arti sebuah pernikahan yang seharusnya dibangun atas dasar cinta dan kasih-sayang tanpa ada sedikit pun unsur penipuan atau paksaan. Oleh karena itu, seorang wali tidak berhak memaksa anaknya untuk menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Atas dasar itulah, Rasūlullāh s.a.w. mengurungkan pernikahan Khansā’ binti Khadzdzam al-Anshārī yang dipaksa ayahnya untuk menikah dengan orang yang tidak diinginkannya.
Khansā’ binti Khadzdzam adalah keturunan Bani ‘Amru bin ‘Auf bin Aus. Ketika masih belia, dia bertemu Nabi s.a.w. pada saat datang ke Madīnah (hijrah). Dia juga meriwayatkan beberapa hadits dari Rasūlullāh s.a.w..
Dia dilamar oleh dua orang, yaitu pertama oleh Abū Lubābah bin Mundzir, salah seorang pahlawan pejuang dari sahabat Nabi; kedua, seorang dari Bani ‘Amr bin ‘Auf (kerabatnya). Khansā’ sendiri tertarik dengan Abū Lubābah, sedangkan ayahnya lebih tertarik dengan anak pamannya itu. Akhirnya, dengan terpaksa Khansā’ dinikahkan dengan anak pamannya itu. Datanglah Khansā’ kepada Rasūlullāh s.a.w. seraya berkata: “Sesungguhnya bapak saya telah memaksa saya untuk kawin dengan orang yang diinginkannya, sedang saya sendiri tidak mau.” Maka Rasūlullāh: bersabda: “Tidak ada nikah dengannya, kawinlah engkau dengan orang yang kamu cintai.” Lalu dia kawin dengan Abū Lubābah.
Para ahli hadits saling berbeda pendapat tentang status Khansā’ saat perkawinannya (kedua) dengan Abū Lubābah.
Dalam riwayat al-Muwaththa’ dan ats-Tsaurī menuturkan bahwa dia (Khansā’) – saat pernikahan kedua – masih perawan. Sedangkan, riwayat Bukhārī dan Ibnu Sa‘ad mengatakan bahwa saat pernikahan kedua dia sudah janda karena Khansā’ pernah berkata kepada Rasūlullāh s.a.w.: “Wahai Rasūlullāh sesungguhnya paman anak saya (yaitu suami Khansā’ pertama) lebih suka kepada saya,” lalu beliau (Rasūlullāh s.a.w.) menyerahkan urusan Khansā’ sepenuhnya kepada dirinya.
Perkataan Khansā’ pada riwayat di atas yang mengatakan: “Sesungguhnya paman anak saya…” mengindikasikan bahwa dia sudah mempunyai anak dari pernikahannya yang pertama. Hal ini ditopang riwayat Syams-ul-A’immah as-Sarkhasyī dalam kitabnya, al-Mabsūth terdapat sebuah hadits Khansā’ binti Khadzdzam sebagai berikut:
Khansā’ berkata: “Sesungguhnya bapak saya memaksa saya untuk menikah dengan keponakannya.” Nabi s.a.w. bersabda: “Laksanakan saja apa yang dimaui bapakmu!” Dia (kembali) berkata: “Saya tidak suka dengan hal tersebut.” Rasūlullāh s.a.w. bersabda: (kalau begitu), pergilah dan nikahlah kamu dengan orang yang kamu sukai.” Lebih lanjut Khansā’ menuturkan: “Saya tidak menolak apa yang dimaui oleh bapak saya, namun saya ingin agar orang-orang tahu bahwa bapak-bapak tidak boleh ikut campur dengan anaknya dalam masalah ini.”
Riwayat di atas mengindikasikan bahwa Khansā’ tidak langsung bercerai dengan suaminya, melainkan dia sempat tinggal beberapa waktu dengan suami pertamanya. Karena Khansā’, sebagaimana dituturkan oleh penulis al-Mabsūth, tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasūlullāh untuk tetap bersama suaminya (yang pertama).
Berbicara tentang Khansā’, mengingatkan kita pada seorang sahabat wanita Rasūl yang bernama Barīrah yang mempunyai kisah yang hampir sama dengan Khansā’. Dia adalah orang Ḥabasyah. Tuannya bernama ‘Utbah bin Abī Lahab yang mengawinkannya dengan seorang budak dari Mughīrah: Namun demikian, sebenarnya Barīrah tidak rela dijodohkan dengan budak tersebut seandainya dia berhak menolak. Hal itu diketahui oleh ‘Ā’isyah, maka dibelilah Barīrah dan dibebaskannya. Setelah bebas, Rasūlullāh s.a.w. bersabda kepadanya: “Kamu telah berhak atas dirimu maka kamu bebas memilih!”
Pada saat yang sama, sang suami yang ternyata membuntuti Barīrah sambil menangis memelas kasihnya, namun Barīrah tidak menghiraukannya. Melihat hal itu, Nabi s.a.w. bersabda kepada para sahabatnya: “Tidakkah kalian takjub akan kebesaran cinta suaminya kepadanya meskipun istrinya begitu membencinya.” Kemudian beliau berkata kepada Barīrah: “Takutlah kepada Allah, sesungguhnya dia adalah suamimu dan bapak dari anakmu.” Barīrah berkata: “Apakah baginda Rasūl menyuruh saya?” Rasūlullāh s.a.w. menjawab: “Saya cuma menyarankan saja.” Dia berkata: “Kalau begitu saya tidak ada kepentingan dengannya.”
Berkaca dari kisah di atas, kita tidak boleh heran jika ditemukan seorang gadis menentang kesewenang-wenangan yang ia terima dari ayah maupun walinya. Karena, menyepelekan pendapat seorang anak dan menikahkannya dengan orang yang tidak sehati lantaran mengejar materi dan harta adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Sekali lagi, hendaknya seorang ayah berpikir lebih jernih dalam hal ini karena kawin paksa sama halnya memikulkan beban penderitaan lahir-batin di pundak anak. Makanya, dalam secarik surat yang ditujukan kepada ayahnya, seorang gadis modern yang dipaksa kawin tanpa sepengetahuannya merintih:
“Wahai ayahku, engkau telah menyiksaku dan membebankan kepadaku suatu beban yang berat. Engkau antarkan diriku kepada orang yang begitu memandang rendah diriku.
Wahai ayahku, kalau bukan karena kegundahan yang begitu menghimpitku, saya tidak memohon kepadamu untuk melepaskanku darinya.”
Demikian juga rintihan seorang gadis yang dipaksa kawin dengan anak pamannya. Dalam syairnya dia berkata:
“Alangkah anehnya seorang perawan cantik yang gaunnya ditarik untuk disandingkan dengan orang tua dari suatu kaum. Pria tua tersebut mengatakan kepadanya bahwa dia mempunyai tali kerabat, maka celakalah buat anak paman baik dari ayah maupun ibu.”