3-2 Al-Qur’an dan Kitab Samawi Lain – ‘Aqa’iduna – Syaikh Makarim Syirazi
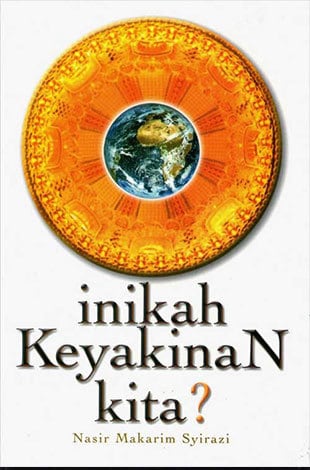
Inikah Keyakinan Kita?
Oleh: Nasir Makarim Syirazi
(Judul Asli: ‘Aqū’idunā)
Penerjemah: Toha al-Musawa
Penerbit: Penerbit al-Mu‘ammal
Diketik oleh: Zaidah Melani
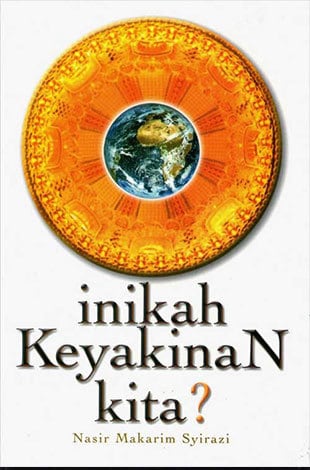
Inikah Keyakinan Kita?
Oleh: Nasir Makarim Syirazi
(Judul Asli: ‘Aqū’idunā)
Penerjemah: Toha al-Musawa
Penerbit: Penerbit al-Mu‘ammal
Diketik oleh: Zaidah Melani
Kajian tentang Penyimpangan
Kita meyakini, selalu saja ada cara yang digunakan untuk mencegah orang Islam dari upaya perlindungan dan pengamalan al-Qur’ān. Di masa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani ‘Abbāsiyyah, mereka melontarkan pembahasan tentang sifat terdahulu (qadīm) dan baru (ḥādits) keterkaitan dengan al-Qur’ān. Karena hal inilah, akhirnya kaum muslimin terbagi menjadi dua kelompok yang saling berperang dan banyak memakan korban.
Sebenarnya, pada masa sekarang ini tidak ada perkara yang harus diperselisihkan. Sebab, kalau yang dimaksud dengan kalāmullāh adalah huruf, gambar, tulisan, dan kertas, tentu saja semua itu merupakan suatu yang baru (ḥādits). Namun, jika yang dimaksud adalah makna al-Qur’ān yang terdapat dalam ilmu Tuhan, tentu saja ilmu Tuhan sebagaimana Dzāt-Nya adalah qadīm dan azalī.
Para penguasa zalim, selama bertahun-tahun, telah menyibukkan kaum muslimin dengan hal ini. Sekarang pun, dengan taktik yang berbeda, mereka berusaha untuk mencegah kaum muslimin dari upaya perenungan dan Pengamalan ayat-ayat al-Qur’ān.
Tolak-ukur Penafsiran al-Qur’ān
Kita meyakini bahwa hendaknya upaya menafsirkan al-Qur’ān didasarkan pada makna budaya setempat (‘urf) dan bahasanya sendiri, kecuali jika terdapat perhubungan secara rasional (qarīnah ‘aqliyyah) ataupun berhubungan secara tekstual (qarīnah naqliyyah) yang terdapat di dalam ayat maupun di luar ayat yang menunjukkan arti lain (namun hendaknya kita menjauhi perhubungan [qarīnah] yang tidak mencapai derajat yakin dan hendaknya tidak menafsirkan al-Qur’ān berdasarkan pemikiran).
Misal, ketika al-Qur’ān berkata sebagai berikut:
Dan barang siapa yang buta di dunia niscaya di akhirat dia akan lebih buta. (al-Isrā’: 72)
Kita meyakini bahwa maksud kata “buta” disini bukanlah buta secara lahiriyah sebagaimana yang dipahami dari arti secara bahasa. Sebab, betapa banyak orang yang buta, namun hatinya suci dan bersih. Akan tetapi, maksud buta disini adalah buta matahati. Dalam hal ini, keberadaan perhubungan secara rasional (qarina naqliyah) menyebabkan ayat diatas harus ditafsirkan seperti ini.
Begitu pula yang berkenaan dengan sekelompok musuh Islam. Dalam al-Qur’ān dinyatakan:
Mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti. ( al-Baqarah: 171)
Jelaslah bahwa mereka itu secara lahiriyah tidaklah tuli dan buta, untuk menggambarkan sifat-sifat batin mereka.
Oleh karena itu, ketika al-Qur’ān, berkenaan dengan Tuhan, menjelaskan sebagai berikut: Bahkan tangan Allah terbelenggu, (al-Mā’idah: 64), dan dalam ayat lain, Allah SWT berfirman: Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan Kami, (Hūd: 37), maka redaksi ayat di atas sama sekali tidak menunjukkan keberadaan anggota tubuh jasmani (materi) seperti mata, telinga dan tangan bagi Tuhan.
Lantaran setiap hal yang bersifat jasmani pasti memiliki bagian-bagian dan memerlukan waktu, tempat, dan arah, di mana semua itu akhirnya akan lenyap dan sirna, sementara Tuhan lebih agung dari penyifatan tersebut, maka maksud kata “tangan-Nya” (yada-hu) adalah kemampuan sempurna Tuhan, di mana seluruh alam ini berada di bawah pengaruh kekuasaan-Nya.
Adapun yang dimaksud dengan “mata-Nya” (a’yun) adalah ilmu dan pengetahuannya atas segala sesuatu. Oleh karena itu, kita tidak dapat menerima segala kejumudan dan tidak adanya perhatian pada hubungan rasional dan tekstual dalam memaknai ayat-ayat di atas; apakah itu berhubungan dengan sifat-sifat Allah SWT maupun selainnya. Itu dikarenakan, metode semacam ini selalu digunakan oleh para pembicara di seluruh dunia. Sementara al-Qur’ān sendiri mengakui (legalitas) metode tersebut. Dalam al-Qur’ān Allah SWT berfirman:
Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya.(Ibrāhīm: 4)
Namun, sebagaimana telah dijelaskan, perhubungan (qarīnah) harus bersifat pasti (qath’i) dan jelas.
Bahaya Penafsiran berdasarkan Pandangan Pribadi (Bir-Ra’yi)
Kita meyakini bahwa penafsiran berdasarkan pandangan pribadi (tafsir bir-ra’yi) merupakan salah satu program yang membahayakan al-Qur’ān. Bahkan, dalam beberapa riwayat, itu dianggap sebagai salah satu dosa besar yang akan menyebabkan pelakunya terjauhkan dari Tuhan. Dalam sebuah hadits disebutkan:
“Tidak beriman orang yang telah menafsirkan al-Qur’ān dengan kehendaknya sendiri.”
Benar, apabila memiliki iman yang benar, niscaya dia akan menerima al-Qur’ān secara apa adanya dan tak akan menafsirkan dengan sekehendak hatinya.
Hadits seperti ini telah diriwayatkan dari Rasūl Saw dalam berbagai sumber terkenal, seperti halnya dalam kitab hadits karya Tirmidzī, Nasā’ī, dan Abū Dāūd yang menyatakan:
Barang siapa telah menafsirkan al-Qur’ān dengan kehendak hatinya, atau secara tidak sengaja menjelaskan sesuatu tentang al-Qur’ān, maka bersiap-siaplah (bahwa) tempat kembalinya adalah neraka.
Yang dimaksud dengan tafsir dengan pandangan pribadi (tafsīr bir-ra’yi) adalah menafsirkan al-Qur’ān sesuai dengan kehendak sendiri atau kelompok, lalu mencocokkannya, tanpa melihat Apakah ada dalil dan bukti tentang hal itu atau tidak. Pelaku perbuatan seperti ini sebenarnya tidak mengikuti al-Qur’ān, tetapi menginginkan al-Qur’ān mengikuti kehendaknya. Jika orang tersebut memiliki keimanan yang benar, maka dia tidak akan melakukan hal semacam ini. Jika tafsir berdasarkan pandangan pribadi (tafsīr bir-ra’yi) diperbolehkan, maka hal itu akan menjatuhkan nilai kebenaran al-Qur’ān, dan setiap orang akan menafsirkan al-Qur’ān sesuai dengan kehendak hatinya, serta akan menyandarkan setiap aqidah yang batil kepada al-Qur’ān.
Oleh karena itu, tafsir berdasarkan pandangan pribadi (tafsīr bir-ra’yi), yaitu tafsir yang bertentangan dengan kaidah ilmu bahasa, sastra ‘Arab, pemahaman ahli bahasa, dan menyandarkan pemikiran yang sesat, khayalan, dan kehendak pribadi atau kelompok, akan mengakibatkan penyimpangan dalam menafsirkan al-Qur’ān.
Namun perlu juga diketahui bahwa tafsir berdasarkan pandangan pribadi (tafsīr bir-ra’yi) memiliki berbagai cabang, seperti pemilah-milahan ayat al-Qur’ān. Maksudnya bahwa dalam membahas syafa‘at, tauhid, atau imamah seseorang hanya mengikuti semua ayat yang sesuai dengan penarikan kesimpulan secara pribadi sebelumnya dan tidak memperhatikan ayat-ayat lain yang tidak sesuai dengan pendapat pribadinya itu, kendati masih berhubungan dengan topik yang akan dibahasnya. Padahal, pada hakekatnya, ayat tersebut dapat dijadikan sebagai penafsir bagi ayat lain; dengan mudahnya dia melewatkan ayat tersebut begitu saja.
Singkat kata, sebagaimana perhatian yang terpaku hanya pada sisi lahiriyah kata yang terdapat dalam al-Qur’ān (jumūd) saja serta tidak memperhatikan semua argumentasi akal dan teks dianggap sebagai sebuah penyimpangan, maka tafsir yang didasarkan pada pendapat pribadi (tafsīr bir-ra’yi) juga dapat dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Keduanya akan menyebabkan sang pelaku semakin jauh dari ajaran-ajaran luhur dan nilai-nilai al-Qur’ān. Renungkanlah!
As-Sunnah Terilhami dari Kandungan al-Qur’ān
Kita meyakini, tak seorangpun yang dapat mengaku, “cukup bagi kami kitab Allah,” dan kemudian tidak menghiraukan hadits-hadits Nabi Saw yang berkenaan dengan tafsir penjelasan tentang hakikat al-Qur’ān, pemahaman tentang ayat-ayat yang menghapus (nāsikh) dan ayat-ayat yang dihapus (mansūkh), ayat-ayat yang khusus dan umum, atau hal-hal yang berhubungan dengan ajaran Islam yang berkait dengan masalah cabang (furū‘) dan asas utama agama (ushūl).
Al-Qur’ān menganggap sunnah Nabi Saw beserta perkataan dan perilakunya sebagai argumentasi dasar bagi kaum muslimin serta merupakan salah satu sumber utama untuk memahami agama dan menggali hukum (istinbāth). Dalam al-Qur’ān, Allah SWT berfirman:
Apa yang diberikan (perintahkan) Rasūl kepadamu maka terimalah ia, dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. (al-Ḥasyr:7)
Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman:
Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasūl-Nya, telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasūl-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat, sesat yang nyata. (al-Aḥzāb: 36)
Orang yang tidak menghiraukan sunnah Nabi Saw, sebenarnya sama saja dengan tidak menghiraukan al-Qur’ān. Meskipun, jelas bagi kita bahwa sebuah hadits dapat ditetapkan melalui cara yang benar dan tidak dapat begitu saja kita menyandarkan setiap perkataan kepada Nabi Saw. Dalam sebuah hadits, Imām ‘Alī a.s. berkata:
“Pada zaman Rasūl Saw telah banyak orang yang menyandarkan perkataannya kepada beliau. Hingga akhirnya beliau bangkit dan berkhutbah: ‘Barang siapa yang berbohong (atas nama) diriku, maka bersiap-siaplah tempat kembalinya adalah neraka.”
Banyak hadits lain yang mirip dengan apa yang tercantum di atas yang telah diriwayatkan dalam kitab Shaḥīḥ Bukhārī.
Ajaran Ahl-ul-Bait Nabi Saw
Kita meyakini, berdasarkan perintah Rasūl Saw, bahwa hadits yang dibawa oleh para imam wajib diikuti. Karena, pertama, dalam hadits mutawatir yang terdapat dalam kebanyakan kitab-kitab hadits Ahl-us-Sunnah maupun Syī‘ah telah dijelaskan tentang hal ini. Dalam kitab hadits Tirmidzī diriwayatkan, Nabi Muḥammad Saw pernah bersabda:
Wahai manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan sesuatu di antara kalian, apabila kamu sekalian berpegang teguh kepadanya, maka (kalian) tidak akan tersesat, yaitu al-Qur’ān dan ‘Itrahku, Ahl-ul-Baitku.”
Kedua, para imam Ahl-ul-Bait a.s. meriwayatkan semua hadis mereka dari Rasūl Saw dan mengatakan bahwa apa yang telah disebutkan berasal dari kakek-kakek mereka dan berujung kepada Rasūl Saw.
Benar, Rasūl Saw memahami dengan baik hal-hal mendatang dan segala permasalahan yang akan dialami kaum muslimin, sebagaimana beliau pun mengetahui solusi yang harus diambil sampai hari kiamat dengan mengikuti al-Qur’ān dan para imam Ahl-ul-Bait a.s.
Mungkinkah bagi kita untuk tidak menghiraukan hadits yang memiliki peran begitu penting dengan kandungan yang luhur dan dengan sanad yang akurat? Atau membiarkannya begitu saja? Dengan alasan inilah akhirnya kita sampai pada sebuah keyakinan bahwa apabila kita memberikan perhatian terhadap hal ini, niacaya kaum muslimin tidak akan menghadapi masalah yang sekarang dihadapi dalam berbagai perkara aqidah, tafsīr, dan fiqih.