3-1 Beberapa Kekeramatan & Keistimewaannya – Imam Muhammad Al-Baqir Putra Imam Ali Zain ul-Abidin
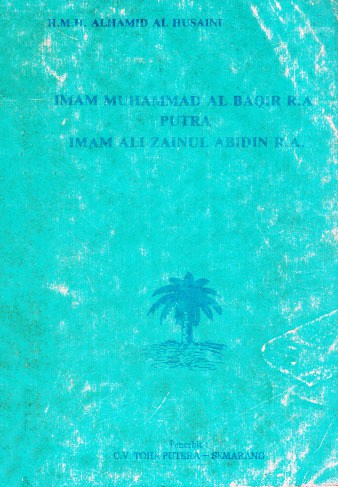
Dari Kitab:
IMAM MUHAMMAD AL-BAQIR R.A.
PUTRA
IMAM ALI ZAIN UL-ABIDIN R.A.
Oleh: H.M.H. Al-Hamid Al-Husaini
Penerbit: C.V. Toha Putera - Semarang
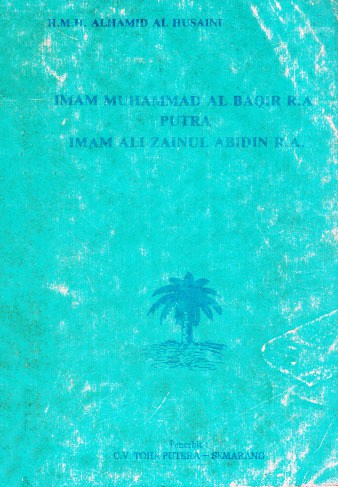
Dari Kitab:
IMAM MUHAMMAD AL-BAQIR R.A.
PUTRA
IMAM ALI ZAIN UL-ABIDIN R.A.
Oleh: H.M.H. Al-Hamid Al-Husaini
Penerbit: C.V. Toha Putera - Semarang
Beberapa Kekeramatan dan Keistimewaannya.
Keramat atau kekeramatan dalam pengertian bahasa, bermakna “kemuliaan” atau “kehormatan”. Sebagai peristilahan khusus, kata “keramat” bermakna kemuliaan khusus yang dilimpahkan Allah s.w.t. kepada hamba-Nya yang hidup zuhud, saleh dan penuh taqwa, berupa pengetahuan mengenai soal-soal ghaib atau hal-hal lainnya yang menyimpang dari hukum kebiasaan.
Sidī ‘Abdul-Ghaniy an-Nabulsiy dalam syarah “ath-Tharīqatul-Muḥammadiyyah” menjelaskan makna “keramat” sebagai berikut: “Keramat adalah suatu persoalan yang menyimpang dari hukum kebiasaan, tanpa dapat ditentang dan tampak pada pribadi hamba Allah yang hidup saleh, mengikuti sepenuhnya tuntunan Nabi dengan iman yang mantap, keyakinan yang lurus dan amal perbuatan yang baik.”
Dalam kehidupan spiritual – kerohanian – kaum Muslimin mengenal adanya orang-orang saleh yang sangat tinggi tingkat kebaktiannya kepada Allah dan Rasul-Nya, memperoleh karunia Ilahi berupa kesanggupan mengetahui beberapa rahasia ghaib. Orang saleh yang demikian itu lazim disebut: “Waliyyullāh” atau “orang keramat”. Martabat kerohanian setinggi itu di kalangan para anggota Ahlul-Bait Rasul Allah s.a.w. bukan soal yang aneh. Hal itu bukan semata-mata karena mereka itu keturunan Rasul Allah s.a.w. melainkan karena mereka itu memiliki taraf keimanan dan ketaqwaan yang sangat tinggi dan hidup membersihkan diri dari segala macam pamrih keduniawian.
Orang tidak akan sulit mempercayai “keramat” yang ada pada para waliyyullāh, jika ia memandang persoalan itu dari sudut kekuasaan Allah s.w.t. Yang Maha Mutlak, yang dapat berbuat apa saja menurut kehendak-Nya dan melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Tak ada apa pun yang dapat merintangi limpahan rahmat-Nya.
“Mā syā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun” Allah dapat berbuat apa saja menurut kehendak-Nya. Apa yang dikehendaki jadilah, dan apa yang tidak dikehendak tak akan terjadi. Itu merupakan prinsip keimanan yang tak dapat diganggu-gugat dan wajib diyakini oleh setiap insan yang beriman.
Dengan demikian tidak ada alasan syar‘iy untuk tidak membenarkan atau tidak mempercayai adanya “keramat”. Karena tidak membenarkan atau tidak mempercayai adanya “keramat” sama artinya dengan tidak membenarkan atau tidak mempercayai kemutlakan kekuasaan Allah s.w.t. untuk berbuat sesuatu menurut kehendak-Nya sekalipun akibat dari perbuatan itu menyimpang dari hukum kebiasaan yang berlaku bagi seluruh alam wujud, termasuk manusia. “Keramat” bukan hasil usaha manusia dan bukan pula suatu kekuatan atau kesanggupan yang bersumber pada kekuasaan manusia, melainkan bersumber pada kekuasaan Allah dan limpahan karunia-Nya kepada seorang hamba yang diridhai-Nya.
“Keramat” tidak mempunyai bentuk tertentu dan tidak pula terjadi dalam waktu-waktu tertentu. Soal bentuk dan waktu terjadinya, tergantung sepenuhnya pada kehendak Allah. Di antara bentuk-bentuk kekeramatan atau “keramat” yang paling banyak dibicarakan orang ialah “ilmu ghaib” atau dengan perkataan lain yang lebih jelas ialah: Mengetahui sesuatu yang belum terjadi.
“Ilmu ghaib” ada dua macam. Yang pertama ialah: Ilmu yang bersifat dzātiy dan mutlak mencakup segala sesuatu. Ilmu yang bersifat demikian itu hanya ada pada Dzāt Allah s.w.t., tak ada apa pun yang menyamai dan menyertai-Nya. Yang kedua ialah ilmu ghaib yang dilimpahkan Allah s.w.t. kepada para hamba yang dikehendaki-Nya, seperti para nabi, para rasul dan para waliyyullāh.
Mengenai sebagian dari “ilmu ghaib” yang dikaruniakan Allah s.w.t. kepada para Nabi dan para waliyyullāh, tidaklah diragukan lagi, karena banyak dalil naqli (ayat-ayat suci al-Qur’ān) telah menegaskan dengan gamblang. Antara lain dalam surat al-Jinn ayat 26-27:
“Dialah Allah Maha Mengetahui segala yang ghaib. Dia tidak memperlihatkan yang ghaib itu kepada siapa pun kecuali kepada para rasul yang diridhai-Nya.”
“Dan telah Kami ajarkan kepadanya (kepada Nabi Khidhir a.s.) ilmu ghaib dari sisi Kami.” (Surat al-Kahfi: 66).
“Allah tidak memperlihatkan hal-hal yang ghaib kepada kalian, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya di antara para rasul-Nya.” (S. Āli ‘Imrān: 179).
“Allah mengetahui segala yang ada di hadapan dan di belakang mereka (yakni yang telah, yang sedang dan yang akan terjadi), sedangkan mereka (para hamba Allah) tidak mengetahui apa pun dari ilmu (pengetahuan) yang ada pada Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh-Nya.” (S. Al-Baqarah: 225).
Ilmu atau pengetahuan Allah mengenai segala sesuatu yang zhahir dan yang ghaib, adalah mutlak dan wajib bagi Dzāt-Nya. Sedangkan yang ada pada manusia tidak mutlak dan tidak wajib (tidak pasti), tetapi “mungkin” yakni bisa ada dan bisa tidak. Sebab ilmu (pengetahuan) yang ada pada manusia itu tidak bersifat dzātiy, tetapi muktasab (diperoleh dari Allah) dan tergantung pada kehendak Allah. Ilmu (pengetahuan) yang ada pada Allah tidak terbatas, sedangkan ilmu (pengetahuan) yang ada pada manusia terbatas, sebatas yang diberikan Allah kepadanya. Ilmu (pengetahuan) Allah kekal dan tidak berubah, sedangkan yang ada pada manusia tidak kekal dan berubah.
Di bawah ini kami kemukakan contoh ilmu ghaib yang oleh Allah dilimpahkan kepada Rasul-Nya, Muḥammad s.a.w., dan kepada seorang hamba-Nya yang saleh yaitu Imām Syāfi‘iy r.a.; kemudian kami susul dengan beberapa riwayat mengenai kekeramatan dan keistimewaan Imām Muḥammad al-Bāqir r.a.
“Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abū Nu‘aim di dalam kitab “ad-Dalā’il” menceritakan bahwa ‘Abdullāh bin ‘Abbās r.a. pernah berkata sebagai berikut:
“Ummul-Fadhl” (yakni bundanya sendiri) menceritakan kepadaku, bahwa pada suatu hari ia lewat di hadapan Rasul Allah s.a.w. Kepada ibuku Rasul Allah berkata: “Anda akan hamil…. dan bila bayi itu telah lahir, bawalah ia kepadaku!. Ummul-Fadhl (ibuku) terperanjat lalu berkata: “Ya Rasul Allah, bagaimana mungkin….. itu menyalahi kebiasaan orang-orang Quraisy”. Rasul Allah s.a.w. menjawab: “Ya, itulah yang kuberitahukan kepada anda!” Beberapa waktu kemudian hamillah Ummul-Fadhl dan setelah melahirkan, anaknya yang masih bayi itu dibawanya menghadap Rasul Allah s.a.w. Beliau lalu mengucapkan adzan pada telinga kanan bayi itu, dan pada telinga kirinya beliau mengucapkan iqamat, kemudian beliau memberi nama “‘Abdullāh”. Setelah itu beliau berkata: “Silakan bawa Abul-Khulafā’ (bapak para Khalīfah) ini.” Oleh Ummul-Fadhl peristiwa itu diberitahukan kepada suaminya, al-‘Abbās bin ‘Abdul-Muththalib. ‘Abbās segera datang menghadap Rasul Allah s.a.w. untuk menanyakan persoalan itu. Rasul Allah s.a.w. menjawab: “Itulah yang kuberitahukan kepada anda. Anak itu akan menjadi Abul-Khulafā’.” (11).
Imām Muḥammad bin Idrīs asy-Syāfi‘iy r.a. beberapa saat menjelang wafatnya berkata kepada beberapa orang sahabatnya: “Engkau hai Abū Ya‘qūb akan mati dalam keadaan terbelenggu!,,,, Engkau, hai Muznī, di Mesir engkau ditimpa musibah besar!…. Engkau, hai ‘Abdul-Ḥakam, besok akan kembali lagi kepada madzhab ayahmu!… Dan engkau hai Rabī‘, akan menjadi orang yang bermanfaat bagiku dalam menyebarkan buku-buku! Hai Ya‘qūb, silakan engkau tinggalkan tempat ini dan terimalah borgol…..!”
Tak lama kemudian setelah Imām Syāfi‘iy wafat pada tahun 104 H. semua yang diucapkannya itu menjadi kenyataan. Demikianlah kata al-Manawiy.
Catatan: