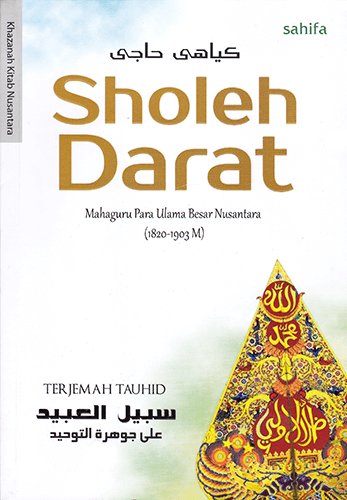Sifat Idrāk
Syaikh Ibrāhīm al-Laqqānī melanjutkan pembahasan dengan membahas tentang perselisihan ulama dalam masalah sifat idrāk.
Beliau berkata:
| فَهَلْ لَهُ إِدْرَاكٌ أَوْ لَا خُلْفُ |
وَ عِنْدَ قُوْمٍ صَحَّ فِيْهِ الْوَقْفُ. |
“Apakah Allah memiliki (sifat) idrāk atau tidak, diperselisihkan oleh ulama. Dan menurut sebagian ulama: “Telah sah padanya tawaqquf”.”
Para ulama berbeda pendapat dalam masalah apakah Allah memiliki sifat idrāk atau tidak. Para ulama muta’akhirin berbeda pendapat dalam masalah ini, pendapat yang dianggap lebih benar adalah mauqif, yakni tidak menetapkan dan juga tidak meniadakan sifat idrāk pada Allah. Wallāhu a‘lam.
Lebih utama tidak membahas masalah ini dengan orang awam, karena bisa menimbulkan prasangka yang tidak patut bagi Allah. Cukuplah mereka meyakini bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Berkehendak. Adapun tentang idrāk dan takwīn, mereka tidak wajib mengetahui, karena keduanya sudah masuk dalam ta‘alluq shifat qudrah yaitu shifat af‘āl. Semua penjelasan di atas adalah pendapat Imām Abū Ḥasan al-Asy‘arī.
Asmā’ Allah yang Diambil dari Sifat-Nya
Syaikh Ibrāhīm al-Laqqānī melanjutkan pembahasan tentang penetapan asmā’ (nama) untuk menjelaskan sifat wajib bertempat pada maushūf (yang disifati).
Beliau berkata:
| حَتَّى عَلِيْمٌ قَادِرٌ مُرِيْدُ |
سَمِعٌ بَصِيْرٌ مَا يَشَا يُرِيْدُ مُتَكَلِّمٌ. |
“(Allah adalah) Dzāt yang Hidup, Ber‘ilmu, Berkuasa,
Berkehendak, Mendengar, dan Melihat. Apa saja yang Dia inginkan maka Dia kehendaki”
“Dan wajib bagi Allah memiliki sifat Kalām, maka Dia adalah) Mutakallim (Dzāt yang berfirman).”
Ketika Allah wajib bersifat ḥayāt (hidup) maka Allah menjadi Ḥayyun (Dzāt Yang Maha Hidup). Ketika Allah wajib bersifat ‘ilmu (mengetahui) maka Allah menjadi ‘Ālimun (Dzāt Yang Maha Mengetahui). Ketika Allah wajib bersifat qudrah (berkuasa) dan irādah (berkehendak) maka Allah menjadi Qādirun (Dzāt Yang Maha Kuasa) dan Murīdun (Dzāt Yang Maha Berkehendak). Ketika Allah wajib bersifat sam‘ (mendengar) dan bashar (melihat) maka Allah menjadi Sāmi‘un (Dzāt Yang Maha Mendengar) dan Bāshirun (Dzāt Yang Maha Melihat). Hal-hal yang dikehendaki dengan masyī’ah juga dikehendaki dengan irādah, ini menunjukkan bahwa masyī’ah dan irādah adalah murādif (beda lafazh tapi maknanya sama). Ketika Allah wajib bersifat kalām (berfirman) maka Allah menjadi Mutakallimun (Dzāt Yang Maha Berfirman). Telah cukup tujuh asmā’ (nama) untuk tujuh sifat ma‘ānī.
Penjelasan
Syaikh Ibrāhīm al-Laqqānī mengikuti Imām Abū Ḥasan al-Asy‘arī yang berpendapat bahwa Allah tidak memiliki ḥāl, maksudnya tidak memiliki shifat ma‘nawiyyah. Oleh karena itu, beliau tidak berkata: “Kaunuhū Ḥayyan”, tapi beliau mengatakan “Ḥayyan” untuk menetapkan asmā’ (nama) yang diambil dari tujuh shifat ma‘ānī yang telah disebutkan. Harusnya qudrah adalah qādirun, harusnya Dzāt yang bersifat irādah adalah murīdun.
Menurut pendapat yang dipilih, Allah tidak memiliki ḥāl (58). Ḥāl itu mustaḥīl bagi Allah s.w.t. Sebab, ḥāl bukanlah sesuatu yang wujūd (ada) juga bukan sesuatu yang ‘adam (tidak ada), tapi di antara keduanya. Perkara yang ditolak oleh Imām Abū Ḥasan al-Asy‘arī adalah tetapnya ḥāl, bukan meniadakan asmā’ (nama), seperti Qādirun, Murīdun, dan seterusnya. Ketika Dzāt Allah telah bersifat qudrah dan irādah, maka secara otomatis wajib memiliki asmā’ Qādirun, Murīdun.
Sedangkan menurut Imām as-Sanusī, mengikuti pendapat Imām Abū Manshūr al-Māturīdī, berpendapat bahwa Allah memiliki ḥāl ma‘nawiyyah. Ketika Dzāt telah bersifat qudrah dan irādah misalnya, maka menjadi tetaplah Dzāt tersebut “kaunuhū qādirun, kaunuhū murīdun” sebagai konsekuensi dari sifat qudrah dan irādah.
Kesimpulannya, ‘ulamā’ Ahl-us-Sunnah wal-Jamā‘ah telah sepakat bahwa Allah itu Qādiran, Murīdan, dan seterusnya, perbedaan hanya dalam masalah ḥāl. Menurut Imām as-Sanusī, tetapnya Qudrah menetapkan ḥāl yang dinamakan ma‘nawiyyah, maka qudrah adalah shifat ma‘ānī, kaunuhū qādiran itu shifat ma‘nawiyyah, Qādiran itu mulāzim (menetap) pada qudrah. Sedangkan menurut ulama yang meniadakan ḥāl, maka Qādiran itu hanya ‘ibārah (ungkapan) dari adanya sifat qudrah yang menetap pada Dzāt, maka qādiran itu amrun i‘tibārī. (59).
Kedua pendapat ini sama-sama dari ‘ulamā’ Ahl-us-Sunnah wal-Jamā‘ah. Pendapat yang mengingkari adanya ḥāl ma‘nawiyyah bukan berarti mengingkari bahwa Allah Qādiran dan Murīdan, sama sekali tidak. Sebab, orang yang mengingkari Qādiran dan Murīdan Allah dihukumi kafir. Na‘ūdzubillāh. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam memahami dua pendapat ini.
Madzhab Mu‘tazilah meniadakan sifat-sifat ma‘ānī yang ada tujuh. Menurut mereka, yang dinamakan qudrah adalah kiasan dari qādirun, mereka bertaka: “Allāhu qādirun bi dzātihī, Murīdun bi dzātihī” (Allah Maha Kuasa dengan Dzāt-Nya, Maha berkehendak dengan Dzāt-Nya) tanpa mempertimbangkan sifat qudrah dan irādah. Ini madzhab sesat yang tidak boleh diikuti.