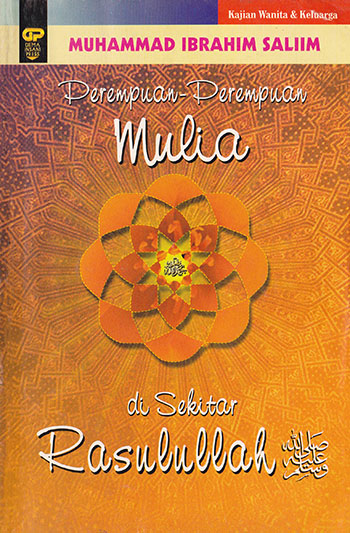3. ZAINAB BINTI MUḤAMMAD BIN ‘ABDULLĀH
Lima belas abad sudah berlalu dari kematian Zainab, namun sosok Zainab meninggalkan kenangan yang harum sepanjang sejarah, baik dalam kesetiaan, ketulusan, maupun keteguhan imannya.
Zainab dilahirkan 30 tahun setelah kelahiran Rasūlullāh s.a.w.. Ketika usianya menginjak dewasa, datanglah bibinya Ḥālah binti Khuwailid (saudari Khadījah binti Khuwailid) guna melamarnya untuk putranya, yaitu Abul-‘Āsh. Setelah semua belah pihak saling menyetujui maka dilangsungkanlah akad nikah.
Di hari pernikahan Zainab dengan Abul-‘Āsh ibn-ur-Rabī‘. Khadījah turut bersuka cita atas pernikahan mereka berdua dan menghadiahkan kalung yang dipakainya untuk disematkan ke leher Zainab sebagai kado pernikahannya.
Perlu digarisbawahi bahwa pernikahan tersebut berlangsung sebelum turunnya wahyu kepada Rasūlullāh s.a.w.. Ketika cahaya wahyu datang menyinari bumi, Zainab termasuk salah seorang yang beriman, sedangkan suaminya (Abul-‘Āsh) tidak mudah begitu saja melepas agamanya yang lama. Hubungan pasangan ini pun terancam retak dengan sebuah kekuatan – yakni perbedaan agama yang dapat mengalahkan cinta mereka.
Pada saat Abul-‘Āsh bersikeras mempertahankan agamanya yang lama seraya berkata: “Wahai Zainab, kita tidak bisa berharap banyak dari hubungan kita, jika kamu bersama agamamu dan saya tetap dengan agama saya.” Zainab pun teguh dengan pendiriannya seraya berkata: “Wahai suamiku, tidak ada pilihan selagi kamu tetap teguh dengan agamamu. Pulangkan saja aku pada ayahku atau masuk Islam bersamaku. Karena Zainab sudah tidak halal lagi bagimu kecuali jika kamu mau beriman sebagaimana aku.”
Di tengah suasana yang cukup dilematis, tiba-tiba terdengar bisikan yang berkata: “Meskipun agama telah memisahkan raga mereka, tapi cinta mereka akan tetap kekal sampai suatu saat nanti agamalah yang akan menyatukan mereka.”
Perpisahan di antara keduanya pun akhirnya tidak bisa dielakkan lagi dan hari terus berlalu sampai datang waktu hijrah Rasūlullāh s.a.w. ke Madīnah di mana Zainab termasuk rombongan dari kaum Muhājirīn.
Pada suatu hari, datanglah kaum Quraisy ke Badar untuk berperang dengan Rasūlullāh s.a.w.. Abul-‘Āsh ibn-ur-Rabī‘ datang bukan untuk mengikrarkan Islamnya, melainkan datang bersama barisan Quraisy yang memerangi Rasūlullāh s.a.w..
Peperangan pun terjadi dengan kemenangan bagi kaum muslimin. Setelah peperangan berakhir, keadaan semakin keruh ketika Abul-‘Āsh termasuk salah seorang tawanan kaum muslimin.
Pada saat orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan tersebut dengan harta benda, Zainab pun mengirim harta dan kalungnya untuk menebus suaminya, Abul-‘Āsh ibn-ur-Rabī‘.
Ketika Rasūlullāh saw. melihat kalung tersebut, hati beliau terenyuh seraya berkata kepada para sahabatnya: “Kalau kalian berpendapat untuk membebaskan tawanan Zainab dan mengembalikan uang tebusannya maka lakukanlah.” Para sahabat menjawab: “Baik, wahai Rasūlullāh”. Dibebaskanlah Abul-‘Āsh dan mengembalikan uang tebusan dari Zainab.
Sebelum berangkat ke Makkah, Rasūlullāh saw. mengambil janji dari Abul-‘Āsh untuk membiarkan Zainab kembali kepadanya ke Madīnah.
Dalam perjalanannya menuju Makkah, tampak jelas bagi Abul-‘Āsh, ketulusan dan kemuliaan istrinya. Sosok istri yang mengorbankan apa yang dimilikinya untuk menebus sang suami tercinta. Kendati demikian, tidak sepatah pun kata terima kasih keluar dari mulut Abul-‘Āsh setibanya mereka di Makkah “Sekarang tiba waktunya kamu harus kembali ke ayahmu Zainab,” itulah kata-kata yang sempat terucap dari mulut Abul-‘Āsh sebagaimana janjinya kepada Rasūlullāh s.a.w..
Di ujung pertemuan yang mungkin kali terakhir itu, Abul-‘Āsh tidak kuasa menahan uraian air mata yang membasahi pipinya. Siapa yang sanggup berpisah dengan orang yang paling dicintai. Perpisahan yang seharusnya tidak terjadi apabila tidak ada “jurang agama” yang membatasi antara keduanya.
Sementara itu, Zaid bin Ḥāritsah dan seorang dari Anshār telah menunggu kedatangan Zainab di luar kota Makkah. Sedangkan yang mengantar Zainab sampai batas luar kota Makkah adalah Kinānah ibn-ur-Rabī‘, adik Abul-‘Āsh ibn-ur-Rabī‘. Sebelum mereka melepas kepergian Zainab, Abul-‘Āsh berpesan kepada adiknya, hai adikku, engkau tahu betapa aku sangat mencintainya (Zainab). Tidak ada wanita Quraisy yang saya cintai kecuali dia. Sungguh, sangat berat bagi saya untuk berpisah dengannya. Antarkan dia sampai di luar kota tempat utusan Muḥammad telah menunggu di sana. Jagalah dia sebagaimana engkau menjaga saudara kandungmu, jaga dan lindungi dia sampai titik darah penghabisanmu.”
Pada saat Zainab sedang berkemas-kemas untuk berangkat, datanglah Hindun binti ‘Utbah lalu berkata: “Wahai putri Muḥammad, saya dengar kamu akan berangkat menemui ayahmu” Zainab menjawab: “Tidak, saya tidak berangkat.” Hindun kembali berkata: “Wahai putri pamanku, jangan urungkan niatmu (untuk berangkat). Kalau memang kamu membutuhkan bekal untuk kamu bawa selama perjalanan, saya telah menyiapkanya dan jangan segan-segan untuk menerimanya. Tidak baik menolak pertolongan sesama wanita.”
Zainab berkata (dalam hatinya): “Demi Allah, saya tidak menyangka dia (Hindun) mengatakan hal itu. Akan tetapi lantaran takut kepadanya, saya tidak berani mengatakan hal yang sebenarnya bahwa saya benar-benar mau berangkat.”
Setelah selesai berkemas, datanglah adik iparnya, Kinānah ibn-ur-Rabī‘ dengan membawa seekor unta. Berangkatlah Zainab siang hari itu di bawah pengawalan adik iparnya yang melengkapi dirinya dengan panah dan busurnya.
Namun, apakah kaum Quraisy Makkah membiarkan Zainab begitu saja, setelah mereka kalah dalam Perang Badar? Tidak, berita tentang pemberangkatan Zainab ternyata sudah tersebar dan kaum Quraisy pun segera membuntutinya dan bertemu di Wadi Thuwa. Habbār ibn-ul-Aswad bin Muththalib dan Nāfi‘ bin ‘Abd-ul-Qais adalah orang yang pertama kali menjumpai Zainab, dan pada saat itu juga Habbār mengarahkan tombaknya ke arah tandu yang membawa Zainab yang pada saat itu dia sedang hamil. Zainab terjatuh dan darah pun mengucur dari perutnya akibat terjatuh itu.
Melihat hal itu, Kinānah ibn-ur-Rabī‘ tidak ambil diam dan dengan membusurkan anak panahnya, dia menantang orang-orang yang mengepungnya seraya berkata: “Demi Allah, kalau ada yang berani mendekat, akan saya panah.”
Ancaman itu pun cukup menggetarkan orang-orang di sekitarnya lalu datanglah Abū Sufyān disela-sela kerumunan orang seraya berkata: “Wahai Kinānah, masukan kembali anak panah tersebut ke sarungnya, dengar apa yang saya katakan: “Setelah Kinānah menyarungkan anak panahnya, datanglah Sufyān mendekatinya lalu berkata: “Sesungguhnya tindakan mu membawa seorang wanita di tengah-tengah kaum lelaki secara terang-terangan adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Yang demikian itu termasuk penghinaan dan pelecehan bagi kami. Sungguh tidak sedikitpun terbetik di dalam diri kami keinginan untuk menawannya lantaran dendam (atas kekalahan) melainkan kami ingin kamu kembali bersama wanita itu dan berangkat denganya menunggu malam tiba”.
Dan ketika malam tiba, berangkatlah Kinānah mengantarkan kakak iparnya sampai batas kota Makkah untuk diserahkan kepada Zaid bin Ḥāritsah dan temannya, ketika sampai di Madīnah, diserahkan Zainab kepada Rasūlullāh s.a.w.
Sejak itu berpisahlah kedua pasangan tersebut dan sulit bagi mereka untuk bertemu lagi. Dengan perasaan gundah dan luka, Abul-‘Āsh yang berada di Makkah, hanya bisa meratapi dan merenungi nasibnya. Sementara Zainab yang raganya berada di Madīnah, hatinya sulit untuk dipisahkan dengan sang suami tercinta.
Tahun demi tahun terus berlalu sehingga datang suatu hari ketika Abul-‘Āsh berpergian ke Syām (Suriah) untuk urusan perniagaan, di tengah perjalanan pulang dari Syām dia bertemu dengan tentara Sariah Rasūlullāh s.a.w. yang merampas semua hartanya termasuk harta orang yang dibawanya. Sulit bagi Abul-‘Āsh untuk mengambil harta itu kembali.
Di tengah kegelisahan Abul-‘Āsh dalam mencari solusi untuk bisa mengambil harta itu kembali dari tangan tentara Sariah Rasūlullāh s.a.w., dia teringat Zainab, sang istri yang pernah membebaskanya. Datanglah Abul-‘Āsh ke Madīnah untuk meminta suaka sekaligus bantuan Zainab untuk mengembalikan hartanya. Zainab pun memberi suaka kepadanya. Dan di pagi hari, ketika para sahabat dan Rasūlullāh s.a.w. sedang shalat shubuh, tiba-tiba terdengar suara dari balik tembok berbicara: “Wahai para jamaah, sesungguhnya saya telah memberi suaka kepada Abul-‘Āsh ibn-ur-Rabī‘ dan dia sekarang berada dalam perlindunganku.” Suara itu ternyata adalah suara Zainab.
Setelah menunaikan shalat, Rasūlullāh s.a.w. berdiri di depan jamaah lalu berkata: “Wahai jamaah, apakah kalian mendengar apa yang telah saya dengar. Sesungguhnya, ada seseorang di belakang kalian yang memberi suaka kepada orang lain.” Kemudian Rasūlullāh s.a.w. masuk ke dalam rumah menemui putrinya. Setelah Zainab menceritakan apa yang terjadi dengan Abul-‘Āsh kepada Rasūlullāh s.a.w., beliau berpesan kepada putrinya: “Hormatilah posisinya, jangan sampai dia berbuat sekehendaknya. Sesungguhnya, kamu tidak halal baginya selama dia masih musyrik.”
Pada saat itu, Rasūlullāh s.a.w. tertegun salut akan putrinya yang begitu setia terhadap suaminya yang ditinggalkannya karena perintah Allah s.w.t.. Bukan hanya itu, Zainab juga harus menahan hasrat nafsunya sebagai seorang istri karena perintah Allah. Namun kendati demikian, Zainab tetap mencurahkan kesetiaan, kasih sayang, dan pertolongannya kepada suaminya.
Di hadapan para sahabatnya, Rasūlullāh s.a.w. kemudian bersabda: “Sebagaimana yang telah kalian ketahui, sesungguhnya laki-laki ini (Abul-‘Āsh) adalah bagian dari (tawanan) kita yang kalian telah berhasil merampas hartanya. Namun, jika kalian berbuat baik kepadanya dengan mengembalikan hartanya, kami sangat senang sekali. Akan tetapi, jika kalian tidak mau (mengembalikan hartanya), itu adalah harta rampasan yang Allah berikan kepada kalian dan kalian lebih berhak atas harta itu.” Para sahabat pun menjawab: “Tidak Rasūlullāh, melainkan kita kembalikan harta itu kepadanya.” Tiba-tiba salah seorang dari sahabat berkata: “Wahai Abul-‘Āsh, bagaimana jika anda masuk Islam sehingga kamu bisa mengambil seluruh harta itu untukmu, toh harta itu milik orang-orang musyrik.” Seketika itu pula Abul-‘Āsh menjawab: “Alangkah kejinya aku harus memulai Islamku dengan mengkhianati amanat yang ditanggungkan ke pundakku.”
Akhirnya, para sahabat mengembalikan harta itu kepada Abul-‘Āsh sebagai rasa hormat mereka kepada Rasūlullāh s.a.w. serta atas (kesetiaan) Zainab. Pulanglah Abul-‘Āsh membawa harta tersebut dengan meninggalkan kesan yang begitu mendalam akan keagungan Islam.
Setibanya di Makkah, Abul-‘Āsh langsung membagikan harta tersebut kepada yang berhak. Setelah selesai membagikan, dia berdiri dan berkata: “Wahai kaum Quraisy, apakah masih ada harta kalian yang bersamaku?” Mereka menjawab: “Tidak, semoga Allah membalas kebaikanmu. Sungguh engkau adalah orang yang jujur dan mulia.” Pada saat itu pula Abul-‘Āsh mengikrarkan Islamnya seraya berkata: “Maka saya bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muḥammad adalah hamba dan utusan-Nya. Sesungguhnya, tidak ada yang menghalangi saya untuk masuk Islam ketika saya datang ke Rasūlullāh untuk mengambil harta tersebut kecuali hanya kekhawatiran saya akan omongan para sahabatnya yang mungkin mengira bahwa Islam saya hanya alasan untuk bisa memakan harta kalian. Ketika Allah memberikan harta itu (melalui saya) kepada kalian dan saya tidak ada urusan lagi dengan harta itu, maka tidak ada lagi penghalang bagi saya untuk masuk Islam.”
Setelah masuk Islam, berangkatlah Abul-‘Āsh menuju Madīnah dan bertemulah kembali dua pasangan yang saling mencintai itu setelah sekian lama berpisah. Namun tidak lama setelah pertemuan tersebut, datanglah ajal menjemput Zainab, sang istri tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan ketulusannya kepada sang suami tercinta. Rasūlullāh saw. sangat berduka atas kematian putrinya tersebut.
Zainab meninggal pada tahun 8 Hijriah dengan meninggalkan sejuta kenangan harum. Sejarah mencatatnya sebagai sosok istri yang setia, tulus, dan teguh keimanannya. Suatu hari dalam perjalanannya menuju Syām, suaminya pernah memujinya dengan syair berikut:
“Wahai putri Amīn (Rasūlullāh saw.) semoga Allah memberimu kesejahteraan Setiap suami pasti akan memuji segala yang ada pada dirimu.”