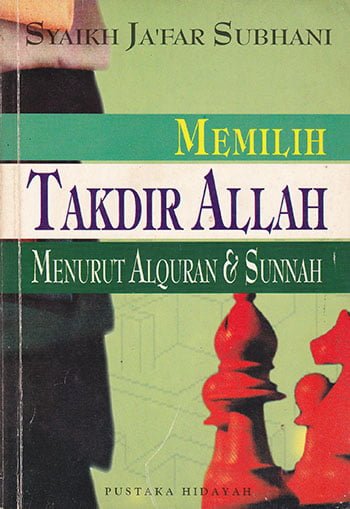PERTANYAAN KELIMA.
Sesungguhnya dari riwayat-riwayat itu, ada dua hal yang dapat disimpulkan. Pertama: perkara-perkara yang definitif, yang tidak terjadi al-Badā’ padanya; Kedua: perkara-perkara atau masalah yang kondisional, yang terjadi al-Badā’ padanya.
Al-‘Ayyāsyī telah meriwayatkan dari al-Fadhil bahwa ia berkata: Aku mendengar Abū Ja‘far r.a. mengatakan: “Di antara perkara itu ada yang definitif dan tidak mustahil, dan ada perkara yang kondisional di sisi Allah yang ditetapkan dan dihapus menurut kehendak-Nya, yang tidak diketahui oleh salah satu makhluk pun. Ada pula yang diberitakan oleh para rasūl tentang masalah yang akan terjadi. Dia tidak mungkin berdusta kepada Diri-Nya, Nabi-Nya, juga kepada malaikat-Nya.” (Biḥār-ul-Anwār, Jilid IV, hlm. 119, hadits No. 58).
Dari pernyataan di atas, muncul pertanyaan: “Atas pertimbangan apa ada perkara-perkara yang definitif dan perkara-perkara yang kondisional?”
JAWAB:
Kita tidak mungkin bisa membuat pertimbangan dan pembatasan bahwa perkara itu definitif atau kondisional, karena penentuannya berpijak kepada pengetahuan tentang segala yang ditulis di Lawḥ-ul-Maḥfūzh dan lainnya. Hanya saja bisa dikatakan, bahwa al-Badā’ tidak mungkin terjadi dalam masalah-masalah berikut ini:
1. Perkara yang berkaitan dengan aturan nubuwwah dan wilāyah; juga masalah-masalah yang berkaitan dengannya, seperti mengenai akhir kenabian. Sesungguhnya terjadinya al-Badā’ dalam hal tersebut mengharuskan rusaknya sistem syarī‘ah. Apabila al-Masīḥ a.s. misalnya, memberitakan tentang akan datangnya seorang Nabi setelah dia, atau jika Nabi s.a.w. memberitakan tentang dirinya, sebagai Nabi terakhir, atau rasūl-rasūl Islam memberitakan bahwa wilāyah sesudahnya adalah wāshī-nya atau para wāshī yang ditentukan, atau memberitakan akan munculnya salah seorang puteranya untuk memenuhi dunia dengan keadilan, dapat dipastikan bahwa tidak mungkin akan terjadi al-Badā’ padanya, karena al-Badā’ ketika itu membatalkan kejadian (ḥikmah) yang akan menyebabkan sesatnya para hamba. Kalau ada kemungkinan terjadi al-Badā’ pada masalah tersebut, maka seorang hamba tidak wajib mengikuti sunnah Nabi s.a.w., menerima al-Wāshī yang shaḥīḥ menurut nash. Sehingga orang-orang tidak memandang Nabi s.a.w. yang mulia sebagai Nabi penutup, dan kemunculan Al-Mahdī sebagai perkara yang dipastikan, dengan alasan bahwa semua perkara itu bisa al-Badā’ padanya, dan di dalam ilmu akidah, ushūl dan sunnah-sunnah. Ilāhiyyah masalah ini bertentangan dengan kebijakan (ḥikmah) dan akan menyesatkan manusia.
2. Lain lagi dengan pemberitaan tentang sesuatu dengan wahyu, sebagaimana kita lihat di dalam kisah Nabi ‘Īsā a.s. ketika mengatakan:
(وَ أُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَ مَا تَدَّخِرِونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لآيَةً إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)
“…Dan aku katakan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu, sesungguhnya yang demikian itu adalah suatu tanda (kebenaran kerasulan) bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman.” (3: 49).
Apabila pemberitaan ini kemudian tidak terjadi, berarti menunjukkan kelemahan pembawa berita dan menyebabkan dituduhnya dia sebagai pembual dan menyebabkan rusaknya kebersihan dan kesucian ucapan dan perbuatannya. Sebagaimana pemberitaan Nabi s.a.w. tentang mati syahidnya ‘Alī, Amīr-ul-Mu’minīn di tangan orang-orang yang paling jahat. Demikian juga mengenai syahidnya Ḥasan atau syahidnya Ḥusain di tanah Karbalā’. Demikian juga tentang berita-berita gaib yang berhubungan dengan Hari Kiamat.
Terjadinya sesuatu yang berbeda dengan apa yang diberitakan akan menyebabkan didustakannya ucapan dan perbuatan para rasūl. Riwayat-riwayat mutawātir dari para Imām menyatakan, bahwasanya Allah s.w.t. tidak akan mendustai Diri-Nya, Nabi-Nya, serta malaikat-Nya. Dengan demikian, pembuktian al-Badā’ terbatas pada hal-hal yang tertentu, yang tidak mungkin dibatasi dengan batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan umat.