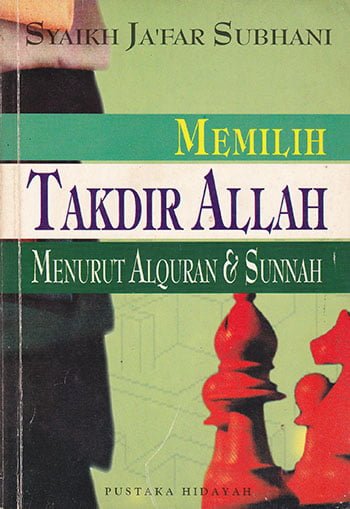PERTANYAAN DAN JAWABAN.
Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang diajukan kepada para pembaca yang budiman, yang harus dijawab. Pertanyaan ini kami ajukan satu per satu, kemudian kami jawab pula satu per satu.
PERTANYAAN PERTAMA:
Bagaimana mungkin al-Badā’ bisa dinisbatkan kepada Allah s.w.t., padahal al-Badā’ berarti “penampakan sesuatu yang sebelumnya tersamar (azh-Zhuhūru Ba’d-al-Khafā’)?”
JAWAB:
Inilah salah satu pertanyaan yang menyudutkan Syī‘ah Imāmiyyah karena keyakinannya terhadap al-Badā’. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut sangatlah jelas. Pertentangan yang terjadi bukanlah dalam hal nama, akan tetapi menyangkut subtansi dan penyandang nama itu. Anda maklum, bahwa hakikat al-Badā’ dalam hal ketetapan (itsbāt) sudah menjadi ijma‘ umat Islam, dan tidak terjadi ikhtilaf di antara mereka. Sebagaimana sudah anda ketahui bahwa yang dimaksud dengan al-badā’ adalah seperti yang dikemukakan dalam al-Qur’ān al-Karīm dan as-Sunnah yang suci.
Baik penamaan dengan kata al-Badā’ ini benar atau tidak, tidaklah layak Syī‘ah Imāmiyyah diserang dari segi etimologi. Ini merupakan suatu tindakan yang tidak berarti. Juga mereka tidak pantas dikecam karena menggunakan kata-kata ini, yakni berkenaan dengan makna tersebut, karena mereka telah mengikuti Nabi mulia s.a.w. ketika menceritakan masalah bencana, dusta, dan kebutaan. Beliau bersabda:
(بَدَا للهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ)
“Sudah nampak bagi Allah untuk memberi cobaan terhadap mereka….” (Imām Muḥyiddīn Ibn ????? an-Nihāyatu fī Gharīb-il-Ḥadītsi wal-Atsār, Abus-Sa‘ādat-ul-Mubārak, Muḥammad al-Jazarī, Jilid I, hlm. 18).
Ucapan para Wāshī pun harus ditafsirkan seperti penafsiran terhadap ucapan Nabi ini.
Sementara mengenai penamaan al-Badā’, ada beberapa pandangan yang dikemukakan oleh suatu kaum:
Pertama: penamaan ini termasuk kategori musyākalah (keserupaan /kemiripan), yang di dalam bahasa ‘Arab mempunyai pengertian sangat luas. Allah s.w.t. telah mengungkapkan perbuatan-Nya sendiri dalam banyak hal dengan ungkapan yang digunakan oleh manusia (ketika mengungkapkan perbuatan mereka sendiri), yakni sebagai musyākalah zhāhiriyyah (kemiripan lahiriyah), karena Dia sedang berdialog dengan manusia, dan sedang berbicara kepada mereka. Contoh-contoh seperti itu telah kami kemukakan sebelumnya.
Di bawah ini adalah cara lain untuk menjelaskan masalah al-Badā’ tersebut, yang akan kami kemukakan satu per satu:
- Secara bahasa, al-Badā’ berarti perpindahan dan perubahan dari satu keputusan kepada keputusan yang lain karena adanya satu pengetahuan (‘ilm) atau dugaan (zhann) mengenai sesuatu, yang sebelumnya tidak terjadi. Akan tetapi, apabila al-Badā’ ini dinisbatkan kepada Allah s.w.t., maka yang dimaksud dengan al-Badā’ di sini adalah sesuatu yang tidak perlu ditunggu; atau sesuatu yang terjadi di luar perhitungan manusia. Juga bisa dikatakan, yang dimaksud dengan azh-Zhuhūru Ba’d-al-Khafā’ (penampakan sesuatu yang sebelumnya tersamar) adalah dalam konteks manusia, karena semua kejadian itu sudah ada dalam Ilmu Allah s.w.t. Dengan kata lain, setiap sesuatu yang tampak setelah sebelumnya tidak tampak adalah al-Badā’ dari Allah untuk manusia, bukan al-Badā’ untuk Allah dan sekaligus untuk manusia. Hanya saja pengertian al-Badā’ di sini diperluas, sebagaimana sering dikatakan: “….badā lillāhi fī hādzih-il-ḥadītsah (telah terjadi al-badā’ dari Allah untuk manusia).”
Firman Allah sehubungan dengan al-Badā’ adalah:
(وَ بَدَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ)
“…Dan jelaslah pada mereka dari Allah apa-apa yang belum pernah mereka perkirakan….” (39: 47).
Tidak diragukan, bahwa sesuatu yang tampak itu dikatakan al-Badā’, yang dimaksud adalah al-Badā’ (penampakkan) dari Allah untuk manusia; hanya penggunaannya diperluas dan digunakan menyangkut Allah s.w.t., sehingga badā lillāhi (dan tampak dari Allah), sejalan dengan apa yang ada dalam perhitungan manusia, dan dengan menganalogikan masalah Allah s.w.t. terhadap masalah mereka. Hal itu sebenarnya tidak apa-apa, selama dalam konteks majāzī (kiasan) dan Muqāyasah (analogi).
- Keterangan yang dikemukakan oleh Syaikh al-Mufīd, menyimpulkan bahwa “Lām” dalam ayat 47 Surat-uz-Zumar di atas, mempunyai arti “Mīm”. Orang-orang ‘Arab berkata: “qad badā li fulān ‘amalun shāliḥun, wa badā lahu kalāmun fashīḥun...” (tampak dari fulan tindakan yang benar, tampak dari kata-kata yang benar). Mereka juga mengatakan: “badā min fulān kadzā….” (dari si fulan tampak demikian). Mereka menjadikan “Lām” menggantikan “Mīm”. Sedangkan menurut pengertian golongan Syī‘ah Imāmiyyah, kalimat “badā lillāhi fī kadzā” artinya “tampak dari Allah”. Yang dimaksud, bukanlah perkataan akhir (final), sedang permasalahan yang sebenarnya masih tersembunyi. Dengan kata lain berarti “seluruh perbuatan Allah s.w.t. yang tampak (zhāhir) pada makhluk-Nya, yang sebelumnya tersamar; atau diketahuinya sesuatu yang belum (diketahui).”
Berdasarkan hal tersebut, maka sesuatu dikatakan al-Badā’, bila sesuatu itu penampakannya berada di luar perhitungan manusia atau terjadi di luar dugaan manusia. (yang ada di antara dua kurung ini menunjukkan pada bentuk yang pertama sebagian tambahan terhadap bahasan bentuk kedua).
- Ilmu Allah s.w.t. terbagi kepada ‘Ilmu Dzātī dan ‘Ilmu Fi‘lī. Yang dimaksud dengan ‘Ilmu Dzātī ialah Dzāt-Nya itu sendiri, yang pada-Nya tidak terjadi perubahan dan pergantian. Sedangkan yang dimaksud dengan Ilmu Fi‘lī Allah adalah yang menyangkut Lawḥ-ul-Mahw dan al-Itsbāt (Lawḥ yang padanya bisa terjadi perubahan dan penetapan). Para malaikat, juga para Nabi dan para Auliyā’, adalah termasuk menifestasi Ilmu Allah. Apabila mereka berkata: “badā Allāhu fī ‘ilmihi” (Allah berbuat al-badā’ dalam Ilmu-Nya), maka yang dimaksud adalah terjadinya al-badā’ dalam ilmu-ilmu ini, yang penisbatannya kepada Allah hanya bersifat Majāz ‘Aqlī, karena merekalah para pembawa pengetahuan tersebut, dan mereka adalah wakil-Nya.
Bisa juga dikatakan, bahwa tingkatan ilmu Allah itu berbeda-beda dan tempatnya bermacam-macam. Ilmu Allah yang pertama dan paling tinggi adalah ‘Ilmu Dzātī, yang masih bersih dari perbuatan dan peringatan; Ilmu yang meliputi segala sesuatu, dan pergantian; Ilmu yang meliputi segala sesuatu, dan segala sesuatu benar-benar diketahui oleh-Nya. Adapun yang dimaksud dengan ‘Ilmu Fi‘lī Allah adalah, bahwa sebagian perbuatan Allah itu merupakan manifestasi ilmu-Nya sebagai Lawḥ-ul-Mahw dan Lawḥ-ul-Itsbāt. Begitu juga para malaikat dan para Nabi, hanya saja peristiwa-peristiwa itu tidak langsung terukir pada malaikat dan Nabi. Demikian juga mengenai ketidakberakhirannya peristiwa tersebut, juga diketahui oleh jiwa Nabi dan malaikat dengan berangsur-angsur dan sedikit demi sedikit; kadang-kadang yang diketahui itu baru sebab sesuatu, selanjutnya baru diketahui sebab sesuatu yang lainnya, yang mengharuskan tidak adanya sebab sesuatu itu, sehingga nampak kepada mereka, bahwa perbuatan yang mereka lakukan berbeda dengan pengetahuan mereka belakangan: Badā lillāh (telah terjadi al-Badā’ dari Allah), atau Badā fī ‘ilmihi (telah terjadi al-Badā’ pada ilmu-Nya). Maka yang dimaksud dengan kata-kata tersebut adalah terjadinya al-Badā’ dan ‘ilmu Fi‘li Allah, bukan dalam ‘ilmu Dzātī Allah.
Shadr Muta’allihīn berkata:
“Sesungguhnya Al-Asmā’-ul-Ḥusnā ini memiliki fenomena dan metafora, dan Allah mempunyai hamba-hamba malakūtī yang semua perbuatannya merupakan ketaatan kepada Allah s.w.t., mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, mereka tidak bermaksiat kepada Allah dengan sesuatu perbuatan dan kehendak mereka. Setiap ada makhluk seperti itu, seluruh perbuatan dan perkataannya pasti benar, karena dalam jiwanya tidak tersirat keinginan yang mempengaruhinya untuk menyalahi kebenaran, bahkan irādah dan kehendaknya lebur di dalam irādah Yang Maha Benar (Allah). Ketaatan mereka kepada Allah s.w.t., adalah seperti tunduknya indera kita terhadap keinginan nafsu, dimana indera tersebut tidak bisa berontak terhadap kehendak nafsu. Ketaatan indera terhadap nafsu tersebut tidak memerlukan perintah dan larangan, ganjaran atau ancaman. Demikian juga ketaatan-ketaatan malaikat di langit terhadap Allah, karena mereka sepenuhnya tunduk kepada perintah Allah. Mereka mendengarkan wahyu-Nya dengan pengamatan batin mereka, sehingga hati para malaikat itu menjadi Kitāb-ul-Mahw dan Itsbāt. Boleh jadi, lukisan yang terukir dalam dada mereka itu bisa hilang, serta berubah, karena keberadaannya yang permisif. Yang tidak mengalami perubahan dan pergantian padanya adalah Dzāt Allah dan sifat-sifatNya yang hakiki. Dengan demikian, hati para Malaikat menjadi al-Alwāḥ-ul-Qadariyyah (lembaran-lembaran takdir), yang termasuk tingkatan ‘Ilmu Fi‘lī Allah. Dan apabila di dalam ‘Ilmu Fi‘lī terjadi perubahan dan pergantian, maka benarlah bila dikatakan: “Badā lillāhi fī ‘ilmihi” (telah terjadi al-Badā’ pada ‘Ilmu Fi‘lī-Nya). (Al-Asfār, Jilid I, hlm. 395-397, dengan sedikit perubahan).
Sampai di sini, paling tidak ada dua hal yang sudah cukup jelas:
Pertama: pembahasan di atas hanya menyangkut substansi dan penyandang nama al-Badā’, bukan pada lafal dan masalah penamaan. Mendiskusikan benar-tidaknya penamaan, tidak perlu menjadi halangan untuk meyakini al-Badā’. Renungkan apa yang dikatakan oleh seorang penyair di bawah ini:
(وَ كُمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلاً صَحِيحًا
وَ آفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ)
“Betapa banyak orang menjadi pencela pembicaraan yang benar, bencananya (berasal dari) pemahaman yang salah.”
Kedua: dibolehkannya pemberian sifat al-Badā’ dengan salah satu cara yang telah dikemukakan di atas.