2-2 Makna-makna Batiniah Puasa dan Syarat-syaratnya – Rahasia Puasa & Zakat
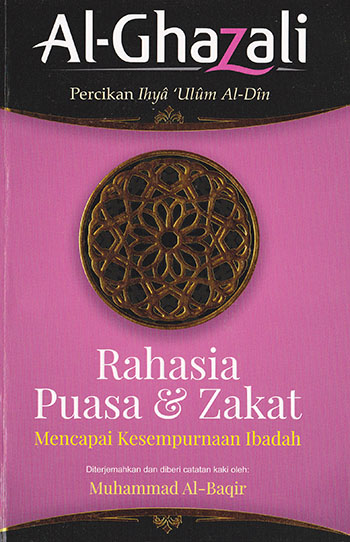
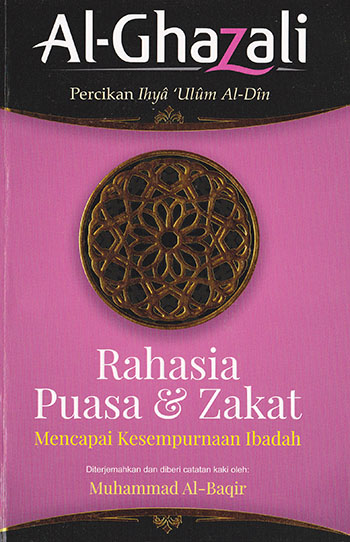
Kelima, ketika berbuka hendaknya mencukupkan diri dengan makanan halal yang sekadarnya saja. Jangan terlalu kenyang, sehingga perutnya penuh dengan makanan (walaupun dari yang halal). Hendaknya pula diingat bahwa: “Tak ada wadah yang lebih dibenci Allah daripada perut yang penuh dengan makanan.”
Bagaimana mungkin seseorang dapat mengambil manfaat puasa yang berupa penghinaan terhadap syaithan, musuh Allah, atau penekanan syahwat hawa-nafsu, kalau orang yang berpuasa itu segera menggantinya – pada saat berbuka – dengan semua yang tidak dapat diperolehnya di siang hari? Atau, adakalanya bahkan menambah-nambah berbagai jenis makanan seperti yang telah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Yaitu, dengan menyimpan macam-macam makanan untuk dimakan pada bulan Ramadhān sejumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya!
Tentunya, telah diketahui bahwa tujuan puasa ialah mengosongkan perut dan mematahkan hawa-nafsu, agar jiwa menjadi kuat guna meningkatkan ketaqwaannya. Maka, jika alat pencernaan seseorang dikosongkan sepanjang hari sampai malam, sehingga selera makannya bergejolak dan keinginannya makin kuat, kemudian diberi makan dan segala yang lezat-lezat sekenyang-kenyangnya, sudah tentu kesenangannya bertambah dan kekuatannya menjadi berlipat-ganda. Bahkan, pelbagai syahwat hawa-nafsunya yang tadinya masih terpendam, kini akan muncul dengan segala kerakusannya.
Jelaslah bahwa ruh puasa dan rahasianya (atau hikmahnya) yang tersembunyi ialah sebagai upaya memperlemah kekuatan-kekuatan fisik, yang merupakan sarana-sarana syaithan dalam mengulangi perbuatan-perbuatan dosa. Oleh sebab itu, tidak akan tercapai ruh puasa, kecuali dengan mengurangi kadar makanan yang dimakan. Yakni, mencukupkan diri dengan sekadar makanan malam yang biasanya dia makan, pada hari-hari ketika dia tidak berpuasa. Adapun jika dia menambahkan makanan yang biasanya dia makan di siang hari dengan makanan malamnya, puasanya itu tidak akan bermanfaat baginya.
Lebih dari itu, di antara pelbagai adab puasa ialah hendaknya orang yang berpuasa tidak memperbanyak tidurnya di siang hari, agar dia benar-benar merasakan lapar dan haus serta makin melemahnya kekuatan tubuh. Dengan demikian, jiwanya pun akan menjadi jernih. Dan hendaknya, dia tetap menjaga berlanjutnya sebagian dari kelemahan itu hingga malam hari, agar terasa ringan baginya untuk bertahajjud dan membaca wirid-wirid yang telah dia tetapkan atas dirinya sendiri. Dengan begitu, dapatlah diharapkan semoga syaithan tidak berani mendekati jiwanya, sehingga dia akan berhasil memandang pada keajaiban kerajaan langit, terutama pada lailat-ul-qadar.
Lailat-ul-qadar ialah malam yang ketika itu akan tersingkap sebagian dan kebesaran alam malakūt (alam atas). Yaitu, yang dimaksud firman Allah:
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.
“Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Qur’ān) pada malam qadar.” (QS. al-Qadr: 1).
Dan, barang siapa menjadikan ruang antara hati dan dadanya sebagai gudang penyimpan makanan, maka akan tertutuplah dia dari pemandangan itu. Bahkan, pengosongan perut pun cukup untuk menyibak tirai penutup itu, jika himmah dikosongkan sama sekali dari apa pun selain Allah. Itulah asas segala-segalanya. Dan, hal itu harus dimulai dengan mengurangi makanan.
Penjelasan selanjutnya yang lebih terinci dapat dibaca pada Kitab tentang Makanan (Bagian dari Kitāb Iḥyā’ ‘Ulūm-id-Dīn – Penerjemah).
Keenam, hendaknya hatinya – setelah selesai berbuka – senantiasa terpaut dan terombang-ambing antara harap dan cemas. Sebab dia tidak tahu, apakah puasanya diterima sehingga dia termasuk golongan muqarrabīn (orang-orang yang didekatkan kepada Allah)? Ataukah ditolak, sehingga dia termasuk golongan mamqutīn (orang-orang yang dibenci oleh-Nya)? Perasaan seperti itulah yang seyogianya menyertai dirinya pada setiap saat, usai melakukan ibadah. Telah diriwayatkan bahwa Ḥasan al-Bashrī melihat (di bulan Ramadhān) sekelompok orang sedang tertawa terbahak-bahak. Dia berkata kepada mereka: “Sesungguhnya Allah s.w.t. menjadikan bulan Ramadhān sebagai arena bagi hamba-hambaNya untuk berlomba-lomba berbakti kepada-Nya. Maka, sebagian orang telah berjaya karena berhasil keluar sebagai pemenang, dan sebagiannya lagi kecewa karena tertinggal di belakang. Karena itu, sungguh amat mengherankan, masih ada orang yang tertawa dan bermain-main pada hari kejayaan orang-orang yang menang, dan kekecewaan orang-orang yang bertindak sia-sia! Demi Allah, seandainya tirai penutup yang ghaib tersibak, niscaya setiap orang yang telah berbuat kebajikan akan sibuk dengan hasil kebajikannya, dan yang telah berbuat kejahatan akan sibuk dengan hasil kejahatannya!” (Yakni, kegembiraan orang yang diterima amalnya akan menyibukkannya dari bermain-main, dan kekecewaan orang yang tertolak amalnya akan menghalanginya dari tertawa).
Pernah ada seorang yang berkata kepada Ahnaf bin Qais: “Anda seorang yang telah berusia lanjut. Sementara puasa akan melemahkan fisik anda!”: Jawab Ahnaf: “Memang, aku menjadikannya sebagai bekal untuk suatu perjalanan amat jauh. Sabar dalam melaksanakan kebaktian kepada Allah lebih ringan daripada sabar menderita ‘adzab-Nya.”
Itulah makna-makna batiniah dalam puasa.
Mungkin anda akan berkata: “Para fuqahā’ (ahli fiqih) telah menyatakan bahwa orang yang berpuasa dan menahan diri dari nafsu makan dan seks, puasanya itu sah adanya, walaupun dia meninggalkan makna-makna batiniah seperti tersebut di atas. Bagaimana ini?”
Jawabnya, kaum fuqahā’ yang hanya memperhatikan hal-hal lahiriah, memang telah menetapkan persyaratan-persyaratan lahiriah bagi sahnya puasa. Akan tetapi, dalil-dalil yang mereka kemukakan lebih lemah daripada syarat-syarat batiniah seperti tersebut di atas. Terutama soal-soal ghibah (pergunjingan) dan sebagainya. Hal ini disebabkan, para fuqaha’ itu tidak menetapkan kewajiban-kewajiban ini kecuali yang mampu dikerjakan oleh semua orang, termasuk mereka yang lalai dan sangat tertarik pada kehidupan dunia. Adapun para ulama yang mengutamakan kehidupan akhirat, menganggap bahwa keabsahan suatu pekerjaan tidak dapat dipisahkan dari kemungkinan diterimanya (oleh Allah s.w.t.). Hanya dengan diterimanya sesuatu oleh-Nya, kita akan mencapai tujuan. Dan, mereka ini memahami bahwa tujuan puasa ialah bertindak dan bersikap dengan dan sesuai dengan akhlak Allah dan sifat-sifatNya. Juga, berusaha sekuatnya menyamai sifat para malaikat dalam hal menahan diri dari segala syahwat hawa-nafsu.
Orang yang berpuasa hendaknya tidak memperbanyak tidurnya di siang hari, supaya benar-benar merasakan lapar dan haus serta makin melemahnya tubuh. Agar jiwanya menjadi jernih.
Sebab, para malaikat adalah makhluk-makhluk yang dijauhkan dari segala macam syahwat dan kecenderungan hawa-nafsu. Adapun tingkatan manusia ialah di atas tingkatan hewan. Hal ini mengingat kemampuannya untuk mematahkan kecenderungan hawa-nafsunya, dengan cahaya akalnya. Tetapi, bersamaan dengan itu, dia berada di bawah tingkatan malaikat, disebabkan adanya kekuasaan hawa-nafsu atas dirinya. Hal itu pula merupakan ujian baginya, mengingat bahwa dia senantiasa harus melawannya. Maka, setiap kali dia membenarkan diri dalam pemuasan hawa-nafsunya, dia meluncur ke tingkatan yang paling bawah sehingga berada di bawah di tengah-tengah alam binatang. Sebaliknya, setiap kali dia dapat menekan dan mengalahkan hawa-nafsunya, dia terbang ke tingkatan yang paling atas sehingga bergabung dengan para malaikat. Sementara para malaikat adalah makhluk yang didekatkan kepada Allah s.w.t. Maka, siapa saja meneladani mereka dan berusaha menyerupai akhlak mereka, dia akan mendekat kepada Allah juga, seperti halnya para malaikat. Dan, siapa saja yang mirip dengan orang yang dekat kepada Allah, dekat juga. Akan tetapi, yang dimaksud dengan kedekatan di sini, bukanlah dekat dalam hal tempat atau ruang, tetapi dekat dengan sifat-sifat.
Nah, jika yang demikian itu merupakan rahasia (hikmah) puasa dalam pandangan orang-orang berakal sehat dan yang menggunakan mata-hatinya, faedah apakah gerangan yang dapat diperoleh dari perbuatan menangguhkan makanan siang hari, untuk kemudian digantikan, bahkan ditambahkan pada makanan di malam hari? Terlebih lagi bila disertai dengan pelampiasan hawa-nafsu sepanjang siang hari?
Seandainya hal seperti itu dianggap berfaedah, apa artinya sabda Nabi s.a.w.:
كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوْعُ وَ الْعَطَشُ.
“Betapa banyak orang berpuasa, tetapi tidak memperoleh sesuatu dari puasanya itu selain rasa lapar dan haus.”.
Karena itulah Abū Dardā’ r.a. berkata: “Alangkah agungnya tidur dan makannya orang-orang yang bijak dan piawai.”
Bagaimana orang-orang berakal tidak mengecam puasa yang dilakukan oleh orang-orang bodoh serta bangun malam mereka, sedangkan sekilas tidurnya orang-orang yang kuat keyakinan dan ketaqwaannya, jauh lebih utama dari ibadah orang-orang yang terkelabui oleh dirinya sendiri, walaupun ibadah mereka itu sebesar gunung. Karena itu pulalah, sebagian para ulama berkata: “Betapa banyak orang berpuasa, padahal dia berbuka (tidak berpuasa). Dan betapa banyak orang berbuka, padahal ia berpuasa.” Yang dimaksud dengan orang berbuka tetapi berpuasa ialah, yang menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan dosa, sementara dia tetap makan dan minum. Adapun yang dimaksud dengan berpuasa tetapi berbuka ialah yang melaparkan perutnya, sementara dia melepaskan kendali bagi anggota tubuhnya yang lain.
Maka, barang siapa telah memahami makna dan rahasia puasa, pasti mengerti bahwa orang yang “berpuasa” (menahan diri dari makan dan minum) sementara dia “berbuka” dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, maka dia sama saja seperti orang yang hanya mengusap sebagian dari anggota tubuhnya – dalam wudhu’- sebanyak tiga kali. Memang, tampaknya dia telah mencukupi bilangan yang diminta darinya. Tetapi pada hakikatnya, dia telah mengabaikan hal yang amat penting, yaitu kewajiban “membasuh”, bukannya “mengusap” (seperti yang dilakukan di atas) Maka, shalatnya pun tertolak akibat kebodohannya itu.
Demikian pula orang yang berbuka (tidak berpuasa) dengan makan dan minum, sementara dia mempuasakan anggota-anggota tubuhnya dari perbuatan dosa, sama seperti orang yang membasuhnya sekali-sekali. In syā’ Allāh, shalatnya akan diterima oleh Allah disebabkan dia telah mengerjakan inti wudhu’ walaupun telah meninggalkan tambahan keutamaannya. Adapun orang yang mengerjakan kedua-duanya (yakni, berpuasa dari makan-minum dan menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa), ibarat orang yang membasuh masing-masing anggota tubuhnya sebanyak tiga kali-tiga kali. Dengan demikian, dia telah mengumpulkan antara yang inti dan yang lebih utama. Itulah yang disebut “kesempurnaan”.
Rasūlullāh s.a.w. telah bersabda:
إِنَّ الصَّوْمَ أَمَانَةٌ فَلْيَحْفَظْ أَحَدُكُمْ أَمَانَتَهُ.
“Sesungguhnya puasa adalah amanah, maka hendaknya masing-masing kamu menjaga amanahnya.” (231).
Rasūlullāh s.a.w. membaca firman Allah: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan semua amanah kepada yang berhak….” Diriwayatkan bahwa ketika itu beliau menunjuk pada telinga dan matanya seraya berkata: “Pendengaran adalah amanah dan penglihatan pun adalah amanah.”
Dan, seandainya yang demikian itu tidak termasuk dalam amanah-amanah puasa, niscaya beliau tidak mengajarkan kepada siapa saja yang diajak bertengkar, sementara dia dalam keadaan puasa, untuk mengatakan: “Aku ini sedang berpuasa. Aku ini sedang berpuasa.” (Yakni: “Aku telah diberi amanah untuk menjaga lidahku. Betapa kini aku akan melepaskannya demi menjawab ajakanmu itu!”).
Kini, telah menjadi jelas bahwa setiap ibadah mempunyai segi lahir dan batin, atau kulit dan isi. Kulitnya pun bertingkat-tingkat. Maka, terserah anda kini untuk memuaskan diri dengan kulitnya saja, tanpa isi. Atau, menggabungkan diri dengan kalangan orang-orang yang terbuka mata-hatinya, yakni mereka yang disebut ulul-albāb.