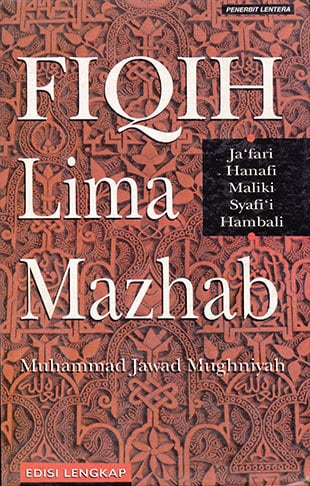BAB 10
(Bagian 2 dari 2)
TAYAMMUM
Tayammum itu mempunyai sebab-sebab yang membolehkan dan materi yang dipergunakannya, cara-cara khusus, dan hukum-hukum yang berlaku.
Cara-cara Bertayammum
Semua ulama madzhab sepakat bahwa tayammum itu tidaklah sah kalau tanpa niat, sampai Ḥanafī berkata: Niat itu adalah merupakaan syarat dalam tayammum, bukan syarat dalam wudhu’. Menurut mereka (Ḥanafī) bahwa tayammum itu dapat menghilangkan hadas, seperti wudhu’ dan mandi. Dari itu, mereka membolehkan untuk berniat menghilangkan hadas, sebagaimana berniat untuk dibolehkannya melalukan shalat. Madzhab-madzhab lain berpendapat bahwa tayammum itu membolehkan, bukan menghilangkan (hadas). Bagi orang yang bertayammum hendaknya berniat agar dibolehkan melakukan apa-apa yang disyaratkan bersuci dengannya, bukan berniat menghilangkan hadas. Tetapi sebagian Imāmiyyah mengatakan bahwa boleh berniat menghilangkan hadas, dengan catatan ia mengetahui kalau tayammum itu tidak menghilangkan hadas, karena menurut mereka di dalam niat menghilangkan hadas terdapat kelaziman arti dari niat kebolehannya (istibāḥah).
Sebaik-baiknya cara untuk mengakumulasi (mengumpulkan) semua pendapat-pendapat di atas adalah orang yang bertayammum itu harus berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti perintah-Nya yang berhubungan dengan masalah tayammum ini, baik ketika memulainya, maupun lahir dari perintah shalat dan semacamnya dari beberapa tujuan tayammum.
Sebagaimana mereka (ulama madzhab) berbeda pendapat tentang arti sha‘īd, mereka juga berbeda pendapat tentang maksud mengusap wajah dan kedua tangan yang dijelaskan dalam ayat al-Qur’ān.
Empat madzhab dan Ibnu Bābawaih dari Imāmiyyah: Yang dimaksud dengan muka itu adalah mengusap semua wajah, yang di dalamnya termasuk janggut, dan yang dua tangan adalah dua telapak tangan, dan pergelangan sampai pada kedua siku-siku. Itulah batas tayammum sebagaimana batas wudhu’. Dan caranya adalah menepuk dengan dua kali tepukan, yang pertama untuk mengusap wajah; dan yang kedua untuk mengusap kedua tangan, dengan cara dari ujung jari-jari sampai kedua siku-siku.
Mālikī dan Ḥanbalī: Bahwa mengusap kedua tangan itu hanya sampai pada pergelangan tangan, dan sampai di situlah yang diwajibkannya, sedangkan sampai pada dua sikut-sikut itu adalah sunnah.
Imāmiyyah: Yang dimaksud dengan muka adalah sebagiannya bukan semuanya, karena huruf bā’ dalam firman Allah:
فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ
memberikan pengertian hanya sebagiannya, karena menunjukkan bahwa ia masuk ke dalam maf‘ūl (obyek). Bila tidak bermakna sebagian, maka huruf bā’ itu berarti bā’ tambahan, karena kata imsaḥū termasuk kata mu’addi binafsihi (kata kerja yang membutuhkan obyek tanpa huruf penghubung). Maka pada dasarnya, kata tersebut adalah tidak adanya tambahan. Imāmiyyah memberikan batas bahwa yang wajib itu adalah mengusapnya dari sebagian muka, yang dimulai dari tumbuhnya rambut sampai pada ujung hidung bagian atas, dan termasuk di dalamnya adalah dahi dan kiri kanan dahi. Sedangkan yang termasuk dua tangan adalah dua telapak tangan saja, karena kata al-yadu dalam perkataan orang ‘Arab mengandung beberapa pengertian. Di antaranya: Telapak tangan itu sendiri, dan pengertian itu inilah yang paling sering dipergunakan. (al-Bidāyatu wan-Nihāyah, karya Ibnu Rusyd, Jilid I, halaman 66).
Pengertian tersebut dapat diperkuat kalau anda berkata: “Inilah dua tangan saya dan mengerjakan suatu perbuatan dengan dua tangan ini.” Dari ungkapan tersebut tidak bisa dipahami kecuali hanya dengan telapak tangan saja. Maka cara bertayammum menurut Imāmiyyah berdasarkan keterangan di atas, seperti berikut: Kedua telapak tangannya dipukulkan ke bumi, lalu mengusapkan kedua tangannya pada mukanya dari tumbuhnya rambut sampai ujung hidung bagian atas. Kemudian memukulkan kedua telapak tangannya lagi ke bumi, lalu mengusapkannya seluruh telapak tangannya yang kanan kepada bagian belakang telapak tangannya yang kiri, begitu juga sebaliknya.
Imāmiyyah: Wajib dilakukan secara tertib, dan kalau dilakukan terbalik, seperti mendahulukan pengusapan tangan dari pengusapan mukannya, maka batallah tayammum. Mereka (Imāmiyyah) mewajibkan pula dari atas lalu ke bawah, maka jika dibalik, batallah tayammum itu. Sebagian besar mereka berpendapat: Wajib menepukkan kedua tangannya pada bumi. Maka kalau hanya diletakkan saja padanya (bumi) tanpa ditepukkan (dipukulkannya), maka batallah tayammumnya.
Ḥanafī: Kalau mukanya terkena debu, lalu meletakkan tangannya padanya (wajahnya) dan mengusapkannya, maka itu sudah cukup, serta sebagai pengganti dari memukulkannya.
Semua ulama madzhab sepakat bahwa sucinya anggota tayammum itu adalah menrupakan syarat sahnya tayammum baik yang diusapnya maupun yang mengusapnya, juga benda yang menjadi bahan tayammum itu harus suci. Mereka juga sepakat bahwa bagi orang yang bertayammum wajib mencopot (menanggalkan) cincinnya ketika bertayammum, dan tidak cukup hanya dengan menggerakkannya, sebagaimana kalau mau berwudhu’.
Tetapi para ulama madzhab berbeda pendapat tentang wajibnya muwālat (berturut-turut).
Mālikī dan Imāmiyyah: Wajib berturut-turut antara bagian-bagian anggota tayammum itu. Maka kalau dipisahkan (dari jarak) dengan waktu yang mengurangi arti berturut-turut, batallah tayammumnya.
Ḥanbalī: Wajib berturut-turut kalau bertayammum untuk menghilangkan hadas kecil, tapi kalau untuk menghilangkan hadas besar tidak wajib berturut-turut. Syāfi‘ī: Hanya wajib tertib saja, bukan berturut-turut. Ḥanafī: Tidak diwajibkan berturut-turut dan tidak diwajibkan pula tertib.
Hukum-hukum Tayammum
Di sini ada beberapa masalah:
- Semua ulama madzhab sepakat bahwa tidak boleh bertayammum untuk shalat sebelum masuk waktu shalat, kecuali menurut Ḥanafī: Sah bertayammum sebelum masuk waktu shalat.
Imāmiyyah: Kalau bertayammum sebelum waktunya untuk tujuan yang dibolehkan bertayammum, kemudian masuk waktu dan tayammumnya belum batal, maka ia boleh shalat dengan tayammum tersebut.
Immiyyah dan Ḥanafī: Boleh bertayammum untuk jama‘ dua shalat dengan satu tayammum.
Syāfi‘ī dan Mālikī: Tidak boleh men-jama‘ dua shalat fardhu dengan satu tayammum saja. Ḥanbalī: Boleh men-jama‘ untuk dua shalat qadhā’ (pengganti) bukan untuk shalat adā’an (shalat pada waktunya).
- Setelah melaksanakan tayammum berdasarkan keterangan syara‘, maka orang yang bertayammum itu hukumnya adalah suci sama seperti sucinya kalau memakai air, dan dibolehkan mengerjakan sesuatu (apa saja) yang dibolehkan pada wudhu’ dan mandi. Dan tayammum itu menjadi batal dengan apa yang membatalkan wudhu’ dan mandi, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan dengan hilang ‘udzur atau sakit.
- Kalau setelah bertayammum itu mendapatkan air, dan pada waktu menemukannya itu sebelum masuk melaksanakan shalat, maka batallah tayammumnya itu, menurut kesepakatan semua ulama madzhab. Tapi kalau mendapatkannya ketika sedang shalat, maka:
Sebagian Imāmiyyah: Kalau ia sebelum ruku‘ dalam rakaat pertama, maka batal tayammumnya dan shalatnya. Tapi bila telah ruku‘ dalam rakaat pertama, maka teruskan shalatnya dan shalat itu sah.
Syāfi‘ī, Mālikī dan Ḥanbalī pada salah satu dari dua riwayatnya, dan sebagian kelompok Imāmiyyah: Kalau ia telah melakukan takbīrat-ul-iḥrām, maka teruskan shalatnya dan shalat itu sah, berdasarkan firman Allah:
“Dan janganlah kalian membatalkan perbuatan-perbuatan kalian.” (Qs. Muḥammad: 33).
Ḥanafī: Batal shalatnya.
Kalau ‘udzur-nya hilang setelah selesai shalat dan waktu masih luas (banyak), maka ia tidak wajib mengulanginya lagi, menurut kesepakatan semua ulama madzhab.
- Kalau orang yang junub bertayammum sebagai pengganti dari mandi, kemudian ia hadas kecil, dan ia mendapatkan air yang cukup untuk berwudhu’ saja; apakah ia wajib berwudhu’ dan bertayammum lagi sebagai ganti dari mandi?
Mālikī dan sebagian besar dari Imāmiyyah: Bertayammum lagi sebagai ganti dari mandi.
Ḥanafī, Syāfi‘ī dan Ḥanbalī serta sekelompok dari Imāmiyyah: Wajib berwudhu’, karena tayammum itu untuk junub. Kemudian batal karena selain junub, maka ia tidak dianggap sebagai junub bila betul-betul tidak junub, hanya ia termasuk hadas kecil.
- Ḥanbalī sendiri yang menganggap bahwa tayammum itu dapat sebagai pengganti untuk menghilangkan najis dari badan, tanpa diikuti oleh madzhab-madzhab yang lain. (al-Fiqhu ‘alal-Madzāhib-il-Arba‘ah, dalam bab Arkān-ut-Tayammum).
- Bila tidak ada yang dapat menyucikan, yaitu air dan tanah, seperti orang yang berada dalam tahanan yang tidak tersedia di dalamnya, dan tidak ada sesuatu yang dapat dijadikan tayammum atau karena sakit yang tidak bisa berwudhu’ dan tidak bisa bertayammum, atau tidak ada seseorang yang mewudhu’kannya atau mentayammumkannya; apakah ia diwajibkan shalat dalam keadaan tidak suci? Dan kalau berdasarkan ketentuan wajibnya shalat, lalu ia shalat, tetapi apakah wajib mengulanginya lagi setelah mampu (bisa) bersuci?
Mālikī: Gugurlah kewajiban melaksanakan shalat maupun qadhā’-nya. Ḥanafī dan Syāfi‘ī: Pernah untuk melaksanakan dan menggantinya itu tidak gugur. Artinya melaksanakannya, menurut Ḥanafī adalah ia harus melaksanakan seperti orang yang shalat. Sedangkan menurut Syāfi‘ī: Ia wajib shalat yang sebenar-benarnya. Maka kalau ‘udzur-nya telah hilang, ia wajib mengulanginya lagi sebagaimana yang dituntut syara‘.
Sebagian besar Imāmiyyah: kewajiban melaksanakan itu gugur, tetapi wajib meng-qadhā’-nya (menggantinya).
Ḥanbalī: Bahkan diwajibkan melaksanakannya, dan gugurlah kewajiban meng-qadhā’-nya.