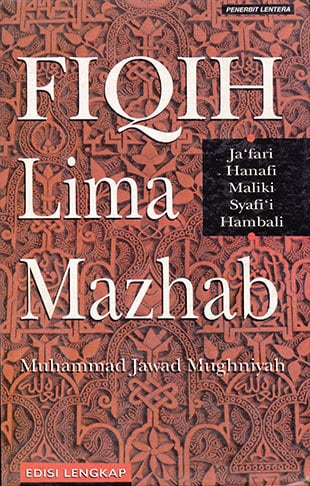BAB 10
(Bagian 1 dari 2)
TAYAMMUM
Tayammum itu mempunyai sebab-sebab yang membolehkan dan materi yang dipergunakannya, cara-cara khusus, dan hukum-hukum yang berlaku.
Sebab-sebab Tayammum
Ulama madzhab berbeda pendapat tentang orang yang bukan musāfir dan sehat (tidak sakit), tetapi ia tidak mendapatkan air, apakah ia boleh bertayammum? Maksudnya, bila tidak ada air, apakah hanya orang berada dalam perjalanan dan sakit sajalah yang dibolehkan bertayammum, atau justru dibolehkan dalam keadaan apapun, sampai pada waktu sehat dan orang yang bukan berada dalam perjalanannya?
Ḥanafī: Orang yang bukan berada dalam perjalanan dan ia sehat (tidak sakit), maka ia tidak boleh bertayammum dan tidak pula shalat kalau tidak ada air. (al-Bidāyatu wan-Nihāyah, Ibnu Rusyd, Jilid I, halaman 63, cetakan tahun 1935, dan juga al-Mughnī, Ibnu Qudamah, Jilid I, halaman 234, cetakan ketiga). Ḥanafī mengemukakan pendapatnya itu berdasarkan ayat 8, surat al-Mā’idah:
“….. Bila kamu sakit atau berada dalam perjalanan, atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air besar (jamban) atau menyentuh perempuan (menyetubuhinya), lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah.….”
Ayat di atas jelas menunjukkan bahwa tidak adanya air saja tidak cukup untuk dijadikan alasan untuk boleh bertayammum selama orang itu bukan musāfir atau sakit. Bila tayammum itu hanya khusus bagi orang yang musāfir dan orang yang sakit, maka orang yang bukan musāfir dan ia sehat dalam keadaan yang tidak ada air, ia berarti tidak diwajibkan shalat, karena ia tidak suci. Dan shalat hanya diwajibkan bagi orang yang suci.
Madzhab-madzhab yang lain sepakat bahwa orang yang tidak mendapatkan air wajib bertayammum dan shalat, baik ia dalam keadaan musāfir maupun bukan. Sakit maupun sehat berdasarkan hadits yang mutawātir:
“Tanah yang baik itu dapat sebagai penyuci orang Islam, sekalipun tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun.”
Mereka menjelaskan bahwa dijelaskannya perjalanan (musāfir) dalam ayat tersebut karena kebiasaan, sebab biasanya orang-orang musāfir tidak mendapatkan air.
Kalau betul apa yang dinyatakan Ḥanafī itu, maka tentu orang-orang musāfir dan orang yang sehat, yang keduanya tetap diwajibkan shalat, sedangkan orang yang bukan musāfir dan sehat tidak diwajibkan shalat; (mengapa mesti terbalik logikanya?)
Syāfi‘ī dan Ḥanbalī: Kalau mendapatkan air tapi tidak cukup untuk berwudhu’ (menyucikan) secara sempurna, maka ia wajib mempergunakan air itu pada sebagian anggota wudhu’ yang mudah, dan sebagian yang lain boleh bertanyammum. Kalau ada air hanya untuk wajah saja, maka cucilah wajahnya kemudian yang lain ditayammuminya.
Madzhab-madzhab yang lain: Adanya air yang tidak cukup itu sama dengan tidak adanya air, maka bagi orang yang demikian tidak diwajibkannya selain bertayammum.
Tapi pada masa sekarang, pembahasan tentang tidak adanya air bukan menjadi topik yang perlu diperdebatkan secara panjang lebar, karena pada saat sekarang air sudah mencukupi bagi setiap manusia, di manapun saja, baik bagi orang yang musāfir maupun yang muqīm. Para ahli fiqih membahas tentang wajibnya mencari air dan kadar usaha untuk mencarinya. Kalau ia khawatir pada dirinya, hartanya, atau kehormatannya dari pencuri dan binatang buas, atau harus mengeluarkan uang yang lebih dari biasanya, dan seterusnya, maka semuanya itu dikarenakan mereka menemukan kesulitan yang berat untuk mendapatkan air.
Kemudharatan Demi Kesehatan
Semua ulama madzhab sepakat bahwa di antara sebab-sebab dibolehkannya bertayammum itu adanya mudharat untuk menjaga kesehatan bila mempergunakan air, walau pun berdasarkan perkiraan saja. Maka barang siapa yang takut ditimpa suatu penyakit, atau penyakitnya bertambah atau memperlambat kesembuhannya, atau justru mempersulit cara mendiagnosanya, maka ia boleh bersuci dengan mempergunakan debu.
(Misalnya) kalau waktunya sudah sempit untuk mempergunakan air sebagaimana kalau ia bangun kesiangan, dan waktunya hanya tinggal sedikit dan kalau bersuci dengan air ia akan shalat di luar waktunya, tapi bila bertayammum ia bisa shalat pada waktunya (keburu); apakah ia wajib bertayammum atau bersuci dengan air, bila keadaan sudah sempit seperti itu?
Mālikī dan Imāmiyyah: Ia harus bertayammum dan shalat, tapi kemudian mengulanginya lagi. Syāfi‘ī: Tidak boleh bertayammum kalau pada waktu itu ada air.
Ḥanbalī: Membedakan antara orang yang musāfir dengan orang yang bukan musāfir. Kalau keadaan seperti itu terjadi pada waktu musāfir, ia harus bertayammum, lalu shalat dan tidak perlu mengulanginya lagi. Tapi kalau terjadi pada orang yang bukan musāfir, maka ia tidak boleh bertayammum.
Ḥanafī: Pada keadaan seperti itu, boleh bertayammum untuk shalat-shalat sunnah yang mempunyai waktu, seperti shalat sunnah setelah Zhuhur dan Maghrib. Sedangkan shalat-shalat yang wajib, maka tidak boleh bertayammum, karena pada waktu itu ada air, sekalipun waktunya sangat sempit, tetapi harus berwudhu’ dan shalat qadhā’ (menggantinya). Kalau ia bertayammum dan shalat pada waktu itu, maka ia wajib mengulanginya lagi di luar waktu tersebut.
Bahan Tayammum
Semua ulama madzhab sepakat bahwa bahan yang wajib dipergunakan tayammum itu adalah tanah yang suci, berdasarkan firman Allah s.w.t.: “Maka bertayammumlah kalian dengan tanah yang suci.” (al-Qur’ān, Surat al-Mā’idah, ayat 6). Juga berdasarkan hadits Rasūlullāh s.a.w.: “Bumi ini dijadikan sebagai masjid (tempat sujud) dan suci”. Suci itu adalah yang tidak terkena najis. Dan ulama madzhab berbeda pendapat tentang arti ash-Sha‘īd.
Ḥanafī dan sebagian kelompok Imāmiyyah: Memahami arti kata tersebut adalah bumi yang ada di permukaan. Dari itu, mereka (Ḥanafī) dan sebagian kelompok Imāmiyyah) membolehkan bertayammum dengan debu, pasir dan batu, hanya mereka melarang bertayammum dengan barang-barang tambang, seperti kapur, garam, sulfur, dan lain-lain.
Syāfi‘ī: Memahaminya adalah tanah dan pasir. Dari itu, mereka (Syāfi‘ī) mewajibkan untuk bertayammum dengan kedua benda tersebut kalau keduanya berdebu. Tetapi kalau bertayammum dengan batu tidak boleh. Ḥanbalī: Memahami arti sha‘īd itu hanya tanah saja. Dari itu tidak boleh bertayammum dengan pasir dan batu. Kebanyakan dari Imāmiyyah berpendapat seperti pendapat tersebut di atas, hanya mereka (Imāmiyyah) membolehkan bertayammum dengan pasir dan batu bila dalam keadaan darurat. Mālikī: Memukul rata pengertian kata sha‘īd itu baik tanah, pasir, batu, es dan barang tambang, kalau barang tambang tersebut tidak dipindahkan dari tempatnya, kecuali (yang dilarang) emas, perak dan permata. Mālikī melarang mempergunakan hal-hal tersebut (emas, perak dan permata) untuk tayammum secara mutlak.