1-5-2-2 Kewajiban 5 – Pantangan 2 Bagian 2 – Rambu-rambu Berteologi Imam al-Ghazali
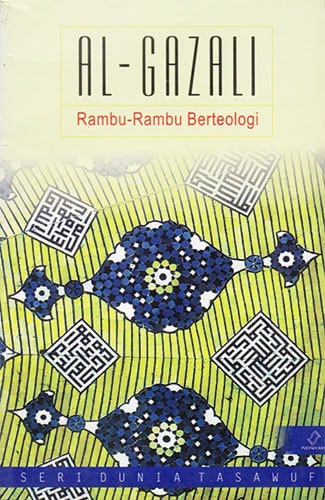
RAMBU-RAMBU BERTEOLOGI
(Judul Asli: Iljām-ul-‘Awāmi ‘an ‘Ilm-il-Kalām)
Oleh: Imām al-Ghazālī
Alih Bahasa: Kamran As‘ad Irsyady
Penerbit: Pustaka Sufi
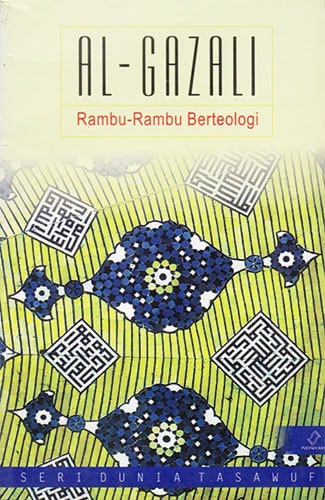
RAMBU-RAMBU BERTEOLOGI
(Judul Asli: Iljām-ul-‘Awāmi ‘an ‘Ilm-il-Kalām)
Oleh: Imām al-Ghazālī
Alih Bahasa: Kamran As‘ad Irsyady
Penerbit: Pustaka Sufi
001-5-2
Kewajiban Kelima
Pantangan Kedua. (Bagian 2 dari 2)
Jawaban kami merujuk pada dua aspek:
1. Para Tābi‘īn sudah mengetahui betul dari dalil-dalil Syara‘ yang mereka terima bahwa tidak boleh menuduh orang adil sebagai pembohong, apalagi dalam wacana sifat-sifat Allah. Jika Abū Bakr ash-Shiddīq meriwayatkan sebuah khabar (hadits) dan menuturkan: “Saya mendengar Rasūlullāh s.a.w. bersabda demikian,” kemudian ada orang yang menyatakannya sebagai telah berbohong dalam meriwayatkan, atau memalsukan hingga alpa, mereka (kaum Tābi‘īn) akan tetap menerimanya. Para Tābi‘īn meriwayatkan misalnya: “Abū Bakar berkata: Rasūlullāh s.a.w. bersabda” atau Anas berkata: Rasūlullāh s.a.w. bersabda” Dan begitu seterusnya hingga Tābi‘īn.
Sekarang, jika memang sudah menjadi ketetapan tersendiri pada mereka dengan dasar dalil-dalil Syar‘ī bahwa tidak ada jalan untuk menuduh perawi yang adil dan bertaqwa dari kalangan seluruhnya, lalu dari mana kewajiban untuk tidak menuduh sangkaan-sangkaan ḥadīts āḥād yang mendudukkan zhann pada posisi naql adil, padahal sebagian zhann adalah dosa. Jika Sang Legilator (Rasūlullāh) mengatakan: “apa-apa yang diinformasikan oleh orang yang adil, maka benarkan dan terimalah, lalu sebarkan dan tampakkanlah,” maka tidak bisa dikatakan sembarangan bahwa “apa yang diinformasikan oleh dirimu berdasarkan sangkaan-sangkaanmu, maka terima, tampakkan dan riwayatkanlah apa yang dikatakan berdasarkan atas sangkaan dari nurani dan jiwa mereka.” Hal terakhir ini jelas tidak semakna dengan teks Nabi s.a.w. di atas. Karena itu harus dinyatakan bahwa apa yang diriwayatkan oleh orang yang bukan ‘adil dalam jenis ini maka haruslah ditolak, dan seyogianya tidak diriwayatkan dan harus waspada dengan pesan-pesan dan amtsal serta sejenisnya yang dikandungnya.
2. Khabar-khabar tersebut diriwayatkan oleh para sahabat karena mereka mendengarnya sendiri dengan segala keyakinan, maka apa yang mereka informasikan pastilah sudah mereka yakini betul, dan para Tābi‘īn hanya menerima dan meriwayatkannya. Para Tābi‘īn tidak mengatakan langsung: “Rasūlullāh bersabda”, melainkan “Fulan (dari kalangan Shahabat, – penj.) berkata: Rasūlullāh s.a.w. bersabda begini.” Mereka ini bersikap jujur dan tidak pernah mengabaikan riwayatnya (Shahabat), karena setiap hadits memuat faedah-faedah.
Adapun lafal hadits yang masih wahm dan ambigu (zhann) bagi orang awam, bagi orang yang tahu adalah makna hakiki dan bukan zhann. Misalnya, riwayat seorang shahabat dari Rasūlullāh:
“Allah s.w.t. turun setiap malam ke langit dunia, kemudian bertitah: “Siapa saja yang berdoa, maka akan Kupenuhi dan siapa saja yang meminta ampun, akan Kuampuni.”
Hadits itu dapat diukur sebagai puncak persuasi (nihāyat-ut-targhīb) untuk menjalankan salat malam, serta mempunyai pengaruh yang besar dalam menggerakkan motivasi untuk tahajjud yang merupakan ibadah yang paling utama. Jika hadits ini dibatalkan (hanya karena memuat lafal nuzūl yang masih ambigu maknanya, – penj.) maka akan hilang pula faedah besar ini, padahal tidak ada jalan untuk mengabaikannya. Lafal nuzūl (turun) yang dikandungnya hanya berpengertian ambigu bagi anak kecil atau orang awam yang seperti anak kecil, toh merupakan hal yang sepele bagi orang yang berakal (al-bashīr) untuk menanamkan di dalam hati orang awam taqdīs dan pensucian tentang gambaran “turun” tersebut, misalnya dengan mengatakan padanya: “Jika memang turun-Nya (Allah) ke langit dunia demi memperdengarkan pada kita seruan dan titahnya, sementara kita tidak bisa mendengarkannya, tentu turunnya Allah di sini tidak mempunyai faedah apa-apa. Toh Dia mampu-mampu saja menyeru kita dari atas singgasana ‘Arsy atau di atas langit tertinggi. (Jadi turunnya Allah ke langit dunia tidak boleh dipahami secara harfiah sebagaimana turunnya kita, – penj.).
Penjelasan ini akan menyadarkan pada orang awam bahwa pemahaman eksoterik (lahir) atas lafal “turun” jelas bāthil. Pemahaman zhāhir-un-nashsh seperti ini bahkan akan sama seperti keinginan orang yang berada di belahan bumi bagian timur untuk memperdengarkan seruan memanggil orang yang berada di belahan bumi bagian barat, kemudian ia berjalan ke barat dengan langkah kaki yang bisa dihitung dan mulai menyerunya, padahal ia tahu bahwa orang yang dipanggilnya tidak akan mendengarkan seruannya. Jelas ini perbuatan yang batil dan sia-sia seperti kelakuan orang gila. Lalu, bagaimana pemahaman seperti ini akan bisa menetap di hati orang yang berakal. Jelas, penjelasan kadar ini juga akan memaksa setiap orang awam untuk menafikan segala gambaran turun (secara lahiriah). Segala bentuk jismiyyah adalah kemustahilan bagi Allah. Dengan demikian, faedah menyebarluaskan khabar-khabar (hadits) ini tetap besar, sementara bahayanya sangat remeh dan kecil. Lalu, mana persamaan hadits ini dengan hikayat zhunūn (yang masih dalam tataran persangkaan, – penj.) yang tersembunyi di dalam diri.
Inilah jalan-jalan yang menarik metodologi ijtihad untuk membolehkan atau melarang penyebutan ta’wīl mazhnūn. Tidak perlu disebutkan di sini aspek ketiga, yaitu melihat indikasi-indikasi (qarīnah) kondisi penanya dan pendengar, meski sebenarnya hal itu bila disebutkan akan bermanfaat dan akan membawa mudarat jika tidak menyebutnya. Betapa banyak orang yang tidak tergerak impuls dalam dirinya untuk mengetahui makna-makna ini dan tidak berpengaruh di dalam dirinya masalah aspek luarannya. Namun banyak juga orang, yang membekas dalam dirinya masalah aspek luaran, sehingga hampir luntur kepercayaannya para Rasūlullāh s.a.w. Ia mengingkari sabda Nabi s.a.w. yang muwahham (mengandung lafal ambigu, – penj.) Orang seperti ini jika disebutkan kemungkinan mazhnūn, meski hanya sekadar kemungkinan yang muncul dari lafal, ia tetap akan mengambilnya. Maka terhadap orang ini tidak apa-apa menyebutkan ta’wil mazhnūn, sebab hal itu akan menjadi obat bagi penyakitnya ini, meski hal itu merupakan racun bagi yang lain. Tapi yang harus dicamkan, si ‘alim seyogianya tidak membeberkannya di atas mimbar publik karena hal itu akan menggerakkan impuls yang diam pada kebanyakan pendengar yang sebelumnya tidak mengubrisnya bahkan mengabaikan aspek-aspek luarannya. Mengingat periode pertama Salaf adalah periode ketenangan hati, maka mereka mampu mencegah untuk tidak mempublikasikan ta’wīl karena kekhawatiran akan menggerakkan impuls-impuls dan mengganggu hati. Generasi di belakang merekalah yang menggerakkan fitnah dan melemparkan keraguan-keraguan ini di hati rakyat awam, padahal hal itu tidak perlu, sehingga mewabahlah dosa. Sekarang, hal itu sudah menyebar di beberapa negeri, sehingga upaya untuk menampakkan hal tersebut dengan harapan akan menghilangkan hal tersebut dengan harapan akan menghilangkan sangkaan-sangkaan (wahm) yang batil dari dalam hati menjadi sebuah kebutuhan.
Selanjutnya, jika ada yang mengatakan: Kamu membedakan antara ta’wīl yang pasti dan ta’wīl yang masih sangkaan, lalu dengan apa kamu memperoleh kepastian akan ke-shaḥīḥ-an ta’wīl?” maka akan kami jawab: dengan dua hal:
Pertama, makna, ketetapannya harus definitif (maqthū‘) dari Allah s.w.t. sebagai ketinggian tingkatan.
Kedua, lafalnya hanya mengandung dua kemungkinan pengertian, di mana salah satunya harus gugur demi yang kedua. Misalnya firman Allah:
“Dan Dia Maha Perkasa di atas hamba-hambaNya.” (QS. Al-An‘ām [6]: 18).
Secara zhahir, lafal “di atas” mengandung pengertian ketinggian tempat atau ketinggian tingkatan. Selanjutnya keginggian tempat jelas gugur mengingat hal tersebut mustahil bagi Allah, sehingga hanya menyisakan pengertian ketinggian tingkatan sebagaimana pengertian “fawq” dalam diksi “tuan di atas budak”, “suami di atas istri,” atau “sultan di atas menteri.” Maka paralel dengan hal tersebut, Allah berada di atas hamba-hambaNya. Ini sudah seperti pengertian definitif bagi lafal fawq (di atas), karena dalam bahasa ‘Arab lafal ini hanya digunakan untuk dua pengertian di atas. Beda dengan lafal istiwā’ yang pengertiannya tidak seringkas ini (lebih dari dua pengertitan makna, – penj.). Jika dari tiga pengertian lafal, hanya dua pengertian saja yang boleh (jā’iz) bagi Allah, sementara makna yang satu batil (gugur demi taqdīs Allāh), maka penentuan salah satu dari dua makna yang ja’iz ini menjadi zhann atau “kemungkinan an-sich.”
Demikianlah pandangan lengkap mengenai pelarangan dan pembatasan ta’wīl.