1-5-2-1 Kewajiban 5 – Pantangan 2 Bagian 1 – Rambu-rambu Berteologi Imam al-Ghazali
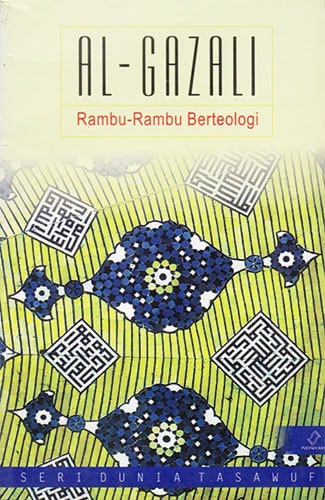
RAMBU-RAMBU BERTEOLOGI
(Judul Asli: Iljām-ul-‘Awāmi ‘an ‘Ilm-il-Kalām)
Oleh: Imām al-Ghazālī
Alih Bahasa: Kamran As‘ad Irsyady
Penerbit: Pustaka Sufi
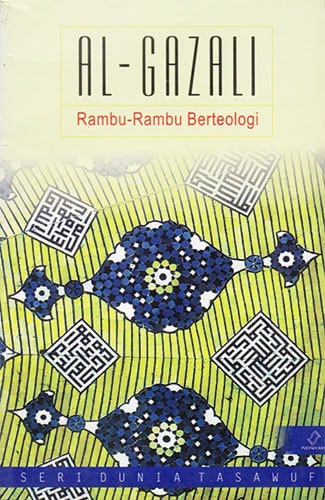
RAMBU-RAMBU BERTEOLOGI
(Judul Asli: Iljām-ul-‘Awāmi ‘an ‘Ilm-il-Kalām)
Oleh: Imām al-Ghazālī
Alih Bahasa: Kamran As‘ad Irsyady
Penerbit: Pustaka Sufi
001-5-2
Kewajiban Kelima
Pantangan Kedua. (Bagian 1 dari 2)
Pantangan kedua: ta’wīl; yaitu menjelaskan maknanya setelah menghilangkan eksoterisnya. Hal ini bisa berlaku pada orang awam sendiri, orang alim dengan orang awam, atau orang alim sendiri dan orang alim dengan Tuhannya. Berikut pemaparannya:
Pertama: pena’wilan orang awam dengan jalan menyibukkan diri di dalamnya. Aktivitas ini haram dan terlarang sebagaimana ketidakbolehan menyelami dasar samudera yang mahadalam bagi orang yang tidak bisa berenang. Apalagi samudera pengetahuan Allah lebih dalam dan lebih banyak jebakan dan bahayanya daripada samudera air, maka jelas dan tidak diragukan lagi keharaman penyelamannya bagi orang awam yang tidak cakap berenang. Ketenggelaman dan kehancuran dalam samudera ini tidak menyisakan asa kehidupan lagi setelahnya, dengan kata lain menghilangkan kehidupan abadi, sementara kehancuran di lautan dunia hanya menghilangkan kehidupan fanā’. Betapa jauhnya perbedaan antara keduanya!
Kedua: pena’wilan orang alim untuk konsumsi orang awam. Hal ini juga diharamkan sebagaimana dilarang kerasnya seorang perenang menyelam lautan bersama orang yang tidak bisa berenang dan menyelam, karena hal itu rentan terhadap resiko kematian. Si perenang ahli tidak akan kuat menjaga si perenang yunior di tengah kedalaman samudera. Meskipun ia mampu menjaganya saat di dekat pantai, namun jika ia menyuruh si yunior untuk berhenti di situ saja, ia pasti tidak mau. Dan jika misalnya si ahli menyuruhnya untuk tetap diam dan bertahan menghadapi deburan ombak dan buaya-buaya, tetap saja ketika si buaya membuka mulutnya bersiap menelan, hati dan badan si yunior akan berguncang. Ia tetap tidak bisa diam sebagaimana yang diinginkan karena keterbatasan energi dan kemampuannya.
Ini adalah permisalan yang benar bagi seorang alim ketika ia membuka pintu pena’wilan dan bertindak menyelisihi lahiriah (eksoteris) untuk orang awam. Semakna dengan orang awam di sini adalah sastrawan, ahli nahwu, pakar hadits, mufassir, teolog, bahkan termasuk juga setiap orang alim selain kalangan yang memang mendalami teknik berenang di lautan samudera pengetahuan dan menghabiskan umurnya hanya untuk mempelajari teknik tersebut, hingga mereka berpaling dari keduniaan dan syahwat, menolak harta, tahta, makhluk, dan segenap subyek (dzāt), ikhlash semata-mata demi Allah dalam berilmu dan beramal, menerapkan semua batasan-batasan dan norma syariah dengan melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran, mengosongkan hati dari selain Allah hanya demi Allah, menyisihkan keduniaan, bahkan Akhirat dan Surga Firdaus yang tertinggi demi meraih asmara Allah. Merekalah orang-orang yang ahli menyelam dalam samudera pengetahuan. Meski begitu, mereka tetap juga rentan terhadap bahaya besar yang bisa menghancurkan 9 dari 10 orang seperti mereka, dan hanya satu orang yang selamat menggapai rahasia yang terpendam. Yang terakhir inilah yang pertama diprioritaskan mendapat segala kebaikan Allah, dan merekalah orang-orang yang menang:
“Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan (di dalam dada mereka) dan apa yang mereka tampakkan.” (QS. Al-Qashash [28]: 69)
Ketiga: pena’wilan orang ‘arif (‘ārif) dengan dan untuk dirinya sendiri, dan ia menyimpannya sebagai rahasia hati antara dirinya dan Allah semata. Di sini terdapat 3 level maksud lafal yang mutasyābihāt, istiwā’ dan fawq misalnya, yang mungkin membekas dalam kerahasiaan diri seseorang antara “yang sudah pasti” (maqthū‘ bīh), “masih diragukan” (masykūk fīh), dan “besar sangkaan” (mazhnūn). Terhadap pengertian lafal mutasyābih yang sudah pasti, maka ia harus meyakininya. Namun jika masih diragukan, maka ia harus berusaha menjauhinya dan jangan sekali-kali ia menentukan maksud dari statemen Allah dan Rasūl-Nya karena masih adanya kemungkinan sepadan yang bertentangan dengannya tanpa bisa ia prioritaskan (tarjīh). Bahkan orang yang masih ragu dalam hal ini wajib berhenti (tawaqquf). Sementara itu, jika pengertiannya atas maksud lafal mutasyābihāt ini masih dalam tataran “besar sangkaan,” maka harus dilihat, pertama apakah pengertian yang telah ia gali dari lafal tersebut boleh diterapkan (jā’iz) bagi konteks Allah ataukah muḥāl diterapkan? Dan kedua setelah mengetahui kepastian kebolehannya, mungkin ia masih ragu apakah hal itu merupakan maksud yang diinginkan atau bukan?
Contoh pertama dari pengertian yang bersifat zhanniyyah ini adalah ketika menafsiri lafal fawq (atas) sebagai “ketinggian immaterial” (al-‘uluww al-ma‘nawī) sebagaimana maksud statemen: sultan di atas menteri. Dengan pengertian ini, kita tidak meragukan lagi ketetapan maknanya bagi Allah, tapi mungkin kita masih meragukan makna lafal fawq dalam firman:
“Mereka takut pada Allah (yang berada) di atas mereka.” (QS. An-Naḥl [16]: 50).
Apakah yang dimaksudkan di sini “ketinggian immaterial” ataukah pengertian lain yang sesuai dengan kebesaran Allah yang juga di luar “ketinggian tempat” yang muḥāl bagi Dzāt yang tiada ber-jisim atau atribut dalam jisim.
Contoh kedua adalah pena’wilan lafal istiwā’ di atas ‘Arsy sebagai nisbat afiliatif tertentu yang hanya khusus untuk konteks ‘Arsy, yaitu bahwa Allah berkuasa atas seluruh alam dan mengatur urusan dari langit ke bumi dengan sarana ‘Arsy. Karena tidak akan muncul gambaran selama tidak terjadi di ‘Arsy. Hal ini sebagaimana seorang pemahat dan penulis yang tidak akan menghasilkan gambaran dan kalimat di atas kertas putih selama tidak tercipta di dalam otak. Bahkan seorang tukang bangunan tidak memperoleh gambaran bangunan selama belum tergambar di dalam otak. Dari pusat otak inilah hati mengatur urusan dunianya, yaitu badan. Mungkin kita masih bimbang apakah penetapan nisbat afiliatif ‘Arsy ini pada Allah boleh (jā‘iz) atau tidak, bisa karena alasan keberadaan ‘Arsy itu sendiri (dalam konteks Allah), atau karena alasan diberlakukannya sunnah dan aturan tradisinya pada konteks Allah, meskipun menyelisihi hukum tersebut sebenarnya juga bukan kemuhalan (bagi Allah). Hal terakhir ini seperti kasus diberlakukannya hukum kendali ini pada hati manusia bahwa tidak mungkin hati mengendalikan badannya tanpa medium otak, meskipun sebenarnya Allah Maha Kuasa untuk mewujudkannya (kemampuan hati mengendalikan badan, – penj.) tanpa otak, kalau saja hal itu tidak didahului oleh penetapan kehendak azali dan kalimah qadīmah-Nya yang sudah merupakan ilmu-Nya, sehingga menyelisihinya menjadi hal terlarang, bukan karena keterbatasan esensi kekuasaan Allah, melainkan lebih karena kemustahilan menyelisihi irādah qadīmah dan ilmu azal-Nya sendiri. Allah berfirman:
“Dan kamu tidak sekali-kali akan mendapati perubahan pada ketentuan sunnatullah.” (QS. Al-Aḥzāb [33]L 62, QS. Al-Fatḥ [48]: 23).
Sunnatullah ini tidak berubah-ubah karena kewajibannya, dan kewajiban ini dikarenakan asalnya dari kehendak azali yang wajib. Konsekuensi wajib adalah wajib dan sebaliknya berarti muḥāl. Dengan catatan bahwa kemuhalan Allah untuk merubah sunnah ini bukanlah kemuhalan dalam dzāt-Nya, melainkan lebih merupakan muḥāl li ghayrih (kemustahilan karena faktor eksternal), yaitu hasilnya yang bisa mengubah ilmu azali dan mencegah kekuasaan kehendak azali.
Dengan demikian, meskipun penetapan penisbatan ini pada Allah bahwa Dia mengatur kerajaan alam dengan medium ‘Arsy boleh secara akal (jā’iz ‘aqlī), namun apakah hal itu terjadi dalam wujud? Inilah yang banyak membuat bimbang para penelaah. Mungkin ia menyangka wujudnya ini seperti sangkaannya dalam esensi makna yang shaḥīḥ dan boleh, namun ada perbedaan antara keduanya. Tapi masing-masing sangkaan jika membekas di dalam diri dan menyesak di dalam dada, maka ia tidak boleh terjebak memilih dengan dorongan jiwa, juga tidak boleh menyangka-sangka, sebab zhann mempunyai sebab-sebab dharūrī (keharusan ada) yang tidak mungkin ditolak, toh Allah tidak membebani jiwa seseorang kecuali dalam batas kemampuannya. Dalam hal ini, ia mempunyai dua tugas:
Pertama: tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam meyakininya secara pasti tanpa perasaan akan kemungkinan keliru di dalamnya. Ia juga tidak seyogianya menghukumi sendiri atas dasar sangkaannya dengan hukum yang pasti (ḥukm jāzim).
Kedua: jika memang harus menyebut, maka jangan ucapkan pernyataan pasti bahwa yang dimaksud istiwā’ adalah ini dan yang dimaksud fawq adalah ini, sebab hal itu adalah bentuk menghukumi sesuatu yang tidak ia ketahui. Allah berfirman:
“Jangan kau sikapi hal yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.” (QS. Al-Isrā’ [17]: 36).
Akan tetapi sebaiknya ia berkata saja: “Saya hanya menyangka bahwa maksudnya adalah demikian.” Dengan begitu ia telah berlaku jujur dalam menginformasikan tentang diri dan nuraninya, dan bukan pula hal itu bentuk penghukuman atas sifat Allah, juga bukan atas maksud pernyataan-Nya, melainkan lebih merupakan hukum atas dirinya dan informasi tentang nuraninya.
Jika ada yang bertanya, bolehkah menyebutkan dan membincangkan sangkaan ini pada publik sebagaimana yang terkandung di dalam batin nuraninya, begitu juga yang sudah pasti, apakah ia wajib membeberkannya? Maka kami katakan:
Perbincangan tentangnya boleh dilakukan dalam 4 level: pada dirinya sendiri; pada orang yang selevelnya dalam istibshār (pengetahuan); pada orang yang bersiap memasuki jenjang istibshār dengan kecerdasan, kepintaran, dan kesahajaannya dalam menuntut makrifat Allah, atau terakhir pada orang awam.
Dalam tataran pengertian muksud yang sudah pasti (qath‘ī), maka ia boleh memperbincangkannya dengan dirinya sendiri dan orang yang selevel dengannya dalam tataran istibshār atau pada orang yang berniat menuntut makrifat Allah dan bersiap untuknya, kosong dari segala kecenderungan pada keduniaan, syahwat, fanatisme pada madzhab, ambisi kedudukan dengan ma‘rifatnya, dan pamer pada orang awam. Terhadap orang-orang yang mempunyai kualifikasi sifat-sifat ini, maka tidak apa-apa memperbincangkan masalah tersebut dengannya, sebab kecerdasan yang selalu kehausan akan pengetahuan adalah semata demi pengetahuan, dan bukan untuk tujuan lain yang bisa menyesakkan di dalam dadanya segala bentuk lahir dan mungkin malah bisa melemparkannya juga ke pena’wilan-pena’wilan yang sesat lantaran nafsunya untuk lari dari implikasi lahiriah (muqtadā-zh-zhawāhir). Sedangkan untuk orang awam tidak seyogianya ia memperbincangkan hal ini dengannya. Termasuk kategori orang awam ini adalah setiap orang yang tidak mempunyai sifat-sifat seperti tersebut di atas, bahkan mereka lebih seperti anak kecil yang masih menyusu yang tidak boleh diberi makanan berat yang belum ia mampu.
Sementara untuk pengertian yang masih mazhnūn (indefinitif), mendiskusikannya dengan dirinya sendiri adalah sebuah urgensi (idhtirār). Karena apa yang terkandung di dalam dirinya dari sangkaan, kebimbangan dan kepastian terus membuntuti dirinya dan ia pun tidak bisa lepas darinya, maka hal itu tidak terlarang. Namun untuk membeberkannya pada orang awam hal itu jelas-jelas dilarang, bahkan lebih terlarang daripada membeberakannya pengertian yang sudah pasti (maqthū‘). Adapun memperbincangkannya dengan orang yang sederajat dengannya dalam taraf pengetahuan atau dengan orang yang bersiap ke sana, maka terdapat beberapa pertimbangan dan pandangan. Bisa jadi hal itu dibolehkan (jā’iz), yaitu ketika ia tidak lebih dari menyatakan dengan segala kejujuran: “aku sangka demikian”. Dan bisa juga hal itu dilarang dengan pertimbangan ia mampu meninggalkannya, karena dengan menyebutkan berarti ia telah melakukan sangkaan pada sifat Allah atau pada maksud pernyataan-Nya, dan ini jelas menyimpan bahaya. Kemampuan meninggalkan ini dapat ditilik dari nashsh, konsensus ulama, atau qiyās nonteks atas manshūsh (yang berteks). Allah berfirman:
“Dan jangan kamu menyikapi hal-hal yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.” (QS. Al-Isrā’ [17]: 36).
Kalangan yang menyatakan bahwa memperbincangkan pengertian yang mazhnūn (indefinitif) dalam konteks sifat-sifat Allah dan firman statemen-Nya boleh-boleh saja dan tidak terlarang berargumentasi dengan tiga hal sebagai berikut:
Pertama, bukti yang menunjukkan kemubahan bertindak shidq (jujur) adalah shidq (kejujuran), karena toh ia telah menyatakan sebelumnya bahwa ia hanya menginformasikan sesuatu berdasarkan sangkaannya.
Kedua, statemen-statemen kalangan mufassir al-Qur’ān lebih berdasarkan intuisi dan sangkaan, karena semua yang mereka paparkan belum pernah dinyatakan oleh Rasūlullāh sebelumnya, melainkan lebih merupakan istinbāth berdasarkan ijtihad. Karena kenyataan inilah, banyak statemen-statemen yang beredar saling bertentangan dan berbeda satu sama lain.
Ketiga, konsensus pada Tābi‘īn (kalangan pasca Shahabat, – penj.) atas ) dibolehkannya) mentransfer data dan khabar-khabar (hadits) yang mutasyābihāt (mengandung pengertian ambigu, – penj.) yang hanya diriwayatkan oleh satu orang Shahabat (ḥadīts aḥad) dan bukan termasuk mutawātir, serta meriwayatkan hadits shaḥīḥ yang mengandung pengertian seperti ini yang diriwayatkan dari dan oleh orang adil. Padahal masalah ‘adl ini lebih diperoleh dari persepsi dan sangkaan semata, tapi nyatanya mereka membolehkan juga.
Jawaban dan bantahan kami: pertama; mubah memang sebuah kejujuran yang tidak perlu ditakutkan bahayanya, namun menyebarkan hal-hal zhanniyyah tidak sepi dari blunder yang berbahaya. Sangat mungkin orang yang menyimaknya menerima dan meyakininya dengan mentah-mentah untuk kemudian menghukumi sifat-sifat Allah tanpa berdasarkan ilmu. Hal ini sangat membahayakan. Ia membuat jiwa lari dan berpaling dari bentuk-bentuk lahir (eksoterik), sehingga jika ada kandungan makna yang mengena di hatinya, ia akan begitu saja menerima sebagai sebuah kepastian, padahal hal itu hanyalah sangkaan, bahkan bisa juga malah keliru. Dengan begitu, ia telah terjebak meyakini sifat-sifat Allah yang batil (salah), atau lancang menemukan maksud dari statemen firman-Nya yang sebenarnya tidak dimaksudkan oleh-Nya.
Menjawab dalih kedua, kita tidak boleh menerima begitu saja statemen-statemen indefinitif yang dilontarkan oleh para mufassir ihwal sifat-sifat Allah, seperti istiwā’, fawq, dan lain-lain. Termasuk statemen indefinitif lain yang tidak boleh diterima begitu saja adalah hukum-hukum fiqh, hikayat-hikayat pada nabi dan orang kafir, petuah-petuah maw’izhah, contoh-contoh aforisma, dan hal-hal yang rentan bahaya dan kesalahan.
Dan tentang yang ketiga, bahwa banyak kalangan yang menyatakan tidak bolehnya berpegangan pada sesuatu dalam diskusi ini kecuali yang memang ada dan berlaku di dalam al-Qur’ān, dan mutawātir dari Nabi Muḥammad s.a.w. Adapun khabar āḥād (yang diriwayatkan satu orang dan tidak mutawātir), dalam hal ini tidak bisa diterima, juga dilarang bersibuk mena’wīlkannya di hadapan orang yang cenderung pada ta’wīl, serta tidak boleh juga meriwayatkannya pada orang yang minus kriteria dalam periwayatan. Sebab hal itu adalah mengukumi sesuatu berdasarkan sangkaan. Apa yang mereka paparkan memang tidaklah jauh beda dengan pendapat kaum Salaf, namun bertentangan dari aspek eksoteris saja, di mana menerima hadits dari perawi yang adil, lalu meriwayatkan dan men-shaḥīḥ-kannya.