1-5-1 Kewajiban 5 – Pantangan 1 – Rambu-rambu Berteologi Imam al-Ghazali
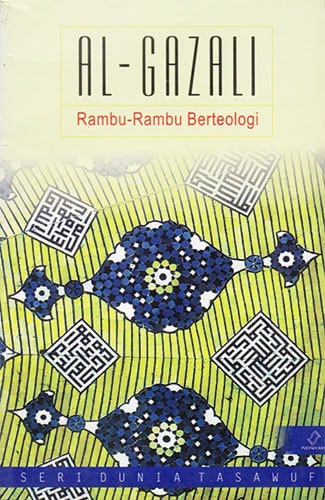
RAMBU-RAMBU BERTEOLOGI
(Judul Asli: Iljām-ul-‘Awāmi ‘an ‘Ilm-il-Kalām)
Oleh: Imām al-Ghazālī
Alih Bahasa: Kamran As‘ad Irsyady
Penerbit: Pustaka Sufi
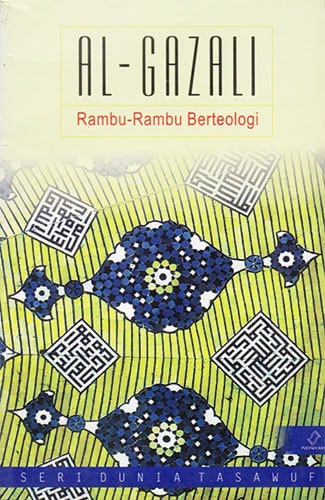
RAMBU-RAMBU BERTEOLOGI
(Judul Asli: Iljām-ul-‘Awāmi ‘an ‘Ilm-il-Kalām)
Oleh: Imām al-Ghazālī
Alih Bahasa: Kamran As‘ad Irsyady
Penerbit: Pustaka Sufi
001-5-1
Kewajiban Kelima
Pantangan Pertama.
Kewajiban keempat: imsāk (mencegah diri) untuk memperlakukan lafal-lafal yang ada. Kaum awam wajib bersikap “stagnan” dalam menanggapi lafal hadits-hadits dalam konteks ini, dan mencegah diri juga untuk mengutak-atik dan memperlakukannya dari 6 aspek: tafsīr, ta’wīl, tashrīf, tafrī‘, jam‘, dan tafrīq.
Pantangan pertama: tafsīr, maksudnya menggubah redaksi bahasanya dengan redaksi bahasa lain, baik yang sama kedudukannya dalam bahasa ‘Arab, atau sepadan pengertiannya dalam bahasa asing (Persia atau Turki). Tidak boleh melafalkannya kecuali dengan redaksi bahasa yang asli, sebab banyak lafal-lafal ‘Arab yang tidak ditemukan padanannya dalam bahasa Persia atau Turki. Kalaupun ada padanan dalam bahasa Persia, dalam tradisi Persia tidak berlaku sistem metafor atas makna (penggunaan makna kiasan) sebagaimana yang berlaku dalam bahasa ‘Arab. Begitu juga banyak lafal-lafal yang musytarak dalam bahasa ‘Arab, namun tidak berlaku demikian dalam bahasa lain.
Kasus diskoneksi pertama misalnya dapat dirujuk pada lafal istiwā’, tidak ada dalam bahasa Persia padanan lafal yang pengertiannya sama persis seperti pengertian istiwā’ di kalangan orang ‘Arab. Dan kalau pun dipaksakan, maka hal itu malah akan semakin menambah blunder. Misalnya istiwā’ dalam bahasa Persia diterjemahkan sebagai “rāsta bastān.” Ini sendiri tersusun dari 2 kata. Kata pertama (rāsta) menunjukkan ketegakan dan kelurusan dalam hal yang sebenarnya dipersepsikan menunduk dan membungkuk. Sedangkan kata kedua (bastān) berpengertian diam dan tetap dalam hal yang sebenarnya dipersepsikan harus bergerak dan berguncang. Terlihat bahwa indefinitas istiwā’ dengan makna-makna ini dan isyarat indikatifnya dalam bahasa non-‘Arab lebih vulgar daripada lafal istiwā’ dan indikasinya (dalam bahasa ‘Arab).
Maka, jika memang ada distingsi pada aspek signifasi (dalālah) dan indefinitas (isy‘ār), maka kata bentukan kedua (gubahan redaksi baik dalam bahasa ‘Arab maupun bahasa asing) tidak bisa dianggap sebagai kata asal. Penggubahan sebuah kata dengan sinonim kata padanannya memang dibolehkan sebatas tidak bertentangan dengan kata pertama dalam satu aspek dari ragam aspek yang ada, juga tidak menyelisihi dan berbeda dengannya meski sekecil, sesedikit dan sesamar bagaimanapun juga.
Kasus kedua, kata “jari” dalam bahasa ‘Arab digunakan untuk kiasan pengertian nikmat, misalnya jika Fulan berkata: “Aku mempunyai jari,” maka artinya adalah saya sedang dianugerahi nikmat. Makna demikian ini tidak ditemukan dalam bahasa Persia dan tidak lazim pula penggunaan metafor ini dalam bahasa asing. Orang ‘Arab lebih banyak menggunakan bahasa metafor daripada porsi penggunaan hal serupa oleh kalangan non-‘Arab, bahkan malah tidak bisa diperbandingkan secara prosentatif antara keleluasaan penggunaan metafor oleh bangsa ‘Arab dan stagnasi bangsa non-‘Arab dalam hal ini. Maka, jika memang pengertian makna metafor dalam bahasa ‘Arab ini sudah halus, sementara pengertian serupa dalam bahasa non-‘Arab masih kasar, maka orang malah akan lari dan tidak mau mendengar pengertian yang kasar tersebut. Dengan demikian, jika memang keduanya berbeda, maka tafsir di sini bukanlah penggubahan sepadan, melainkan kontradiktif, padahal tidak boleh melakukan penggubahan kecuali dengan yang sepadan.
Kasus ketiga, adalah al-‘ayn. Orang yang menafsirkannya secara ekstrinsik akan memunculkan makna bahwa mata adalah jisim. Padahal dalam bahasa ‘Arab, kata tersebut berpengertian musytarak antara organ yang menang (al-‘udw an-nātsir) dengan air, emas, dan perak. Pengertian yang sama juga terdapat dalam kasus kata al-janb dan al-wajh.
Merujuk kenyataan-kenyataan di atas, kami berpendapat menolak setiap bentuk penggubahan dan mendorong pembatasan pengertian dalam bahasa ‘Arab. Jika ada yang menyanggah: “Kesenjangan ini tidak bisa kamu pukul-ratakan secara serampangan pada seluruh kata. Ini tidak benar, sebab tidak ada beda antara engkau berkata roti dan nān, dengan saat engkau berkata daging dan kūsytā. Jika memang kamu mengakui bahwa kesenjangan pengertian terjadi dalam beberapa kasus, maka cegahlah penggubahan yang sumbang saja, jangan cegah penggubahan yang memang sepadan.” Maka akan kami jawab: “Benar bahwa kesenjangan memang terjadi pada beberapa kasus mikro, dan bukan makro.” Anggap saja misalnya kata al-yadd dan ad-dast mempunyai kesamaan dalam bahasa, isytirāk, metafor dan segenap aspek lain, namun jika lafal ini terbagi atau “yang boleh” dan “yang tidak boleh” tanpa adanya perbedaan yang jelas, maka akan sangat susah menentukan rincian kesenjangannya bagi manusia biasa, bahkan hal itu malah menjadi blunder tersendiri bagi orang awam. Mereka tidak bisa membedakan lagi titik-titik kesenjangan dengan titik-titik kesepadanan. Kalau dihadapkan pada dua opsi menutup pintu rapat-rapat sebagai tindakan preventif, karena toh penggubahan tidak mempunyai urgensi yang signifikan, atau membukanya lebar-lebar untuk orang awam dan melibatkan mereka dalam lingkaran bahaya, maka di sini tidak perlu dipertimbangkan lagi mana yang lebih aman dalam membahas Dzāt Allah dan sifat-sifatNya. Menurut saya, orang yang berakal dan beragama tentunya tidak akan menganggap masalah ini membahayakan, tapi bila ada bahaya yang mengancam dari penafsiran sifat-sifat ketuhanan ini, maka ia wajib dijauhi (untuk tidak diutak-atik dan dipertanyakan sebagai tindakan preventif – penj.). Syariat misalnya mewajibkan ‘iddah (masa tunggu dalam jangka waktu tertentu, – penj.) bagi seorang isteri yang berstatus telah disenggamai (yang ditinggal mati atau diceraikan suaminya) demi mengetahui kesucian rahimnya (dan benih si suami) serta untuk menjauhkan campur-aduk nasab sebagai tindakan preventif dalam hukum kewalian dan warisan, serta kasus-kasus hukum lain yang memperhatikan status nasab. Namun orang-orang malah ada yang mengatakan bahwa kewajiban ‘iddah seharusnya juga berlaku bagi istri yang mandul, menopause, anak kecil, dan istri yang menggunakan sistem KB, sebab kandungan rahim mampu dilihat oleh Sang Maha Tahu segala keghaiban. Allah mengetahui semua yang tersimpan di dalam rahim. Maka jika kita membuka pintu diskusi dalam hal-hal yang rinci, berarti kita telah menyusuri jalan yang berbahaya. Sebab ‘iddah hanya diwajibkan demi memastikan tidak ada kehamilan. Berpegang pada hukum global ini lebih mudah daripada harus menempuh bahaya perincian yang macam-macam. Sama halnya dengan kewajiban hukum ‘iddah, pengharaman penggubahan bahasa ‘Arab (dalam konteks nas al-Qur’ān dan Ḥadīts – penj.) juga merupakan hukum legal syar‘i yang dikukuhkan berdasarkan ijtihad dan tarjīḥ. Jelas bahwa bersikap hati-hati dalam menyikapi informasi tentang Allah dan sifat-sifatNya, juga informasi tentang pengertian yang dimaksudkan oleh lafal-lafal al-Qur’ān lebih penting dan urgen daripada unsur kehati-hatian dalam hukum ‘iddah serta semua hal yang diberi marka hati-hati oleh kalangan fuqahā’.