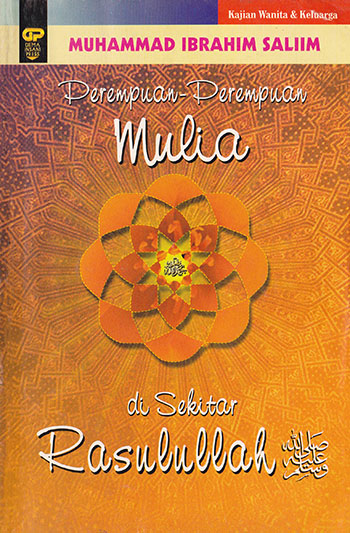4. UMMU AIMĀN BARAKAH BINTI MUḤSIN
Seorang anak yatim terkadang menemukan seseorang yang menggantikan posisi ibunya dalam memberikan kasih-sayangnya dan merawatnya sebagaimana kisah Ummu Aimān yang sering merawat Rasūlullāh s.a.w. bersama ibu kandungnya Āminah binti Wahb.
Pada saat penduduk ‘Arab – sebelum kelahiran Rasūlullāh s.a.w. – bersorak ria atas kemenangan mereka terhadap tentara gajah (Ashḥāb-ul-Fīl) yang datang menyerang Ka‘bah, Āminah binti Wahab yang saat itu sedang hamil tua lebih memilih menyendiri dari keramaian kota Makkah. Dia ingin merasakan ketenangan dan kebahagiaan dengan bayi yang sebentar lagi akan dilahirkannya. Namun, sesaat dia teringat suaminya yang telah meninggal dunia sehingga tidak ikut merasakan saat-saat yang berbahagia dalam kehidupan suami-istri (saat kelahiran seorang anak). Namun, cahaya yang ia lihat – sebelum kelahiran Rasūlullāh s.a.w. – memberikan ketenteraman dan ketenangan dalam hatinya serta melupakannya dari segala kegundahan.
Kasih-sayang Allah s.w.t. kepada bayi yang lahir dalam keadaan yatim tersebut turun mengembuskan rasa-sayang dan kelembutan kepada hati-hati para pengasuh bayi tersebut.
Seorang budak Ḥabasyah yang mewarisi anak yatim yang kehilangan ayahnya tersebut diembusi rasa sayang oleh Allah. Oleh karena itu, ia curahkan segala perhatian, kasih-sayang, dan kelembutannya kepada buah hatinya yang semata wayang (anak tunggal). Belum beberapa lama sang bayi diasuh dan dirawat dalam buaian ibunya, sang ibu harus rela melepaskan bayi tersebut untuk disusui oleh seorang ibu yang yang tak kalah sayangnya kepada bayi tersebut. Dibawalah bayi tersebut meninggalkan kota Makkah ke alam pedesaan yang terpencil (al-Bādiyah).
Selang beberapa waktu kemudian, bayi tersebut dibawa kembali ke Makkah untuk diasuh di bawah buaian sang ibu kandung dan pengasuhnya. Ketika sang ibu kandung hendak bertandang ke Yatsrib (Madīnah) bersama anaknya untuk mengunjungi paman-pamannya dari Bani Najjār, ibu pengasuh pun ikut menemani mereka berdua. Setelah si anak dan ibunya merampungkan keperluannya di Yatsrib, pulanglah anak tersebut ke Makkah di bawah belaian kedua ibunya (ibu kandung dan ibu asuh). Namun, belum jauh dari kota Yatsrib, sang ibu kandung terkena sakit sebagaimana yang dialami bapaknya sebelum dia dilahirkan. Akhirnya, ketika mereka hampir mendekati sebuah tempat dekat Abwā’, sang ibu menemui ajalnya.
Pulanglah anak yatim-piatu tersebut dengan ibu asuhnya menemui kakek dan paman-pamannya di Makkah tanpa ada seorang pun yang menemani perjalanan mereka. Sejak saat itu, ibu asuh merawat anak kecil tersebut hingga tumbuh dewasa. Setelah menginjak usia dewasa, sang anak melepaskan ibu asuhnya dengan memberi hak-haknya untuk hidup mandiri. Tidak lama kemudian, sang ibu asuh menikah dengan seorang pendatang dari Yatsrib. Sang ibu asuh pun ikut suaminya ke Yatsrib setelah tinggal beberapa waktu di Makkah. Sepeninggal suaminya sang ibu asuh kembali ke Makkah dengan seorang putra, Aimān bin ‘Ubaid – hasil pernikahan mereka – guna menemui putra pertamanya (Muḥammad s.a.w.) dan hidup bersama-sama lagi.
Karunia Allah kepada anak yatim tersebut (Muḥammad s.a.w.) semakin sempurna karena anak yatim tersebut sama sekali tidak pernah merepotkan ibu asuhnya. Dalam salah satu sabdanya, Rasūlullāh s.a.w. pernah mengekspresikan kelembutan dan kasih-sayang ibu asuhnya dengan berkata:
“Sesungguhnya dia (Ummu Aimān) sisa dari keluargaku.”
Sebaliknya, kasih-sayang Rasūlullāh s.a.w. kepada ibu asuhnya pun sangat besar dan dalam banyak kesempatan beliau selalu berusaha agar ibu asuhnya bisa hidup bahagia. Untuk itu, beliau pernah bersabda:
“Barang siapa yang ingin mendapat kebahagiaan untuk menikahi seorang wanita ahli surga, hendaknya dia menikahi Ummu Aimān.” (2)
Mendengar hadits di atas, bergegaslah seorang bekas budak Rasūlullāh s.a.w., Zaid, untuk menikahinya. Setelah berlangsung pernikahan, Ummu Aimān kembali ke Madīnah untuk menemui orang yang paling dicintainya, yaitu putranya, Zaid bin ‘Ubaid (hasil pernikahannya dengan ‘Ubaid). Selama di Madīnah, Ummu Aimān selalu berada di samping putranya. Bahkan, dalam kancah peperangan, Ummu Aimān pun ikut serta dalam barisan tentara kaum muslimin; memberi minuman dan mengobati mereka yang luka. Di antara peperangan yang ia ikuti adalah Perang Uhud, Perang Khaibar. Dalam perang tersebut, ia curahkan seluruh kasih-sayangnya, tidak hanya kepada putranya, bahkan kepada seluruh tentara kaum muslimin.
Dalam keadaan damai (tidak ada peperangan), Rasūlullāh s.a.w. kerap sekali menjenguk Ummu Aimān dan bercanda dengannya. Kendati demikian, Rasūlullāh s.a.w. tetap dalam batas-batas kebenaran sebagaimana layaknya seorang rasūl yang ma‘shūm (terjaga dari kesalahan).
Demikianlah Ummu Aimān, bekas budak (maula) sekaligus ibu asuh Rasūlullāh s.a.w. yang beliau warisi dari ayahnya. Kemudian beliau memerdekakannya ketika pernikahannya dengan Khadījah binti Khuwailid. Tidak lama kemudian, (setelah dimerdekakan) Ummu Aimān dinikahi ‘Ubaid bin Zaid. Dari pernikahan tersebut, mereka dikarunia seorang putra yang diberi nama “Aimān” yang pernah menemani Rasūlullāh s.a.w. dan meninggal dalam Perang Ḥunain. Sepeninggal ‘Ubaid. Datanglah Zaid bin Ḥāritsah – bekas budak Khadījah yang diberikan kepada Rasūlullah s.a.w. lalu dimerdekakan – menikahi Umma Aimān. Dari pernikahan tersebut, mereka dikarunia seorang putra yang diberi nama Usāmah bin Zaid.
Ummu Aimān juga meriwayatkan hadits dari Rasūlullāh s.a.w. sebanyak lima hadits. Dia juga salah seorang yang ikut hijrah dua kali. Dia meninggal pada masa-masa awal pemerintahan ‘Utsmān.