1-4-1 Sifat-sifat & Karakternya (Bagian 1) Al-Qasim Bin Muhammad Bin Abi Bakar – Kisah Para Tabi’in
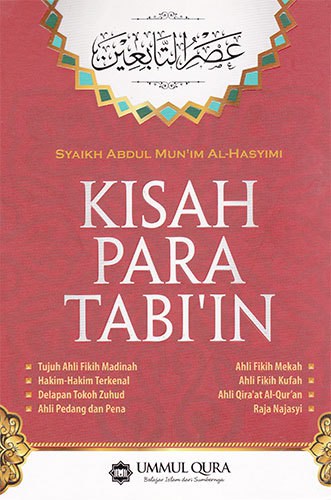
KISAH PARA TĀBI‘ĪN
Judul Asli: ‘Ashr-ut-Tābi‘īn
Penulis Abdul-Mun‘im al-Hasyimi
Alih Bahasa: Faqih Fatwa
Penerbit: UMMUL QURA
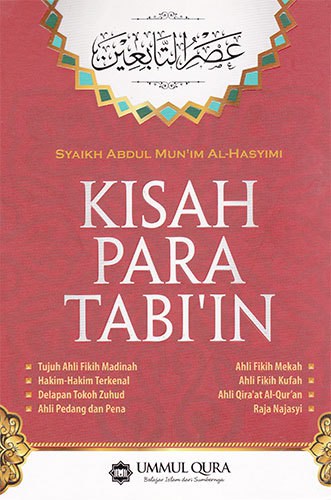
KISAH PARA TĀBI‘ĪN
Judul Asli: ‘Ashr-ut-Tābi‘īn
Penulis Abdul-Mun‘im al-Hasyimi
Alih Bahasa: Faqih Fatwa
Penerbit: UMMUL QURA
Sifat-sifat dan karakternya.
“Kami tidak mengetahui seorang pun di Madīnah yang lebih kami utamakan daripada al-Qāsim bin Muḥammad.”Yaḥyā bin Sa‘īd
“Aku tidak melihat seorang ahli fikih pun yang lebih utama daripada al-Qāsim bin Muḥammad.”Abuz-Zinād
Demikianlah dua kalimat sanjungan dari orang-orang yang hidup se-zaman dengan al-Qāsim bin Muḥammad bin Abī Bakar. Apakah kami perlu memberikan gambaran menyeluruh tentang sifat-sifatnya?
Dia biasa memakai peci tenun hijau yang terbuat dari sutra dan bulu juga selendang putih bersih. Dia r.h. adalah manusia yang paling mirip dengan kakeknya, Abū Bakar ash-Shiddīq r.a. Orang-orang yang hidup se-zaman dengannya pernah berkata tentang dirinya: “Abū Bakar tidak memiliki keturunan pun yang lebih mirip dengannya daripada pemuda ini. Sungguh dia sangat menyerupainya dalam hal kemuliaan akhlaknya, kecerdikannya, kekuatan imannya, sikap wara‘ dan ketaqwaannya, kelapangan jiwanya, serta kedermawanan tangannya.”
Di antara riwayat yang menguatkan apa yang disampaikan oleh para pendahulu kita tentang sifat-sifat dan karakter laki-laki itu adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Isḥāq (11) ketika itu dia sedang berada di masjid: “Aku melihat al-Qāsim bin Muḥammad melaksanakan shalat, tiba-tiba seorang ‘Arab Badui datang sambil berkata: “Siapakah di antara kalian berdua yang paling berilmu, kamu atau Sālim bin ‘Abdullāh bin ‘Umar?” Al-Qāsim pun berkata: “Subḥānallāh. Semua orang akan memberitahumu tentang apa yang mereka ketahui.” Laki-laki itu bertanya lagi: “Siapakah yang paling berilmu di antara kalian berdua?” Al-Qāsim berkata: “Subḥānallāh.” Laki-laki itu pun mengulangi pertanyaannya untuk yang ketiga kalinya, maka al-Qāsim berkata: “Itu adalah Sālim, pergilah dan tanyakanlah kepadanya”.”
Ibnu Isḥāq dan orang-orang yang duduk satu majelis dengannya pernah berkata: Al-Qāsim tidak suka untuk mengatakan: “Aku lebih berilmu dari padanya (Sālim),” karena hal itu termasuk memuji diri sendiri, dan beliau juga tidak suka untuk mengatakan: “Dia (Sālim) lebih berilmu dari padaku,” karena dengan begitu berarti dia telah berdusta.
Adz-Dzahabī menambahkan: “Al-Qāsim adalah orang yang paling berilmu di antara keduanya. Demikianlah, dari tutur katanya tampaklah akhlak seorang alim yang rendah hati dan haus akan ilmu.”
Dia r.h. tidak pernah menerima hadiah atau pemberian dari siapapun, dia selalu menjaga kehormatan dirinya dari meminta sesuatu dari tangan orang lain. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa seorang laki-laki pernah mengirimkan lima ratus dinar kepada al-Qāsim namun dia menolak untuk menerimanya. Demikian juga halnya dia tidak pernah mencela orang lain.
Berkenaan dengan berbagai karakter baik yang melekat pada dirinya ini, suatu hari ‘Umar bin ‘Abd-il-‘Azīz pernah berkata tentangnya: “Seandainya aku memiliki wewenang untuk mengamanatkan urusan kaum muslimin kepada seseorang, maka aku akan mengangkat al-Qāsim bin Muḥammad bin Abī Bakar ash-Shiddīq sebagai khalifah.” Dan ketika ungkapan kalimat baik ini sampai kepada al-Qāsim, dia pun bertanya-tanya penuh keheranan: “Sungguh, aku begitu lemah dalam mengurusi keluargaku, bagaimana mungkin aku mampu mengatasi urusan umat!!” (22).
Suatu ketika, dia diberi amanat untuk membagikan zakat kepada para mustahiknya dari golongan fakir miskin kaum muslimin, dia pun berijtihad sekuat kemampuannya, dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Setelah dia menyelesaikan kewajibannya, tiba-tiba seseorang yang merasa tidak ridha dengan bagian yang telah diberikan kepadanya mendatanginya. Dia pun datang ke masjid, ketika itu al-Qāsim sedang berdiri melaksanakan shalat. Lalu dia mulai berbicara tentang perkara zakat. Putra al-Qāsim yang sedang duduk di masjid bersama jama‘ah lainnya mendengar apa yang dikatakan oleh laki-laki itu, maka dia pun berkata kepadanya: “Demi Allah, sesungguhnya kamu membicarakan seseorang yang tidak memperoleh dari zakat kalian satu dirham pun dan tidak pula seperenam dirham pun. Bahkan dia juga tidak merasakan satu butir kurma pun daripadanya.
Al-Qāsim mendengar seluruh percakapan ini, dia pun segera mengakhiri shalatnya lalu mempercepat shalatnya dan menoleh ke arah anaknya seraya berkata: “Wahai anakku, janganlah kamu berkata setelah hari ini apa yang kamu tidak tahu.” Akan tetapi orang-orang berkata: “Sungguh, anaknya telah berkata benar. Memang dia tidak memperoleh satu dirham pun dari zakat mereka, bahkan dia juga tidak merasakan satu butir kurma pun daripadanya, akan tetapi al-Qāsim bermaksud untuk mendidik putranya agar dia menjaga lisannya dari mengatakan suatu perkataan yang tidak ada gunanya sehingga dia tidak menjadi orang yang banyak cakap.”
Pada masa kekhalifahan al-Walīd bin ‘Abd-il-Mālik, kaum muslimin bermaksud untuk memperluas al-Ḥaram an-Nabawī yang mulia. Al-Walīd pun bertekad untuk merealisasikan cita-cita ini namun rencana ini tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan menghilangkan rumah istri-istri Nabi dan menggabungkannya ke masjid. Hal ini sangat menyulitkan orang-orang, mereka tidak senang dengan hal tersebut karena rumah itu memiliki kedudukan yang mulia dalam diri mereka. Ketika itulah al-Walīd menulis sepucuk surat kepada gubernur Madīnah saat itu, yaitu ‘Umar bin ‘Abd-il-‘Azīz, dalam surat itu dia mengatakan:
“Kami bermaksud untuk memperluas masjid Rasūlullāh s.a.w. hingga luasnya menjadi dua ratus hasta kali dua ratus hasta. Maka robohkanlah keempat dindingnya dan masukkanlah kamar-kamar istri Nabi s.a.w. ke dalamnya. Belilah rumah-rumah yang ada di sekitarnya dan majukanlah qiblatnya bila kamu mampu. Sesungguhnya, kamu akan dapat mewujudkannya karena kedudukan paman-pamanmu ‘Alī al-Khaththāb (keluarga al-Khaththāb) dan kedudukan mereka di hati manusia. Apabila penduduk Madīnah enggan menjalankan perintahmu itu, maka mintalah bantuan kepada al-Qāsim bin Muḥammad dan Sālim bin ‘Abdullāh bin ‘Umar, ikutkanlah mereka berdua dalam urusan ini. Bayarlah harga rumah-rumah mereka dengan penuh kedermawanan, sesungguhnya kamu memiliki dua pendahulu yang dapat dipercaya dalam hal tersebut, mereka adalah ‘Umar bin al-Khaththāb dan ‘Utsmān bin ‘Affān.”
Demikianlah akhir dari surat al-Walīd, lalu ‘Umar bin ‘Abd-il-‘Azīz mengundang al-Qāsim bin Muḥammad dan Sālim bin ‘Abdullāh serta sejumlah ulama Madīnah. Dia pun menyampaikan isi surat amīr-ul-mu’minīn kepada mereka. Mereka pun menyetujui rencana tersebut dan sangat bersemangat untuk melaksanakannya.
Ketika orang-orang melihat dua alim Madīnah, yaitu al-Qāsim bin Muḥammad dan Sālim bin ‘Abdullāh bin ‘Umar telah menyetujui pendapatnya dan langsung turun tangan untuk melakukan renovasi masjid, mereka berdua adalah panutan yang dipatuhi pada masanya sehingga ‘Umar bin ‘Abd-il-‘Azīz pun pernah memohon pertolongan dengan kedudukannya karena condongnya hati umat manusia kepadanya juga karena kepatuhan mereka kepadanya sebagai salah seorang ulama, guru yang dimuliakan, juga sebagai seorang ahli fikih yang terkenal di antara mereka. Ketika itu pasukan kaum muslimin tengah bersiap-siap untuk menyerang kota Konstantinopel di bawah komando Maslamah bin ‘Abd-il-Mālik bin Marwān, kaisar Romawi pun menginginkan untuk berdamai dengan Amīr-ul-Mu’minīn dan mendekatinya karena takut terhadap pasukan muslim yang sangat besar ini. Maka ketika dia mendengar rencana Amīr-ul-Mu’minīn untuk memperluas masjid Nabawi yang mulia dia pun segera memanfaatkan kesempatan yang ada dengan mengirimkan seratus mitsqal emas dan seratus orang pekerja yang merupakan ahli bangunan paling mahir di negeri Romawi, serta membekali para pekerja tersebut dengan empat puluh muatan yang terdiri dari potongan-potongan kecil marmer berwarna cemerlang yang disebut fusaifisā’. Kemudian al-Walīd mengirimkan semua itu kepada ‘Umar bin ‘Abd-il-‘Azīz guna membantunya dalam pembangunan masjid. Lalu semua barang itu didatangkannya ke kota Madīnah. Setelah bermusyawarah dengan Syaikh al-Qāsim bin Muḥammad bin Abī Bakar, ‘Umar bin ‘Abd-il-‘Azīz pun mendistribusikannya dan memanfaatkannya untuk perluasan masjid Nabawi yang mulia.
Musyawarah ini bukanlah satu-satunya yang dilakukan ‘Umar bin ‘Abd-il-‘Azīz, namun hal itu tetap berlangsung pada tahun-tahun berikutnya sampai meninggalnya ‘Abd-ul-Mālik bin Marwān, ‘Umar bin ‘Abd-il-‘Azīz pun merasa sangat sedih dan berduka cita karenanya hingga tak dapat menjalani kehidupan yang menyenangkan. Lalu al-Qāsim bin Muḥammad berkata kepadanya: “Tahukah kamu, wahai ‘Umar, bahwa siapapun yang telah meninggal dari para pendahulu kita mereka senang menghadapi berbagai musibah dengan kesabaran dan menghadapi berbagai kenikmatan dengan kerendahan hati.” (33) Maka pada malam harinya ‘Umar pun pergi untuk membeli beberapa potong pakaian dari penduduk Yaman dan meninggalkan segala hal yang dilakukannya selama dirudung duka dan kesedihan karena kepergian Amīr-ul-Mu’minīn ‘Abd-ul-Mālik bin Marwān.
Demikianlah dia selalu mencurahkan berbagai nasihat dan arahannya kepada setiap orang di sekitarnya yang tengah mengalami kesedihan, semua itu dilakukannya semata-mata untuk mengharap keridhaan Allah ‘azza wa jalla. Sungguh, berbagai kesusahan dan musibah pernah menimpa ‘Umar bin ‘Abd-il-‘Azīz, al-Qāsim pun mengingatkannya dengan apa yang pernah menimpa salaf-ush-shāliḥ. Bukankah pada diri salaf-ush-shāliḥ terdapat segala kebaikan yang kita harapkan? Kalau begitu kenapa kita tidak menjadikan mereka sebagai pelita yang menerangi jalan kita dan menjadikannya sebagai petunjuk yang menjauhkan kita dari segala kesesatan yang menyergap kehidupan kita.
Semoga Allah merahmati al-Qāsim karena penghargaannya terhadap salaf-ush-shāliḥ, dia adalah orang yang memiliki kedudukan sangat mulia, dia adalah orang yang paling mengetahui as-Sunnah pada zamannya. Dia memiliki ilmu dan pengetahun yang sempurna setelah bertahun-tahun menghabiskan waktu untuk menghadiri berbagai halaqah ilmu, dia juga telah mengambil banyak sekali hadits Rasūlullāh s.a.w. dari bibinya, ‘Ā’isyah. Berkenaan dengan hal ini al-Qāsim mengatakan: “‘Ā’isyah memberikan fatwa secara independen pada masa kekhalifahan Abū Bakar, ‘Umar, dan seterusnya hingga akhir hayatnya. Aku senantiasa mengikutinya, aku juga sering menghadiri majelis al-bahr, Ibnu ‘Abbās, menghadiri majelis Abū Harairah, juga Ibnu ‘Umar hingga aku banyak meriwayatkan hadits darinya, di sana (pada diri Ibnu ‘Abbās) terdapat sikap wara‘, ilmu yang melimpah, dan dia menghindarkan untuk menyampaikan perkara yang tidak dia ketahui.
Di antara hadits yang diterimanya dari bibirnya, ‘Ā’isyah, ketika dia mengikutinya, dia berkata: “Pada suatu hari aku pernah berkata kepada bibiku, ‘Ā’isyah r.a.: “Wahai Ibu, perlihatkanlah kepadaku kuburan Nabi s.a.w. dan kuburan dua sahabatnya, sungguh aku ingin melihatnya.” Ketiga kuburan tersebut masih berada di dalam rumahnya. Namun, dia telah menutupnya dengan tabir sehingga dapat menghalanginya dari memandangnya. Dia pun memperlihatkan kepadaku ketiga kuburnya tersebut. Kuburan itu tidaklah menggunduk tinggi dan tidak pula rendah. Ia telah dihampari dengan kerikil merah yang ada di halaman masjid. Aku berkata: “Manakah kuburan Rasūlullāh s.a.w.?”
Dia pun menunjukkan dengan tangannya seraya berkata: “Ini.” Kemudian meneteslah dua air mata di pipinya. Diapun segera mengusapnya agar aku tidak dapat melihatnya. Kuburan Nabi s.a.w. berada di depan kuburan kedua sahabatnya. Aku berkata: “Manakah kuburan kakekku, Abū Bakar?”
Dia pun menjawab: “Yang ini.” Ternyata dia dikubur di sisi kepala Nabi s.a.w. Lalu aku berkata: “Dan yang ini kuburan ‘Umar?” Dia pun menjawab: “Ya.” Kepala ‘Umar r.a. berada di sisi pinggang kakekku, dekat dengan kaki Nabi s.a.w.” Demikianlah awal kebersamaannya bersama bibinya, ‘Ā’isyah, dia bertanya tentang segala sesuatu.
Kemudian dia meriwayatkan dari Abū Hurairah, ‘Abdullāh bin ‘Umar, ‘Abdullāh bin ‘Abbās, ‘Abdullāh bin az-Zubair, Rafī‘ bin Khudaij, Aslam maula ‘Umar bin al-Khaththāb r.a., dan yang lainnya hingga dia menjadi seorang alim, ahli fikih, dan ahli ijtihad. Bahkan dia mempunyai metode sendiri dalam periwayatannya, yaitu dia hanya menyampaikan hadits sesuai dengan hurufnya (redaksi aslinya).
Salah seorang ulama yang hidup semasa dengannya pernah berkata: “Al-Qāsim, Ibnu Sīrīn, dan Rajā’ bin Ḥaiwah mereka menyampaikan hadits berdasarkan hurufnya (sesuai dengan redaksi aslinya), sementara al-Ḥasan, Ibrāhīm, dan asy-Sya‘bī meriwayatkan hadits berdasarkan maknanya.”
Jumhur ulama dari generasi salaf maupun khalaf telah bersepakat mengenai bolehnya meriwayatkan hadits berdasarkan makna jika orang yang meriwayatkan mengetahui lafal dan maksud dari lafal tersebut, memahami perkara yang dapat merubah maknanya, serta mengetahui kadar perbedaan yang terletak di antara lafal-lafal yang ada. Hal itu dapat dilihat dari hadits-hadits yang shahih dan yang lainnya, di mana peristiwa yang terjadi adalah satu namun redaksi yang disampaikan bermacam-macam dari jalan yang berbeda-beda, dan kebanyakan periwayatan para sahabat dan tabi‘in berdasarkan makna kecuali jika berkenaan dengan lafal yang digunakan dalam ibadah seperti bacaan tasyahhud, qunut, dan bacaan shalat, serta apa yang menjadi bagian dari jawāmi‘ul-ḥikam s.a.w. (kalimat yang sederhana namun memiliki makna yang sangat dalam), maka para perawi hadits berusaha dengan kuat untuk meriwayatkannya dengan redaksi sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi s.a.w.
Catatan: