1-3 Memperhatikan Zikir & Doa di Dalam Shalat – Belajar Khusyuk
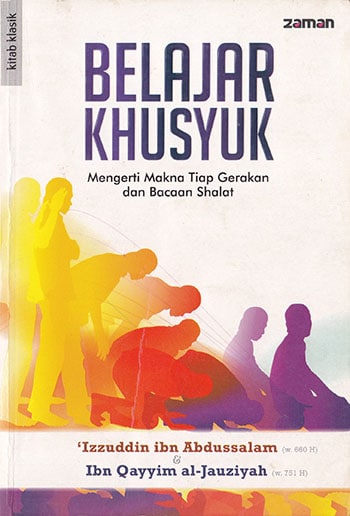
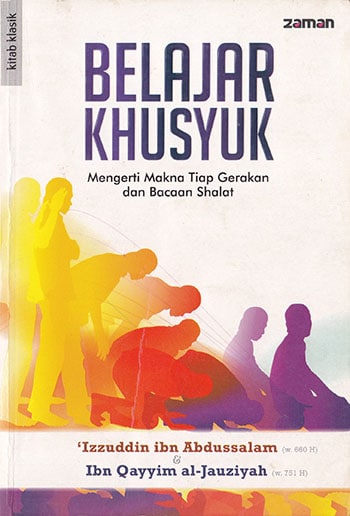
Memperhatikan bacaan setiap zikir dan doa di dalam shalat artinya memahami dan memperhatikan makna di dalamnya dalam bentuk upaya menghadirkan hati (hudhūr al-qalb), memuji Allah dengan lidah, dan hati senantiasa fokus pada setiap makna bacaan yang diucapkan. Dengan kata lain, saat shalat, kita memuji Allah dengan hati dan lidah sekaligus; tidak mengingat bacaan lain meski bacaan tersebut lebih baik. Sebab, tiap-tiap gerakan memiliki bacaannya sendiri.
Begitulah aturan pada setiap bacaan. (141) Selain itu, kita juga mesti berupaya penuh mendengarkan bacaan al-Qur’an dengan sikap penghambaan yang sebenarnya di hadapan Rabb yang Maha Agung, di samping memperhatikan setiap makna bacaan, serta tidak boleh disibukkan oleh makna-makna selain
Lihatlah kebaikan-kebaikan dan keberkahan yang terhimpun di dalam shalat. Diawali dengan menyebut nama Allah s.w.t., kemudian dilanjutkan dengan permohonan hal-hal terpenting dalam kehidupan. Lalu, diakhiri dengan pujian-pujian kepada-Nya dalam taḥiyyāt.
makna bacaannya, meskipun makna bacaan itu dianggap lebih utama. Sebab, dengan demikian, berarti ia telah menolak mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah tata cara yang buruk yang bisa memberi kesempatan pada setan untuk menggoda para ahli makrifat.
Setan membuat kita sibuk memikirkan hal-hal lain di luar bacaan al-Qur’an. Seandainya setan tidak berhasil dengan cara begitu lantaran hamba yang sedang digodanya adalah seorang yang taat dan ahli makrifat, maka setan akan mengalihkan perhatian hamba itu dari makna bacaan al-Qur’an kepada bacaan dan zikir lain yang tidak ada kaitannya dengan shalat. (152) Saking pentingnya hal di atas diperhatikan, Yahyā ibn Mu‘ādz al-Rāzi pernah mengatakan: “Sesungguhnya setan mengalihkan kekhusyukanku dalam shalat dengan mengingat surga dan neraka.”
Jika tengah membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah s.w.t., hendaknya kita tidak memperhatikan hal-hal lain. Ketika membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu kisah, hendaknya kita memperhatikan pelajaran dan teladan di dalamnya. Demikian pula ketika membaca ayat-ayat perintah dan larangan, hendaknya kita memperhatikan apa saja yang diperintahkan maupun yang dilarang sembari bertekad untuk menaati dan mempraktikkannya. (163).
Sebagai contoh, saat kita mengucapkan subḥāna rabbiyal ‘azhīmi (Maha Suci Rabbku yang Maha Agung), hendaknya ia memperhatikan kembali makna tasbih, yaitu menyucikan Zat dan sifat-sifat Allah dari segala kekurangan, di samping makna rububiyah dan ‘ubudiyah Allah di dalam kalimat rabbī. Karena, kalimat tersebut memadukan dua makna sekaligus: makna keagungan (rubūbiyah) dan kemahasuican (tasbīh).
Selain itu, kita juga mesti memperhatikan makna al-‘uluw (ketinggian) di dalam kalimat subḥāna rabbiyal a‘lā. Jika tidak, berarti kita telah melalaikan zikir hati sebagai zikir paling utama.
Pada saat mengucapkan iyyaka na‘budu (hanya kepada-Mu kami menyembah), mestinya kita memperhatikan makna ibadah; yaitu ketaatan dan ketundukan.
Pada saat membaca iyyaka nasta‘īn (hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan), hendaknya ia memperhatikan makna isti‘ānah (pertolongan), dan apa yang berkaitan dengan Allah s.w.t. secara khusus sebagai satu-satunya yang boleh dimintai pertolongan. (174).
Jika ia memohon hidayah (dengan membaca ihdinā ash-shirāth al-mustaqīm), hendaknya ia memperhatikan makna hidayah dan menggambarkan makna keindahan makrifat di dalam hatinya.
Ia juga mesti memperhatikan makna ash-shirāth yang berarti tauhid atau “agama Islam” dan mengerjakan kewajiban-kewajibannya. Dan, saat seorang mushalli telah sampai pada bacaan tahiyyat dan shalawat atas Rasulullah s.a.w., hendaknya ia memperhatikan makna dari setiap kata yang dibacanya.
Shalat seperti inilah yang dimaksud oleh Allah s.w.t. dalam firman-Nya:
إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ
“…. mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.” (al-‘Ankabūt [29]: 45). Memperhatikan makna setiap bacaan shalat akan membuat hati kita merasakan getaran kebesaran Allah s.w.t. dan kepatuhan terhadap-Nya, sehingga kita dapat menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar.
Dengan merenungi sifat-sifat Allah saat membaca ayat al-Qur’an: “Qul huwa Allāh aḥad.” (Katakanlah: wahai Muhammad, bahwa Dia adalah Allah Yang Maha Esa) (al-Ikhlāsh [112]: 1), mestinya ia memperhatikan pula makna Maha Esa, Maha Tunggal, baik dalam Zat maupun sifat-sifatNya, Maha Abadi dan Zat-Nya tiada tertandingi. Dia Tunggal dalam af‘āl (perbuatan)-Nya; tiada pencipta selain Dia. Dia Tuhan yang sebenarnya; tiada Tuhan selain Dia. Perintah dan larangan-Nya mesti ditaati, sebab tiada ketetapan yang paling lurus selain ketetapan-Nya. Dia Maha Esa, Maha Agung, Maha Sempurna, Maha Pemberi nikmat dan karunia. Sungguh, tiada yang mampu berbuat sesuatu selain Dia.
Kemudian, dengan memperhatikan makna “ash-Shamad.” Yakni, bahwa Dia adalah Tuhan yang kebaikannya tidak pernah berhenti mengalir. Dari segi sifat Zat-Nya, Dialah tempat bergantung saat kita tengah membutuhkan sesuatu. Dari segi af‘āl-Nya, Dia bersifat nonmateri, tidak berfisik.
Jika diperhatikan lebih jauh, pada ayat-ayat yang telah disebutkan, terdapat makna tauhid, seperti:
“Lam yalid” (Dia tidak melahirkan) adalah bentuk pengingkaran akan adanya sesuatu yang
Itulah sebabnya kita diwajibkan bertakbir pada setiap perpindahan gerakan shalat. Sebab, konsentrasi yang penuh terhadap bacaan-bacaan shalat kerap kali membuat kita lalai akan kebesaran Allah s.w.t.
menyerupai-Nya. Seorang anak saja tidak serupa dengan bapaknya.
“Wa lam yūlad” (dan Dia tidak dilahirkan) adalah bentuk pengingkaran akan adanya keserupaan terhadap wujud Allah s.w.t.
“Wa lam yakun lahu kufuwan aḥad.” (dan tiada sesuatu pun yang menyamai-Nya) adalah bentuk pengingkaran terhadap keserupaan sesuatu dengan-Nya dalam segala hal.
Karena kandungan surah al-Ikhlāsh yang merangkum makna tauhid secara menyeluruh inilah maka nilai surah ini kemudian dianggap sama dengan sepertiga al-Qur’an, (185) sebagaimana ayat Kursi disebut sebagai ayat paling agung. (196) Selain itu, di antara ayat-ayat al-Qur’an lain terdapat beberapa ayat yang dianggap lebih utama dibandingkan dengan yang lain, meski pada dasarnya seluruh surah di dalam al-Qur’an sama mulianya, sebab bersumber dari Allah s.w.t. Tentu, firman Allah s.w.t. yang berisi gambaran tentang Diri-Nya sendiri lebih utama nilainya dibandingkan dengan firman-Nya yang berkenaan dengan gambaran tentang selain-Nya. Sebab, firman jenis yang pertama memiliki dua kemuliaan: pertama, mulia lantaran ia memuat sifat-sifatNya. Dan, kedua, mulia lantaran kandungannya berkaitan dengan Allah s.w.t., sebagaimana perkataan kita tentang Allah s.w.t. tentu lebih utama dibandingkan dengan perkataan kita tentang selain-Nya. (207)
Para ahli makrifat menyatakan bahwa jika segala sesuatu bertitik tolak dari Allah s.w.t. dan bermuara pada hal-hal yang berhubungan dengan-Nya, maka hal itu tentu lebih utama dibandingkan dengan hal lain. Sebab, apa pun yang dimulai dari-Nya dan kembali kepada-Nya, lebih mulia dibandingkan dengan sesuatu yang dimulai dari-Nya tapi tidak kembali kepada-Nya.
Sebagai contoh, ada ungkapan yang mengatakan bahwa maḥabbah (cinta) memiliki dua aspek: pertama, jamāl (keindahan) dan kamal (kesempurnaan). Kedua, in‘ām (anugerah nikmat) dan ifdhāl (karunia). Siapa saja yang mencintai-Nya lantaran keagungan dan kesempurnaan-Nya, maka hal itu jauh lebih utama dibandingkan dengan mereka yang mencintai-Nya lantaran Dia menganugerahi nikmat dan karunia kepada mereka. Sebab, cinta kepada Allah s.w.t. atas dasar keagungan dan kesempurnaan-Nya, berkaitan langsung dengan Zat dan sifat-sifatNya. Sedangkan, cinta yang didasari atas anugerah nikmat dan karunia semata, tak lebih dari kesibukan diri pada selain-Nya.
Orang yang mencintai Allah lantaran keagungan dan kesempurnaan, sesungguhnya telah menyibukkan diri dengan Allah s.w.t. dan keagungan-kesempurnaanNya sekaligus. Sedangkan, orang yang mencintai-Nya lantaran anugerah dan karunia-Nya, sesungguhnya ia telah menyibukkan diri dengan-Nya pada satu sisi, dan dengan anugerah nikmat pada sisi yang lain.
Para ahli makrifat juga menyatakan bahwa perasaan malu dan ta‘zhim kepada Allah jauh lebih utama dan agung dibandingkan dengan perasaan khauf (takut) dan rajā’ (harap). Sebab, perasaan malu dan ta‘zhim kepada-Nya merupakan pujian yang lebih mulia dibandingkan dengan sekadar memperhatikan Zat dan sifat-sifatNya. Sedangkan, rasa khauf (takut) dan rajā’ (harap) hanya bersumber dari Zat dan sifat-sifat Allah s.w.t.; tetapi, itu masih merupakan sebuah kesibukan dengan selain-Nya. Sementara, perasaan malu dan ta‘zhim kepada-Nya merupakan kesibukan hanya dengan dan kepada-Nya. (218)
Adapun makna doa di antara dua sujud adalah sebagai berikut:
Makna kalimat rabbī ighfir lī (wahai Tuhanku, ampunilah aku) (229) diawali dengan pengakuan akan Allah s.w.t., Tuhan sekalian makhluk
Memperhatikan makna setiap bacaan shalat akan membuat hati kita merasakan getaran kebesaran Allah s.w.t. dan kepatuhan terhadap-Nya, sehingga kita dapat menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar.
(tauhīd rubūbiyah), kemudian disusul dengan pengakuan akan kehinaan diri sebagai seorang hamba. Ucapan ighfir lī mengandung arti “hapuskan dosaku, hilangkan aibku.” Kata al-ghafr pada mulanya memiliki arti “tirai”. Dari kata inilah muncul kata al-mighfar yang berarti “kain penutup kepala”.
Warḥamnī mengandung arti “perlakukan aku dengan penuh kasih sayang dan berilah aku rahmat.” Salah satu bentuk rahmat-Nya adalah limpahan anugerah dan perlindungan dari berbagai bahaya.
Wajburnī berakar dari kata al-jabr yang berarti “perbaikan”, seperti kalimat: “Aku berbuat baik terhadap orang yang lebih besar dan orang miskin.”
Warfa‘nī berakar dari kata rif‘ah (ketinggian) yang maksudnya adalah tingginya kedudukan dengan makrifat dan ketaatan.
Warzuqnī berakar dari kata rizq yang berarti segala sesuatu yang diberikan atau dihadiahkan kepada manusia, lalu bermanfaat baginya.
Doa ini menghimpun kebaikan di dunia dan akhirat. Saat membacanya kita hendaknya memperhatikan tiap maknanya dan mengarahkan permohonan hanya kepada-Nya.
Tentang bacaan at-taḥiyyāt di dalam tasyahud, para ulama bersilang pendapat. Sebagian mereka mengatakan bahwa kata ini bermakna “kekuasaan hanya milik Allah s.w.t.,” seperti ungkapan syair: “Apa pun yang dimiliki orang lain, aku pun memilikinya, kecuali “al-taḥiyyāt””. (2310) Al-Taḥiyyāt di sini diartikan dengan “kekuasaan”.
Sebagian mereka mengatakan bahwa at-taḥiyyāt berarti al-‘azhamah (keagungan). Ini pendapat Ibnu ‘Abbas. Sebab, menurutnya, para raja diagungkan dengan menggunakan kata at-taḥiyyāt.” Jadi, kata ini digunakan untuk menunjukkan keagungan. Sedangkan tambahan alif dan lām di dalam kata ini dimaksudkan untuk memperkaya makna keagungan. Ada juga yang mengatakan bahwa kata at-taḥiyyāt memiliki makna al-baqā’ (keabadian).
al-Mubārakāt diambil dari kata al-barakah yang berarti tumbuh dan bertambahnya kebaikan serta ketetapannya. Semua itu adalah milik Allah s.w.t.
Ash-Shalawāt maksudnya adalah segala bentuk shalawat (doa) yang dianjurkan. Ia juga bisa berarti segala bentuk ta‘zhīm (penghormatan) dan ijlāl (pengagungan) dengan hati, lisan, dan fisik. Semua itu adalah milik Allah s.w.t.
Ath-Thayyibāt berakar dari kata thayyibah (baik), mencakup segala bentuk pujian yang hanya ditujukan kepada Allah s.w.t., seperti di dalam firman-Nya: Dan, kepada-Nyalah kalimat yang baik itu naik (Fāthir [35]: 10). Maksudnya di sini adalah mengesakan dan memuji-Nya.
Bacaan tahiyyat diawali dengan sesuatu yang amat penting, yaitu pujian-pujian kepada Allah, dilanjutkan dengan shalawat atas Rasulullah sebagai pujian terpenting kedua setelah pujian kepada Allah. Setelah itu, doa untuk diri sang mushalli, sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w.: “Mulailah dari dirimu.” (2411) Kemudian, ditutup dengan doa untuk seluruh hamba yang saleh, sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim a.s.: “Wahai Rabb kami! Ampunilah aku, kedua orangtuaku, dan seluruh orang beriman pada hari perhitungan.” (Ibrāhīm [14]: 41).
Nabi Ibrahim mulai berdoa untuk dirinya sendiri, baru kemudian untuk kedua orangtuanya, dan ditutup dengan doa untuk kaum beriman. Nabi Nuh a.s. pun demikian, beliau berdoa: “Wahai Rabbku! Ampunilah aku, kedua orangtuaku, siapa saja yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, dan bagi kaum beriman; baik yang laki-laki maupun perempuan.” (Nūh [71]: 28). Nabi Nuh a.s. memulai dengan doa untuk dirinya sendiri, lalu untuk kedua orangtuanya, orang yang ia kenal, dan seluruh umat beriman.
Kalimat asyhadu an lā ilāha illā Allāh (aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah) merupakan bentuk pengakuan bahwa yang berhak disembah (ma‘būd berakar dari ibadah) hanyalah Allah, bukan selain-Nya. Sementara, makna ibadah itu sendiri adalah ketaatan dan ketundukan dengan menghinakan diri di hadapan Allah s.w.t. Tentu, tak ada yang berhak diperlakukan seperti itu selain Dia yang memiliki segala sifat keindahan dan kesempurnaan. Kalimat itu kemudian dilanjutkan dengan pengakuan atas kebenaran risalah yang dibawa Nabi Muhammad s.a.w. sebagai penegas komitmen keislamannya. Bukankah salah satu rukun Islam itu adalah mengakui risalah beliau?
Kalimat allāhumma shalli ‘alā Muḥammad wa ‘alā āli Muḥammad (Ya Allah, limpahkan shalawat atas Nabi Muhammad dan keluarganya). Kata shalli berakar dari ash-shalāh yang berarti doa. Jika ash-shalāh itu dilakukan oleh Allah s.w.t., maka maksudnya adalah rahmat-Nya. Kalimat ini menjadi petunjuk akan hak-hak Rasulullah s.a.w., tidak buat orang lain.
Kalau toh orang lain mendapatkan doa ini, itu pun setelah Rasulullah s.a.w., seperti di dalam bacaan allāhumma shalli ‘alā Muḥammad wa ‘alā āli Muḥammad (Ya Allah, limpahkan shalawat atas Nabi Muhammad dan keluarganya). Kata “dan” di atas merupakan hak kita. Sedangkan hak beliau adalah mendoakan siapa saja yang dikehendakinya, seperti kalimat: “Ya Allah, limpahkan shalawat (doa) atas ayah dan ibuku.” Doa seperti itu adalah hak beliau. Rasulullah s.a.w. juga berhak memberikan doanya kepada setiap umatnya; siapa pun dia, sementara kita tidak berhak mencampuri hak beliau. (2512).
Shalat adalah penyejuk hati orang yang mencintai Allah, nikmat bagi siapa pun yang mengesakan-Nya, taman indah bagi para ahli ibadah, kesenangan jiwa bagi kalangan yang khusyuk, kemuliaan bagi orang yang meyakini kebenaran janji-Nya, penanda kemurnian kalangan yang menempuh jalan-Nya, dan rahmat Allah bagi hamba-hambaNya yang beriman.
Selanjutnya, kalimat kamā shallaita ‘alā Ibrāhīm, atau boleh juga kamā shallaita ‘alā Ibrāhīm wa ‘alā āli Ibrāhīm innaka ḥamīd majīd (2613) (sebagaimana Engkau limpahkan shalawat atas Ibrahim dan keluarganya, Engkau Maha terpuji lagi Maha Mulia). Ada banyak pertanyaan seputar kalimat ini, di antaranya, apakah kalimat ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim a.s. lebih mulia dibandingkan dengan Nabi Muhammas s.a.w.?
Kami akan menjawab pertanyaan ini dari dua aspek, yaitu:
Pertama, sesungguhnya Allah s.w.t. menyerupakan shalawat atas keluarga Nabi Muhammad dengan shalawat atas Nabi Ibrahim a.s.
Kedua, dan ini yang lebih mendekati kebenaran, yaitu bahwa Allah s.w.t. menyerupakan shalawat atas Muhammad dan keluarganya dengan shalawat atas Ibrahim a.s. dan keluarganya. Artinya, rahmat dan rida Allah yang diberikan kepada Muhammad dan keluarganya hampir sama banyaknya dengan yang diterima oleh Ibrahim dan keluarganya. Sebab, anak keturunan Ibrahim rata-rata adalah para nabi, termasuk nabi kita, Muhammad s.a.w. Dari keseluruhan shalawat itu masih dibagikan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya.
Memang, shalawat yang diterima keluarga Muhammad tidak sebanyak yang diterima keluarga Ibrahim. Sebab, keluarga Ibrahim sebagian besar adalah para nabi; sementara keluarga Muhammad tak seorang pun yang menjadi nabi. Meski demikian, rahmat Allah kepada Muhammad dan keluarganya tetap melimpah ruah. Ini menunjukkan bahwa Muhammad s.a.w. sendiri lebih utama dibandingkan dengan Ibrahim a.s. (2714)
Kemudian innaka ḥamīd majīd. Kata hamīd di sini berarti yang terpuji. Sebab, kata yang di-fā‘il-kan lebih tegas dibandingkan dengan kata yang di-maf‘ūl-kan. Artinya, Allah s.w.t. adalah Zat Yang paling berhak atas segala bentuk pujian. Sebab, kata majīd atau al-majd mengandung arti asy-syarf (kemuliaan), dan kata majīd adalah sīghah mubālaghah (superlatif) dari kata mājid (mulia). Singkatnya, kalimat ini berarti: “Engkaulah Yang paling berhak atas segala bentuk pujian, sebab Engkau memiliki segala sifat mulia.”
Sementara itu, doa qunut sesungguhnya merupakan himpunan doa kebaikan di dunia dan di akhirat. Sebab, bacaannya berisi permohonan kebaikan sekaligus perlindungan dari berbagai bahaya, baik di dunia maupun di akhirat.
Allāhumm-ahdinī fī man hadait adalah permohonan kebaikan saat ini, yaitu kebaikan dalam hal agama. Kalimat ini lebih didahulukan lantaran keutamaan agama di sisi Tuhan.
Wa ‘āfinī fī man ‘afait adalah permohonan kesehatan fisik setelah diberi kesempurnaan beragama.
Wa tawallanī fī man tawallait merupakan bentuk ketaatan. Sebab, Allah s.w.t. cukup memperhatikan hamba yang diangkatnya; baik dengan melimpahkan rahmat atau menolak bahaya darinya.
Wa bārik lī fī mā a‘thait adalah permohonan agar diberi tambahan manfaat dalam beragama.
Shalat juga akan meluaskan rezekinya dan menjadikannya hamba yang dicintai hamba-hamba lainnya. Tidak hanya itu, malaikat pun akan mencintainya, begitu pula seluruh isi bumi, gunung-gunung, pepohonan, dan sungai-sungai.
Wa qinī syarra mā qadhait berisi permohonan perlindungan dari segala bahaya, di dunia dan di akhirat.
Setelah itu, dilanjutkan dengan puji-pujian kepada Allah s.w.t. Dia Yang Menguasai dan tidak dikuasai oleh apa dan siapa pun. Dia Yang Maha Memaksa dan tidak ada yang dapat memaksa-Nya. Dia Yang Menetapkan aturan, bukan Dia yang menaati peraturan.
Fa innaka taqdhī wa lā yuqdhā alaik, innaka lā yadzillu man walait, tabārakta wa ta‘ālait. (2815) Tidak akan hina orang yang menjadikan Allah s.w.t. sebagai pelindungan. Seluruh ciptaan dan segala urusan adalah milik-Nya. Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam.
Di dalam al-Fawā’idu fī Mukhtashar-il-Qawā’id, (10/alif), beliau juga mengatakan: “…sikap maḥabbah (pengakuan cinta terhadap Allah s.w.t.) dan ijlāl lebih utama dibandingkan dengan khauf dan rajā’. Jika kau ingin mengetahui keutamaan para wali, maka lihatlah pengaruh makrifat dan keadaan batin yang tampak dari dalam diri mereka. Siapa saja di antara mereka yang memiliki sifat utama, seperti ta‘zhīm dan ijlāl, mereka itulah orang yang terbaik. Dan, siapa di antara mereka yang memiliki sifat-sifat di bawah sifat utama tadi, semisal khauf dan rajā’, maka mereka itulah orang yang lebih rendah derajatnya.”