1-2 Maksud Bacaan di Dalam Shalat – Belajar Khusyuk
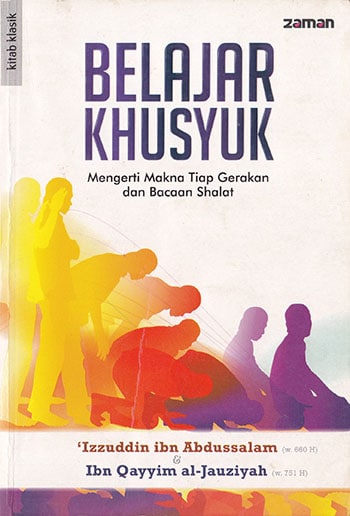
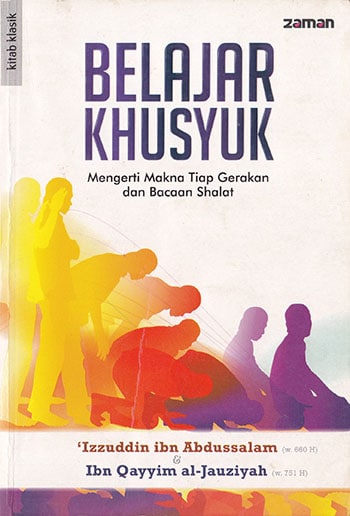
Gerakan takbir, berdiri, ruku‘ beserta tasbihnya, i‘tidal beserta bacaannya, dan sujud, semuanya hanya untuk Allah s.w.t.
Sementara, bacaan doa saat duduk di antara dua sujud adalah untuk hamba yang mendirikan shalat. Nilai ketundukan dan kekhusyu‘annya adalah milik Allah s.w.t. Semua bacaan di atas hukumnya sunnah, kecuali takbiratul-ihram yang hukumnya wajib.
Tujuan hakiki shalat adalah upaya memperbarui perjanjian (kontrak) kita dengan Allah s.w.t. Shalat itu sendiri mencakup aktivitas hati, lisan dan anggota tubuh sekaligus. Aktivitas ini tidak terdapat dalam ibadah-ibadah lainnya.
Dalam bacaan tasyahud awal dan akhir terdapat hak-hak Allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w., di samping terdapat hak orang yang mendirikan shalat (mushalli) dan orang-orang beriman. Hak Allah berupa puji-pujian kepada-Nya. Dan, hak Rasulullah s.a.w. berupa permohonan keselamatan atas beliau dan kesaksian atas kebenaran risalahnya, serta shalawat (doa) bagi beliau, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam: “Semoga keselamatan (salām) dilimpahkan kepada kami dan atas semua hamba Allah yang saleh.”
Kata salam merupakan bentuk masdar dari akar kata salima-yaslamu-salām. Ada pula yang berpendapat bahwa kata tersebut adalah bentuk jama‘ (plural) dari kata salāmah, seperti kata malāmah menjadi malām, Kata salam berisi doa permohonan keselamatan dari segala kehancuran dan bencana. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa taḥiyyāt (penghormatan) yang baik dan penuh berkah datangnya hanya dari Allah s.w.t. Tidak ada yang lebih utama dibandingkan dengan berkah keselamatan dari segala sesuatu yang buruk, terlebih jika dimanfaatkan dalam hal ketaatan dan ibadah kepada Allah s.w.t.
Begitu pula dengan doa untuk diri sendiri dan seluruh umat Islam yang dibaca di penghujung shalat, atau doa pada waktu salam. Keduanya merupakan permohonan keselamatan khusus bagi hamba beriman yang melaksanakan shalat.
Lihatlah kebaikan-kebaikan dan keberkahan yang terhimpun di dalam shalat. Diawali dengan menyebut nama Allah s.w.t., kemudian dilanjutkan dengan permohonan hal-hal terpenting dalam kehidupan, seperti permintaan petunjuk ke jalan yang lurus menuju Allah s.w.t. Lalu, diakhiri dengan pujian-pujian kepada-Nya dalam taḥiyyāt. Berikutnya, permohonan keselamatan bagi sayyid al-mursalīn, Muhammad s.a.w., dan bagi diri mushalli sendiri: “Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kami dan kepada semua hamba Allah yang saleh.”
Shalat juga mencakup bacaan al-bāqiyāt ash-shāliḥāt berupa pujian-pujian kepada Allah s.w.t. dengan segala keagungan dan kesempurnaan-Nya; baik dengan ungkapan yang khusus maupun umum.
Shalat juga memuat pujian-pujian seperti yang terdapat di dalam surah al-Fātiḥah dan bacaan ketika bangkit dari ruku‘ (rabbanā wa laka al-ḥamd). Keduanya merangkum segala sifat sempurna yang hanya dimiliki oleh Allah s.w.t.
Shalat juga mengandung tasbih kepada Allah s.w.t.; yang menunjukkan bahwa Dia Maha Suci dari segala cela dan kekurangan. Dalam takbir terkandung sifat-sifat sempurna yang hanya dimiliki Allah s.w.t.; tak satu pun makhluk yang memilikinya, bahkan para malaikat dan nabi sekalipun.
Terdapat pula ungkapan kesaksian akan keesaan Allah s.w.t. (tauhid) yang terangkum di dalam kalimat: “Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah.” Tauhid yang dimaksud adalah bahwa hanya Allah s.w.t. yang berhak atas penghambaan (ibadah) setiap makhluk. Hak seperti ini hanya dimiliki oleh Zat Yang memiliki sifat-sifat seperti yang telah disebutkan di atas.
Shalat juga menjadi hiasan bacaan al-Qur’an yang mencakup seluruh pengetahuan keagamaan orang-orang terdahulu dan yang akan datang, (61) berikut penjelasannya secara ringkas.
Tegak berdiri di dalam shalat menunjukkan sebuah sikap ta‘zhīm (hormat), seperti halnya gerakan ruku‘ dan sujud. Itulah sebabnya, bacaan ruku‘ berbunyi: “Maha Suci Rabb-ku yang Maha Agung.” (72) Sebab, pengakuan akan keagungan Allah s.w.t. menuntut sikap pengakuan akan kehinaan dan ketundukan pengucapnya. Jika seorang hamba telah sampai pada kesadaran dan pengakuan akan dirinya yang hina, maka ia pun akan mengakui bahwa yang ia sembah adalah Zat Yang Maha Agung. Dari sinilah lahir sikap tunduk dan patuh. Dan, pada saat sujud, ia merasa jauh lebih tunduk dibandingkan dengan saat ruku‘. Coba lihat bacaan berikut: “Maha Suci Rabb-ku Yang Maha Tinggi.” Pada saat ia mencapai puncak ketundukannya, ia akan baru mengakui bahwa yang sedang ia sembah adalah Zat Yang sungguh berhak atas segala ketinggian. (83).
Satu hal yang perlu diketahui, cara melakukan
“Sesungguhnya setan mengalihkan kekhusyukanku dalam shalat dengan mengingat surga dan neraka.”Yahyā ibn Mu‘ādz al-Rāzi
gerakan shalat, seperti berdiri, duduk, ruku‘, dan sujud, harus berbeda dari biasanya, agar tidak mirip dengan gerakan-gerakan yang dilakukan untuk selain Allah s.w.t. Misalnya, dengan menghadap kiblat atau gerakan lainnya.
Jika sikap berdiri dan duduk yang dilakukannya biasa-biasa saja, maka hendaklah ia memperbaiki sikap tersebut agar terbentuk sebuah sikap istimewa yang membedakannya dari gerakan yang lain.
Jika gerakan berdiri dan duduk tidak boleh sama dengan gerakan biasa yang dilakukan manusia, maka tentunya menyerupai gerakan binatang jauh lebih dilarang. Karena itu, orang yang shalat dilarang meniru gerakan anjing, (94) keledai, (105) atau binatang lainnya. Selain itu, ia juga harus memperhatikan makna bacaan shalatnya.
Secara garis besar, ada tiga macam pengetahuan tentang hati:
Pertama, terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan Allah s.w.t., seperti makrifat, iman, dan pengamatan tentang keagungan dan kesempurnaan-Nya. Kalimat “Subḥānallāh wal-ḥamdu lillāh” secara umum ditujukan kepada Allah s.w.t.
Kedua, terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan selain-Nya, seperti perhatian yang berlebihan hal-hal yang bersifat duniawi.
Ketiga, terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan-Nya pada satu sisi dan dengan selain-Nya pada sisi yang lain, seperti rasa takut (khauf) dan harap (rajā’). Keduanya berhubungan dengan kehendak dan keinginan manusia untuk memperoleh manfaat atau menghindari bahaya, di samping merupakan berntuk penerimaan terhadap Allah s.w.t. pada satu sisi dan sikap penolakan terhadap-Nya pada sisi yang lain.
Begitu pula dengan sikap tawakal. Tanpa dibarengi pengetahuan memadai tentang maknanya, tawakal menjadi tidak sempurna. Sebab, menyandarkan hati kepada Allah s.w.t. berikut ketetapan-Nya sesungguhnya bersumber dari kemampuan hati; dengan memperhatikan tujuannya.
Jika tujuan shalat adalah zikir (mengingat Allah s.w.t.), maka pelakunya mesti mengetahui betul kemampuan Zat yang dimaksud. Sehingga, dengan demikian, ia memiliki akhlak dan sopan santun di hadapan-Nya. Ia memulai takbiratul ihram dengan menyebut-nyebut kebesaran-Nya, agar ia mengetahui untuk siapa gerangan ai berdiri, duduk, ruku‘, dan sujud, di samping agar ia tunduk dengan sempurna atas segala kebesaran-Nya.
Setelah memperhatikan dan mengetahui kebesaran-Nya, tentunya seseorang akan memperhatikan tata cara dan etika shalat, bersuci, dan membersihkan diri lahir dan batin sebelumnya, serta menyibukkan diri hanya dengan Allah s.w.t. Isyarat seperti ini dilukiskan oleh Rasulullah s.a.w.: “…. dan dia (orang yang shalat) mengosongkan hatinya hanya untuk Allah….” (116) Atau jawaban beliau ketika ditanya makna ihsan, “…. engkau menyembah Allah seolah-olah melihat-Nya.” (127) Siapa pun yang menyembah Allah s.w.t., hendaklah mengosongkan hati dan “keluar” dari alam semesta ini terlebih dahulu.
Itulah sebabnya, kita diwajibkan bertakbir pada setiap perpindahan gerakan shalat. Sebab, konsentrasi yang penuh terhadap bacaan-bacaan shalat kerap kali membuat kita lalai akan kebesaran Allah s.w.t. Maka, pada setiap awal pergantian gerakan shalat, kita dituntut untuk memperbarui ingatan akan kebesaran-Nya, agar shalat kita kembali khusyu‘ dan tunduk.
Setelah takbiratul ihram, sang mushalli berkata: “Aku hadapkan wajahku kepada Dia Yang menciptakan langit dan bumi, dengan penuh kecondongan dan ketundukan (hanīfan musliman). Dan, bukanlah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang musyrik (wa mā anā min al-musyrikīn).” (138). Atau, dengan kata lain: “…. aku arahkan tujuanku hanya kepada-Nya.” Inilah inti tauhid; pengembalian diri dan taqrir (ketetapan hati). Sebab, ia menjadikan seluruh tujuan hidupnya hanya kepada Zat Yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah fathir yang berarti “mencipta,” “memulai,” atau “membelah.” Allah s.w.t. telah menciptakan yang “tiada” menjadi “ada.” Penciptaan langit dan bumi hanya dapat dilakukan oleh Tuhan yang sesungguhnya.
Kata ḥanīfan berasal dari kata ḥanīf, yang berarti “condong.” Jadi, al-ḥanīf adalah kecenderungan seseorang untuk memilih hanya satu agama yang paling benar. Sebab, Allah s.w.t. mengeluarkan
Kata salām berisi doa permohonan keselamatan dari segala kehancuran dan bencana. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa taḥiyyāt (penghormatan) yang baik dan penuh berkah datangnya hanya dari Allah s.w.t. Tidak ada yang lebih utama dibandingkan dengan berkah keselamatan dari segala sesuatu yang buruk, terlebih jika dimanfaatkan dalam hal ketaatan dan ibadah kepada Allah s.w.t.
seluruh makhluk dari perut ibunya dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Maka, siapa pun yang beriman kepada Allah s.w.t. dan memiliki pengetahuan tentang-Nya, ia berarti telah “berpaling” dari keadaan saat ia dilahirkan (tidak berpengetahuan).
Kata musliman maksudnya adalah kepatuhan dan ketaatan lahir dan batin; secara tersembunyi maupun terang-terangan.
Kalimat wa mā anā min al-musyrikīn, maksudnya adalah syirik yang menafikan tauhid; baik berkenaan dengan Zat, sifat, maupun peribadahan kepada-Nya.
Ada lima bentuk syirik, yaitu:
Pertama, syirik dalam ketuhanan. Yaitu, tidak mengakui bahwa tiada tuhan selain Dia, seperti yang dilakukan oleh umat Nasrani dan penganut paganisme.
Kedua, syirik dengan melakukan tasybih (menyerupakan Allah s.w.t. dengan sesuatu), dan menafikan bahwa: “…. tak ada sesuatu pun yang menyerupai-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (asy-Syūrā [42]: 11), seperti yang dilakukan oleh golongan Hasywiyah atau sejenisnya.
Ketiga, syirik atas sifat qidam (keabadian Allah s.w.t.). Yaitu, tidak mengakui bahwa tiada yang abadi selain-Nya, seperti yang dilakukan oleh para filsuf yang menyatakan bahwa justru alamlah yang abadi. Sesungguhnya Allah s.w.t. tiada tertandingi dalam hal keabadian, dan tiada sekutu bagi-Nya dalam hal ketuhanan.
Keempat, syirik atas af‘āl (perbuatan Allah s.w.t.). Yaitu, menafikan bahwa tidak ada yang dapat “berbuat” selain Dia, seperti yang dilakukan oleh golongan Qadariyah. Sesungguhnya Allah s.w.t. tidak tertandingi dalam perbuatan-perbuatanNya, sebagaimana di dalam hal ketuhanan dan keabadian-Nya.
Kelima, syirik dalam ibadah. Yaitu, tidak mengakui bahwa tidak ada yang patut disembah selain Dia, seperti yang dilakukan semua penyembah tuhan selain-Nya.
Syirik juga sering kali diartikan dalam beberapa pengertian. Semuanya terangkum dalam firman-Nya: “….. dan tidaklah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang musyrik (al-musyrikīn).” (al-An‘ām [6]: 79). Kata al-musyrikīn pada ayat ini dibubuhi alif dan lām (ta‘rīf) untuk menunjukkan hal tertentu.
Kemudian, masih di dalam bacaan doa iftitah, ada kalimat yang berbunyi: Inna shalātī wa nusukī (sesungguhnya shalat dan ibadahku) adalah penegasan penolakan terhadap perilaku syirik dalam hal ibadah, sebagaimana ucapan wa maḥyāya wa mamātī (hidup dan matiku) adalah penegasan penolakan terhadap perilaku syirik dalam hal kemaharajaan Allah s.w.t. Sebab, setiap yang hidup sebenarnya tidak menguasai kehidupan dan kematiannya sendiri, apalagi hidup dan kematian orang lain. Allah s.w.t. berfirman: “… maka siapa (selain Allah) yang memiliki pendengaran dan penglihatan, dan siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian, serta mengeluarkan kematian dari kehidupan, dan siapa yang mengurus segala urusan?” (Yūnus [10]: 31).
Kata al-‘ālamīn pada kalimat Rabb al-‘ālamīn (Rabb alam semesta) berarti “seluruh ciptaan.” Ungkapan ini menunjukkan bahwa Allah s.w.t. adalah Rabb semesta alam, yang diungkapkan secara lebih tegas dibandingkan dengan puji-pujian kepada-Nya. Sebab sifat rububiyah-Nya meliputi segala sesuatu.
Kata Rabb sendiri memiliki beberapa arti, salah satunya: “pemilik/penguasa,” seperti pada kalimat rabb ad-dābbah (pemilik binatang), atau rabb ad-dār (pemilik rumah). Ketika seseorang mushalli memuji-Nya dengan pernyataan bahwa Dia adalah “pemilik/penguasa,” atas hidup dan kematiannya, makna pernyataan ini berlanjut pada pujian terhadap Allah s.w.t. atas kekuasaan-Nya yang tidak hanya terbatas pada alam semesta ini.
Kalimat yang berbunyi lā syarīka lahu (tidak ada sekutu bagi-Nya), berarti tidak ada sekutu bagi-Nya dalam hal rububiyah, penciptaan alam semesta, dan dalam hak-Nya untuk disembah.
Kalimat yang berbunyi wa bi dzālika umirtu (dan atas hal itulah aku diperintahkan), mengisyaratkan perintah kepada mushalli untuk menghadapkan “wajah”nya hanya kepada yang berhak (Allah s.w.t.).
Kalimat yang berbunyi wa anā min al-muslimīn (dan aku termasuk golongan orang-orang islam/berserah diri). Maksudnya adalah orang-orang muslim yang selalu melaksanakan perintah Allah s.w.t.
Terdapat pula keterangan serupa tentang ‘Izz-ud-Dīn, di antaranya bahwa beliau pernah berfatwa tentang bolehnya memejamkan mata saat shalat. Jika dengan membuka mata seseorang sulit khusyuk dan mencapai ḥudhūr-ul-qalb, maka boleh memejamkan mata, meski pun tidak ada satu pun dalilnya di dalam al-Qur’an maupun Sunnah yang membolehkan hal demikian. Sebagian ulama malah ada yang melarangnya. Alasannya, hal itu dianggap sebagai cara yang buruk dilakukan seorang hamba ketika tengah menghadap Allah s.w.t. Apalagi, saat itu ia sedang bermunajat kepada-Nya. Pantaskah seseorang yang sedang bermunajat tidur? ‘Izz-ud-Dīn juga menjelaskan tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam shalat, seperti menggunakan sajadah yang bergambar, atau penuh hiasan sehingga mengganggu kekhusyukannya, atau tempat shalat yang terlalu tinggi. Sebab, shalat harus dilakukan dalam kondisi tawādhu‘ dan tenang, seperti kita lihat banyak orang di Makkah dan Madinah yang shalat di atas tanah, pasir, dan batu untuk menunjukkan rasa tawādhu‘nya di hadapan Allah s.w.t. Hal terbaik yang seyogianya dilakukan adalah dengan mengikuti model shalat Rasulullah s.a.w. Beliau amat jarang melakukan shalat di atas khumrah (tikar kecil), yang sebenarnya boleh dipakai saat uzur. Lihat al-Fatāwā karya ‘Izz-ud-Dīn, nomor 40 dan 41. Atau, Mughn-il-Muḥtāj karya asy-Syarbinī, 1/230, dan al-Imām al-‘Izz karya penyunting, 1/501-502.
Di dalam Qawā’id-ul-Aḥkāmi fī Mashālih-il-Anām, 1/38, pasal Fī mā Yatafāwatu Ajruhu bi Tafāwut Taḥammul Masyaqqah, ‘Izz-ud-Dīn menyatakan: “Pelaksanaan shalat zuhur dengan menunggu saat matahari lebih teduh yang berdampak pada penundaan (ta’khīr) shalat adalah termasuk ke dalam “mendahulukan maslahat yang lebih utama dibandingkan dengan maslahat yang kurang utama.” Sebab, orang yang berjalan menuju jamaah di tengah terik matahari akan merusak kekhusyukan yang menjadi keutamaan shalat. Karena itu, utamakanlah menjaga kekhusyukan shalat dibandingkan dengan pelaksanaan shalat tepat waktu.” Dari sini juga jelas bahwa keluar rumah untuk shalat berjamaah hendaklah dilakukan dengan suasana tenang dan tidak berburu-buru, meskipun hal itu bisa jadi menyebabkan seorang makmum tertinggal oleh imam. Sebab, jika terburu-buru, pasti ia akan sulit khusyū‘ nantinya. Maka, utamakanlah kekhusyū‘an dibandingkan dengan pelaksanaan shalat di awal waktu namun dengan terburu-buru. Begitu pula dengan mengakhirkan shalat demi memenuhi hal-hal yang dapat mengganggu kekhusyū‘an, seperti makan dan minum.