1-1 Sejarah Singkat Imam Syafi’i – Biografi Imam Syafi’i
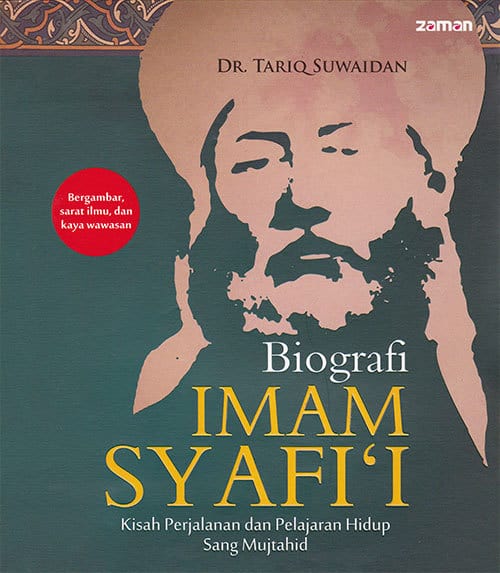
Biografi IMĀM SYĀFI‘Ī
(Judul Asli: Silsilat al-Aimmah al-Mushawwarah (2): al-Imām al-Syāfi‘ī)
Oleh: Dr. Tariq Suwaidan
Penerjemah: Iman Firdaus Lc. Q. 16
Penerbit: Zaman
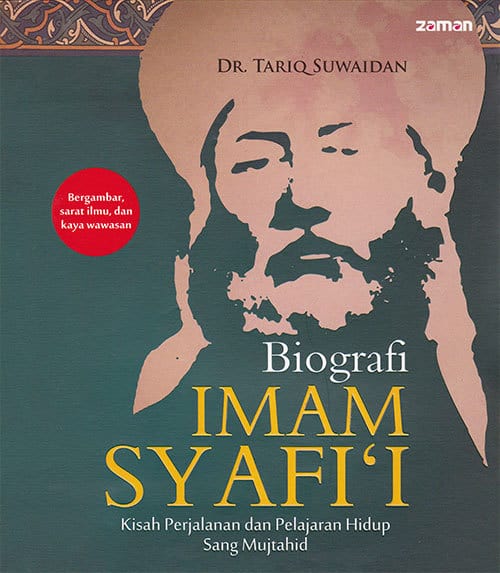
Biografi IMĀM SYĀFI‘Ī
(Judul Asli: Silsilat al-Aimmah al-Mushawwarah (2): al-Imām al-Syāfi‘ī)
Oleh: Dr. Tariq Suwaidan
Penerjemah: Iman Firdaus Lc. Q. 16
Penerbit: Zaman
BAGIAN SATU: MENGENAL IMĀM SYĀFI‘Ī
Bab 1
SEJARAH SINGKAT IMĀM SYĀFI‘Ī
1. PUTRA KELAHIRAN PALESTINA
Imām Syāfi‘ī dilahirkan pada 150 Hijrah, sama dengan wafatnya Imām Abū Ḥanīfah, guru para ahli fikih Irak dan imam metode qiyas. Mayoritas riwayat menyatakan bahwa Syāfi‘ī dilahirkan di Ghaza, Palestina, seperti yang diriwayatkan oleh Ḥākim melalui Muḥammad ibn ‘Abdillāh ibn al-Ḥakam. Ia berkata: “Kudengar Syāfi‘ī bertutur: “Aku dilahirkan di Ghaza, kemudian ibuku memboyongku ke Asqalan.”
Imām Syāfi‘ī dilahirkan di Ghaza, Palestina, pada tahun 150 Hijrah, yaitu tahun wafatnya Imām Abū Ḥanīfah.
2. NASAB YANG MULIA
Nama lengkap Imām Syāfi‘ī adalah Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-‘Abbās ibn ‘Utsmān ibn Syāfi‘ ibn al-Sā’ib ibn ‘Ubaid ibn ‘Abd Yazīd ibn Hāsyim ibn Muthallib ibn ‘Abdi Manaf. Akar nasab Syāfi‘ī bertemu dengan akar nasab Nabi s.a.w., tepatnya di moyangnya yang bernama ‘Abdi Manaf.
‘Abdi Manaf adalah moyang Nabi s.a.w. yang memiliki empat putra: Hasyim, darinya terlahir Nabi s.a.w.; Muththalib, darinya terlahir Imām Syāfi‘ī; Naufal, kakek dari Jābir ibn Muth‘im; dan ‘Abd Syams, kakek moyang Bani Umayyah. Dengan demikian, nasab keluarga Muḥammad ibn Idrīs ibn ‘Abdullāh al-Syāfi‘ī bertemu dengan nasab Nabi, tepatnya di ‘Abdi Manaf sebagai kakek moyang Nabi s.a.w.
Ada satu syair tentang nasabnya ini:
Nasabnya seakan disinari mentari pagi
Dan menjadi tiang bagi lentera
Di dalamnya hanya para pemuka dan putra para pemuka
Yang terhormat, mulia, dan bertakwa.
3. KELUARGA ‘ARAB MURNI
Muththalib ibn ‘Abdi Manaf
Muththalib ibn ‘Abdi Manaf adalah paman ‘Abdul-Muththalib, kakek Nabi s.a.w. Ada yang berpendapat bahwa ‘Abdul-Muththalib dipanggil dengan nama “‘Abd” karena dia dirawat oleh Muḥammad ibn ‘Abdi Manaf. Di zaman Jahiliah, seorang anak yatim disebut “‘Abd” bagi orang yang merawatnya.
‘Abdul-Muththalib hidup bersama pamannya, Muththalib, hingga sang paman meninggal dunia. Ketika itu Bani Muththalib merupakan sekutu Bani Hāsyim, baik di zaman Jahiliah maupun di zaman Islam. Tatkala kaum Quraisy memboikot keluarga Bani Hāsyim karena mereka melindungi Nabi, Bani Muththalib-lah yang selalu mendamping Bani Hāsyim. Mereka rela tinggal di tenda-tenda pengungsian dan menerima segala perlakuan yang diterima oleh Bani Hāsyim. Karena itu, Nabi s.a.w. sangat menghargai peran dan jasa mereka. Beliau membagi dua seperlima jatah harta rampasan perang yang diperuntukkan bagi kerabat beliau untuk Bani Hāsyim dan Bani Muththalib. Hal ini mendorong Bani Umayyah dan Bani Naufal meminta jatah seperti mereka.
Jābir ibn Muth‘im menuturkan: “Ketika Rasulullah membagikan hasil rampasan perang Khaibar yang menjadi jatah kerabatnya kepada Bani Hāsyim dan Bani ‘Abdul-Muththalib, aku dan ‘Utsmān ibn ‘Affān menghadap beliau. Kataku: “Wahai Rasulullah, mereka adalah saudara-saudaramu dari Bani Hāsyim yang keutamaannya tak diragukan, karena Allah telah memilihmu dari kalangan mereka. Akan tetapi, engkau memberi jatah ‘Abdul-Muththalib, sementara kami kau abaikan. Padahal kami dan mereka sama saja.”
Mendengar hal ini, beliau menjawab: “Mereka tidak pernah meninggalkan kami di masa Jahiliah dan di masa Islam. Bani Hāsyim dan Bani Muththalib itu sama.” Rasulullah mengucapkan hal itu sambil mencengkeramkan jari-jari tangannya.
Bani Muththalib tak pernah menjauhi Nabi di masa Jahiliah dan Islam. Rasulullah sangat mencintai mereka seperti beliau mencintai Bani Hāsyim.
Hāsyim ibn ‘Abdul-Muththalib dan Keturunannya.
Hāsyim ibn Muththalib adalah ayah ‘Abdul-Muththalib, kakek Nabi. Karena kedekatan dan kecintaan Muththalib terhadap Hāsyim, Hāsyim pun menamakan putranya dengan nama ‘Abdul-Muththalib. ‘Abdu Yazīd ibn Hāsyim punya nama lain: Abū Rukanah. Ia memiliki empat putra yang bernama Rukanah, ‘Ujair, ‘Umair, dan ‘Ubaid. Ibunda ‘Ubaid ibn ‘Abd Yazīd sendiri bernama al-Sifā’ binti al-Arqam ibn Nadhālah.
Putra ‘Ubaid yang bernama al-Sā’ib tadinya adalah seorang musyrik. Ia bertugas sebagai pengusung panji Bani Hāsyim pada perang Badar. Tetapi ia ditawan, kemudian menebus dirinya sendiri. Setelah itu ia masuk Islam. Ketika ditanya kenapa tak masuk Islam sebelum menebus dirinya sendiri, ia menjawab: “Aku tidak mau menghalangi kaum mu’min membalas sikapku terhadap mereka.”
Saat al-Sā’ib dan ‘Abbās, paman Rasulullah, dibawa menghadap beliau sebagai dua orang tawanan, Rasulullah s.a.w. bersabda tentang al-Sā’ib: “Dia saudaraku dan aku saudaranya.” Konon, al-Sā’ib ini sangat mirip dengan Nabi s.a.w.
Suatu ketika, al-Sā’ib sakit. ‘Umar berkata kepada para sahabatnya: “Mari kita menjenguk al-Sā’ib ibn ‘Ubaid karena ia orang Quraisy pilihan.”
Al-Sā’ib ibn ‘Ubaid termasuk keturunan Hāsyim. Ia memeluk Islam seusai perang Badar. Konon, ia mirip sekali dengan Rasulullah s.a.w.
Syāfi‘ ibn al-Sā’ib dan Keturunannya
Syāfi‘ ibn al-Sā’ib
Ia adalah kakek dari kakek Imām Syāfi‘ī. Nama Imām Syāfi‘ī dinisbahkan kepadanya. Ia termasuk sahabat Rasulullah generasi akhir. Semua riwayat sepakat bahwa ia pernah bertemu dengan Nabi saat ia dewasa. Tentangnya, ada satu hadits yang diriwayatkan oleh Hakim dari Anas bahwa suatu hari Nabi s.a.w. tengah berada di Fusthath. Tiba-tiba beliau didatangi oleh al-Sā’ib ibn ‘Ubaid sambil membawa putranya yang masih belia, Syāfi‘ ibn al-Sā’ib. Nabi s.a.w. pun memandang sang putra, lalu bersabda: “Termasuk kebahagiaan seseorang jika ia mirip dengan bapaknya.”
Syāfi‘ memiliki saudara bernama ‘Abdullāh yang pernah menjadi Gubernur Makkah, seperti diriwayatkan Ḥākim.
Kakek dari kakek Imām Syāfi‘ī adalah Syāfi‘ ibn al-Sā’ib, seorang sahabat kecil generasi akhir. Kepadanyalah nama Imām Syāfi‘ī dinisbahkan.
‘Utsmān ibn Syāfi‘
Ia adalah ayah kakek Imām Syāfi‘ī. Ia hidup hingga masa kekhilafahan Abī al-‘Abbās al-Saffāḥ, salah seorang khalifah Dinasti ‘Abbāsiah. Namanya pernah disebut dalam kisah Bani Muththalib. Ketika al-Saffāḥ ingin menyisihkan Bani Muththalib dari jatah seperlima rampasan perang yang sudah ditentukan Allah dan mengkhususkan untuk Bani Hāsyim saja, maka ‘Utsmān menentangnya dan meluruskan kondisinya hingga seperti di zaman Nabi s.a.w.
Al-‘Abbās ibn ‘Utsmān
Ia adalah kakek Imām Syāfi‘ī. Ia banyak meriwayatkan hadits dan banyak hadits diriwayatkan darinya. Al-Khazajī menyebut namanya dalam kitab Khalāshah. Disebutkan bahwa ‘Abbās meriwayatkan hadits dari ‘Umar ibn Muḥammad ibn ‘Alī ibn Abī Thālib r.a.
Idrīs ibn ‘Abbās
Adapun bapak Imām Syāfi‘ī adalah Idris ibn ‘Abbas. Ia berasal dari Tabalah (bagian dari negeri Tahamah yang terkenal). Tadinya ia bermukim di Madinah, tetapi di sana ia banyak menemui hal yang tidak menyenangkan. Akhirnya, ia hijrah ke Asqalan (kota di Palestina). Ia pun menetap di sana hingga wafat. Ketika itu Imām Syāfi‘ī masih dalam buaian sang ibu. Idrīs hidup miskin.
Inilah nasab keluarga Imām Syāfi‘ī yang memiliki darah keturunan ‘Arab yang sangag murni. Silsilah nasabnya sangat tinggi karena di antara mereka ada dua orang yang termasuk sahabat Nabi s.a.w. Dengan demikian, nasab Imām Syāfi‘ī adalah yang paling tinggi dan paling mulia dibandingkan tiga imam mazhab lainnya.
4. BUNDA SANG PEMBIMBING
Ibunda Imām Syāfi‘ī berasal dari Azad, salah satu kabilah ‘Arab yang masih murni. Ia tidak termasuk kabilah Quraisy, meskipun sekelompok orang fanatik terhadap Imām Syāfi‘ī mengaku-aku bahwa ibunda Syāfi‘ī berasal dari kaum Quraisy Alawi. Pendapat yang benar adalah ia berasal dari kaum Azad karena riwayat-riwayat yang bersumber dari Syāfi‘ī menegaskan bahwa ibunya berasal dari Azad. Para ulama pun sepakat akan keabsahan riwayat tersebut.
Ibunda Imām Syāfi‘ī
Seorang ibu yang sadar adalah ibu yang mendidik putra-putrinya dengan kebaikan dan keutamaan. Demikian pula halnya dengan ibunda Imām Syāfi‘ī; ia merupakan sosok ibu yang memiliki andil besar dalam membentuk dan membina kepribadiannya. Ibunda Imām Syāfi‘ī berasal dari kabilah Azad, satu kabilah ‘Arab yang masih murni.
Ahli Ibadah yang Cerdas
Ibunda Imām Syāfi‘ī termasuk perempuan paling suci, taat beribadah, dan berakhlak baik. Di antara hal menarik tentang kecerdasannya adalah saat ia menjadi salah seorang saksi di hadapan pengadilan Makkah bersama seorang saksi perempuan lain dan seorang saksi laki-laki. Ketika itu hakim ingin memisahkan antara kesaksian dua orang perempuan tersebut. Akan tetapi, ibunda Imām Syāfi‘ī berseru: “Kau tidak layak melakukan hal itu karena Allah telah berfirman: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antara kalian). Jika tak ada dua orang lelaki maka (boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kalian ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya (al-Baqarah: 282).” Akhirnya sang hakim menarik kembali pendapatnya.
Belakangan, sosok seorang ibu seperti dirinya memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk kepribadian Imām Syāfi‘ī
5. HIDUP MISKIN
Syāfi‘ī terlahir dari seorang bapak keturunan Quraisy. Bapaknya meninggal dunia saat Syāfi‘ī masih dalam buaian ibunya. Dengan demikian, Syāfi‘ī menjalani hidup sebagai anak yatim dan miskin, sementara nasabnya sangat mulia. Jika kemiskinan disandingkan dengan keturunan yang mulia maka orang yang dibina dalam kondisi ini akan tumbuh baik, memiliki akhlak yang lurus, dan menempuh jalur yang mulia. Karena, ketinggian nasab mendorong seorang anak untuk memiliki nilai-nilai mulia dan menjauhi hal-hal yang hina sejak kecil. Selain itu, hakikat “pertumbuhan” sendiri selalu bergerak ke arah ketinggan dan nilai-nilai baik. Kemiskinan yang disertai dengan ketinggian nasab inilah yang membuat Syāfi‘ī kecil dekat dengan masyarakat dan ikut merasakan penderitaan mereka. Syāfi‘ī sering berbaur dengan mereka dan merasakan apa yang mereka rasakan.
Syāfi‘ī Pindah ke Makkah
Nilai-nilai luhur telah tertanam dalam diri Syāfi‘ī. Ibunya selalu membimbing Syāfi‘ī untuk terus meraihnya dengan mengirim Syāfi‘ī dari Ghaza ke Makkah. Hal ini ia lakukan agar Syāfi‘ī bisa hidup tidak jauh dari pusat ilmu kala itu. Sang ibu juga takut Syāfi‘ī kehilangan garis nasabnya di sana.
Al-Baghdādī meriwayatkan, dalam Tārīkh Baghdād, dengan sanad yang tersambung hingga Syāfi‘ī bahwa Syāfi‘ī pernah berkata: “Aku dilahirkan di desa Yaman (desa di Palestina). Ibuku khawatir aku tersia-siakan. Ia berpesan kepadaku: “Carilah garis nasab keluargamu agar kau menjadi seperti mereka. Aku takut garis nasabmu hilang.” Kemudian ibuku mempersiapkan segalanya untuk perjalananku ke Makkah. Aku pun berangkat ke sana. Ketika itu aku masih berumur sekitar sepuluh tahun. Aku menetap di rumah salah seorang kerabatku dan mulai menuntut ilmu di sana.”
Kehidupan miskin dan ketinggian nasab disertai dengan bimbingan yang lurus membuat seseorang selalu mencari nilai-nilai luhur dan mendorongnya untuk dekat dengan orang-orang, merasakan apa yang mereka rasa, dan ikut menderita seperti yang mereka derita. Begitulah yang dialami Imām Syāfi‘ī