1-1 Kewajiban Pertama – Rambu-rambu Berteologi Imam al-Ghazali
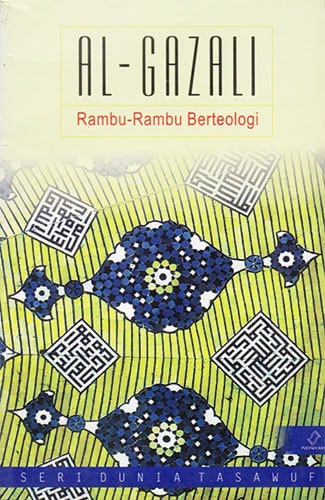
RAMBU-RAMBU BERTEOLOGI
(Judul Asli: Iljām-ul-‘Awāmi ‘an ‘Ilm-il-Kalām)
Oleh: Imām al-Ghazālī
Alih Bahasa: Kamran As‘ad Irsyady
Penerbit: Pustaka Sufi
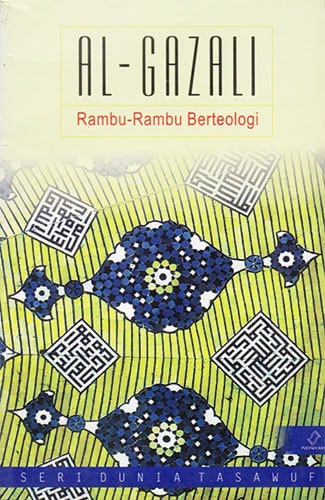
RAMBU-RAMBU BERTEOLOGI
(Judul Asli: Iljām-ul-‘Awāmi ‘an ‘Ilm-il-Kalām)
Oleh: Imām al-Ghazālī
Alih Bahasa: Kamran As‘ad Irsyady
Penerbit: Pustaka Sufi
001-1
Kewajiban pertama.
Kewajiban pertama: taqdīs (transendensi). Artinya, ketika seorang awam mendengar penyebutan “tangan” dan “jari” dalam sabda Rasūlullāh s.a.w.:
“Sesungguhnya Allah mengolah tanah liat (bahan diciptakannya) Adam dengan tangan-Nya”
Dan
“Sesungguhnya hati orang Mu’min berada di antara jari-jemari Sang Maha Pengasih,”
ia seyogianya mengetahui bahwa “tangan” mempunyai 2 makna; salah satunya adalah makna bentukan asal, yaitu organ tubuh yang tersusun dari daging dan urat syaraf (‘atsab) serta daging dan tulang. Urat syaraf adalah jisim khusus dengan sifat-sifat atributif khusus. Yang saya maksud jisim di sini adalah ungkapan dari kadar yang mempunyai panjang, lebar, yang tidak memungkinkan sesuatu yang lain berada di suatu tempat, manakala jisim itu berada di tempat tersebut, sampai kemudian ia meninggalkannya. Lafal “tangan” juga sering dimetaforkan untuk makna lain yang bukan makna asalnya, jisim. Seperti kata “seluruh negeri berada di tangan sang penguasa.” Hal ini sudah dipahami umum sebagai berarti kekuasaan, meskipun tangan si raja buntung misalnya.
Dengan demikian, orang awam dan non-awam harus meyakini secara pasti dan yakin bahwa Rasūlullāh tidak memaksudkan “tangan” dalam sabda di atas sebagai jisim, yaitu organ tubuh yang tersusun dari daging, darah dan tulang, karena hal itu muḥāl bagi Allah dan Dia tersucikan darinya.
Jika terbetik dalam benaknya bahwa Allah adalah jisim yang tersusun dari organ-organnya, maka dia penyembah berhala, karena setiap yang berjisim adalah makhluk (yang diciptakan) dan menyembah makhluk adalah perbuatan kafir. Menyembah berhala juga adalah perbuatan kafir karena berhala adalah makhluk. Berhala disebut makhluk karena ia adalah jisim. Dan barang siapa yang menyembah jisim maka ia telah kafir dengan konsensus segenap Imām Salaf dan Khalaf, tanpa memandang apakah jisim tersebut kasar seperti gunung yang bisu dan kekar menjulang; atau lembut laksana udara dan air, gelap seperti bumi; atau bersinar laksana matahari, bulan dan bintang-bintang; bisa dirasa tetapi tanpa warna seperti udara, megah seperti Singgasana, Kursi, dan Langit; atau kecil seperti atom dan debu; keras seperti batu; atau berupa hewan seperti manusia. Jisim tetaplah sama dengan berhala walaupun dibungkus dengan apa pun. Barang siapa menafikan jismiyyah; tangan dan jari-jemari, maka ia telah menafikan organisme; daging dan urat saraf, yang berarti menyucikan Allah dari hal-hal yang berimplikasi ḥudūts (kebaruan). Maka yakinilah setelah penjelasan ini semua, bahwa tangan dan jari-jemari dalam sabda di atas adalah hanya sekadar ungkapan makna (esensi) bukan jisim yang sesuai dengan Allah. Jika ia memang tidak tahu maknanya serta tidak memahami substansi dan kesejatiannya, maka ia tidak mempunyai beban taklif apa-apa dalam hal ini. Karena mengetahui ta’wil penafsiran dan pemaknaannya tidaklah diwajibkan kepadanya. Orang awam yang tidak tahu apa-apa tentang hal ini hanya berkewajiban untuk tidak menggelutinya sebagaimana yang akan kami jelaskan.
Contoh lain, jika orang awam mendengar kata “shūrah” (formula, bentuk) dalam sabda Nabi s.a.w.:
“Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dengan bentuk (shurah)-Nya”,
dan sabda:
“Dan sesungguhnya aku melihat Tuhanku dalam penampilan (shūrah) yang paling baik,”
maka ia harus tahu bahwa formula (shūrah) adalah ism musytarak (kata yang mempunyai dualitas makna, – penj.) yang kadang digunakan untuk makna bentuk (form) yang terdapat dalam tubuh yang tersusun dengan susunan tertentu seperti hidung, mata, mulut, dan pipi yang merupakan jismiyyah, yang berdaging dan bertulang. Namun terkadang juga dimaksudkan untuk makna sesuatu yang bukan jisim (ragawi) atau bentuk pada raga, dan bukan pula susunan dalam raga seperti perkataanmu “kenalilah bentuknya,” serta hal-hal lain yang senada. Setiap Mu’min harus mengimani bahwa formula (shūrah) dalam konteks Allah tidak dimaksudkan untuk makna pertama yang merupakan raga berdaging dan bertulang yang tersusun dari hidung, mulut dan pipi, sebab semua itu adalah jisim dan bentuk dalam jisim. Pencipta raga dan bentuk dalam raga tersucikan dari penyamaan dengan sifat-sifatnya. Jika memang orang awam tersebut sudah tahu secara yakin, maka ia telah beriman (Mu’min). Dan ketika terlintas di hadapannya bahwa hal itu masih mempunyai makna yang ambigu, maka ia sebaiknya tahu bahwa hal tersebut tidak boleh dipercayai, bahkan ia diperintahkan untuk tidak terjebak menggelutinya karena hal itu di luar batas kemampuannya, melainkan harus berkeyakinan bahwa hal itu dimaksudkan untuk makna yang sesuai dengan kebebasan Allah dan keagungan-Nya yang tidak beraga atau membentuk dalam raga.
Satu contoh lagi, jika telinganya mendengar kata “nuzūl” (turun) dalam sabda:
“Allah s.w.t. turun di setiap malam ke langit dunia,”
maka wajib atasnya untuk mengetahui dengan segala kesadaran bahwa “turun” adalah kata musytarak. Kata ini kadang disematkan untuk maksud yang membutuhkan 3 jisim: jisim atas yang merupakan tempat bagi kediamannya, jisim bawah begitu juga, dan jisim yang berpindah naik dari bawah ke atas atau turun dari atas ke bawah. Jika dari bawah ke atas, maka keadaan itu disebut naik, menanjak, dan meninggi. Dan jika dari atas ke bawah, maka keadaan itu disebut turun dan anjlok. Terkadang pula kata “nuzūl” dimaksudkan untuk makna lain yang tidak membutuhkan perpindahan dan gerakan dalam jisim, sebagaimana firman Allah:
“Dan diturunkan atas kamu sekalian dari binatang ternak sebanyak 8 pasang.” (QS. Az-Zumar [39]: 6).
Tidak akan pernah terlihat ada domba dan sapi yang turun dari langit dengan perpindahan fisik yang jelas muḥāl, melainkan harus dipahami sebagai terciptakan dalam rahim. Petunjuk lain adalah statemen Imām asy-Syāfi‘ī r.a.: “Aku masuk Mesir, namun mereka (penduduk Mesir) tidak mendengarkan kata-kataku, maka aku pun kemudian turun, lalu turun, dan turun.” Turun, dengan demikian, tidak bisa diartikan fisikal sebagai perpidahan jasad ke bawah. Maka seorang Mu’min harus yakin seyakin-yakinnya bahwa turun dalam konteks Allah bukanlah makna asal, yaitu perpindahan fisik tubuh dan raga manusia dari atas ke bawah, sebab orang tubuh adalah jisim, sementara Tuhan Yang Maha Agung keagungan-Nya tidak berbentuk (jisim). Jika memang orang awam tersebut belum mengerti juga, maka harus dikatakan kepadanya: “Jika untuk memahami turunnya domba dari langit saja, kamu tidak mampu, apalagi memahami turunnya Allah s.w.t. Ini bukan urusanmu. Kembali bersibuklah dengan ibadah dan pekerjaanmu, lalu berdiam dirilah. Ketahuilah bahwa hal itu dimaksudkan untuk makna yang telah ditentukan untuk kata “turun” dalam bahasa ‘Arab, dan hal itu sesuai dengan kebesaran Allah dan keagungan-Nya jika memang kamu tidak tahu hakikat dan kualitasnya.
Contoh lain lagi, jika seorang awam mendengar lafal “atas” (fawq) dalam firman Allah:
“Dan Dia adalah Yang Maha Perkasa di atas hamba-hambaNya.” (QS. Al-An‘ām [6]: 18)
serta firman:
“Mereka takut pada Tuhan mereka di atas mereka.” (QS. An-Naḥl [16]: 50)
maka ketahuilah pula bahwa fawq (atas) adalah ism musytarak yang mempunyai dua pengertian.
Pertama: afiliasi jisim pada jisim, di mana jisim yang satu berada di atas jisim lain di bawahnya. Kata ini juga sering digunakan untuk menunjukkan ketinggian kedudukan, sebagaimana adagium “khalifah (kedudukannya) di atas sultan, dan sultan di atas menteri,” juga adagium “Ilmu di atas ilmu.” Yang pertama ini menuntut afiliasi badan dengan badan.
Sementara yang kedua tidak menuntut. Seorang Mu’min harus meyakini secara pasti bahwa makna yang pertama bukanlah maksud ayat di atas, kerena hal itu mustahil bagi Allah. Hal itu lebih merupakan konsekuensi jisim dan organ jisim. Maka, jika memang ia sudah tahu akan penafian ke-muḥāl-an ini, tidak ada keterengan maksud yang lainnya, ia harus tahu apa yang dimaksudkan dalam konteks Allah s.w.t.
Selanjutnya, bandingkanlah semua yang belum kami sebutkan di sini dengan sampel-sampel yang telah kami paparkan di atas.