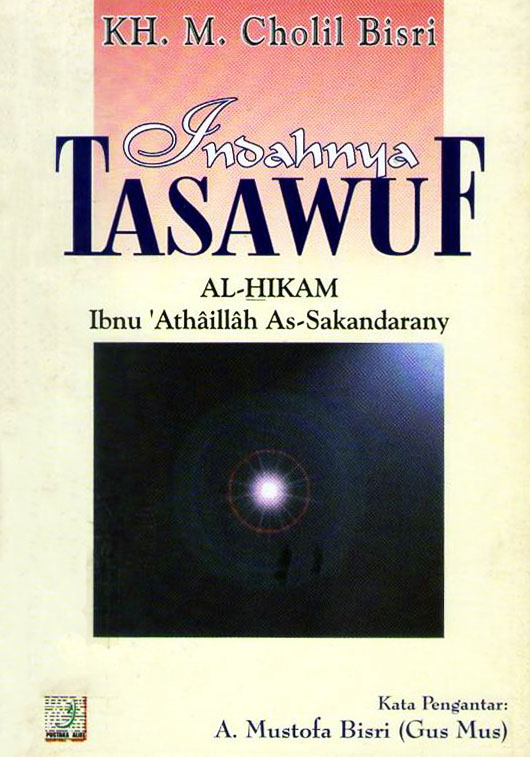6. لَا يَكُنْ تَأَخُّرُ أَمَدِ الْعَطَاءِ مَعَ الْإِلْحَاحِ فِي الدُّعَاءِ مُوْجِبًا لِيَأْسِكَ فَهُوَ ضَمِنَ لَكَ الْإِجَابَةَ فِيْمَا يَخْتَارُهُ لَكَ لَا فِيْمَا تَخْتَارُ لِنَفْسِكَ وَ فِي الْوَقْتِ الَّذِيْ يُرِيْدُ لَا فِي الْوَقْتِ الَّذِيْ تُرِيْدُ
(Jangan kiranya tertundanya waktu pengkabulan doa yang sungguh-sungguh, menyebabkan keputus-asaanmu. Allah menjamin terkabulnya doamu menurut apa yang Allah pilihkan buatmu, bukan menuru pilihanmu).
Bersungguh-sungguh dalam berdoa menandakan bahwa orang yang mengajukan permohonan (doa) benar-benar mengharapkan ijābah. Ijābah bagi doa itu ada wakutnya. Bisa jadi begitu berdoa langsung ijābah, bisa pula memerlukan tenggang waktu. Kapan waktu ijābah mendapatkan ijābah sesuai dengan janji Allah sendiri (40: 60 & 2: 186). Dengan demikian, jika doa tidak dengan “cepat” dikabulkan, bukan berarti permohonan atau doa “ditolak”. Karena itu tidak perlu membuat orang yang berdoa berputus asa. Berputus asa – terutama dari rahmat Allah – adalah fasik (12: 87). Sebaliknya mengembangkan “rajā’”, optimisme dan terus mengharap adalah sikap yang dianjurkan.
Orang tua yang sayang kepada anaknya, tidak selalu meluluskan semua permintaan anaknya itu. Dia yang sedang pilek, tidak akan mendapatkan yang diminta dari orang tuanya, jika dia meminta dibelikan es. Orang tua bisa menggantinya dengan memberikan roti kesukaan anaknya, misalnya. Allah yang sayangnya kepada makhluk ciptaan-Nya sekian kali lipat, tidak selalu meluluskan permohonan hamba-Nya sesuai dengan permohonan yang diajukan. Tetapi menggantikannya yang lain, yang – nota bene – lebih berguna dan lebih baik bagi hamba-Nya itu. Jadi Allah-lah yang memilihkan bagi pemohon. Bukan pemohon itu musti mendapatkan yang diajukan. Karena Allah yang menciptakan makhluk, maka Dia lebih mengetahui apa yang bermanfaat bagi ciptaan-Nya itu. Namun, tidak jarang, bahkan selalu, syetan membisikkan ketergesa-gesaan kepada manusia dan membujuk egoisme manusia (nafsu dan hawa nafsunya) untuk “harus” mendapatkan yang diminta. Padahal yang diminta itu belum tentu bermanfaat baginya. Sikap seperti ini dapat membuat orang berburuk sangka. Karena itu waspada terhadap godaan syaithan adalah niscaya.
7. لَا يُشَكِّكَنَّكَ فِي الْوَعْدِ عَدَمُ وُقُوْعِ الْمَوْعُوْدِ وَ إِنْ تَعَيَّنَ زَمَنُهُ لِئَلَّا يَكُوْنَ ذلِكَ قَدْحًا فِيْ بَصِيْرَتِكَ وَ إِخْمَادًا لِنُوْرِ سَرِيْرَتِكَ
(Tak terjadinya sesuatu yang dijanjikan, tidak membuat kamu ragu terhadap janji itu sendiri, meskipun waktunya telah ditentukan. Supaya yang demikian itu tidak mengaburkan matahatimu dan tidak memudarkan cahaya nuranimu.)
Jelas bahwa Allah tidak akan khilaf janji. Jika Allah menjanjikan kepada salah seorang dari hamba-Nya, bahwa pada suatu ketika akan terjadi peristiwa “anu” terhadap hamba Allah. Kemudian peristiwa itu tidak terjadi, maka tidak pada tempatnya, kemudian hamba Allah itu ragu kepada janji Allah. Karena bisa saja ada peristiwa yang dijanjikan terjadi itu, berkaitan dengan sebab atau syarat tertentu. Sedang sebab atau syarat itu tidak terpenuhi. Dengan tidak ragu itu, keyakinan dan iman seseorang tidak akan tergoncang. Barang siapa sudah sampai pada tataran ini maka dia mendekati “ma‘rifah” kepada Allah. Namun jika tidak terjadinya peristiwa yang dijanjikan itu meragukannya, pasti akan membuat matahatinya kabur dan nuraninya membeku. Dengan demikian dia makin jauh saja dari derajat “ma‘rifah” kepada Allah.
Menurut Imām Syarqawī, pemberitahuan tentang janji akan terjadinya peristiwa itu bisa lewat mimpi, ilham dari Malaikat atau yang disebut dengan “ilhām raḥmānī” yaitu ilham dari al-Ḥaqq.
8. إِذَا فَتَحَ لَكَ وِجْهَةً مِنَ التَّعَرُّفِ فَلَا تُبَالِ مَعَهَا إِنْ قَلَّ عَمَلُكَ فَإِنَّهُ مَا فَتَحَهَا لَكَ إِلَّا وَ هُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَتَعَرَّفَ إِلَيْكَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ التَّعَرُّفَ هُوَ مُوْرِدُهُ عَلَيْكَ وَ الْأَعْمَالُ أَنْتَ مُهْدِيهَا إِلَيْهِ وَ أَيْنَ مَا تُهْدِيْهِ إِلَيْهِ مِمَّا هُوَ مُوْرِدُهُ عَلَيْكَ
(Ketika Allah membuka jalan “ma‘rifah” kepadamu, kamu jangan mempedulikan mengapa jalan itu dibukakan untukmu. Padahal – kamu merasa – ‘amalmu baru sedikit. Allah membuka jalan itu bagimu, bukan lain, karena Allah menghendaki untuk memasukkan ma‘rifah kepadamu. Tidakkah kamu yakin bahwa Allah berkenan menyalurkan ma‘rifah kepadamu yang semua ‘amal ibadah yang kamu lakukan kamu arahkan kepada ma‘rifah itu? Ke mana lagi arah ‘amal ibadah itu kamu tujukan kalau tidak bermuara kepada tempuhan yang menyampaikanmu ke sana?).
Ma‘rifah kepada Allah adalah tujuan akhir, puncak dari segala cita-cita dan keinginan, serta dambaan para ‘Ābid (termasuk kita). Ma‘rifah, atau boleh diartikan “kenal benar”, adalah gerbang ke arah “intim”. Dalam intim termuat cinta, kasih dan sayang. Jika kita, setelah melihat, tertarik dan ada keinginan untuk lebih mengenal “tetangga” kita yang kita minati, biasanya lalu ada dorongan untuk sering mondar-mandir di muka gerbang yang ingin kita kenal itu. Pada saat tertentu, mungkin dalam waktu dekat atau lama, lalu ada sebab tertentu yang kemudian “memperkenalkan” kita dengan penghuni rumah di muka gerbang di mana kita telah beberapa hari mondar-mandir di sana. Yang kita minati kemudian memberi peluang kepada kita untuk berkenalan dan intim dengannya. Kita melakukan amal ibadah setiap saat, berarti kita telah mondar-mandir di muka gerbang Allah, karena kita mendambakan untuk dapat mengenalnya. Karena kita telah “menyaksikan” sendiri bagaimana “Keindahan” Allah. Jika kita sungguh-sungguh menginginkan untuk mengenal-Nya, Allah akan mengarahkan keinginan kita itu dengan sebab yang ditentukan. Boleh jadi dalam waktu singkat, saat yang kita merasa belum lama mondar-mandir di muka gerbang-Nya. Atau boleh jadi lama. Tergantung kepada “irādah” Allah.
Jika Allah berkenan, kemudian mengarahkan hamba-Nya dengan sebab yang ditentukan untuk ma‘rifah”, meskipun ibadah hamba itu belum lama benar, adalah merupakan anugerah dan itu sangat mudah bagi Allah.
9. تَنَوَّعَتْ أَجْنَاسُ الْأَعْمَالِ لَتَنَوُّعِ وَارِدَاتِ الْأَحْوَالِ
(Jenis-jenis ‘amal sangat beraneka, karena beragamanya peragaan tingkah laku).
Tingkah laku secara umum bisa dibentuk oleh latar belakang adat istiadat, budaya, lingkungan dan sebagainya. Bahkan oleh watak pembawaan sejak lahir. Sedang “tingkah laku” di sini (disebutkan dengan “wāridāt-ul-aḥwāl”) adalah dorongan “dari dalam hati” yang didesakkan oleh Allah terhadap seseorang untuk melakukan ibadah kepada-Nya atau “wirid” tertentu. Yang demikian itu disebut “Wārid Ilāhī”. Siapapun yang merasa mendapat dorongan ke arah ibadah, hendaknya tidak “menghalangi”-nya dengan bermalas-malas, misalnya. Dorongan tersebut bisa terjadi jika seseorang tidak dalam bimbingan guru. Jika dalam bimbingan guru, dia tidak melalukan selain yang diajarkannya. Jenisnya bisa bervariasi. Adalah merupakan salah satu ‘amal yang beraneka itu.
10. اَلْأَعْمَالُ صُوَرٌ قَائِمَةٌ وَ أَرْوَاحُهَا وُجُوْدُ سِرِّ الْإِخْلاَصِ فِيْهَا
(‘Amal adalah sosok yang tegak berdiri, nyawanya adalah adanya ikhlas yang tersembunyi di dalam ‘amal itu).
Diibaratkan ‘amal itu bagaikan raga. Dia hidup dan berkembang jika ada nyawanya. Nyawa dari raga (‘amal) itu adalah keikhlasan. Raga akan mati tanpa nyawa. Begitu pula ‘amal tanpa keikhlasan berarti mati. Tidak ada artinya sama sekali. Keikhlasan para ‘Ābid (orang yang beribadah) bertingkat-tingkat. Orang yang tergolong “al-Abrār”, derajat keikhlasannya ditentukan dengan tiadanya “riyā’” – baik yang jalī maupun yang khafī – ketika dia melakukan ‘amal. Orang-orang ini benar-benar menghayati firman “Iyyāka na‘budu”; hanya kepada-Mu saya beribadah, menyembah dan mengabdi. Mereka melihat diri mereka sebagai yang tidak akan mampu menanggung siksaan apabila dia tidak ikhlas dan mereka sangat mengharapkan pahala dan surga “Na‘īm”, sebagai imbalan ‘amal mereka. Dengan kata lain, dalam hal mereka ber-‘amal masih memperhatikan keuntungan yang akan dia peroleh. Sedangkan mereka yang tergolong “al-Muqarrabūn”, keikhlasan mereka sama sekali tidak melihat kepada keuntungan yang akan diperolehnya. Mereka – orang-orang yang dekat dengan Allah – sama sekali tidak peduli, apakah ibadahnya mendapat pahala atau tidak. Apakah nantinya dia di surga atau tidak. Mereka hanya menginginkan “ridhā” Allah semata-mata. Karena itu “Iyyāka nasta‘īn”, dihayatinya sebagai sebuah permohonan untuk mendapat pertolongan dalam meraih “ridhā” Allah itu.