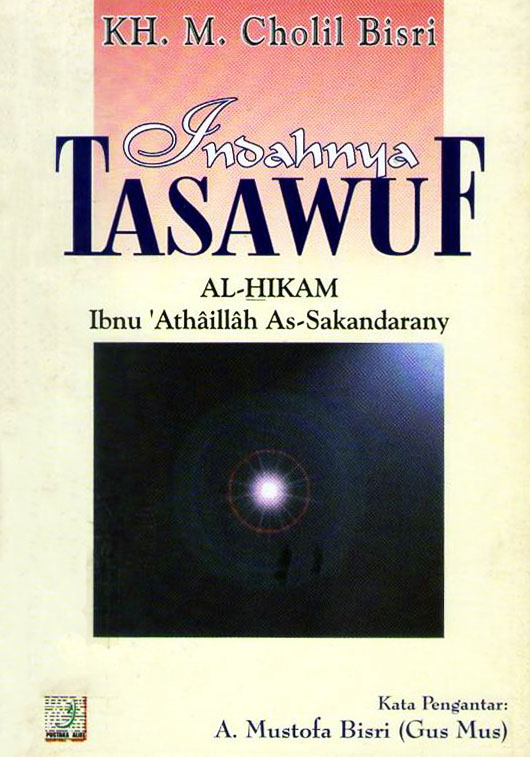17. مَا تَرَكَ مِنَ الْجَهْلِ شَيْئًا مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْدِثَ فِي الْوَقْتِ غَيْرَ مَا أَظْهَرَهُ اللهُ فِيْهِ
(Orang yang menghendaki terjadinya sesuatu pada suatu waktu tertentu. Di luar yang diperlihatkan Allah, dia sama sekali tidak menyisakan kebodohannya sedikitpun).
Artinya, bodoh sekali orang yang menginginkan perubahan keadaan yang sudah ditentukan Allah. Apalagi yang dikehendaki berubah itu sudah terjadi. Makhluk hamba Allah harus menerima apa yang dialami dengan rela. Tidak rela berarti bodohlah dia. Karena itu bagi yang telah melakukan atau mendapatkan atau menekuni sesuatu yang tidak bertentangan dengan syara‘, ketentuan agama, harus berusaha melestarikannya dan rela terhadap bagian yang diterima, sampai Allah menentukan lain. Imām Abū ‘Utsmān berkata: “Selama empat puluh tahun, saya terus dalam keadaan saya kini dan tidak berubah. Saya menyukainya meski saya inginkan lainnya.”
Mengenai “waktu”, sebagian ulama ma‘rifat mengatakannya sebagai “pedang” tajam yang bisa memotong. Dikatakan “sayf”. Pedang lentur tajam, bisa menjadi sahabat dan musuh sekaligus. Dia sahabat dari yang bisa melenturkan dan menjadi musuh atas penentangnya. Al-Imām Abul-Qāsim berkata: “Man sa‘atuh-ul-waqtu, fal-waqtu lahu waqtun. Wa man nakadah-ul-waqtu fal-waqtu ‘alaihi muqtun.” Barang siapa dibahagiakan oleh waktu, maka waktu berguna baginya. Barang siapa dicelakakan waktu, maka waktu telah memurkainya.
18. إِحَالَتُكَ الْأَعْمَالَ عَلَى وُجُوْدِ الْفَرَاغِ مِنْ رُعُوْنَاتِ النَّفْسِ
(Jika amal-amalmu didasarkan atas terwujudnya kekosongan waktu(mu), maka itu merupakan ketololan diri).
Ketika kamu ditegur; mengapa masih saja berkutat dengan keduniawian, padahal usia semakin pendek saja, kamu menjawab: “Belum ada waktu”, maka menunggu sampai ada “waktu” itu adalah kebodohan. Sering kita dengar di kalangan masyarakat, untuk melakukan ibadah secara tekun, dengan menyisihkan sebagian waktu kerjanya, kata-kata: “masih muda ini” itu, sebenarnya suatu kebodohan. Sebab tentu dia meyakini bahwa kesempatan untuk “tetap hidup”, jelas tidak berada di tangannya. Memenangkan sikap mencari “kenikmatan” dunia dengan “menunda” upaya memperoleh kenikmatan akhirat, berseberangan dengan pesan al-Qur’ān:
بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى
Artinya: Bahkan kamu memenangkan kehidupan dunia, padahal (kehidupan) akhirat lebih baik dan lebih kekal. (87: 16-17).
Orang menunda beramal akan mendapatkan salah satu dari dua kemungkinan. Yaitu mati dan makin bertambahnya kesibukan. Kedua-duanya jelas akan membuat yang bersangkutan sama sekali tidak ber‘amal (ibadah) dalam hidupnya. Dari dhawuh (ucapan, ajaran, nasihat) tersebut, kebodohan itu ada beberapa macam, antara lain:
Satu: mengunggulkan kehidupan dunia dengan mengabaikan bagian akhirat. Ini jelas tidak sesuai dengan sikap orang mukmin yang cerdas.
Dua: Menunda ‘amal sampai dia tidak mempunyai kesibukan duniawi. Dia tidak akan menemukan kesempatan itu, karena (misalnya) keburu mati atau kesibukannya bertambah-tambah.
Tiga: Dia tidak menemukan kekosongan waktu kecuali bagi hal-hal yang tidak dia sukai. Pada ketika itu dia menjadi lemah semangat dan rapuh niat.
Itulah kebodohan. Karena itu dalam beramal orang tidak perlu menunggu saat kosong atau waktu menganggur. Yang harus ditunggu adalah datangnya kesempatan dan tawakkal kepada Allah.
19. لَا تَطْلُبْ مِنْهُ أَنْ يُخْرِجَكَ مِنْ حَالَةٍ لِيَسْتَعْمِلَكَ فِيْمَا سِوَاهَا فَلَوْ أَرَادَكَ لَاسْتَعْمَلَكَ مِنْ غَيْرِ إِخْرَاجٍ
(Kamu jangan menuntut agar Allah mengeluarkan kamu dari suatu keadaan untuk beralih kepada keadaan lain. Jika Allah menghendaki kamu, pasti Dia akan membuatmu berada pada keadaan lain itu tanpa harus mengeluarkan dari keadaanmu semula).
Ketika seseorang dalam kondisi tertekan, sifat manusiawinya tentu menginginkan “keluar” dari kondisi itu. Lalu mengupayakan untuk bisa masuk ke dalam kondisi lain yang menguntungkan baginya. Bisa juga karena kejenuhan, orang menginginkan keluar dari kedudukan (baik urusan dunia maupun agama) yang sekarang diperankan. Dengan masih memerankan kedudukan semula, bisa saja Gusti Allah memberi peran ganda kepadanya. Artinya dia memperoleh peran baru tanpa harus melepas peran pertamanya.
20 مَا أَرَادَتْ هِمَّةُ سَالِكٍ أَنْ تَقِفَ عِنْدَ مَا كُشِفَ لَهَا إِلَّا وَ نَادَتْهُ هَوَاتِفُ الْحَقِيْقَةِ الَّذِيْ تَطْلُبُ أَمَامَكَ وَ لَا تَبَرَّجَتْ ظَوَاهِرُ الْكَوَّنَاتِ إِلَّا وَ نَادَتْكَ حَقَائِقُهَا: إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ
(Cita-cita orang yang menempuh jalan hakikat menuju Allah, tidak menghendaki berhenti pada saat cita-cita itu sudah tercapai, kecuali hakikat yang dituntut, yang berada di depannya, memanggilnya. Dia ciptaan Allah yang kelihatan, tidak tampak indah kecuali kesejatian ciptaan itu memanggilnya dengan ungkapan: kami hanyalah ujian, karena itu jangan kamu terjebak dalam fitnah).
Cita-cita seorang ‘Ābid tidak berhenti pada tingkat “Kasysyāf” (mampu membuka tabir kegelapan di hadapannya, dia bisa melihat apa yang berada di “balik dinding”) saja. Namun, terus berlanjut dengan ber “sulūk” (menempuh alur jalan mustaqīm/lurus yang disediakan) menuju kesejatian yang dibisikkan berada di depannya. Sehingga segala sesuatu yang diciptakan Allah, menjadi indah, apapun dan bagaimanapun. Keindahan yang dilihat, didengar, diraba, dirasa atau diindera banyak ditentukan oleh “Pembawanya” oleh “Penciptanya”. Sebuah souvenir akan sangat indah jika dibuat dan diterima dari Kekasih, yang dicintai. Namun keindahan yang berada di depan, bisa saja menjadi ujian yang di sini disebut sebagai “fitnah”. Dalam ujian orang bisa dihormati atau dihinakan. Dalam menghadapi “fitnah” orang bisa berpicuk, terpengaruh dan bahkan terbelenggu. Karena itu harus hati-hati dan waspada. Tidak jarang semua itu menjadikan orang lupa diri yang berarti juga lupa kepada Gusti Allah.
21. طَلَبُكَ مِنْهُ اتِّهَامٌ لَهُ وَ طَلَبُكَ لَهُ غَيْبَةٌ عَنْهُ مِنْكَ وَ طَلَبُكَ لِغَيْرِهِ لِقِلَّةِ حَيَائِكَ مِنْهُ وَ طَلَبُكَ مِنْ غَيْرِهِ لِوُجُوْدِ بُعْدِكَ عَنْهُ
(Tuntutanmu untuk mendapatkan sesuatu dari Allah, berarti curiga kepada-Nya. Tuntutanmu kepada-Nya berarti kamu sedang kehilangan Dia (menjauhkan kamu dari Dia). Tuntutanmu kepada selain Allah, adalah karena kamu tidak punya rasa malu. Tuntutanmu untuk mendapatkan sesuatu dari selain Allah adalah karena kamu jauh dari Allah).
Menuntut untuk mendapatkan sesuatu, misalnya rizki atau menuntut untuk mendapatkan lebih dari yang telah diterima, bisa berarti menaruh curiga kepada Allah yang Allah tidak memperhatikan. Padahal tidak begitu kenyataannya. Janji Allah adalah pasti. Curiga, ittihām, sū’-uzh-zhann atau buruk sangka, apalagi kepada Allah, kepada sesama manusia saja, merupakan sikap tercela adanya. Jika ditanya, kenapa kita harus memohon, harus berdoa, segala yang sudah ada, sedang dan akan terjadi sudah ditentukan? Para ‘Ārif billāh mengatakan: “Apa yang kita lakukan dari mengajukan permohonan atau doa, bukan lain untuk memperlihatkan kecingkrangan, kefakiran, atau kelemahan diri, melakukan perintah dan berniat ibadah. Bukan karena kita sedang ber-ittihām kepada Allah.”
Dalam kancah kehidupan, orang tidak bisa mengelak dari “bergaul” dengan “al-Khāliq” dan dengan “al-Khalq” (makhluk ciptaan Allah). Jika hamba Allah dekat dengan Allah, sudah pasti dia tidak dekat (jauh) dengan selain Allah. Begitu pula sebaliknya. Jika dia memohon kepada Allah itu karena memang diperintahkan, kecuali untuk menampilkan kelemahan, juga untuk menunjukkan “kedekatan”. Namun jika dia memohon kepada selain Allah, berarti dia harus menyingkirkan rasa malu. Andaikata dia melakukannya juga, maka berarti dia tidak mempunyai rasa malu, yang secara niscaya harus terus melekat pada diri manusia.
22. مَا مِنْ نَفْسٍ تُبْدِيْهِ إِلَّا وَ لَهُ قَدَرٌ فِيْكَ يُمْضِيْهِ
(Setiap nafas yang kamu lalui sudah ditakar oleh Allah dan bisa kamu gunakan untuk taat, maksiat, mengenyam nikmat atau merasakan cobaan).
Sebagian dari Ulama ‘Ārifīn mengatakan: “Ath-thuruqu illallāhi bi ‘adadi anfās-il-khalā’iq” jalan menuju Allah adalah sepanjang hitungan nafas para makhluk.
23. لَا تَتَرَقَّبْ فُرُوْغَ الْأَغْيَارِ فَإِنَّ ذلِكَ يَقْطَعُكَ عَنْ وُجُوْدِ الْمُرَاقَبَةِ لَهُ فِيْمَا هُوَ مُقِيْمُكَ فِيْهِ
(Jangan mengintai kekosongan perubahan/sesama makhluk. Sebab yang demikian itu dapat memutuskanmu dari adanya “Muraqabah” kepada Allah di tempat yang semestinya kamu ada).
“Murāqabah” arti logatnya: mengintai (nginjen-injen – Jawa). Ketika ‘Ābid sudah tiba saatnya untuk meningkat ke tataran ‘Ārif, dia harus terus “mengintai” kesempatan untuk kemudian masuk ke dalam kesejatian ibadah yang lalu harus berada di sana sebagai tempat dia bermukim sampai benar-benar dia mampu ma‘rifat kepada Allah. Murāqabah itu adalah sarana dan sebab yang harus dilalui oleh seorang ‘Ābid manakala akan meningkatkan tataran. Yang menempatkan pada posisi muqārabah itu hanya Allah. Untuk bisa sampai pada tataran yang dikehendaki, kadang membutuhkan waktu yang lama. Dalam menantikan peningkatan tataran, ‘Ābid tidak boleh berpaling, kalau dia tidak ingin kehilangan kesempatan. Tidak hanya itu, bahkan segala yang ditentukan Allah terjadi, tidak perlu dinantikan datangnya perubahan. Syaikh Sahl bin ‘Abdullāh berkata: “Ketika malam menyelimutimu, jangan kamu mengangankan siang. Sehingga kamu bisa melalui malammu dengan selamat dan menunaikan kewajibanmu kepada Allah dengan menyadari kedirianmu. Demikian pula waktu siang, jangan kamu mengangankan datangnya malam.”
Baik dan buruk, sejahtera dan sengsara, sehat dan sakit, kaya dan miskin, suka dan duka dan sebagainya; menurut Imām al-Baghawī adalah keniscayaan untuk mengukur sampai sebesar apa kesyukuran dan kesabaran hamba Allah.