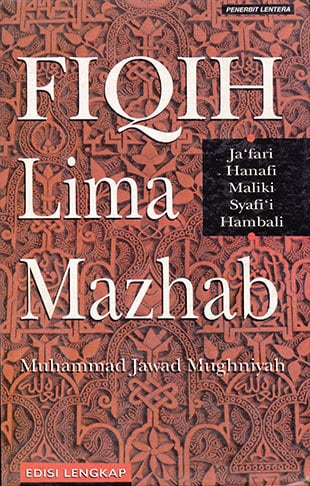BAB 1
THAHĀRAH
Kaum Muslimin sangat memperhatikan masalah thahārah. Banyak buku yang mereka tulis tentang hal itu. Mereka melatih dan mengajar anak-anak mereka bekenaan dengan thahārah. Ulama fiqih sendiri menganggap thahārah merupakan satu syarat pokok sahnya ibādah. Tidaklah berlebihan jika saya katakan, tidak ada satu agama pun yang betul-betul memperhatikan thahārah seperti agama Islam.
Thahārah menurut bahasa berarti bersih. Menurut istilah fuqahā’ (ahli fiqih) berarti membersihkan hadats atau menghilangkan najis, yaitu najis jasmani seperti darah, air kencing, dan tinja. Hadats secara maknawi berlaku bagi manusia. Mereka yang terkena hadats ini terlarang untuk melakukan shalat, dan untuk menyucikannya mereka wajib wudhū’, mandi, dan tayammum.
Thahārah dari hadats maknawi itu tidak akan sempurna kecuali dengan niat taqarrub dan taat kepada Allah s.w.t. Adapun thahārah dari najis pada tangan, pakaian, atau bejana, maka kesempurnaannya bukanlah dengan niat. Bahkan jika secarik kain terkena najis lalu ditiup angin dan jatuh ke dalam air yang banyak, maka kain itu dengan sendirinya menjadi suci.
Thahārah dari hadats dan najis itu menggunakan air, sebagaimana firman Allah s.w.t.:
“…. dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu.….” (QS. al-Anfāl: 11)
“….dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih…..” (QS. al-Furqān: 48).
Thahūr (pada ayat di atas) berarti suci pada dirinya sendiri dan menyucikan yang lain. Para ulama membagi air menjadi dua macam, berdasarkan banyak sedikitnya atau berdasarkan keadaannya, yaitu:
1. Air Muthlaq dan Air Musta‘mal.
2. Air Mudhāf.
Air Muthlaq.
Air muthlaq ialah air yang menurut sifat asalnya, seperti air yang turun dari langit atau keluar dari bumi: Air hujan, air laut, air sungai, air telaga, dan setiap air yang keluar dari bumi, salju atau air beku yang mencair. Begitu juga air yang masih tetap namanya walaupun berubah karena sesuatu yang sulit dihindari, seperti tanah, debu, atau sebab yang lain seperti kejatuhan daun, kayu atau karena mengalir di tempat yang asin atau mengandung belerang, dan sebagainya.
Menurut ittifāq (kesepakatan) ulama, air muthlaq itu suci dan menyucikan. Adapun yang diriwayatkan oleh ‘Abdullāh bin ‘Umar, bahwa tayammum lebih disukai daripada air laut, riwayat itu bertentangan dengan hadits Nabi yang berbunyi:
“Siapa yang tidak dibersihkan oleh air laut, maka Allah tidak membersihkannya.”
Air Musta‘mal
Apabila kita membersihkan najis dari badan, pakaian, atau bejana dengan air muthlaq, lalu berpisahlah air bekas basuhan itu dengan sendirinya atau dengan jalan diperas, maka air yang terpisah itu disebut air musta‘mal. Air semacam itu hukumnya najis, karena telah bersentuhan dengan benda najis, meskipun itu tidak mengalami perubahan apapun. Air itu tidak dapat digunakan lagi untuk membersihkan hadats atau najis.
Para ulama madzhab berkata: Apabila air berpisah dari tempat yang dibasuh bersama najis, maka air itu hukumnya menjadi najis. Kalau air itu berpisah tidak bersama najis, maka hukumnya bergantung pada tempat yang dibasuh. Jika tempat itu bersih, maka air itu pun suci. Sebaliknya, jika tempat itu kotor, maka air itu pun kotor. Hal itu tidak dapat dipastikan melainkan kita memperhatikan lebih dahulu tempat aliran air yang bersangkutan. Kalau hal itu tidak mungkin dilakukan, maka dianggap bahwa tempat yang dilalui air atau dibasuh itu bersih, sedangkan air yang terpisah dari tempat itu hukumnya najis.
Air musta‘mal telah digunakan untuk berwudhū’ atau mandi sunnah, seperti mandi taubat dan mandi jum‘at, hukumnya suci dan menyucikan untuk hadats dan najis; artinya air itu dapat digunakan untuk mandi wajib, berwudhū’, atau menghilangkan najis. Adapun air musta‘mal yang telah digunakan untuk mandi wajib, seperti mandi junub, dan mandi setelah haidh, maka ulama Imāmiyyah sepakat bahwa air itu dapat menyucikan najis tetapi berbeda pendapat tentang dapat tidaknya air itu digunakan untuk menghilangkan hadats dan berwudhū’, sebagian mereka membolehkan dan sebagian lain melarang.
Catatan:
Apabila orang yang berjunub menyelam ke dalam air yang sedikit, setelah ia menyucikan tempat yang terkena najis, dengan niat membersihkan hadats, maka menurut Imām Ḥanbalī air itu menjadi musta‘mal dan tidak menghilangkan janābah, malah orang itu wajib mandi lagi. Sedangkan Syāfi‘ī, Imāmiyyah dan Ḥanafī berpendapat bahwa air itu menjadi musta‘mal tetapi menyucikan janābah orang tersebut, sehingga ia tidak wajib mandi lagi. (1).
Catatan: