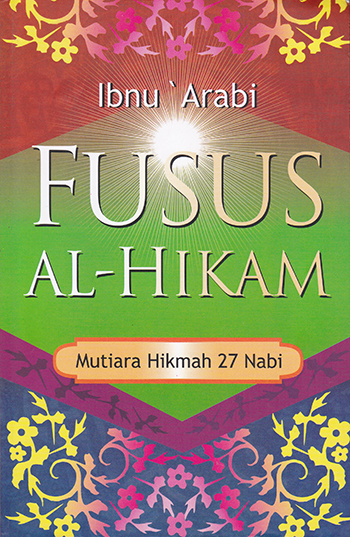1
HIKMAH KEILAHIAN DALAM FIRMAN TENTANG ĀDAM
CATATAN PENGANTAR
Bab ini, sebagaimana disugesti judulnya, sebagian besar berkaitan dengan hubungan antara Ādam – yang di sini melambangkan arketip kemanusiaan – dan Allah. Lebih khusus, bab ini berkaitan dengan fungsi Ādam dalam proses kreatif, sebagai prinsip keagenan, transmisi, refleksi, dan bahkan sebagai alasan bagi penciptaan Kosmos. Bab ini juga membahas hakikat malaikat, dan hubungan antara pelbagai pasangan konsep-konsep yang penting bagi pemahaman proses kreatif, seperti universal-individual, pasti-kontingen, pertama-terakhir, luar-dalam, cahaya-kegelapan, dan persetujuan-kemarahan.
Namun, Ibn ‘Arabī membuka bab ini dengan persoalan Nama-nama ilahi dan hubungannya dengan Esensi ilahi. Dengan istilah “Nama-nama” (Asmā’), dia menempatkan Nama Allāh sebagai Nama tertinggi. Pada hakikatnya, Nama-nama ini berperan untuk menggambarkan modalitas yang tidak terbatas dan kompleks dari polaritas Allah-Kosmos. Nama tertinggi, sebagai wujud Allah itu sendiri, jelas menggambarkan seluruh dan hakikat universal dari hubungan ini, sementara Kosmos pada hakikatnya tidak riil dan sepenuhnya bergantung. Dengan istilah “Esensi” (Dzāt), dia memaknai wujud ilahi dalam Diri-Nya, yang bebas dari polaritas atau hubungan apa pun dengan sebuah kosmos. Istilah ini seharusnya tidak dirancukan dengan “Realitas”, yang agaknya menunjukkan bahwa Wujūd primordial dan Persepsi abadi menyatukan polaritas dan nonpolaritas. Jadi, Nama-nama, termasuk Nama tertinggi, mempunyai relevansi atau makna hanya dalam konteks polaritas Keilahan-Kosmos, dan Ādam dengan tepat merepresentasikan prinsip ini, yang sekaligus memerantarai dan menetapkan keseluruhan pengalaman polaritas itu. Wujud yang terlepas dari hubungan viral ini, pada seluruh kejadian kesadaran-Diri ilahi, tidaklah mungkin.
Selanjutnya, Ibn ‘Arabī melukiskan fungsi Ādam dengan salah satu citra favoritnya, yaitu cermin, di mana dia berusaha menjelaskan rahasia dari “refleksi terhadap realitas dalam cermin ilusi.” Dalam citra yang halus ini, terdapat dua unsur: cermin itu sendiri dan subjek yang mengamati, yang melihat gambarnya sendiri terefleksikan dalam cermin sebagai objek. Ādam, sebagai faktor penghubung dalam proses refleksi dan pengakuan terhadap refleksi, adalah wakil dari cermin dan subjek pengamat. Cermin itu sendiri adalah sebagai sebuah simbol reseptivitas dan refleksivitas alam kosmik, serta subjek pengamat sebagai Allah itu sendiri. Jadi, Ādam digambarkan oleh Ibn ‘Arabī sebagai “prinsip refleksi” dan “ruh dari bentuk yang direfleksikan.” Namun, Ibn ‘Arabī tidak memikirkan tentang cermin khusus yang dilapisi kaca di masa kita sekarang, melainkan tentang logam yang digosok sangat halus sebagaimana yang dikenal di masanya. Cermin semacam ini lebih berfungsi untuk mengilustrasikan masalah-masalah metafisik yang dia bahas. Pada mulanya, cermin-cermin semacam ini tetap digosok untuk mempertahankan kualitas reflektifnya, dan selanjutnya, membutuhkan keterampilan yang rata. Karena itu, dengan sebuah cermin semacam ini, selalu ada kemungkinan pemburukan permukaan dan distorsi. Jadi, sepanjang cermin digosok dan diratakan dengan sempurna, subjek pengamat mungkin melihat bentuk citra dirinya sendiri secara sempurna yang tercermin pada permukaannya, di mana kelainan cermin itu sendiri direduksi pada yang terkecil dalam kesadarannya yang diteliti, atau bahkan dihilangkan secara sempurna. Namun, sampai batas tertentu, bahwa cermin mencerminkan sebuah citra yang pudar atau terdistorsi, ia memanifestasikan kelainannya dan mengurangi identitas citra dan subjek. Memang, citra yang terdistorsi dan tidak sempurna menunjukkan sesuatu yang asing pada subjeknya, yang kemudian berusaha untuk memperbaiki dan menyempurnakan cermin itu, sehingga dia bisa mencapai sebuah kesadaran-diri yang lebih sempurna. Jadi, di dalam cermin, kita mempunyai sebuah simbol yang sangat tepat dari polaritas ilahi-kosmik. Di satu sisi, hubungan alam kosmik yang ekstrem terancam untuk menyerap dan mengasimilasikan subjeknya ke dalam ketidakterbatasan dan kompleksitas dari dorongan kreatifnya. Sementara, di sisi lain, Subjek ilahi tampak melenyapkan Alam dalam penegasan kembali identitas, masing-masing menjadi sesuatu yang lain dan sekaligus bukan pula yang lain.
Oleh karena itu, Ādam, sebagai arketip kemanusiaan, berada dalam hakikat esensialnya sekaligus medium penglihatan dengan mana subjek refleksi dengan mana kosmik-Nya, atau refleksi dan medium refleksi dengan mana kosmik “lain” kembali pada dirinya sendiri. Karena itu, sebagai medium, Ādam-lah yang merupakan prinsip hubungan polar, dan yang, sebagaimana adanya, mengenal Nama-nama Allah, di mana dia diperintahkan dalam al-Qur’ān untuk mengajarkannya kepada para malaikat.
Subjek tentang keadaan malaikat selalu menjadi sesuatu yang problematis dalam teologi. Bagi Ibn ‘Arabī, malaikat tampak menjadi partikularisasi dari kekuasaan ilahi, apakah ia kreatif ataukah rekreatif, wujud-wujud yang di satu sisi dekat dengan kehadiran ilahi namun di sisi lain tidak mempunyai kesamaan aktualitas fisik dan formal dari penciptaan kosmik. Jadi, mereka adalah murni wujud spiritual, sangat tidak sama dengan wujud Ādam bipolar dan sintetik yang dia sendiri, dari semua penciptaan, mempunyai kesamaan dengan kesadaran-diri dari Realitas. Lagi pula, penciptaan binatang, sebagai partikularisasi dari kehidupan kosmik murni, terletak di luar pengalaman sintetik unik dari keadaan manusia.
Citra lain yang digunakan Ibn ‘Arabī dalam bab ini, dan lebih tepat lagi khususnya dalam karya ini, adalah cincin-tanda. Dalam citra ini, manusia dipandang sebagai tanda yang menyegel dan melindungi rumah kosmik kepunyaan Allah dan dicap dengan stempel Pemiliknya. Jadi, Ādam, sebagai manusia, adalah lilin penerima yang menanggung citra dari Nama Allah Yang Maha Meliputi dan Maha Tinggi, keputusan di mana capnya berarti akhir dari semua kejadian kosmik.
Namun, sebagaimana dijelaskan di atas, sementara umumnya ditegaskan ketinggian abadi dari kutub kognitif dan volitif, Ibn ‘Arabī selalu merujuk pada ketergantungan mendasar dari pengalaman polar, dengan mempertahankan konsep fundamental tentang Kesatuan Wujud (Waḥdat-ul-Wujūd). Jadi, sebagaimana dia jelaskan di sini, istilah “asal-usul” tidaklah bermakna tanpa mengasumsikan eksistensi dari sesuatu yang “diasali”, dan demikian juga dengan semua konsep polar, termasuk istilah “Allah” dan “Tuhan”, yang hanya bermakna jika istilah-istilah yang sesuai “penyembah” dan “budak/hamba” ditunjukkan secara tidak langsung.
Dengan mempertahankan premis dasar Ibn ‘Arabī ini, tidak mengejutkan jika gagasannya tentang Iblīs atau Syaithān agak berbeda dengan teologi umum. Bahkan, dia melihat prinsip diabolik ini dengan dua cara atau prinsip. Pertama, prinsip yang menentang dorongan pengejawantahan-diri untuk menciptakan objek lain dari dirinya dan menegaskan ruh murni dan transenden, sebagai alasan untuk penolakan Syaithān dalam mengabaikan perintah Allah untuk bersujud di hadapan Ādam, dari kecemburuan karena bersatunya ruh murni. Kedua, juga prinsip yang menegaskan realitas terpisah dari kehidupan dan substansi kosmik serta yang menyangkal semua keutamaan dari Rūḥ. Dengan kata lain, prinsiplah yang berusaha menegaskan realitas dari kutub, dengan mengorbankan yang lain, dan kemudian menghalangi keseluruhan orisinal dari pengalaman ilahi sebagai Realitas, dengan mencoba memutuskan mata rantai yang sangat penting antara “sendiri” dan “yang lain”, dan mengasingkan masing-masing pada isolasi yang saling terpisah dalam absurditas.