08 Iman dan Sifat-sifatnya – Intisari Ilmu Tauhid (1/2)
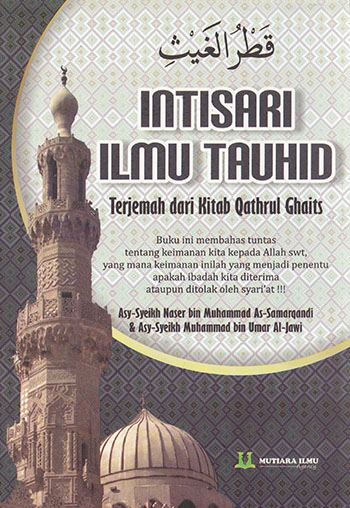
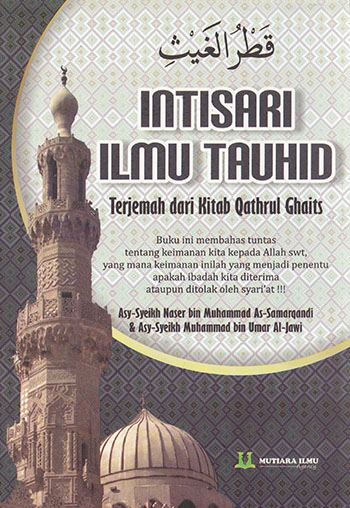
BAB VIII
مَسْئَلَةٌ إِذَا قِيْلَ لَكَ:
اَلْإِيْمَانُ يُتَجَزَّأُ أَمْ لَا؟
فَالْجَوَابُ الْإِيْمَانُ لَا يُتَجَزَّأُ لِأَنَّهُ نُوْرٌ فِي الْقَلْبِ وَ الْعَقْلِ وَ الرُّوْحِ مِنْ بَنِيْ آدَمَ وَ هُوَ هِدَايِةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَمَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْهَا فَقَدْ كَفَرَ.
S: “Apabila ditanyakan kepada engkau: “Apakah Īmān itu dapat terbagi atau tidak?”.”
J: “Īmān itu tidak dapat terbagi-bagi, karena īmān itu merupakan Nūr (cahaya) dalam akal dan ruh manusia, ia merupakan hidāyah (Petunjuk) Allah kepadanya, barang siapa mengingkari atau ragu bahwa īmān adalah hidayah Allah, maka ia benar-benar kāfir.”
مَسْئَلَةٌ إِذَا قِيْلَ لَكَ:
مَا الْمُرَادُ بِالْإِيْمَانِ؟
فَالْجَوَابُ الْإِيْمَانُ عِبَارَةٌ عَنِ التَّوْعِيْدِ.
S: “Apabila ditanyakan kepada engkau: “Apa yang dimaksud Īmān?”.”
J: “Īmān adalah merupakan perkataan dari tauhid.”
Īmān adalah ungkapan dari tauhid, menurut ‘ulamā’ ahli Kalām, Tauhid ialah mengesakan Tuhan yang disembah melalui wadah dengan mengakui keesaan-Nya dalam dzāt, shifat, dan af‘āl (tindakan)-Nya. Dikatakan juga tauhid adalah meyakini hal-hal yang pasti pada Allah dan Rasūl-Nya, hal-hal yang jā’iz dan hal-hal yang mustaḥīl.
Menurut ‘Ulamā’ Ahli Tashawwuf, Tauhid adalah bahwa seseorang itu tidak melihat kecuali hanya kepada Allah. Artinya, seluruh perbuatan, gerak dan diam, seluruh kejadian pada makhluk, itu semuanya dari Allah ta‘ālā Yang Maha Esa tidak ada sekutu bagi-Nya. ‘Ulamā’ Ahli Tashawwuf sama sekali tidak memandang adanya perbuatan terhadap selain Allah ta‘ālā. Terkadang perkataan Īmān itu diartikan tanda-tanda keimanan seperti yang pernah ditanyakan oleh Nabi s.a.w. kepada orang-orang ‘Arab:
أَتَدْرُوْنَ مَا الْإِيْمَانُ بِاللهِ تَعَالَى وَحْدَهُ. فَقَالُوْا: اللهُ وَ رَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ (ص): شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَ صَوْمِ رَمَضَانَ وَ أَنْ تُعْطُوْا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ.
“Apakah kamu semua mengerti, apa arti Īmān kepada Allah s.w.t.?” Mereka menjawab: “Allah dan Rasūl-Nya lebih mengetahui.” Beliau bersabda: “Yaitu bersaksi tidak tuhan selain Allah, dan aku adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhān, dan menyerahkan seperlima hasil rampasan perang.”
مَسْئَلَةٌ إِذَا قِيْلَ لَكَ:
الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الزَّكَاةُ وَ حُبُّ الْمَلَائِكَةِ وَ حُبُّ الْكُتُبِ وَ حُبُّ الرُّسُلِ وَ حُبُّ الْقَدَرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَ غَيْرِ ذلِكَ مِنَ الْأَمْرِ وَ النَّهْيِ وَ اتِّبَاعِ سُنَّةِ النَّبِيِّ (ص) أَهُوَ مِنَ الْإِيْمَانِ أَمْ لَا؟
فَالْجَوَابُ: لَا، لِأَنَّ الْإِيْمَانَ عِبَارَةٌ عَنِ التَّوْحِيْدِ وَ مَا سِوَى ذلِكَ شَرْطٌ مِنْ شَرَائِطِ الْإِيْمَانِ.
S: “Apabila ditanyakan kepada engkau: “Apakah shalat, puasa, zakat, mencintai Malaikat, mencintai kitab-kitab, mencintai para rasūl, senang pada taqdīr Allah baik maupun buruknya, perintah dan larangan-Nya, dan mengikuti sunnah Nabi s.a.w. termasuk īmān atau tidak?”.”
J: “Semua yang tersebut di atas tidak termasuk Īmān, sebab īmān itu sebuah ungkapan dari tauhid dan segala sesuatu selain tauhid hanyalah merupakan syarat sahnya Īmān.”
Shalat, puasa, zakat, mencintai malaikat, kitab, para utusan dan ridhā pada taqdīr Allah baik dan buruknya, senang menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah serta mengikuti sunnah Nabi s.a.w., itu semua tidak termasuk hakekat atau pokok Īmān, tetapi hanyalah cabang dari īmān sebab īmān adalah ungkapan dari tauhid sebagaimana diterangkan di atas, selain itu adalah syarat sahnya īmān dan cabangnya, sebab termasuk syarat sahnya īmān adalah senang pada Malaikat Allah, para Nabi-Nya dan para Wali-Nya, takut pada siksa-Nya, berharap rahmat-Nya, memperhatikan perintah dan larangan-Nya, serta membenci musuh-Nya yaitu orang-orang kāfir.
Adapun shalat, puasa, zakat, dan haji adalah menjadi syarat sempurnanya Īmān menurut pendapat yang dipilih di kalangan ‘Ulamā’ Ahl-us-Sunnah. Jadi orang yang meninggalkan shalat, zakat dan yang lain sedangkan ia mengakui dan membenarkan kalau hal itu diwajibkan atas dirinya, atau meninggalkan salah satunya sedang ia mengi‘tiqadkan wajibnya, maka ia disebut orang mu’min yang sempurna dalam hal berlakunya hukum-hukum bagi orang mu’min di dunia dan akhirat. Sebab pada akhirnya akan masuk surga, sekalipun masuk neraka kalau tidak mendapat syafā‘at dari salah seorang yang diidzinkan memberi syafā‘at atau mendapat ampunan Allah. Dan orang Mu’min ini disebut mu’min yang kurang, dari segi lemahnya īmān. Sebab ia meninggalkan perintah-perintah Allah. Jika ia meninggalkan perintah-perintah itu karena kejam terhadap peraturan Agama, atau merupakan kewajibannya, maka dia seorang kafir berdasarkan Ijma‘ ‘Ulamā’. Demikian pula jika ia meninggalkan salah satu dari empat perintah wajib di atas secara kejam. Sebab perintah itu berdasarkan dalil Syara‘.
Ketahuilah, urusan agama itu ada empat:
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.
“Semua ‘amal perbuatan itu sah hanya dengan niat.”
Apabila engkau ditanyakan kepadamu bahwa kekafiran itu sebab qadhā’ Allah s.w.t. dan qadar-Nya, sedangkan ridhā (menerima) qadhā’ dan qadar Allah adalah wajib, padahal ridhā (menerima) kekafiran adalah sebuah kekafiran. Bagaimana mengkompromikan hal yang wajib dan kekafiran?
Saya tegaskan, bahwa kekufuran adalah perkara yang telah dipastikan dan ditaqdirkan, bukan qadhā’ dan qadar. Sedangkan yang diwajibkan adalah menerima (ridhā) adalah pada qadhā’ dan qadar Allah, bukan pada perkara yang di-taqdīr-kan. Selain itu, bahwa perkara yang berlainan dengan syara‘ (hukum agama) itu dengan sendirinya tidak disukai oleh setiap hamba. Kalau memandang bahwa adanya perkara itu diqadhā’ oleh Allah, seseorang dapat ridhā dalam arti bahwa ia tidak menentang apa yang dikehendaki Allah dalam hal urusan yang bertentangan dengan Syara‘ itu dia tidak dipaksakan untuk mencintai perkara yang bertentangan dengan syara‘, sekalipun dipandang dari segi kedudukan perkara itu dapat diqadhā’ oleh Allah. Seseorang hamba hanya dipaksa meninggalkan menentang Allah, dan mengi‘tiqadkan adanya hikmah pada qadhā’ dan membenarkan sifat ‘Adilnya Allah.